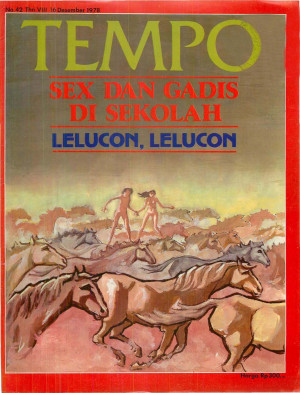SAMPAH ternyata tidak dimusuhi semua manusia. Ia memiliki nilai
sosial yang tinggi di mata para pemburu sampah, sebagai sumber
hidup. Sebab dari berbagai sisa yang dilemparkan oleh wargakota
dari rumah masing-masing, ternyata masih ada yang bisa
dijualbelikan kembali.
Radjak, 50 tahun, asal Kuningan, sudah setahun ini hidup dari
sampah ibukota. Ia memasuki Jakarta tahun 1951, digaet oleh
seorang pemborong, untuk menggali empang di daerah Grogol. Dari
kuli kemudian ia merubah nasib jadi pekerja Dinas Kebersihan DKI
Prestasi yang dicapainya hanya sampai kepada ketrampilan
menyetir buldozer. Dengan status honorer dan bayaran Rp 500 per
hari, ia merobohkan gunung-gunung sampah. Barangkali dari
pergaulannya itu kemudian timbul ide mencintai sampah.
Sebetulnya Radjak bukan cinta pada sampah. Ia hanya butuh
beberapa liter beras dan uang kontan yang bisa diperoleh dengan
menyulap sampah jadi barang dagangan. Caranya mudah saja. Dengan
modal Rp 5000, Radjak mengumpulkan barang-barang bekas mulai
dari kardus, kertas dan kaleng. Ia beli kaleng Rp 1 per biji,
atau borongan dua gerobak sampah dengan harga Rp 5 ribu. Dari
gerobak itu setiap hari selalu dapat disisihkan dua sampai tiga
ikat kertas yang menghasilkan 2 liter beras. " Lumayan," kata
isteri Radjak.
Kaleng berbagai bekas minuman, makanan dan obat harus digunting
dulu sebelum dijual. Per kilogram Rp 30-harga sebelum devaluasi.
Tutup kaleng yang berupa aluminium dipisahkan, per kilogram
sampai berharga Rp 150. Radjak tinggal menumpuk saja. Sekali
seminggu datang pemborong untuk mengangkutnya ke Bandung.
Kabarnya diolah jadi krop minuman dan pengganjal obat nyamuk.
Total jenderal Radjak hanya dapat Rp 1000. "Kalau
dihitung-hitung rugi juga, lha tenaga saya untuk menggunting ini
3 hari," ujar Radjak. Untung dua tiga liter beras yang didapat
tiap hari agak menghibur.
Dulu tempat penumpukan sampah di Cawang bagaikan gunung. Rumah
Radjak persis di kaki gunung itu. Kini gunung kempes karena
ditutup. Di samping itu sudah begitu banyak orang menggerayangi
sampah untuk mengisap unsur-unsur yang masih bisa dijual dan
disebarkan kembali ke masyarakat. "Lihat di kali Malang, Slipi,
Kebayoran bahkan juga Ancol, semua orang jadi tukang gunting
kaleng," kata Radjak menuding saingan-saingannya. Tetapi ia
tidak gentar. Kalau tak ada kaleng, ia ambil gerobaknya dan
pergi ke Halim, Kebon Kosong atau Kalibata, mengaduk sampah yang
bisa dimanfaatkan. Mengapa gerobak? "Bapak nggak kuat mikul
keranjang, lebih enteng gerobak, lagian orang kan tak mencurigai
kita," ujar Radjak yang tua itu.
Radjak menganggap kerja itu halal, karena itu ia tidak malu.
Satu atau dua kali seminggu ia berangkat dengan gerobak menempuh
jarak 5 atau 6 kilo. Badannya jadi hitam karena tak pernah pakai
baju. Satu kali ia ditegur tentara di Kalibata. Ia ditanyai.
Kemudian ketahuan karena ia memakai celana hijau. Tentara itu
rupanya barusan kehilangan celana dari jemuran. Radjak panas
juga menerima dakwaan itu, tapi ya mau apa. "Sebetulnya bukan
didakwa tapi dicurigai, tapi kan nggak enak." Untung saja ia
punya KTP DKI sehingga persoalan itu selesai dengan baik.
Karier Radjak sebagai pemburu sampah yang tinggal di sepetak
tanah ukuran 3« x 6 meter milik pak Hadji, lumayan. Memang belum
bisa beli tv, tapi ia punya radio. Rumahnya berharga Rp 1000,
dikerjakan sendiri dari kayu dan kardus. Di dalamnya ada gambar
Panca Sila. Sebuah foto Mayjen Sugandhi bersama isteri. "Tak
ada foto pak Harto, kan harus beli, mana ada uang, kalau ini kan
saya dikasih," kata Radjak. Di atas meja rumahnya ada vas bunga
dari bekas peluru mortir. Ini kenang-kenangan dari keponakannya
yang pernah bertugas di Tim-Tim. Anak Radjak, seorang saja,
sudah besar, jadi petani di kampung. Setahun sekali Radjak
pulang ke kampung membawa duit Rp 10 ribu.
Meskipun menghirup udara busuk dari sampah setiap hari, ia tak
pernah Sakit. Isterinya malah pernah ditimpa tipus, sehingga
Radjak harus keluar Rp 50 ribu. Untung ada sumbangan dari
keluarga. Isterinya itu pula yang kelihatannya tidak begitu puas
dengan kehidupan tukang buru sampah. "Bapak ini malas," kata
perempuan itu kepada Widi Yarmanto dari TEMPO, "nggak mau kayak
orang lain yang cari. Kalau nggak ada kaleng sudah aja diam.
Mana rokoknya kempas-kempus terus, maunya jarum coklat dua
bungkus sehari."
Kebebasan
Ada seorang tukang kumpul sampah yang sukses. Ia tidak saja
berhasil beli tv tapi juga kolt dan menanggap golek waktu
menyunatkan anaknya. Namanya Karya. Ia tinggal di bilangan Jalan
Pramuka (Jakarta). Banyak orang tahu ia adalah contoh yang baik
dari kelas tukang sampah. Hanya saja tingkatnya agak berbeda.
Karya tidak hanya mengandalkan tenaga. Ia memiliki modal.
Mula-mula ia seperti halnya dengan pemburu sampah lain. Tapi
otaknya bekerja terus. Belakangan ia tidak hanya mengorek
sampah, tapi juga memborong sampah pabrik-pabrik. Sayang tak ada
yang tahu di mana tinggalnya sekarang. Yang ada hanya
tetangganya bernama Momon, yang dulu sampai sekarang tetap jadi
tukang buru sampah kelas biasa.
Momon beberapa strip di bawah Karya. Ia memasuki Jakarta 1972
dengan tangan hampa. Sekarang ia sudah punya rumah meskipun
bukan di tanah milik sendiri. Kelebihannya karena ia punya 2
orang pembantu. Operasinya tidak di tempat penumpukan sampah
masal, tapi di depan rumahnya sendiri, berkat kerjasama dengan
supir truk sampah. Kelebihannya yang lain adalah karena di
samping profesinya ia sempat jadi Hansip menjelang pemilihan
umum lalu. "Habis pemilu berhenti, tapi banyak aja yang masih
menyangka saya Hansip," kata Momon.
Momon, 31 tahun, aslinya bernama Ngadiman. Tak pernah marah,
suka ketawa, gemuk dan tentu saja hitam. Sudah berkeluarga, anak
satu. Amat bangga kalau dapat membuat dirinya berfungsi sosial.
Karena itu ia selalu diikutkan dalam soal-soal keamanan kampung.
Di mana ada kerja bersama di situ ia ada. Mengorek sampah
baginya sesuatu yang sama halalnya dengan kerja lain. Ia ingin
hidup ini seperti begini saja. Ia sudah merasa cukup pantas,
cukup tenang sebagai tukang kumpul sampah. Ia tidak setuju
dengan transmigrasi. "Saya tidak mau. Saya di sini saja,"
ujarnya menunjuk ke arah sampah.
Berbeda dengan Radjak, Karya dan Momon, adalah seorang putera
Solo yang tinggal di balik gunung sampah Jalan Soeprapto
(Jakarta). Namanya Marno, 35 tahun. Setiap hari ia menempuh
jalan 15 km, karena ia tidak menguber sampah di tempat
penimbunan, tapi menguntitnya ke rumah-rumah penduduk. Ia mulai
dinasnya pukul 7 pagi, berakhir pukul 9 untuk babak pertama.
Pukul 11 berangkat lagi dan kembali pukul 1 siang. Belum habis.
Babak ketiga dimulai pukul 2 dan usai pukul 5 sore. "Hasilnya
lumayan, satu hari bisa dua ribu lebih," kata Marno. Ongkos
makan dan rokoknya Rp 750. Jadi paling sedikit ia menabung Rp
1000 sehari.
"Pokoknya di Jakarta ini asal tidak malu bisa hidup," kata Marno
memberikan ulasan. Di Solo ia tidak melihat keramahan hidup
macam itu. Dengan tenang ia menyusuri Pulomas, Cempaka Putih,
Galur setiap hari. Kalau ada yang mengawasinya karena curiga ia
pakai saraf baja. "Toh saya tidak nyuri atau nyolong," ujarnya.
Ia mengaku pekerjaan itu disambutnya karena terpaksa. "Habis mau
kerja apa lagi," kata Marno.
Para pengumpul sampah tidak terbatas pada mereka yang sudah tua
dan dewasa. Banyak anak-anak remaja tak segan untuk memangku
jabatan ini. Ada yang bernama Timbun (18 tahun) asal Salatiga.
Ia ke Jakarta untuk merubah nasib. Mula-mula sebagai buruh
pabrik roti. Tapi jiwa petualangannya menyebabkan ia sebal di
pabrik. Keluar. Langsung bergaul dengan sampah. Tidur di sekitar
sampah dan berusaha menghindari orang-orang yang mungkin
mengenalnya. "Kalau orang tua saya tahu, pasti tak boleh," kata
Timbun. Untuk meninggalkan sampah ia ogah. Kenapa? Baru sebulan
ia merasakan nikmatnya punya penghasilan sambil merasakan
kebebasan, tidak diperintah orang lain dan kerja semaunya.
Kebebasan, alangkah menariknya kata itu. Sore hari dari balik
gunung-gunung sampah itu kebebasan menunjukkan artinya. Beberapa
orang tampak keluar dengan pakaian-pakaian neces. Mereka adalah
orang-orang yang tadi siang letek, berbau sampah dan agaknya
menjadi bagian dari pemandangan ibukota yang kurang terhormat.
Dari badannya meruap wangi yang tajam dari bekas sabun. Tapi
mereka tak diperintah oleh siapa-siapa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini