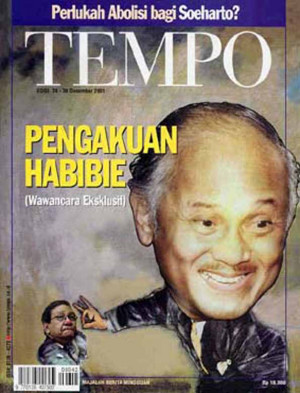TIDAK mengherankan bila Nancy, kita sebut saja namanya begitu, merasa trauma berat hingga sekarang. Beberapa bulan silam, wanita 25 tahun itu kehilangan bayi pertamanya, yang tidak bisa diselamatkan oleh operasi caesar yang terlambat—bayinya sempat divakum sebelum ditolong dengan operasi caesar. Namun, kemalangannya ternyata belum cukup. Operasi caesar yang dijalaninya menyisakan penderitaan lain. Bila buang air kecil, ia selalu mengalami perdarahan.
Ternyata ini biang keladinya: dari foto rontgen, terlihat bahwa sebelah ureter (saluran kencing) Nancy luka terpotong gunting bedah. Bekas luka gunting itu pun tampaknya dijahit secara ceroboh sehingga justru mengunci total ureter sebelah yang lain. Ia pun terpaksa kembali dibaringkan di meja operasi.
Kecerobohan itu, meski disangkal oleh sang dokter, agaknya diakui oleh rumah sakit di Jakarta tempat Nancy dirawat. Pihak rumah sakit telah meminta maaf dan memutuskan kontrak dengan sang dokter. Nancy sendiri memilih ingin segera melupakan pengalaman traumatisnya dan memetieskan perkaranya.
Pengalaman buruk para ibu yang tengah berjuang melahirkan bayinya seperti itu sebenarnya bukan hanya milik Nancy. Umumnya mereka memilih bersikap seperti Nancy: pasrah. Toh, ada juga satu-dua pasien yang merasa mendapat pelayanan tak layak dari rumah sakit dan dokter yang berani bersuara lantang. Dwi Sugianti, misalnya. Wanita 27 tahun itu kini melayangkan gugatan kepada Rumah Sakit William Booth, Surabaya, dan Dokter Lili Dewata Azinar, setelah ia kehilangan putra ketiganya pertengahan November lalu. Dwi yakin nyawa bayinya melayang karena dokter mengabaikan permintaannya untuk melahirkan melalui operasi caesar.
Dwi menceritakan, sesungguhnya kehamilannya berlangsung lancar dan dokter pun menyatakan janinnya sehat. Hanya, Dwi meminta dokter melakukan bedah caesar jika saat melahirkan tiba. Ia tak ingin mengulang kejadian beberapa tahun silam saat dia me-lahirkan anak pertama. Kala itu, ukuran bayinya kelewat besar sehingga menyulitkan proses bersalin dan si bayi meninggal begitu dilahirkan. Namun, permintaan bedah caesar tidak kontan terkabul. Persalinannya semula dilakukan dengan alat bantu vakum. Bayinya memang sempat lahir selamat, dengan sedikit bekas memar di kepalanya.
Kebahagiaan Dwi dan Purnomo memang tak bertahan lama. Dua jam kemudian, bayi seberat 4,2 kg itu berhenti bernapas. Pasangan Dwi-Purnomo pun yakin kejadian tragis ini bermuara pada dokter yang mengabaikan permintaan bedah caesar. Mereka pun segera mengambil langkah hukum dan menunjuk Dading P. Handojo sebagai pengacara untuk menuntut Rumah Sakit William Booth dan Lila Dewata Azinar.
Sementara itu, Lila Dewata menolak tindakan medisnya dinilai sembarangan. Menurut dia, kondisi janin saat itu sudah mendesak harus dikeluarkan dari rahim dan prosedur yang paling cocok adalah menggunakan alat bantu vakum. "Bedah caesar akan terlalu lama," kata Lila kepada Adi Mawardi dari TEMPO. Lagi pula, Lila melanjutkan, postur tubuh Dwi cukup menunjang untuk melahirkan secara alami tanpa bedah caesar.
Lila juga menolak jika kepala bayi yang memar dinilai sebagai sebab kematian. Alat bantu vakum memang biasa menyisakan bekas memar di kepala. Tapi, secara medis, memar janin tak berdampak fatal, apalagi mematikan. Karena itu, Lila menduga si bayi mengalami kondisi serius sehingga berujung pada kematian. Artinya, "Bedah caesar juga tak menjamin anak bertahan hidup," kata Lila, yang kini mengaku pasrah menghadapi gugatan Dwi-Purnomo.
Keterangan Lila didukung oleh Djuharto Sutanto, Direktur Akademi Perawat Rumah Sakit William Booth, yang juga menjadi kuasa hukum rumah sakit itu. Berdasar penyelidikan sementara, Djuharto yakin tak ada indikasi malapraktek oleh dokter dan rumah sakit.
Tentu saja, sepanjang proses hukum belum tuntas, Lila belum bisa disebut melakukan malapraktek. Apalagi prosedur standar medis memang tak selalu sesuai dengan harapan dan pemahaman pasien. Ketidaksesuaian ini, yang diperparah dengan rendahnya mutu komunikasi dokter-pasien, kerap memicu kesalahpahaman yang fatal.
Namun, lepas dari pengalaman buruk Nancy dan Dwi, tampaknya harus diakui bahwa tenaga medis kerap mengabaikan sikap profesional saat menangani pasien. Sikap inilah yang sering menyulut terjadinya kekeliruan medis atau medical error, baik saat persiapan, selama operasi, maupun sepanjang pengobatan (lihat Kekeliruan Medis Ada di Mana-Mana).
Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Jakarta, juga mencatat adanya sikap tak profesional sebagian tenaga medis. Sepanjang 2001, misalnya, YPKKI telah menerima 42 pengaduan, antara lain meliputi kurangnya informasi dari dokter, operasi bedah oleh tenaga medis yang tidak kompeten, dan kekeliruan pengobatan.
Sementara itu, berdasar catatan TEMPO tentang beberapa kasus di Jawa Tengah, setidaknya ada empat kasus gugatan malapraktek yang melaju ke pengadilan sepanjang 2001. Dan tak satu pun pasien yang memenangi gugatan. Salah satu kasus yang berlarut-larut hingga sekarang adalah yang diajukan Eko Tjiptotartono, konsultan bangunan yang tinggal di Semarang.
Sembilan tahun silam, tepatnya 9 Juni 1991, Sri Wahyuni Handayani, istri Eko, melahirkan di Rumah Sakit Bersalin Bahagia, Semarang. Alih-alih bahagia dikarunia putra, pasangan Eko-Sri justru memanen bencana. Bayinya hanya bertahan hidup 26 jam, sedangkan Wahyuni langsung koma usai bersalin. Sepanjang dua tahun Wahyuni lumpuh total dan hanya sanggup berbaring di ranjang. Kini, Wahyuni mulai bisa berjalan meskipun harus dengan kaki yang terseret-seret.
Prihatin dengan nasib sang istri, dua tahun lalu Eko mengajukan gugatan setelah upaya damai tak membuahkan hasil. Akhirnya, April 2001, majelis hakim memutuskan tidak menemukan kesalahan medis yang dilakukan Hamidun Kosim, dokter yang menangani Wahyuni. Eko, yang tak puas dengan keputusan hakim ini, terus bertekad naik banding.
Namun, hanya sedikit yang bertekad teguh seperti Eko. Seperti diungkapkan Marius Widjajarta, hampir semua korban malapraktek yang dia temui enggan beperkara ke pengadilan. Umumnya mereka segan menghadapi proses hukum yang melelahkan. Bahkan, "Ada juga yang takut karena diteror dokter atau rumah sakit," katanya.
Nah, karena keengganan beperkara itu, Marius yakin persoalan malapraktek seperti fenomena gunung es: kasus yang terangkat ke permukaan jauh lebih sedikit dari kejadian sesungguhnya.
Mardiyah Chamim, Hadriani Pudjiarti (Jakarta), dan Bandelan Amaruddin (Semarang)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini