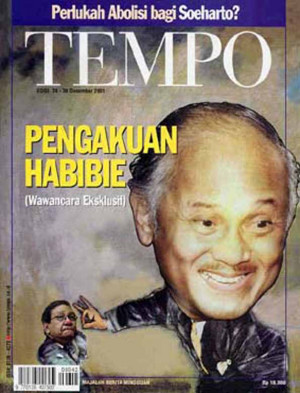Dani Wahyu Munggoro*)
*) Peneliti Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin)
Banjir kembali menyapu kampung-kampung di Jawa bagian selatan dan Sumatra bagian barat sepanjang tahun 2001. Ia bukan hanya meluluhlantakkan kekayaan alam dan harta benda, tapi juga merenggut banyak nyawa. Banjir Kebumen menewaskan 11 jiwa, sedangkan banjir Nias meminta korban 107 jiwa. Ini baru cerita dua kabupaten. Padahal puluhan kabupaten di Indonesia adalah wilayah rawan banjir.
Mengapa banjir semakin heboh sepanjang tahun 2001? Sebuah siklus perubahan iklim? Atau pertanda carut-marutnya cara kita mengeruk kekayaan alam? Jawabannya, ada benang merah antara politik ekonomi kehutanan dan bencana banjir.
Suatu hari di tahun 1971, Presiden Soeharto, saat meresmikan Pasar Klewer di Solo, menyatakan Indonesia akan membayar utang-utangnya dengan menjual kekayaan hutan. Soeharto ternyata tidak main-main. Bagi Soeharto, pemanfaatan hutan adalah fresh money bagi pembangunan
Ia memberikan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 64 juta hektare kepada 500-an perusahaan swasta asing dan nasional. Pembukaan hutan besar-besaran masa itu tidak dibarengi aturan hukum dan kecakapan yang memadai. Aturan-aturan hukum dan kebijakan pun tanpa melalui penelitian dan konsultasi publik, cukup dengan mencontek Malaysia dan Filipina, yang jelas-jelas pengelolaannya tidak lestari.
Holiganisme Soeharto tidak cukup hanya memberikan HPH kepada para jenderal dan konco-konconya. Ia pun memberikan 30 juta hektare kawasan hutan konversi kepada ratusan perusahaan swasta nasional dan multinasional. Hutan-hutan itu dibangun menjadi perkebunan-perkebunan besar, pertambangan, dan lahan-lahan pertanian baru.
Walau sektor kehutanan mampu meraup devisa US$ 8 miliar per tahun, holiganisme rezim Soeharto itu, menurut data Forest Watch Indonesia (2001), telah membuat negeri ini kehilangan hutan alam seluas 60 juta hektare.
Adakah lengsernya Soeharto menghentikan perusakan hutan? Tidak. Laju kerusakan hutan mendekati 2 juta hektare per tahun. Pada tahun 2000, Pulau Jawa saja kehilangan 350 ribu hektare hutan produksi akibat illegal logging dan penjarahan rakyat (Perhutani, 2001). Lahan kritis dilaporkan telah mencapai 25 juta hektare. Illegal logging terus merajalela.
Maklum saja jika permintaan kayu mencapai 80 juta meter kubik per tahun, sementara suplai hanya sekitar 18 juta meter kubik. Maka, defisit permintaan kayu dipenuhi dengan illegal logging. Ketidakmenentuan kehutanan seperti ini membuat hutan tidak mungkin terselamatkan. Bank Dunia memprediksi, dalam 10 tahun Indonesia tidak punya hutan produksi alam lagi.
Saat ini lanskap alam Indonesia bukan lagi laksana jamrud khatulistiwa, melainkan mosaik yang berisikan padang ilalang, tanah tandus, lahan kritis, tegakan pohon yang carang, erosi tanah, dan sungai-sungai yang semakin dangkal dan kotor. Lanskap ini tidak mampu melaksanakan berbagai tugas ekologinya seperti menyerap karbon dioksida, menyerap air hujan, dan mengatur tata air. Hutan-hutan itu telah mati.
Perubahan iklim global sebagai respons menciutnya hutan-hutan alam dunia dan meningkatnya aktivitas industri di belahan utara bumi telah menimbulkan apa yang disebut gejala El Nino dan El Nina. El Nino, sebagai gejala alam yang ditemukan oleh para nelayan di Amerika Selatan, ditandai musim panas yang panjang dan kering di seluruh Indonesia. Gejala alam ini telah membakar 5,5 juta hektare lahan hutan sepanjang tahun 1997-1998.
Sebaliknya, gejala El Nina menimbulkan curah hujan di atas normal bagi kepulauan Indonesia. Gejala inilah yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di sepanjang pantai barat Sumatra dan pantai selatan Jawa. Dua gejala iklim ini masih sering diperdebatkan, tapi yang semakin jelas adalah bahwa iklim global merupakan sebuah sistem yang kompleks dan chaos.
Sepanjang tahun 2001 Indonesia mengalami triple chaos, yakni kekacauan politik dan ekonomi, kekacauan hutan, dan kekacauan iklim. Kekacauan politik dan ekonomi ditandai runtuhnya sektor industri dan perkotaan, yang menimbulkan tumpahan pengangguran ke kampung-kampung yang pada akhirnya merambah kekayaan hutan (illegal logging).
Kekacauan hutan ditandai dengan munculnya izin-izin baru di bidang kehutanan dan perkebunan skala menengah dan kecil. Konflik antara pihak-pihak yang legal dan kuasi legal dalam bisnis perkayuan menimbulkan illegal logging dan illegal export. Kekacauan iklim ditandai dengan ketidakpastian bercocok tanam dan panen hasil tanaman bagi petani. Akibatnya, petani lokal dan petani migran pun ramai-ramai merambah hutan.
Masyarakat Nias menyatakan, pulaunya tidak pernah mengalami banjir selama 60 tahun terakhir. Barulah setelah kebun-kebun nilam menggantikan hutan-hutan di perbukitan, banjir datang. Demikian pula masyarakat Kebumen, mereka menceritakan banjir kecil adalah hal yang biasa. Namun, banjir seburuk ini baru terjadi kali ini. Boleh jadi kejadian ini dipicu oleh kegiatan peremajaan pohon-pohon pinus milik Perhutani di sepanjang perbukitan Menoreh.
Ketiga ketidakmenentuan ini berpuncak pada tahun 2000, dan sepanjang tahun ini kita memetik buahnya berupa panen banjir dan panen longsor.
Indonesia harus belajar dari sejarah. Pertama, belajar dari Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), yang berani mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan jati di Jawa selama 30 tahun mengingat kondisi hutan yang amat buruk akibat perluasan industri galangan kapal.
Kedua, belajar dari Thailand. Pemerintah Thailand melarang kegiatan logging pada 10 Januari 1989. Kebijakan ini sebagai respons bencana banjir pada tahun 1988 yang menewaskan 350 jiwa dan menimbulkan kerugian material sebesar Rp 1,2 triliun.
Kedua pelajaran penting ini semestinya diambil oleh pemerintahan Megawati sebelum korban semakin banyak dan kerugian semakin besar. Kita tidak mampu keluar dari kubangan banjir bila moratorium penebangan hutan alam dan pluralisme kehutanan tidak dipilih menjadi agenda politik kehutanan mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini