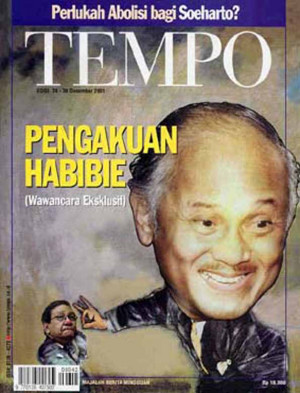Seberapa tinggi gunung es kekeliruan medis di Indonesia? Sayang, tak ada satu pun data komplet yang tersedia sehingga potret sang gunung es hanya muncul samar-samar.
Namun, Iwan Dwiprahasto dari Unit Biostatistik dan Epidemiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yakin bahwa gunung itu menjulang cukup tinggi. "Cukup banyak dokter dan perawat yang mengabaikan prosedur standar medis," kata Iwan di tengah sebuah seminar yang diselenggarakan Persatuan Rumah Sakit se-Indonesia (Persi), awal November 2001.
Contoh yang paling sederhana adalah tindakan melubangi tabung infus dengan jarum. Sepintas, langkah untuk memudahkan keluarnya cairan infus ini cukup masuk akal. Betulkah demikian? Ternyata tidak. "Membolongi infus sama saja mengundang masuk kuman penyakit. Ini juga termasuk kategori medical error," katanya.
Memang, kekeliruan medis yang sering kali berujung pada malapraktek muncul tanpa kesengajaan. Hal ini biasanya terjadi pada dokter favorit dengan pasien melimpah. Ketatnya jadwal melayani pasien membuat dokter tak lagi sempat memantau perkembangan kedokteran mutakhir. Padahal banyak sekali tindakan medis yang telah ketinggalan zaman.
Misalnya, episiotomy atau pemotongan dinding luar vagina perempuan saat pertama kali melahirkan. Langkah ini tadinya dipercaya sebagai tindakan penting guna memudahkan persalinan. Tapi kini episiotomy sudah ditinggalkan karena terbukti justru mengundang infeksi yang membahayakan kandungan. Nyatanya, "Masih banyak dokter kita yang me-lakukan episiotomy," kata Iwan.
Namun, Iwan membesarkan hati, sesungguhnya medical error bukan hanya monopoli negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara maju. Bedanya, medical error di negara maju jauh lebih terekam rapi karena adanya industri asuransi yang memantau akuntabilitas pelayanan kesehatan.
Di Amerika Serikat, misalnya, kerugian akibat kekeliruan medis diperkirakan menggiring kematian hampir 100 ribu pasien tiap tahun. Sementara itu, pemerintah Inggris harus menyiapkan 8 miliar pound (sekitar Rp 128 triliun) per tahun guna membayar ganti rugi medical error. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus Harold F. Shipman, dokter bedah yang diduga menyebabkan kematian 15 pasien wanita—di antaranya karena keliru mengambil organ ginjal yang sehat.
Nah, berangkat dari tingginya medical error, sejak 1998 Departemen Kesehatan Inggris mengembangkan kerangka kerja (framework) clinical governance. Konsep ini mengharuskan setiap tindakan medis bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Operasi bedah, misalnya, harus didukung parameter yang didapat dari bukti gambar peralatan canggih, semisal rontgen, CT Scan, dan USG. Jadi, "Dokter tak bisa memutuskan operasi hanya berdasar pengamatan mata telanjang atau perasaan," katanya.
Menurut Iwan, saat ini Departemen Kesehatan juga tengah merintis penerapan clinical governance di Indonesia. Tentu saja hasilnya belum bisa ditunggu dalam sekejap, dan mutlak menuntut peran semua lapisan. Para dokter, misalnya, sebaiknya terus memutakhirkan ilmunya. Sedangkan pasien pun hendaknya tak gampang minta operasi bedah caesar tanpa indikasi jelas. "Sebab, setiap sayatan pisau bedah pasti punya dampak yang serius bagi tubuh," kata Iwan.
M.Ch.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini