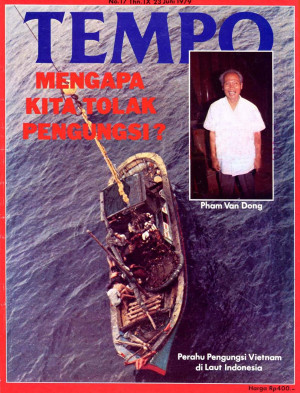BANYAK hal yang menarik dari masyarakat Betawi. Sementara mereka
meneruskan hidup dengan cara yang lama -- Jakarta makin berubah.
Lapangan baru dengan kemungkinan yang lebih baik berkembang.
Arus urbanisasi pun tak bisa dibendung.
Sering dikhawatirkan penduduk Betawi asli akan merasa asing di
daerah kelahirannya sendiri. Tetapi syukurlah mereka memiliki
hati terbuka, sehingga sampai sekarang kerukunan dapat
dipertahankan. Seperti kata Mutridi bin Maisin, petani salak
berusia 70 tahun di Condet, Balaikambang: "Saya tidak merasa
terdesak. Orang memang lain-lain, ada yang dari Jawa, Sumatera,
Ambon, tetapi sukunya kan sama!"
Madjuk, 47 tahun, asal Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, sudah
sejak belasan tahun yang lalu punya "kereta benhur". Ini istilah
baru buat gerobak kuda yang mengangkut bahan-bahan material
bangunan dan kadang-kadang juga diisi dengan meubel. Daerah
operasinya sampai ke Tebet, Senen atau Kota, yang memerlukan
setengah hari perjalanan. Biasanya dilakukan bersama-sama
gerobak temannya, sehingga merupakan konvoi. "Yah mulanya seneng
juga," kata Madjuk merenungi pekerjaannya.
Kongkow-Kongkow
Usaha Madjuk mulai terganggu tatkala polisi mengadakan
penertiban. Beberapa daerah ditentukan tidak boleh dijamah
gerobak. Sementara itu pabrik colt dan honda dari Jepang
menyerang terus dengan alat pengangkutan yang lebih praktis.
"Kalau kita angkut dari Gandaria ke Pondok Pinang harus Rp 2000
per kubik kayu, colt berani Rp 1.500 Kan payah. Apalagi mereka
angkut sejam, kita sampai tiga jam lebih," kata Madjuk sambil
mengerenyitkan keningnya.
Untuk menahan serangan itu, Madjuk kemudian tidak hanya mangkal
di tempat penjualan material. Ia juga nempel di toko meubel.
Lemari atau bufet yang tidak bisa ditancap dengan beca, ia oper.
Untuk sementara memang lumayan. "Tetapi orang beli perabot kan
kagak sehari-hari ada. Malah sering sehari nggak ngangkut,"
ujarnya. Akibatnya Madjuk terpaksa puter dia punya otak.
Walhasil dia putuskan merangkap kerja dengan jual es. Dengan
biaya Rp 30 ribu, dibuatnya sebuah warung. "Kalau warung enak,
bisa buat kongkow-kongkow," kata Madjuk. Tapi nasib, hanya tiga
bulan warung itu gulung tikar.
Seperti kebanyakan orang Betawi Madjuk kemudian menoleh kepada
"rumah petak"nya. Karena keadaan tambah rawan, coba-coba
dikontrakkan. Malang sampai sekarang belum ada yang sudi.
Kenapa? Ya biasa, tidak ada yang cocok. Tetangga Madjuk sendiri
mulai tidak betah bersebelahan gara-gara kudanya merengek setiap
malam. Belum tahi dan kencingnya yang pesing. "Dalam keadaan
begitu kuping saya tidak boleh dengerin omongan tetangga,
salahsalah bisa berantem," ujarnya.
Menjelang lebaran, tahun lalu, akhirnya kereta benhur itu
dilego. "Supaya tidak bikin ribut, lagian juga untuk modal,"
kata Madjuk. Ia dapat Rp 75 ribu. Hutang-hutang dibereskan. Beli
sepeda dan pakaian untuk anak-anaknya. Lalu ia mulai bangun
pukul 3 subuh, langsung pergi ke Pondok Labu membawa keranjang
besar di kiri-kanan sepeda. Dibelinya pepaya, kacang panjang
terong, lalu dibawa ke Pasar Cipete. Demikianlah anak Betawi ini
menyulap dirinya dari pengusaha gerobak menjadi pedagang sayur.
Untungnya bisa mencapai Rp 1.000 sehari."Tapi buat rokok saja
sudah Rp 500, dapur Rp 1.000, lama-lama habis aja itu modal,"
katanya dengan sedih.
Kebijaksanaan baru menyusul. Sepeda ditukar dengan yang lebih
murah. Uangnya dipakai untuk jualan pisang goreng. Tapi bangkrut
juga, karena anak-anaknya ikut nyomot, sehingga dagangan habis
dimakan sendiri. Untung ada tetangga ngajak jadi tukang kuli
bangunan. Hasilnya dia pakai modal jadi tukang sayur kembali. Ia
memborong kebon kangkung Rp 3.500, lalu dijual dan bisa mencapai
Rp 6.000. Lumayan juga. Sebagai tambahan kadang-kadang ia
memburuh, mengerjakan sawah orang.
Sebagai orang Betawi, Madjuk sudah berjuang dan bertahan dengan
ulet. Ia juga tidak fanatik. Seandainya Tuhan mengijinkan ia
dapat menerima menantu orang mana saja -- tak perlu harus
Betawi. Hanya saja, belakangan ini muncul gagasan untuk menjual
rumahnya. Ini penyakit umum. Ia ingin mengungsi ke luar kota.
Kalau bisa ingin punya tanah sedikit untuk menanam sayur, lalu
menyuapi orang-orang di Jakarta dengan daun-daunan segar. Madjuk
tentulah bukan orang Betawi pertama yang punya gagasan itu.
Barangkali sudah banyak yang mendahuluinya pindah ke luar kota,
mencari daerah yang lebih aman buat keluarganya. Satu segi yang
menyedihkan buat orang Betawi.
Tapi tidak semua orang Betawi seperti Madjuk. Halimah dan
suaminya engkong Kasak -- penjual kerak telor, ingin bertahan.
"Jual rumah itu malah bikin morat-marit saja. Pegang uang 'kan
cepat hilang," ujarnya. Biar bagaimanapun keadaan rumahnya, ia
berusaha untuk tetap di tempat. Rumah yang doyong diperbaiki,
sambil berusaha, tawakal dan sabar. "Kita memang nggak keturunan
orang kaya," katanya.
Halimah dan Kasak yang tinggal di bilangan Tanah Abang, sudah
hidup bersama selama 50 tahun. Halimah mengaku orang Betawi asli
yang dipungut oleh orang Cina. Sedangkan Kasak memang keturunan
Tionghoa. Hidup mereka bergantung kerak telor. Untuk itu engkong
Kasak yang berusia 80 tahun memang orang yang beken. Sejak zaman
Belanda namanya sudah harum dalam bisnis kerak telor. Hanya
zaman Jepang ia berhenti. Begitu Jepang pergi dia mengangkat
pikulan, kembali.
Kerak telor dibuat dari ketan yang direndam seharian. Tambah
lada, cabe, bawang goreng, kelapa goreng, vetsin, udang kering
dan tentu saja telor. Digoreng di atas anglo kemudian ditaburi
bumbu. Harganya Rp 250 satu bungkus. Di sekitar gerbang Jakarta
Fair, selalu bisa dijumpai pedagang beginian. "Tapi kerak telor
bapak memang mahal sedikit," kata Halimah. Para pengamat kerak
telor memang mengatakan telor Kasak rasanya memang lebih enak
dari yang lain-lain, karena lebih asli. Ada kerak telor yang
disimpan semalam sudah basi. Jualan engkong Kasak dijamin
mutunya.
Dua puluh tahun lalu ngkong Kasak masih ngider membawa
pikulannya, sejak magrib sampai tengah malam. Sekarang ia sudah
tidak kuat. Kini dagangan diangkut dengan becak ke Kebon Kacang
I dibantu oleh seorang anggota keluarga bernama Unus. Mereka
nangkring di samping tukang goreng ayam. "Tengah malam, kalau
lampu yang jualan ayam goreng mati, kita juga ikut pulang," kata
Halimah.
Halimah yang berusia 77 tahun sempat mengandung 12 kali. Tapi
karena keguguran, atau meninggal, anaknya tinggal tiga. Semuanya
sudah berkeluarga. Sekarang ia punya cucu 15 dan buyut 2.
Penghasilan keluarga menurut Halimah lumayan untuk hidup. "Hidup
kan Tuhan yang ngatur, kita nggak berkuasa," ujarnya.
Demikianlah ia berjualan dengan hati tenang. Kasak sendiri
sebenarnya sudah tidak kuat lagi. Ia pernah terkulai di bangku,
lalu-byur jatuh ke dalam got karena ngantuk. Untung gotnya
kering. Toh orang tua itu selalu berada di pos. "Istilahnya buat
pajangan," kata Halimah. "Soalnya banyak langganan senang lihat
bapak, ada juga yang suka kasih uang rokok sampai Rp 1.000."
Tidak Mampu
Halimah dan Kasak hidup pas-pasan. Mereka tinggal dalam sebuah
rumah yang selalu kebanjiran kalau hujan. Pada saat-saat seperti
itu, kalau ada mobil lewat, Halimah merasa seperti nonton ombak
di Cilincing. Ada niat untuk memperbaiki, tapi ia tidak mampu,
di samping itu selalu sibuk. "Tak apa, syukur-syukur aja bisa
hidup, rumah bocor itu biasa, gedung saja bisa bocor, apalagi
yang gubuk," ujarnya menghibur diri. Walhasil, penduduk Betawi
ini tetap berada di tempatnya sampai sekarang.
Di Condet, seorang pemilik kebon salak bernama Dullah juga
berniat untuk bertahan. Lelaki Betawi usia 40 tahun ini mewarisi
sekitar 1400 meter tanah --kebon salak dan duku -- dari orang
tuanya. Ia pernah merantau ke Indramayu untuk mencari hidup.
"Ternyata tidak cocok. Di mana-mana tidak cocok kecuali di
Condet," ujarnya. Kenapa? "Yah di sini kita sudah mengenal
daerah kita. Bahkan teman-teman yang sudah pindah dari sini,
akhirnya cari makannya juga di sini," kata Dullah.
Bagi penduduk Betawi yang tinggal di Condet, mungkin bergantung
dari kebon salak saja tidak cukup. Kalau musim hujan, salaknya
memang bisa menghasilkan sampai dua kali setahun. Tapi kalau
panas lebih banyak, kebon tak bisa banyak diharapkan. Untung di
situ ada kali. "Jadi kalau hujan, kita hidup dari salak. Kalau
panas, kita turun ke sungai mengeduk pasir," kata Mutridi bin
Maisin.
Selain tidak merasa terdesak, si tua Mutridi juga merasa sangat
bangga dengan daerahnya, karena ia merasa gampang mencari makan.
"Sekarang keadaan lebih baik, kita tidak lagi digencet Belanda.
Meskipun harga beras satu liter Rp 150, cari barang dua liter
satu hari bisa. Tapi dulu waktu harga beras hanya 6 sen banyak
orang yang tidak makan," katanya mencoba membandingkan. Apa iya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini