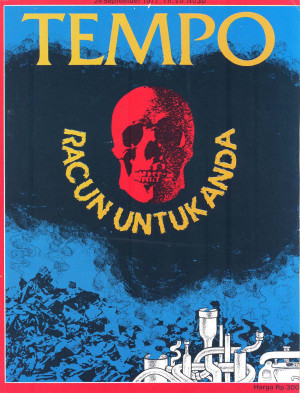WAKTU film India Boot Polish menaburkan air mata di tahun-tahun
50-an, kita masih hanya terlibat secara emosionil. Anak-anak
kecil yang mencari-nafkah sebagai tukang semir jalanan itu
rasanya masih merupakan gambaran kepahitan hidup masyarakat
lain. Maklum: jangankan sebagai sumber nafkah. Sepatunya sendiri
sebagai barang pakai sehari-hari masih merupakan benda yang agak
tuan-tuanan.
Tapi sekarang, hampir 20 tahun sesudah itu, duilah. Di mana-mana
terlihat anak-anak menggantungkan kotak kecil di pundak. Mereka
bertebaran di stasiun, menduduki restoran, muncul di
tempat-tempat ramai. Setiap sepatu tidak luput dari perhatian.
Mereka mendesak. Kadangkala merayu dan merengek. Di Jakarta,
yang paling sering mereka ucapkan adalah: "Oom, untuk ongkos
sekolah."
Jebolan Sekolah Teknik
Benarkah mereka sekolah? Ya. Ada yang benar-benar masih sekolah.
Iwan yang kecil gepeng, dijumpai Linda Djalil dari TEMPO di
pinggir jalan, duduk di kelas 2 SD. Jangan main-main: ia sudah
memiliki masa kerja 2 tahun - sama sekali tidak atas suruhan
atau paksaan orang tua. Ia bisa meyakinkan itu. Teman-teman
sekelasnya pun pada tahu, setiap hari ia mencantelkan kotak
semir (ia sendiri menamakannya "kotak wasiat"). "Saya tidak
malu," ujarnya dengan mata yang tajam. "Tapi untuk diberitahukan
pada ibu guru, ya masih malu juga."
Sudiman, 5 tahun lebih tua dari Iwan, sebaliknya. Ia nyemir
sepatu sejak 2 tahun lalu memang semata-mata untuk nafkah. "Saya
lari aja ke sini dari Surabaya. Kerja apa saja, pokoknya dapet
duit. Tapi nggak nyangka jadi tukang semir," kata anak yang
kelihatannya kumal itu. Scbcnarnya ia sudah sempat rnencapai
kelas 2 Sekolah Teknik. Tapi, biasa, karena biaya tak ada, ia
berhenti. Apalagi ia mulai mendapat kewajiban menghidupi orang
tuanya yang tidak bekerja lagi. Bersama salah seorang kakaknya
yang menjadi tukang parkir, ia mencari nafkah di Jakarta dengan
cara hidup tak menentu.
Untuk orang yang sendirian, untuk seorang anak kecil,
penghasilan berburu sepatu memang agak lumayan. Dengan tarif Rp
50 rata-rata, Iwan - sanggup mengumpulkan Rp 500 sehari. Artinya
10 pasang kaki manusia. Maklum ia hanya bekerja antara pukul
8.00 sampai pukul 12.00. Karena sesudah itu, sore hari ia harus
berhadapan dengan sepatu ibu guru - bukan untuk disemir,
meskipun ia sering melirik-liriknya. Kalau lagi liburan, angka
pendapatan kadang membiak jadi Rp 750-Rp 1.000.
Lain halnya dengan Sudiman yang bekerja sejak pukul 8 pagi
sampai 12 malam. Dengan medan operasi seluas daerah Jalan
Sabang-Sarinah, ia mampu mengumpulkan Rp 1.500 satu hari. Tak
heran kalau ia bisa secara tetap makan 3 kali dengan biaya Rp
300. Bahkan asap rokok pun bergelung di mulutnya. Bajetnya: Rp
125 satu hari.
Nasi Pakai Tempe
Setiap bulan, Sudiman menjadi orang baik yang mampu balas budi.
Dengan membawa Rp 2.000, ia menjenguk orang tuanya. Pemberian
yang sebenarnya kecil sekali ini menjadi sangat luhur, kalau
mengin&at tak pernah ada bantuan dari kakak kandungnya sendiri -
seorang dokter. Ini mungkin disebabkan karena orangtua dan kakak
kandung itu terlibat persoalan keluarga yan memang pelik
dipccahkan. Satu hal yang menolong Sudiman adalah: kepintarannya
untuk tidak mengeluarkan biayakalau naik kereta api. Boleh
dilaporkan kereta yang dipakainya selalu KA Gaya Baru. Tapi
bagaimana caranya luput terus dari kondektur selama 2 tahun,
boleh ditiru. "Bilang saja, kasihan pak, saya orang nggak
punya," katanya sambil tertawa.
Tidak mau kalah dengan Sudiman, Iwan juga mencoba memberi arti
pada perolehannya. Ia mengaku sangat ketat dan pelit dalam
merencanakan pengeluaran uang. Maklum. Pekerjaannya sekarang ini
dimulai dengan nol. Ia tahu benar bagaimana caranya maju: hemat,
hemat, dan memikirkan hari depan. Iwan ini, sebelum punya kotak
semir sendiri, dulunya membonceng kerja lewat kotak kawannya.
Ia waktu itu berkongsi sambil belajar nyemir: perolehan yang
diterimanya hanya separuh. Karena itu sekarang, setelah memiliki
kotak sendiri, ia selalu menyisihkan uang untuk tabungan.
Seminggu sekali ia pergi ke loket sebuah bank di Pusat
Perdagangan Senen untuk menyerahkan Rp 200. Ini sudah
berlangsung lama. Sekarang sudah lumayanlah banyaknya.
"Jumlahnya saya sengaja nggak tahu," kata Iwan. "Nggak mau
diinget, tahu-tahu nanti udah banyak! Gitu."
Duka pekerjaan semacam ini tentu saja agak kabur. Karena ia
lebih merupakan penyaluran energi, kalau pelakunya anak-anak.
Daripada terbuang dengan sia-sia untuk mengejar layang-layang
putus, atau terlibat jadi pemadat rokok pada saat paru-paru
mereka masih berkembang, atau pokoknya hanya melulu menuruti
hawa nafsu -- ya nafsu anak-anak. Hanya saja kemungkinan
mendapat uang dengan cara menunggu sampai larut malam memang
bisa membuat kesehatan mereka terganggu. Ada kalanya juga
pendapatan itu membuatmereka justru segan ke sekolah. Makanan
pun mereka mulai memilih.
"Makanan sih sederhana saja," bantah Iwan. "Nasi pakai tempe."
Ya, Iwan memang lain. Ia pintar di sekolah. Untuk pelajaran
berhitung ia dapat 8 di rapot. Ini mungkin karena hidup
keluarganya tidak terlalu miskin. Ibunya tidak jarang mampu
memberikan Rp 100 untuk belanja sehari. Ia memburu sepatu
sekedar bisa membebaskan beban sang ibu dari membeli buku
sekolah. Ibu sendiri bekerja sebagai tukang masak dan cuci.
Perempuan yang memiliki 6 anak ini (4 sudah menikah) dan sudah
ditinggal mati suami, malah masih mampu membawa Iwan
sekali-sekali nonton bioskop. Engkongnya sendiri punya pesawat
TV. Jadi ini jenis lain lagi dari anak penyemir sepatu.
Direktur
Apalagi modal tukang semir toh murah saja. Asal berani melawan
rasa malu, dan rasa malu ini memang mengganggu pembangunan. Iwan
membawa semir coklat dan hitam, masing-masing berharga Rp 150
satu kaleng. 2 hari sekali ia harus membeli yang baru. Sekaleng
semir putih, itu seperti yang ada di kotak Sudiman, harganya
lebih mahal -- bisa sampai Rp 450. Tentu saja untuk sepatu putih
tarifnya lain. Apalagi jenis sepatu lain model sekarang: tidak
cukup membungkus kaki - tapi terus naik melllbalut ujung betis.
Itu namanya rezeki. Hanya celakanya kalau kebetulan musim hujan.
Nyemir sepatu tidak hallya berarti.membuat sepatu jadi klimis,
tapi juga mencakar-cakar lumpur. Tak jarang kuku jadi pedas.
Iwan dan Sudiman yang beroperasi di Jakarta sama saja dengan
pemburu sepatu di tempat lain. Seorang tukang semir sepatu yang
diketemukan TEMPO di Stasiun Semut, Surabaya, yang juga pernah
memiliki pengalaman di Jakarta mengatakan nafkah tukang semir
sebenarnya cukup. Ia juga sering mondar-mandir ke Malang untuk
mengantarkan tabungan - buat orang tua. Ia mendapat prioritas
memasuki stasiun karena pada malam hari ia membantu sebagai
penjaga gudang.
Hidupnya ternyata tidak serawan tukang semir sepatu di layar
putih. Mukanya kelihatan gembira. Ia sama sekali tidak terancam
persaingan dengan tukang semir sepatu yang lain, karena ia yakin
sekali pada peruntungannya. "Tapi untuk menjaga apa-apa, saya
terpaksa selalu siap tidak makan sehari-sehari, jadi tidak hanya
tergantung hasil," ujarnya - dengan gembira.
Jangan dikira tukang semir tak punya cita-cita. Sudiman, yang
menumpang hidup di emperan kantor bersama 50 pekerja jalanan,
memang tidak tegas menyatakan ingin merubah nasib. Tapi
bagaimana bisa puas bergabung menjadi kelas bawah bersama
rekan-rekannya tukang parkir, tukang rokok dan calo taksi? Iwan,
sambil menatap seorang tukang besi yang lagi bekerja -- di Gang
Kenanga, Jakarta, di mana ia operasi berkata: "Saya nanti ingin
jadi direktur." Apa artinya, direktur? Anak itu senyum-senyum.
Katanya: "Pokoknya orang kaya!" ....
Tentunya anda tahu, siapa musuh tukang semir. Anak-anak ini
selalu memandang ke bawah - ke arah kaki - setiap ada orang
datang. Dan alangkah kecewanya mereka, kalau si tuan ini
ternyata pakai sepatu kain. Atau sandal Jepang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini