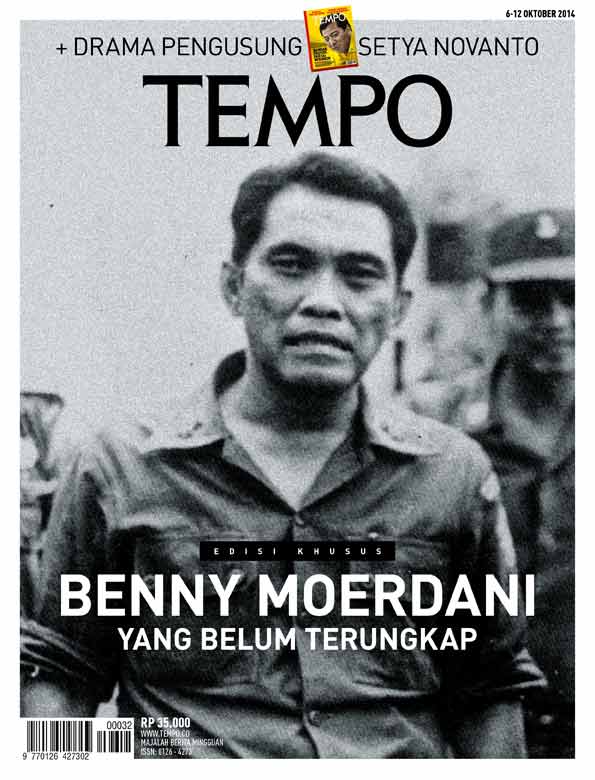Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Halal adalah harga mati bagi Rini Rakhmawati. Label halal dari Majelis Ulama Indonesia adalah patokannya dalam memilih produk makanan, obat, dan kosmetik. Kesetiaan menerapkan prinsip halal membuat Rini ogah menebus resep dokter yang belum berlabel halal MUI. "Kalau dikasih resep obat yang belum tentu halal, obat itu tidak aku minum," katanya Rabu pekan lalu. Bahkan, ketika melahirkan putra pertama pada akhir September lalu, ia tak menyentuh vitamin dan obat pelancar air susu dari dokter di rumah sakit. "Cukup buah dan sayur saja untuk memperlancar," ujar Rini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo