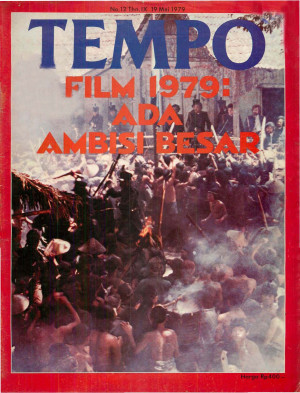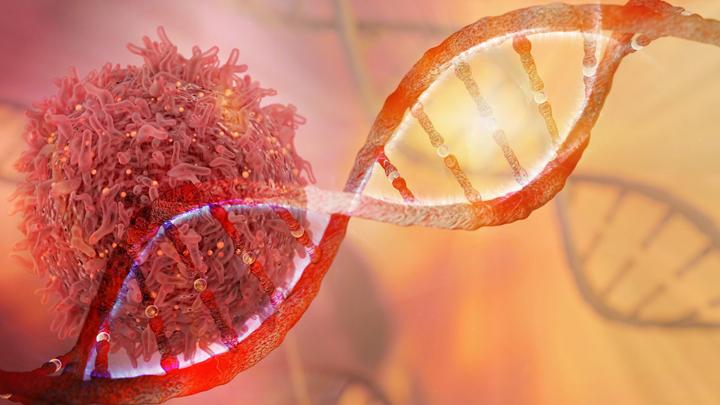JURI Festival Film Indonesia pernah mengajak orang-orang film
"mencari wajah Indonesia". Sutradara, pemain-pemain juga para
penulis skenario mengejap-ngejapkan mata lalu menelan ludah.
Mereka mengerti, faham, tapi mungkin juga bosan. Soalnya
produksi film nasional memang hasil cakaran tangan mereka. Cuma
saja sering dilupakan, mereka yang langsung menguasai arahnya,
adalah para produser. Golongan ini kata orang terdiri dari kaum
pedagang tulen.
"Pokoknya sampai nanti kalau masyarakat tinggi penilaiannya pada
film, baru kami akan membuat film-film bermutu. Sekarang biarlah
kami disebut produser film konyol," kata Thamin dari Adhiyasa
Film terus terang. Produser ini membuat film untuk masyarakat
tertentu yang berkubang di bioskop-bioskop kelas kambing.
Kesenangan-kesenangan kelompok itulah yang digarapnya, sebagai
acuan arah produksi. Akibatnya ia tidak pernah berusaha untuk
bikin film berdasarkan cerita novel yang kwalitasnya dapat
dipertanggungjawabkan. "Mana ada sih novel yang konyol, sedang
film kita selalu konyol," ujarnya.
Cinta
Adhiyasa adalah sebagian dari produser film yang lahir akibat
adanya SK Menteri Penerangan (Mashuri) no. 53 dahulu. Pada
mulanya ia adalah importir. Produksi film memang akhirnya hanya
merupakan semacam tanda kutip kerja paksa, untuk meloloskan 3
film impornya. Idealisme dari produksinya tentu saja supaya
perdagangan impor film terus licin. "Pokoknya asal perusahaan
tidak rugi saja, itu sudah cukup," katanya tenang-tenang.
Insantra Film yang sama idealismenya dengan Adhiyasa menjelaskan
bahwa membuat film sebenarnya "sukar" rugi. "Asal sedikitnya
tiga buah film," kata Yudha Suryoso mewakili Insantra. Produser
ini pernah membuat film cinta dengan biaya Rp 80 juta, yang
kemudian untung tiga kali lipat. Tapi rata-rata laba filmnya
yang lain tidak begitu besar. Berapa? "Dua puluh lima juta
untuk satu produksi, sudah lumayan," ujarnya.
Baik Thamin maupun Suryoso menyetujui syarat untuk menjadi
pedagang film yang baik yaitu sedikitnya tiga film harus
diproduksi dalam satu tahun. Investasi ini makan waktu 6 sampai
9 bulan sebelum membawa hasil. Kurang dari satu film akan rugi,
karena mereka berproduksi dengan kredit bank dengan bunga tiga
prosen yang jalan terus. Kalau produksi bisa sambung menyambung
sampai film ketiga selesai digarap, film pertama sudah memasuki
"musim bunga". Paling tidak setiap film bisa membawa keuntungan
Rp 15 juta -- menurut Adhiyasa.
Tetapi itu memerlukan jaringan penjualan yang baik. Karena tidak
semua film begitu jadi langsung laku. Kadang-kadang harus
dijajakan. Babak ini merupakan soal yang cukup rumit, setelah
begitu banyak keruwetan dalam proses produksi.
Untuk melicinkan bisnis dengan kwalitas miring itu produser
harus banyak akal. Suryoso misalnya mengaku punya taktik
mengajak para wartawan untuk berpartisipasi sebagai konco.
Artinya kadangkala ia bisa titip pesan-pesan khusus, sambil
tersenyum penuh arti. "Bung, kritiklah film saya, tapi kalau
terlalu jelek lebih baik tidak usah ditulis. Kecuali kalau
menulis beritanya saja. oke?"
Sementara itu kuping pun terpaksa ditajamkan ke arah sensor.
Setiap kali berproduksi, dia selalu memperhitungkan agar jangan
sampai keserempet gunting. Caranya gampang. Setiap saat harus
sedia waktu untuk kongko-kongko dengan para anggota sensor.
Menanyakan film apa yang bisa lancar dan adegan bagaimana yang
kira-kira pasti selamat. Jadi praktis para anggota sensor itu
menjadi sutradara bayangan atau supervisor di balik layar. Ini
juga sebagian dari bukti bahwa film Indonesia tidak hanya
tergantung pada para sutradara, bintang atau skenarionya. Setiap
produksi, terpaksa dijejalkan unsur "pendidikan" di samping
unsur-unsur "komersial", tepat atau pun janggal.
"Tidak benar produser bergelimang uang dan wanita," kata Thamin.
Suryoso melanjutkan bahwa di samping uang, wanita merupakan
persoalan serius seorang produser. Soalnya menurut dia bukan
hanya masyarakat, tapi juga bintang film sendiri menganggap
produser dikelilingi wanita. Mereka menganggap seakan-akan
produser bisa dijinakkan dengan tubuh kaum hawa. Sekali
peristiwa muncul calon bintang yang melirik-lirik genit dan
langsung mengatakan ia bersedia dicoba apa saja. "Itu ancaman
buat produser. Kalau wibawa sudah turun, kebangkrutan di ambang
pintu," kata produser itu.
Tatkala SK Menteri No. 53 masih berlaku, tak kurang dari 137
orang produser yang tercatat. Sepuluh prosen di antaranya
pribumi, sisanya India dan keturunan Cina. Dari sepuluh prosen
pribumi banyak yang sebenarnya bukan produser sejati. Mereka
hanya pajangan untuk cukong yang bersembunyi di belakangnya. Ada
juga yang lahir dan berstatus sebagai pemborong untuk
melaksanakan tugas para importir film yang tidak berpengalaman
berproduksi sendiri -- hanya untuk memenuhi SK Menteri.
Produser Murni
Sekarang setelah film seret, tak tahu berapa produser yang telah
mampus. Salah satunya adalah Tuty Mutia dari Tuti Mutia Film.
Wanita itu kita kenal sebagai produser murni -- artinya
berproduksi bukan hanya untuk mendapatkan jatah impor. Tapi
sejak tahun lalu ia berhenti. Kenapa? "Apalagi kalau bukan
karena nggak ada duit," kata Tuty.
Wanita ini telah membuat film-film antara lain Anjing-Anjing
Geladak, Laki-laki Pilihan, Semalam di Malaysia, Prahara, Ita
Anak Pungut, Yang Jatuh di Kaki Lelaki dan Lonceng Maut.
Sekarang ia terjun menjadi pemain. "Jelas lebih enak main,"
katanya membandingkan. "Untuk jadi produser banyak hal yang
mesti difikirkan. Terutama pemasarannya."
Tuty terus terang mengaku lemah di bidang pemasaran. "Kenop-15
sendiri tidak banyak pengaruhnya. Lagi pula mosok hal itu yang
dipakai alasan terus-terusan kenapa film kita lesu," ujarnya. Ia
mengatakan produser murni sulit bersaing dengan para importir
yang banyak menguasai cara pemasaran dan terutama karena mereka
memiliki bioskop. "Karena itu Perfin yang mengatur peredaran
film nasional mesti ditunjang sepenuhnya untuk kepentingan film
nasional dan produser murni," katanya berkampanye.
Thamin dari Adhiyasa tak sependapat dengan Tuty. Meskipun
importir, ia merasa babak pengedaran film sesuatu yang rumit.
Para distributor harus dipikat terlebih dahulu dalam "malam
perdana". "Seringkali juga distributor tidak sudi, terpaksa
pengedarannya digenjot sendiri," kata Thamin. Ini berarti harus
ada promosi dengan biaya tidak kecil. Apalagi kalau harus
menunda untuk menjaga jangan sampai bentrok dengan film impor
sejenis yang mungkin lebih kuat. "Kembali uang bisa terlambat
sampai sekitar satu tahun," katanya.
Berbeda dengan Tuty Mutia, Sutopo lladi dari bagian produksi
Safari Film mengaku produksi Safari sampai sekarang tetap
lancar. Perusahaan ini sudah membuat 19 buah film. Mereka sempat
meledak dalam beberapa produksi antara lain Bing Slamet Cowboy
Cengeng dan Kampus Biru. "Mungkin karena modal Safari kuat dan
tidak tergantung dari kredit bank," kata Sutopo. Tapi ia sempat
menyebut juga salah satu film Safari terakhir yang sampai
sekarang tak lolos sensor, meskipun sudah menelan biaya Rp 150
juta. "Secara bisnis itu jelas rugi. Kalau modal tidak kuat,
pasti gulung tikar," kata Sutopo.
Bencana terganjal di sensor setelah susah payah kerja tidak
hanya menimpa Safari. Bersamaan dengan film Safari ada dua film
lain yang juga ditolak yang tentunya menyebabkan produser bisa
nangis. Mau diedit lagi stok tidak ada. Mau diperbaiki, para
artis entah di mana, biaya tambah sedang sensor belum tentu juga
licin. Ini berarti bahwa skenario lolos masih belum ada jaminan
film lancar. Main mata dengan pihak sensor harus terus
dilancarkan. Barangkali "wajah Indonesia" mcmang ada di kamar
sensor pada saat ini.
"Tambah lama saya jadi tambah takut bergerak di film ini," kata
Tuty Mutiah mengeluh. "Berkali-kali saya dapat pengalaman yang
tak menggembirakan serta tahu betul betapa rumitnya segala
urusan." Ia bermaksud dalam satu dua tahun mendatang ini tetap
tidak berproduksi. Tak kurang dari 7 produksi yang diikutinya
sebagai pemain. Untuk itu ia mendapat satu sampai sepuluh juta
untuk satu film. Jumlah yang memang menggiurkan juga mengingat
produser hampir selalu terlibat dengan perang urat syaraf,
meskipun barangkali uangnya lebih banyak.
Perang urat syaraf juga pernah dialami oleh almarhum Usmar
Ismail dan almarhum Brigjen Sofyar ketika bekerja sama dengan
perusahaan Itali membuat film di Bali. Kedua produksi itu
sama-sama berkepanjangan, sehingga lebih banyak merupakan arena
benturan antara produser pribumi dengan produser Itali. Film
Usmar kemudian tak sempat beredar di Indonesia. Sedangkan film
Sofyar tidak begitu laku. Padahal entah berapa duit sudah keluar
untuk semua itu.
Tentu saja produser akan ramai-ramai memampuskan dirinya kalau
memang dunia ini memang lebih banyak duka. Buktinya sampai
sekarang masih ada saja yang mau berproduksi. Dan untunglah
tidak semuanya ngebet memperdagangkan "selera rendah" sekelompok
penonton. Mungkin karena memang punya sedikit idealisme,
kegendengan, atau juga kebetulan. "Kami tidak menekankan faktor
komersialnya saja. Dipikirkan juga tema-tema yang punya pesan,"
kata seorang produser -- meskipun kedengarannya sulit dipercaya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini