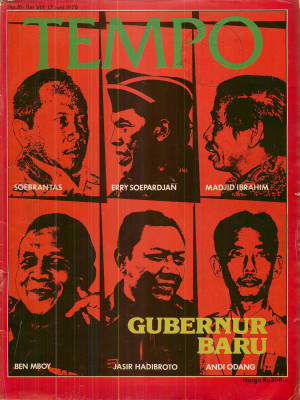DARI 40 ribu rakyat Aceh Barat yang diobrak-abrik banjir
pertengahan Mei yang lalu, sudah ada yang mencoba tegak kembali.
Dengan hati yang perih mereka menyaksikan rumah ladang, kebun,
lumbung-lumbung, serta mungkin juga hari depan, dikeremus dengan
ganas. Sambil memikirkan apa yang bisa dimasukkan ke mulut,
mereka menegakkan tiang membangun gubuk sementara. Dan para
petani yang sudah bertekad tidak menyerah berusaha mencari bibit
untuk mulai menanam lagi.
Sapiyah, Zainal dan Kasno mengadu kepada Darmansyah dari TEMPO:
betapa dahsyatnya bencana itu. Kasno, petani usia 58 tahun yang
telah 40 tahun tinggal di Desa Prowodadi, Kecamatan Kuala, tak
pernah melihat banjir sebuas itu. Krueng Meureubo, sungai itu,
paling hanya muntah sebatas tulang kering di kaki. Itupun tak
pernah deras. Tapi kini Kasno sampai-sampai memikul isterinya --
Suparti -- di pundak dan memanjat pohon kelapa. "Mungkin ini
pertanda dari Tuhan atas kita-kita ini," kata orang tua asli
Wonogiri itu.
Kuli Kontrak
Kasno termasuk beruntung karena mulai bertindak tatkala air baru
menggerayangi lantai rumahnya. Ke-4 orang anaknya cepat-cepat ia
ungsikan ke rumah adiknya di Kompleks Perkebunan Socfindo. Waktu
ia kembali bersama isterinya untuk menyelamatkan harta benda,
ternyata air sudah menjamah meja dan tempat tidur. Ia masih
mencoba berbuat sesuatu -- tapi kemudian sebatang kayu besar
hanyut menghantam tubuh rumah. Dinding samping jebol. Letaknya
bergeser. Dan petani tua ini jadi keder juga -- apalagi air
meluap cepat mencapai ketinggian 1,5 meter. Untung dekat
rumahnya ada 3 batang kelapa berdekatan. Maka di sanalah Kasno
dan bininya bertengger.
Kalau tidak ditolong oleh pohon kelapa itu, barangkali Kasno
laki-bini tidak ketemu Darmansyah. Tidak bisa menceritakan,
betapa dahsyatnya malapetaka itu. Mula-mula rumahnya mulai
bergerak-gerak. Kemudian bruk, roboh, dindingnya copot
satu-satu. Dari robohan itu berserak segala perabot rumah,
seperti mengucapkan selamat tinggal. Sedih hati Kasno -- tapi
yang lebih kuat lagi adalah takut. Parto saja, seorang jirannya
yang terlambat menyelamatkan diri karena hendak membela harta
benda, hanyut dan tewas. "Air naik pukul 3 sore. Saya bertahan
di pohon kelapa sampai pagi hari," tutur Kasno dengan lidah
medok Jawa.
Kasno terlempar ke Aceh sebagai kuli kontrak perusahaan
Socfindo. Tengah menyadap karet di perkebunan, ia menemukan
jodohnya: Suparti -- 28 tahun yang lalu -- wanita yang juga asal
Wonogiri. Kasno berhenti jadi kuli, membuka ladang. Tapi akibat
kemurkaan Krueng Meureubo, satu hektar sawah yang baru ditanami
1 bulan tertimbun pasir. Sementara satu hektar ladang palawija
ikut porak poranda. Ia hanya bisa menarik nafas berat
menyaksikan semua itu. Di atas tapak rumahnya yang sudah fana,
ia mencoba mengumpulkan tiang dan papan yang masih bisa dipakai.
"Mungkin beberapa hari lagi gubuk darurat saya bisa siap,"
ujarnya.
Ia sudah lapor kehilangan rumah. Kehilangan padi. Selama 5 hari
hanya makan pisang rebus. Tapi belum juga menerima bantuan
Pemerintah. Kecuali ada petugas dari Kecamatan yang tanyatanya.
Matanya berbinar-binar mendengar kabar, bahwa mereka yang
kehilangan rumah dapat bantuan Rp 10 ribu plus beras. "Betul itu
Pak?" tanyanya. Kebetulan Bupati mengadakan kunjungan. Kasno
jadi bungah: laporannya bahwa ia belum menerima bantuan, sudah
dicatat. "Bahkan Pak Bupati marah betul sama Camat," kata Kasno.
"Saya ada poto bersama Pak Bupati sebagai bukti."
Bahaya kelaparan sudah jelas. Tapi Kasno masih belum ketakutan.
Sesuai dengan dalil orang Jawa, ia berkata: "Sebagai mahluk
Tuhan saya harus nrimo dengan nasib begini." Dan sebagai
pantulan dari kebandelannya yang lugu, ia menambahkan: "Saya
akan tetap di sini walau apapun yang terjadi." Isterinya tak
mengatakan apa-apa. Perempuan itu sudah menanggalkan kalung dan
giwang anaknya yang berbobot 9 gram. Dilego di Meulaboh dengan
susah payah. "Kata pemilik toko mas di sana, ia sedang tak punya
uang," tutur Kasno.
Merangkak Ke Bukit
Dibanding dengan Kasno, Zainal Abidin (35 tahun) asal Desa Tutut
Kecamatan Sungai Mas, menderita kekalahan lebih besar. Petani
muda ini mengolah sepetak sawah 2 naleh bibit. Sebagai usaha
sampingan ia membuka jualan di samping rumah. Hidupnya
pas-pasan, tapi ia bersama 6 mulut anak yang ditanggungnya
termasuk pintar untuk merasakan kebahagiaan dari kesederhanaan.
Bagaimana tidak. Di samping sebuah rumah ia juga punya 2 ekor
kerbau, kebun, dan sebuah lumbung padi. Tapi semua itu sekarang
harus dicoret. Ia tak memiliki apa-apa lagi. Banjir sudah
menjilat ludas -- tandas. Maklum kecamatannya memang terbilang
kawasan yang paling robek dalam musibah Mei itu. Bayangkan:
hanya 4 buah rumah yang mampu bertahan di seluruh desa. "Itu pun
karena letaknya kebetulan agak tinggi," kata Zainal.
Waktu air menyerang dengan kecepatan tinggi, Zainal memimpin
keluarganya merangkak ke atas bukit -- hanya 200 meter dari
rumahnya. Zainal sendiri pada mulanya ingin bertahan sebagai
seorang yang jantan. Untung isterinya pakai akal sehat: ia
mendesak supaya cepat mengungsi. Zainal masih berusaha
menyelamatkan barang-barang yang ringan. Tapi isterinya ngotot
agar yang paling penting diusahakan adalah keluar dari air yang
sudah merogoh pinggang itu. Zainal untung menuruti hardikan
isterinya. Mula-mula anak-anak yang diantar ke bukit, dengan
harapan ada waktu untuk kembali menjemput barang-barang. Tentu
saja tidak.
Melawan arus dengan beban menyelamatkan nyawa anak-anak, bukan
pekerjaan yang ringan. "Untung saja luapan air itu sore hari.
Kalau malamlah air naik, tamatlah riwayat kami," kata Zainal.
Meskipun sulit sekali, Zainal berhasil mencapai bukit tanpa
mengorbankan nyawa anak-anak yang dibesarkannya itu. Tapi waktu
ia menoleh ke belakang, ya Tuhan, air sudah melonjak 3 meter
lebih. Maka ia hanya memandang ke depan. Di bukit itu ia bertemu
dengan 4 buah keluarga pengungsi lain.
Barak darurat dibangun. Atapnya daun pisang, lantainya daun
kelapa. 2 hari Zainal sekeluarga bertahan di situ. Menu mereka
anak-beranak, dari nasi berobah menjadi pisang muda yang
dipanggang. Sedang untuk minum, tak ada pilihan lain kecuali
menelan air butek. Waktu perang itu kemudian reda, yakni tatkala
air sudah surut kembali, keluarga Zainal memandang dari bukit ke
lembah dengan rasa yang kosong. Hancur, dan sakit. Tak ada lagi
sisa-sisa kehidupan. Yang ada hanya seruan, anjuran, agar para
pengungsi bergerak menuju ke sebuah SD Inpres.
Pahlawan
Zainal lalu memimpin keluarganya ke tempat pengungsian itu. Tapi
anaknya yang nomor 4 (perempuan, 6 tahun) diserang sakit keras.
"Mungkin karena makanan tak sempurna," kata Zainal. Hanya 2 hari
sakit itu bisa ditahan. Anak itu, ya Tuhan, meninggal di tempat
pengungsian. Isteri Zainal menundukkan kepala. Tapi di daerah
pengungsian pasti tidak hanya mereka yang menderita. Berbagai
keluhan, berbagai penderitaan dari begitu banyak orang
berkerumun menjadi satu. Pada saat-saat semacam itu adakalanya
orang berubah menjadi tabah dan kuat, termasuk juga isteri
Zainal. Ketabahan itulah yang membantu Zainal menahan segalanya.
Keluhan yang paling keras diucapkan setiap mulut pengungsi,
adalah perkara makan. Bukan karena mereka memilihmilih. Tapi
karena makanan memang tidak ada. Kaum pengungsi itu mengupas
pisang dan buah sukun pada hari-hari pertama. Tapi sampai hari
ke delapan banjir, bahan makanan habis. Perut harus tetap diisi.
Penduduk mulai mencari umbut kelapa. "Pokoknya segala apa yang
bisa menopang jeritan perut kami telan saja," kata Zainal. Ia
sendiri akhirnya tak mampu bertahan lama-lama di daerah
pengungsian, karena bantuan belum juga datang. "Desa kami di
udik sekali, tidak mudah mencapainya," tuturnya.
Pada hari kesembilan, Zainal memutuskan untuk berangkat
meninggalkan Desa Tutut. Tak ada jalan lain lagi. Ia kuatkan
hati keluarganya untuk meninggalkan makam anaknya yang baru
dikebumikan, dan bersama menempuh 2 hari perjalanan. Untunglah
usaha ini berhasil. Mereka dapat mencapai Suak Seumaseh, di
Kecamatan Sama Tiga, meskipun dalam keadaan yang berantakan sama
sekali. Zainal bahkan hampir tak bisa bersuara lagi. Di rumah
Keucik Suak Seumasah mereka mendapat nasi. Zainal pulalah orang
pertama di antara yang lolos dari desa yang berhasil mencapai
kota kabupaten Meulaboh. Ia seperti seorang pahlawan. Zainal
menjadi pahlawan. Ia menghadap Bupati dan melaporkan kelaparan
yang mencekik warga desanya di Tutut.
"Yang saya susahkan, bagaimana nasib teman-teman saya di desa
sekarang," kata Zainal. Ia sendiri sudah mendapat bantuan Rp 10
ribu sebagai ganti rumahnya, serta beras 10 kilo. Berbagai cara
telah ditempuh untuk merangkul Desa Tutut dan desa lainnya yang
disapu banjir. Makanan dan obat-obatan secara estafet mengalir
di atas roda, perahu, ataupun diangkut lewat jalan setapak.
Zainal sendiri bersedia berangkat dengan tim penolong, karena ia
sudah merasakan sendiri betapa terdesaknya nasib kawan-kawannya.
"Bahaya paling besar adalah kelaparan," katanya dengan tegas.
Sekarang mereka masih menumpang di rumah abangnya di Krueng
Sabee untuk jangka waktu yang tak dapat dipastikan. Seperti
Kasno, petani muda ini juga beringas untuk kembali membangun
sawahnya. Di samping itu ia memikirkan bagaimana tetap
meneruskan sekolah tiga anaknya. "Mereka tak boleh bodoh seperti
saya," kata bapak yang hanya lepasan SD kelas IV. "Pak Bupati
telah menjanjikan bibit dan bantuan pangan untuk besok-besok,"
katanya dengan gembira dan optimis. Namun ia selalu khawatir
kalau mengingat kemungkinan banjir di masa datang. "Apa nanti
tidak lagi banjir, Bang?"
Lailaha illallah
Sapiyah, seorang janda yang bermula dikabarkan mati dalam banjir
itu, belum sempat memikirkan ancaman banjir di masa datang.
Perempuan berusia 35 tahun tetapi nampak macam nenek-nenek ini
masih menikmati rasa lega, karena terlepas dari lubang kubur.
"Yah, Tuhan masih mengizinkan saya hidup," ujarnya kepada TEMPO.
"Dari Kepala Kampung saya sudah diumumkan mati."
Sejak suarninya meninggal 3 tahun lalu, ia tinggal bersama anak
perempuan tunggalnya (12 tahun) di Desa Putim Kecamatan Kaway
XVI. Menghuni sebuah rumah reot, maklum hidupnya hanya dari jual
tenaga di sawah-sawah tetangga. Ia tak punya tanah. Rumah itu
pun menumpang di tanah orang kampung.
Waktu air menyerang, ia amat panik. Hasnah, anaknya, sedang
bekerja di sawah tetangga. "Saya hanya mengumpulkan kain-kain,
diikat dalam satu bungkusan," ujarnya mengenang peristiwa itu.
"Kalau sekiranya terjadi apa-apa, harta itulah kekayaan terakhir
saya." Tapi ia tidak pergi. Ia "setia" kepada rumahnya. Juga
ketika air yang binal dan garang mulai merendam rumah. Janda itu
mulai berdoa sembari memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Tapi
air tak mendengar suaranya -- malahan mulai mendorong rumah.
Rumah Sapiyah bergerak mengikuti gerakan air. Sapiyah tak tahu
harus berbuat apa. "Saya betul-betul senewen," katanya. Hanya
sepanjang ingatannya ia tetap berdoa.
Tapi rumah tetap bergerak. Dan bagai dituntun oleh kalimat la
ilaha illallah yang diucapkan oleh bibir janda yang melarat,
rumah itu bergerak bagai sebuah rakit, dan akhirnya tersangkut
di pohon kuini. Dengan kehendak Yang Maha Kuasa, rumah tetap
tersangkut. Tetap tersangkut di situ, sampai air surut. Sapiyah
seperti bangun dari mimpi yang paling asing. Ia keluar rumah.
Dan berusaha turun. Ingatan kepada nasib anaknya makin melecut.
Ia berjalan ke tapak rumahnya semula, kira-kira 700 meter
jauhnya. Dan di sana, di sana, ditemukannya seorang gadis kecil
sedang menangis.
Ya Tuhan, itulah Hasnah, anaknya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini