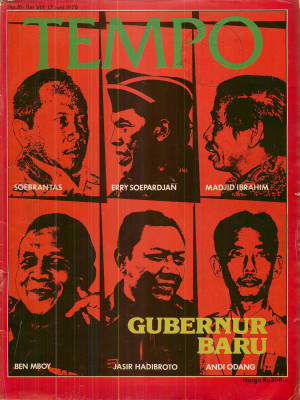DI Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, pekan lalu berakhirlah
Seminar Nasional Pengembangan Lingkungan Hidup Dihadiri oleh 200
peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah dan cendekiawan di
dalam dan di luar universitas. Seminar akhirnya menghasilkan
sejumlah pendapat yang dibacakan oleb Menteri Negara PPLH
(Pengawasan Pembangunan & Lingkungan Hidup).
Tak banyak yang baru dari sana, seidaknya bagi para pembaca
masalah lingkungan. Tapi menarik juga sebuab pendapat dari ir.
Anton Sudjarwo, dari Yayasan Dian Desa serta Unit Teknologi Desa
BUTSI di Yogya. Ia berbicara tentang cara pemecahan krisis air
tanah dan aliran mantap yang konon akan menimpa P. Jawa s/d Nusa
Tenggara akhir abad ini:
PULAU Jawa bakal kering di tahun 2000. Bagaimana? Menurut
taksiran para ahli Dinas Pekerjaan Umum dalam Seminar Nasional
Pengembangan Lingkungan Hidup pekan lalu, perhitungannya begini.
Potensi air dan aliran mantap yang sekarang masih 560
m3/jiwa/tahun, di akhir abad ini -- tak sampai 25 tahun lagi --
akan turun dari 436 m3/jiwa/tahun. Sementara itu, kebutuhan akan
air untuk pemukiman, perkantoran, industri dan pertanian akan
naik dari 403 m3/jiwa/tahun sekarang ini menjadi 702
m3/jiwa/tahun di tahun 2000 nanti.
Itu sebabnya, Kelompok Teknologi yang diketuai ir Anton Sudjarwo
dari Gajah Mada sudah mengusulkan pembuatan bak-bak air tadah
hujan dari ferro-cement, agar orang di kota dan di desa tak
terus menyedot air tanah di Jawa yang semakin langka.
Anton dulu adalah pekerja sosial di Gunung Kidul yang tandus
itu. Waktu itu ia masih kuliah di Gajah Mada.
Tergugah hati untuk memecahkan krisis air yang sudah kronis di
sana, ia bersama penduduk setempat membuat pipa bambu yang
mengalirkan air dari sumber di puncak bukit ke perkampungan di
bawah. Namun kemudian dia punya ide lain, setelah menemukan
bahan baru yang dianggapnya masih cukup murah bagi penduduk
desa: ferro-cement.
Kawat kasa penghalang nyamuk kalau dipoles semen
sebelah-menyebelah ternyata dapat menjadi bak air yang ringan,
kuat, dan tak mudah bocor. Dengan bahan itulah dibuatnya bak air
tadah hujan, yang kemudian ditiru oleh penduduk Gunung Kidul.
"Ini lebih sesuai dengan persepsi mereka tentang air, daripada
mengajarkan mereka membuat sumur bor," tuturnya kepada TEMPO.
Maksudnya: karena harus menggali terlalu dalam di tanah yang
keras, penduduk Gunung Kidul biasa berpasrah menanti jatuhnya
air dari langit.
Pabrik Mobil
Yang menarik ialah bahwa menurut Anton, orang bisa mencobanya di
kota. Dalam kertas kerjanya, insinyur ini mengusulkan agar
pabrik besar pun membangun atap ferro-cement yang sekaligus
berfungsi sebagai bak air tadah hujan. Pabrik mobil yang
memprodusir 10 mobil setiap hari, membutuhkan 50-100 ribu gallon
air sehari. Jika luas atap 50 x 60 m, maka air hujan sudah dapat
mengisi 20% dari kebutuhan airnya.
Contoh itu menunjukkan, kata Anton Sudjarwo, "bagaimana dengan
memotong siklus hidrologi kita dapat meringankan beban air tanah
di suatu daerah industri." Sehingga lebih banyak air tanah yang
bebas untuk pertanian. Apalagi bila di wilayah pemukiman pun
lebih banyak air ditadah dari langit pula. Gagasan ini, yang
menurut Anton dipetik dari kebiasaan rakyat Kalimantan
menyediakan gentong kayu raksasa di samping rumahnya guna
menampung curahan hujan, merupakan salah satu pemecahan -- dan
sekaligus pencegahan -- bahaya eksploitasi air tanah secara
berlebihan.
Tapi bagaimana pemecahan krisis kayu bakar -- "krisis enerji
rakyat desa" yang sudah tak perlu menanti tahun 2000 lagi?
Ketika soal ini ditanyakan oleh Ketua Seminar, Prof. Emil Salim
dalam sidang pleno terakhir, Anton sudah siap pula dengan
jawahannya: alat pencerna gas-bio (methane, CH4) dengan bahan
baku kotoran ternak. Atau penggunaan alkohol sebagai bahan
bakar, yang disuling dari aren, tetes tebu atau sumber nabati
lainnya. Ketimbang cuma diminum sebagai arak.
Kayu Bakar: Defisit
Emil Salim memang tampak lebih prihatin terhadap soal krisis
kayu bakar itu, ketimbang krisis bahan bakar di kota. Hal itu
memang selaras dengan kesimpulan Loka Karya Enerji 1978 yang
baru diselenggarakan di gedung Pertamina Pusat, akhir Mei lalu.
Di sana disimpulkan, bahwa sumber enerji yang dapat diandalkan
untuk daerah pedesaan untuk Repelita III, bukanlah minyak tanah.
Tapi, kembali ke kayu bakar dan limbah pertanian.
Hal itu memang tak perlu lagi dianjurkan. Konsumsi enerji kayu
bakar dan limbah pertanian sejak 1967-1976 toh sudah naik dari
33 juta ton jadi 58 juta ton. Sedang di Jawa saja, naik dari 21
juta ton menjadi 37 juta ton. Dan walaupun saham total kayu
bakar dan limbah pertanian dari seluruh konsumsi enerji turun
dari 67,5% (1969) menjadi 51,7% (1976), di Jawa dan Bali saja
tercatat ada "defisit kayu bakar" sebanyak 10,3 juta ton alias
14,42 juta meter kubik (1974).
"Penggunaan kayu bakar, tak dapat dihapus secara total. Tapi
bisa sebagian disubstitusi oleh gas bio dan alkohol. Ditambah
lagi dengan pengembangan tungku sederhana yang dapat menghemat
kayu bakar," kata Anton Sudjarwo menjelaskan.
Hal ini memang dibenarkan oleh beberapa ahli pertanian dalam
seminar, sebab pengembangan gas bio membutuhkan ternak, dan
ternak membutuhkan padang rumput. Dengan persaingan yang kian
menajam antara ternak, pertanian, hutan lindung, dan 1001
kebutuhan manusia, jumlah ternak yang bisa dipelihara untuk
dibakar tahinya, tentunya ada batasnya. Apalagi kalau disadari
bahwa pemakan kayu bakar yang terbesar bukan dapur orang desa
itu, tapi tungku pabrik-pabrik pembakaran kapur, batu bata,
penyulingan minyak atsiri, dan sebagainya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini