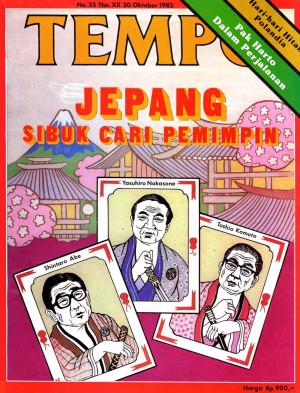GEDUNG pertunjukan itu senyap. Grup wayang orang Ngesti Pandowo
tidak mentas. Padahal sudah 30 tahun lebih teter tradisional
yang terkenal di Jawa Tengah ini setiap malam bermain di Gedung
GRIS Jalan Pemuda, di jantung Kota Semarang yang ramai itu.
Tapi mandeknya Ngesti Pandowo sebenarnya tidak aneh. Bukan hanya
faktor-faktor di dalam menyebabkan ia lumpuh. Tapi juga
kenyataan bahwa ia, seperti banyak grup tradisional lain, kalah
berlomba dengan waktu. Memang banyak grup yang mengalami
kemerosotan serius.
Ngesti Pandowo sendiri misalnya, para pemainnya tidak lagi 100%
"loyal". Paling tidak tentunya menurut anggapan pimpinannya,
Sastro Sudirdjo. Laki-laki 70 tahun ini, tidak berdaya melarang
anak-buahnya beramai-ramai bermain ketoprak di Pati.
"Saya tidak mengajak. Mereka sendiri yang ikut," kilah
Nartosabdho. yang memimpin rombongan ngamen di Pati itu. Dalang
wayang kulit yang sangat terkenal ini sering diundang ke
kota-kota lain. Narto tidak punya grup ketoprak atau wayang
orang, tapi ia memang memenuhi undangan main ketoprak di Pati
--dengan para pemain Ngesti Pandowo. Barangkali ia malah
bermaksud membantu teman-temannya sealmamater. Narto sendiri
dibesarkan oleh Ngesti.
Didirikan di Temanggung, Jawa Timur, 1937, sebenarnya sudah
sejak 10 tahun terakhir ini pamor Ngesti merosot. Setiap malam
hanya 10-15 % dari 1.000 lembar karcis yang terjual. Padahal
karcis paling mahal (VIP) hanya Rp 750. Ini membikin pusing
kepala Sastro, sebab untuk membayar sewa gedung saja sebulan ia
harus mengeluarkan Rp 50.000 lebih. Belum lagi membayar imbalan
para pemain dan karyawan, antara Rp 150-Rp 750 per orang setiap
malam.
Sedikitnya ada 100 kk yang menggantungkan nasib pada Ngesti.
Mereka juga harus dipenuhi kebutuhan lainnya seperti perawatan
kesehatan, juga pembayaran uang sekolah bagi 60 anak karyawan.
Untuk menutupi utang-utangnya, Sastro sempat menjual tanahnya
seluas 900 m2 seharga Rp 8 juta, 1974. Bahkan bulan lalu menjual
seperangkat gamelan slendro pelog yang sudah berusia 70 tahun
seharga Rp 10 juta, kepada seorang pejabat tinggi di Kejaksaan
Jakarta. "Saya terpaksa bekerja sendiri. Yang mengaku dibesarkan
oleh Nesti tidak pernah lagi memikirkan," kata Sasto mengeluh
.
Ia menunjuk Kusni, bekas pimpinan Ngesti, dan Nartosabdho. "Saya
resminya masih menjadi penasihat. Dulu saya pernah memberi
beberapa saran, tapi tidak diperhatikan," sahut Kusni.
Nartosabdho menyerang lebih telak. "Pimpinan Ngesti harus
kolektif seperti dulu. Pimpinan yang sekarang ini tidak mengerti
kesenian," katanya.
Mungkin. Tapi nasib buruk tidak hanya dialami oleh Ngesti. Grup
wayang orang dan ketoprak Sri Wanito, dekat Pasar Dargo,
Semarang, sudah berusia 40 tahun. Ia lebih parah: semalam hanya
sekitar Rp 5.000 saja uang karcis yang masuk. Padahal tak kurang
dari 60 pemain yang setiap hari membayar-tanpa tambahan uang
beras, kesehatan, transpor. Wayang orang Wahyu Budoyo, atau grup
ketoprak di THR Tegalu areng, bernasib sama.
MESKI begitu para seniman rakyat itu cukup gigih. Misalnya
Radjiman, 48 tahun, pimpinan wayang orang Wiromo Budoyo di THR
Yogyakarta. Subsidi bulanan Pemda sekitar Rp 200.000 (dibagi
rata 50 orang) tentu tak mencukupi. Apalagi karcis yang terjual
setiap malam rata-rata 25 lembar, itu pun sebagian besar karcis
kelas III seharga Rp 200. Karcis kelas I dan II sangat jarang
laku.
Tapi, katanya, "kami memang tidak mengharapkan nafkah dari
Wiromo. Tapi kami tetap akan mempertahankannya." Minat penonton
sejak 1977 merosot. "Malah kami pernah main dengan penonton 10
orang, ditambah beberapa keluarga kami sendiri."
Mereka memang nekat, meskipun setiap malam rata-rata hanya
mendapat imbalan Rp 75 - Rp 100. Maka seperti halnya grup-grup
lain, di luar panggung para pemain Wiromo juga bekerja apa saja:
jadi kernet bis, pengumpul koran bekas, tukang becak, tukang
loak, penjual minuman, calo, bahkan ada yang mencari puntung.
Nasib seperti itu jua melanda wayang orang Sriwedarl Sala yang
sudah puluhan tahun. Setiap,malam penontonnya cuma puluhan.
Malah pernah hanya seorang turis asing saja yang menikmati.
"Tiada lain usaha kami kecuali bertahan," ujar Martoyo, 64
tahun, sutradaranya. Martoyo merasa tidak berkewajiban memajukan
grupnya. Sebab hal itu dianggapnya urusan Pemda Kotamadya
Surakarta.
Para pemain wayang orang Sriwedari setiap malam mendapat
honorarium sama rata Rp 400 per orang, ditambah insentif bulanan
antara Rp 2.000 sampai Rp 5.000 per orang. Sejak zaman baberapa
mereka diberi janji akan diangkat jadi pegawai negeri, namun
sampai saat ini hal itu masih menjadi impian. Merosotnya minat
penonton juga melanda wayang orang Sri Wandowo, di THR Surabaya.
"Setiap malam cuma 50 orang," kata pimpinannya, Kol (purn.)
Soemarsono.
Grup-grup sandiwara Sunda, yang bermain di Gedung Yayasan Pusat
Kebudayaan Bandung (YPKB) di Jalan Naripan yang cukup strategis
itu, bagaimana? sarwa wae, alias sami mawon. Dua tahun
belakangan ini jumlah penonton hanya sekitar 50 dari 600 kursi
yang terisi, setiap malam. Padahal yang tampil di panggung
pemain-pemain top--gabungan dari lima grup sandiwara: Sri Murni,
Dewi Murni, Sri Mukti, Swadaya, dan Sanggar Vikta.
Orang Sunda tampaknya lebih gemar nonton wayang golek setiap
malam Minggu yang selalu berakhir subuh, sementara sandiwara
hanya sampai pukul 23.00. Dengan karcis Rp 500, rata-rata 300
sampai 400 penonton bisa diandalkan selalu hadir. Wayang golek
Sunda yang laris ini mulai dipentaskan sejak 1950. "Malah
akhir-akhir ini nampaknya ada kecenderungan jumlah penonton
meningkat," ujar A.S. Basiri, 47 tahun, Kepala Pelaksana Harian
YPKB.
Merosotnya jumlah pengunjung, terutama selama dasawarsa
terakhir, tentunya disebabkan oleh semakin mudahnya orang
mendapatkan pilihan lain. Contoh dari tanah Sunda itu, larinya
penonton sandiwara ke wayang golek, sudah merupakan bukti.
Jangan dikata lagi saingan berupa film, televisi, dan sekarang
video. rtu herarti pengurus sebuah grup memang mesti
pandai-pandai ber"improvisasi", misa.lnya bersama dengan orang
luar yang populer.
Sri Wandowo di THR Surabaa minggu depan ini mendatangkan
beberapa pemain ketoprak dari Jawa Tengah. Bahkan pada
posternya tercantum nama Nartosabdho sebagai sutradara. Pernah
pula grup ini memancing penonton dengan mengundang pelawak
Kardjo AC/DC. Hal serupa juga dilakukan oleh Srimulat Jakarta.
Pernah mengundang Jojon, Ateng, Bagio, Bokir, dan akhir bulan
ini Lidya Kandou.
Ludruk Mandala, yang kini sedang main di Pasar Seni Ancol,
Jakarta, tak segan pula mementaskan cerita dengan pemain
gabungan dari beberapa grup ludruk. Grup ini juga pernah
memanggil Ateng dkk. atau penyanyi Mamiek Slamet. Bahkan grup
wayang orang Bharatadi Kalilio-Senen, Jakarta, tak
tanggung-tanggung: Maret lalu sempat bermain bersama tokoh
pantomim Prancis yang terkenal, Pradel.
Yang jelas, pasaran hiburan di Jakarta ternyata lebih ramai.
Karcis Rp 2.500 dengan mudah terjual habis, terutama di malam
Minggu. "Orang Jakarta kan mudah buang duit," ujar Teguh, 52
tahun, pimpinan Srimulat Jakarta, yang kini main di Taman Ria
Remaja Senayan. Srimulat kini punya 2 cabang, Surabaya dan Sala.
Tapi tetap saja, "penonton di Surabaya tetap yang paling
banyak," kata Teguh lagi --- dibanding dengan Jakarta. Itu
berarti bahwa bukan faktor 'suka buang duit' itu benar yang jadi
ukuran. Yang agak sepi Srimulat cabang Sala, meski penanggung
jawabnya Djudjuk sendiri, sang primadona yang juga istri Teguh
itu.
Menurut Teguh, merosotnya penggemar teater tradisional seperti
Ngesti Pandowo sebetulnya, antara lain, karena pertunjukannya
yang monoton. Hampir tidak pernah melakukan pembaruan. Juga
kurang menampilkan ekspresi. Pemain yang menangis misalnya,
cukup menutup muka dengan selendang, sementara sang dalang
bercerita bahwa sang tokoh sedang menangis.
Dengan kata lain, sementara zaman berubah, pembaruan telah
mandek di Ngesti Pandowo. Sebab jangan dilupakan, grup inilah
yang -- misalnya--tercatat pertama kali menyuguhkan adegan
terbang untuk Gatutkaca misalnya, di aman ketika adegan terbang
dalam film pun belum populer. Atau menyuguhkan barisan prajurit
lengkap dengan pasukan gajah bikinan, diiringi gending yang
hebat. Nartosabdho, di samping juga Sastro Sudirdjo, ambil
peranan dalam berbagai pembaruan itu.
Sekarang memang tetap ada Gatutkaca terbang. Tapi apa lagi
anehnya, di tahun 1982 ini? Dengan kata lain, seperti juga
ditulis budayawan Umar Kayam di harian Kompas, yang dibutuhkan
grup yang mau bertahan tak kurang dari tenaga-tenaga 'pemikir'.
Untunglah akhirnya Gubernur Supardjo Roestam turun tangan.
Bahkan Wallkota Semarang Imam Suparto menjanjikan anggaran
khusus lewat APBD, mulai tahun depan, untuk Ngesti Pandowo.
"Setiap bulan akan saya bantu Rp 2.500 setiap orang."
Namun bagi Supangat, 42 tahun, pimpinan wayang orang Bharata,
Jakarta, bantuan seperti itu 'kan tidak mungkin diterima
terus-menerus. "Bahkan dengan mendapat bantuan, para seniman
tidak bisa kreatif," katanya. Meski begitu cepat-cepat
ditambahkannya: "Tapi sesungguhnya saya ngiri juga, mengapa cuma
Ngesti yang diperhatikan."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini