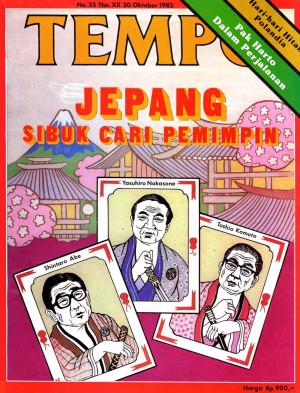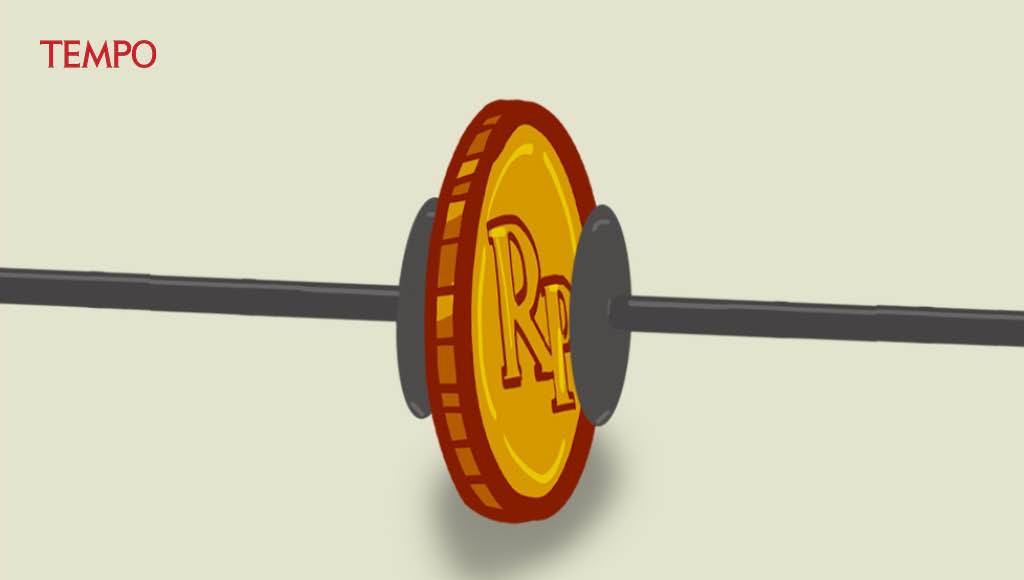ADA dua pendapat tentang apakah Indonesia harus meningkatkan
laju pembangunannya pada saat penghasilan ekspor di luar minyak
menurun, dJn pada saat dia kehilangan US$ 10 juta sehari dari
produksi dan ekspor minyak yang berkurang. Pendapat yang satu
mengatakan sebaiknya Indonesia mengurangi kecepatan
pembangunannya dengan menunda beberapa proyek yang membutuhkan
banyak devisa.
Pendapat ini umumnya berasal dari kalangan ekonom swasta,
terutama dari beberapa bank AS. "Indonesia harus menunda
beberapa proyek, dan menundanya untuk jangka waktu lama,"
demikian kata Eric Rasmussen, ekonom pada Chemical Bank of the
US, yang berkedudukan di Singapura. Mereka yang berpendapat
Indonesia harus menurunkan kegiatan pembangunannya mendasarkan
argumennya bahwa memaksakan pembangunan di saat cadangan devisa
terus berkurang bisa menimbulkan krisis yang lebih buruk.
Pendapat kedua mengatakan, justru Indonesia harus mempercepat
laju pertumbuhan ekonominya sekalipun dana yang tersedia
berkurang. Pendapat ini berasal dari Bank Dunia. Dalam
laporannya tentang ekonomi Indonesia 1982, Bank Dunia
mengemukakan, Indonesia tidak bisa memperlambat laju
pembangunan, karena ada alasan yang cukup mencekam delapan tahun
lagi 20 juta orang akan membanjiri pasaran tenaga kerja, dan
harus memperoleh pekerjaan. Dari sensus terakhir ternyata,
hampir separuh dari 147 juta penduduk Indonesia berumur di bawah
17 tahun.
Banyak pertanyaan tentunya akan dialamatkan kepada Presiden
Bank Dunia Clausen, yang akan mengunjungi Indonesia antara 25 -
30 Oktober. Sebab pemerintah Indonesia memutuskan untuk
mengikuti anjuran Bank Dunia. Ketika melantik para anggota baru
MPR, Presiden Soeharto menyatakan tekadnya bahwa "kita akan
melanjutkan kebijaksanaan yang selama ini sudah memberikan
hasil, dan harus meneruskan laju pembangunan ekonomi kita lebih
cepat lagi." Yang menjadi pertanyaan, kalau pertumbuhan ekonomi
akan tetap dipertahankan, dari mana dananya harus dicari?
Bank Dunia memperkirakan, untuk menutup defisit dari menurunnya
ekspor, Indonesia memerlukan tambahandana US$ 12 milyar selama
empat tahun mendatang. Dari jumlah ini, US$9 milyar bisa berasal
dari IGGI, dan sisanya US$3 milyar harus dicari dari bank-bank
komersial swasta.
Utang luar negeri Indonesia sendiri sekarang sudah mencapai US$
15 milyar, jumlah rekor terbesar sejak krisis keuangan Pertamina
pada 1976. Utang sebesar itu sebagian merupakan pinjaman dari
bank-bank swasta luar negeri. Pinjaman dari bank-bank swasta itu
bukan hal yang baru bagi Indonesia. Sudah beberapa kali
pemerintah Indonesia menerima pinjaman dari bank-bank swasta.
Akhir tahun lalu dan awal tahun ini saja, pemerintah menerima
masing-masing US$ 300 juta pinjaman dari sindikat beberapa bank
swasta luar negeri.
Ketika menghadiri pertemuan Dewan Moneter Internasional (IMF) di
Toronto baru-baru ini, Gubernur Bank Sentral Rachmat Saleh dan
Menteri Keuangan Ali Wardhana menggunakan kesempatan itu untuk
bertemu dengan beberapa bankir swasta. Lobbymg seperti itu
memang perlu. Karena pinjaman dari bank swasta mempunyai bunga
yang lebih ini dari pinjaman yang berasal dari IGGI atau Bank
Dunia, penting sekali bagi pemerintah untuk tawar-menawar bunga
yang harus dibayar.
Sialnya, sekarang bukan waktunya lagi bank untuk bersikap mudah
dalam tawar-menawar bunga pinjaman ini. Ketidaksanggupan
Meksiko, Polandia, Brazil dan beberapa negara lain untuk
membayar pinjaman kepada bank-bank, telah menimbulkan kerugian
besar bagi bankbank swasta ini. Trauma ini masih tebal, dan
sulit sekali bagi bank untuk memberi bunga yang 'miring' pada
pinjamannya.
Prancis baru-baru ini harus membayar bunga 0,5% di atas Libor
(tingkat bunga pinjaman antarbank di London) untuk pinjaman US$4
milyar yang diperlukan untuk dana pendukung mata uangnya.
Tingkat itu adalah terkini yang pernah terjadi. Sekarang
beberapa bank malah mengaitkan bunga pinjamannya dengan bunga
dasar (prime rate) yang diberikan bank-bank AS untuk
nasabah-nasabah utamanya. Bunga ini memang cukup tinggi.
Malaysia merupakan negara yang terkena tingkat bunga ini, untuk
pinjamannya yang US$ 1,1 milyar baru-baru ini.
Untungnya, Indonesia masih dinilai lain oleh bank-bank swasta.
Untuk pinjaman US$ 250 juta yang baru-baru ini diperoleh dari
sindikat bank terdiri dari Bank of Tokyo, Chase Manhattan, Lloyd
Bank of London dan sebuah bank pemberi kredit jangka panjang
Jepang, Indonesia masih dikenakan 0,375% di atas Libor, sama
seperti bunga untuk pinjaman sebelumnya. Jangka waktunya 10
tahun, dan pembayaran kembali di mulai lima tahun sesudah
penandatanganan perjanjian. Sebelumnya, dua bank Arab
masing-masing Gulf International dan Saudi International Bank
telah setuju memberi pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 75
juta, dengan bunga sedikit di bawah sindikat empat bank tadi:
0,25% di atas Libor.
Apakah bank-bank swasta ini akan terus bersikap murah terhadap
Indonesia, akan tergantung pada apa yang akan terjadi pada
ekonomi Indonesia. Rupiah yang terus merosot, defisit neraca
pembayaran yang makin besar, merupakan dua hal yang bakal
diperhatikan oleh bank-bank swasta asing itu.
Beberapa pejabat pemerintah juga tak serta merta menyambut
anjuran Bank Dunia itu. "Memang anggaran yang sekarang terasa
paling berat, tapi kita perlu berhati-hati jangan sampai
menumpuk utang dari bank-bank asing," kata seorang pejabat
ekonomi. Kisah Meksiko, negeri minyak yang dilanda utang
komersial itu, agaknya membuat Indonesia lebih selektif dalam
mencari utang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini