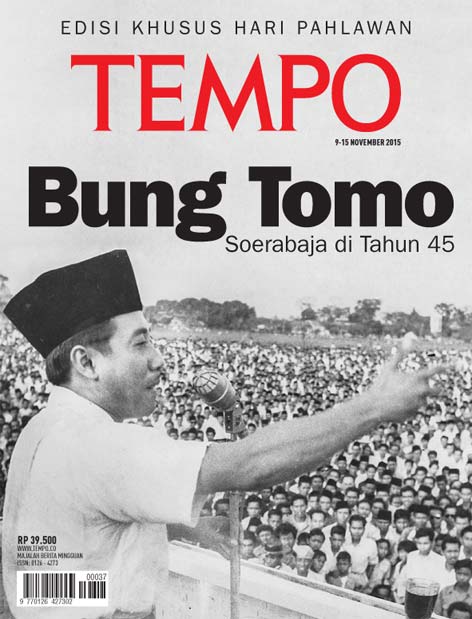Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NURSYAHBANI Katjasungkana menyimpan rapat-rapat jadwal keberangkatan dia menuju Den Haag, Belanda. Pengacara dan aktivis hak asasi manusia ini hanya memberitahukan nama pesawat dan waktu penerbangan kepada orang-orang terdekat. Ia pun mempertimbangkan saran dari rekan-rekannya untuk membawa makanan sendiri selama penerbangan.
Nursyahbani sejatinya sudah terbiasa bolak-balik Jakarta-Den Haag. Tapi, kali ini, dia bersama kawan-kawannya bertolak ke Belanda untuk acara yang spesial. Mereka menjadi panitia International People's Tribunal 1965, yang akan berlangsung pada 10-13 November 2015. Nursyahbani menjadi koordinator panitia dalam perhelatan "pengadilan rakyat" untuk menguak rentetan kekerasan pada 1965 itu.
"Untuk keselamatan tim, kami juga tidak berangkat bersama dari Indonesia," kata Nursyahbani ketika ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu.
Menurut Nursyahbani, disiapkan sejak dua tahun lalu, International People's Tribunal 1965 merupakan langkah awal menuju pengakuan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara. Setelah pengadilan rakyat digelar, Nursyahbani berharap pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia yang menjadi korban. "Selama ini mereka mendapat perlakuan dan stigma buruk," ujar Nursyahbani.
Usul menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965 muncul ketika Nursyahbani tinggal di Den Haag untuk penulisan sebuah buku. Ceritanya, pada 22 Maret 2013, Nursyahbani mengundang Joshua Oppenheimer untuk memutar filmya, Jagal: The Act of Killing, yang dibuat pada 2012. Setelah membuat Jagal, Oppenheimer membikin film berjudul Senyap: The Look of Silence (2014). Kedua film itu sama-sama bertemakan kejahatan atas kemanusiaan pada 1965, terutama yang dialami anggota dan simpatisan PKI.
Siang itu, ada tujuh warga Indonesia yang diundang ke rumah Nursyahbani, termasuk dua orang yang berada dalam pengasingan (eksil). Seusai pemutaran film dan diskusi, Oppenheimer mengatakan bahwa dia telah menuntaskan pekerjaannya sebagai intelektual, seniman, dan pekerja film. Oppenheimer lalu "menantang" warga Indonesia untuk mengangkat martabatnya sendiri dan meluruskan sejarah bangsanya.
Terpantik tantangan itu, seorang peserta diskusi mengusulkan Nursyahbani menggelar pengadilan rakyat untuk kasus 1965. Alasan dia, Nursyahbani telah punya pengalaman menggelar kegiatan serupa untuk memperjuangkan hak perempuan korban tentara Jepang (jugun ianfu) pada 2000.
Sejak itu, rencana menggelar pengadilan rakyat untuk tragedi 1965 terus dimatangkan. Nursyahbani dan kawan-kawan membentuk tim peneliti untuk menggali informasi tentang seluk-beluk tragedi 1965 serta nasib para korban. Nursyahbani pun turut berkeliling ke beberapa kota di Jawa, Sumatera, sampai Nusa Tenggara Timur.
Meski tak pernah mendapat ancaman spesifik, selama penelitian itu, Nursyahbani dan kawan-kawan tak jarang mendapat kecaman. Pernah suatu waktu, di sebuah forum diskusi, seorang pensiunan jenderal tentara menyebut Nursyahbani pengkhianat. "Saya tertawa saja," kata Nursyahbani.
Kritik juga kadang menghujani Nursyahbani dan kawan-kawan di jejaring media sosial. Ada pengkritik yang menganggap Nursyahbani dkk berlebihan membela PKI. Sebaliknya, Nursyahbani dkk dituduh tak pernah membela kelompok masyarakat lain yang menjadi korban anggota PKI.
Alih-alih mundur, Nursyahbani justru menjadikan aneka kritik itu sebagai bahan introspeksi. Ia mengakui belum bisa menjelaskan kepada orang awam bahwa pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada 1965 serta stempel buruk yang terus dilekatkan pemerintah merupakan pelanggaran hak asasi.
Kepada para pengkritiknya, Nursyahbani dkk berusaha menjelaskan, bila anggota PKI melakukan kekerasan terhadap masyarakat lain, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana biasa. "Itu konflik horizontal, bukan perlakuan pemerintah terhadap rakyatnya," ujarnya. Meski begitu, di akun Facebook-nya, Nursyahbani menyatakan siapa pun yang mempunyai data valid seputar korban keganasan PKI akan dia advokasi juga.
Di Den Haag, ada sekitar 100 relawan yang menyiapkan acara pengadilan rakyat tersebut. Menurut salah satu relawan, Reza Muharam, persiapan pada hari-hari terakhir tinggal memastikan kedatangan para saksi. Nama para saksi baru akan dipublikasikan pada 9 November 2015. "Itu pun demi keamanan mereka," kata Reza ketika dihubungi Kamis pekan lalu.
MESKI International People's Tribunal 1965 merupakan pengadilan partikelir, prosesnya akan mirip dengan pengadilan resmi kasus-kasus pelanggaran HAM. Di samping dihadiri perwakilan saksi dan korban, sidang akan dihadiri panel ahli dan praktisi hukum yang berperan laiknya majelis hakim. Termasuk dalam panel hakim antara lain Sir Geoffrey Nice, mantan deputi jaksa pada International Criminal Tribunal bekas Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic.
Ada juga sekelompok praktisi dan ahli hukum yang berperan sebagai jaksa penuntut umum. Termasuk dalam barisan "jaksa" ini adalah pengacara senior asal Indonesia, Todung Mulya Lubis.
Mengumpulkan ahli dan praktisi hukum yang punya reputasi bagus di level internasional menjadi tantangan sendiri. Todung saja, misalnya, tak langsung menyanggupi ketika Nursyahbani meminta dia menjadi jaksa dalam pengadilan rakyat ini. "Saya tidak bilang ya atau tidak," ujar Todung.
Pada Oktober 2013, menurut cerita Todung, Nursyahbani sampai terbang khusus menemuinya di Boston, Amerika Serikat. Kala itu Todung sedang menjadi fellow di Harvard Kennedy School. Todung akhirnya menyanggupi permintaan Nursyahbani karena dia pun menginginkan kejelasan soal tragedi 1965. "Itu peristiwa brutal. Kita punya utang sejarah," kata Todung.
Pada awal sidang International People's di Den Haag pekan ini, Todung dan kawan-kawan akan memaparkan berbagai "dakwaan" seputar tragedi 1965. Menurut Todung, ada sembilan poin "dakwaan" yang bakal dia sampaikan bersama anggota tim. Antara lain dakwaan tentang dugaan pembunuhan massal, pemenjaraan besar-besaran, penyiksaan, kekerasan seksual, propaganda kejahatan karena kebencian (hate crime), pengasingan, dan penghilangan paksa. Yang akan menjadi "terdakwa" untuk berbagai dugaan kejahatan tersebut adalah negara Indonesia.
Di samping itu, ada "dakwaan" soal dugaan keterlibatan negara asing, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam tragedi 1965. "Istilahnya complicity of other state," ujar Todung.
Untuk membuktikan dakwaan itu, Nursyahbani dan kawan-kawan sudah menyiapkan laporan hasil penelitian tentang tragedi 1965. Versi lengkap laporan itu setebal 1.200 halaman. Agar mudah dipelajari "panel hakim", laporan sudah diringkas menjadi 250 halaman.
Keterangan para saksi korban akan mendukung dokumen tertulis itu. Saksi korban yang akan dihadirkan ke Den Haag antara lain berasal dari Kupang, Medan, dan Yogyakarta.
Pada akhirnya, panel hakimlah yang akan menyimpulkan apakah "dakwaan" yang disampaikan Todung dan kawan-kawan terbukti atau tidak. Apa pun bunyinya, menurut Todung, putusan "panel hakim" itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jangankan untuk mematuhi, kalau tidak mau membaca putusannya pun pemerintah Indonesia tak bisa dipaksa.
Meski begitu, kata Todung, pemerintah Indonesia tak bisa mengabaikan begitu saja putusan pengadilan rakyat ini. "Akan ada tekanan diplomatis dari negara-negara yang punya perhatian terhadap masalah ini." Karena itu, menurut Todung, pemerintah Indonesia lebih baik menjadikan hasil International People's Tribunal 1965 sebagai bahan tambahan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Ujungnya semestinya ke arah sana," ujar Todung.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir, mengatakan pemerintah Indonesia tak akan mengambil sikap apa pun terhadap pelaksanaan International People's Tribunal di Den Haag. Bagi pemerintah, upaya rekonsiliasi telah dilakukan dan sudah ditutup. Kini pemerintah tengah berupaya merehabilitasi nama-nama yang terduga terlibat dalam peristiwa 1965. "Bila terus mengangkat isu itu, harus dilihat seberapa jauh kita mundur ke belakang," kata Arrmanatha.
Nur Haryanto, Anton A., Mitra T., Arkhelaus W., Istman M.P., Yohanes P., Bagus P.
International People's Tribunal 1965
FORUM "pengadilan rakyat" ini digagas sejumlah pegiat hak asasi manusia, keluarga korban, serta ahli dan praktisi hukum yang memiliki reputasi di tingkat internasional. Forum ini tak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court atau Badan Hak Asasi Manusia Tertentu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Putusan pengadilan partikelir ini pun tak punya kekuatan hukum mengikat, tapi bisa memperkuat advokasi, baik di level nasional maupun internasional.
Waktu dan Tempat
Prosedur
Tindak Lanjut
"Tim Penuntut"
"Panel Hakim"
1. Sir Geoffrey Nice (mantan deputi jaksa untuk International Criminal Tribunal bekas Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic).
2. Helen Jarvis (Wakil Presiden Permanent People's Tribunal, duduk di Dewan Penasihat Pusat Studi Genosida dan Keadilan di Dhaka, Bangladesh).
3. John Gittings (pengamat Asia Timur dan jurnalis The Guardian 1983-2003).
4. Mireille Fanon Mendes (anggota Permanent People's Tribunal, tenaga ahli di PBB).
5. Asma Jahangir (advokat bidang hak asasi manusia di Pakistan, Pelapor Khusus PBB tentang Ekstrayudisial, Arbitrase, atau Ringkasan Eksekusi pada 1998-2004).
Sumber: ITP 1965| Mitra Tarigan | Linda Hairani
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo