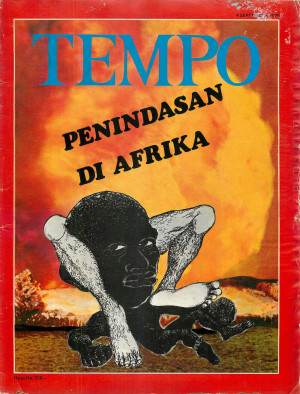UJUNG Selatan Afrika minggu lalu adalah salah satu daerah yang
paling cemas di dunia. Di Republik Afrika Selatan, kerusuhan
belum sepenuhnya enyah dari Soweto. Daerah perkotaan di barat
daya kota Johannesburg ini (Soweto = South Western Township) --
yang disediakan untuk penduduk kulit hitam -- masih diliputi
suasana kacau balau. Kerusuhan yang bermula sejak Juni yang lalu
sebagai protes anak-anak sekolah (TEMPO 21 Agustus) telah
berkembang menjadi perkelahian antara suku-suku kulit hitam.
Gerakan untuk mogok yang didesakkan para pelajar hitam yang
menentang pemerintah, rupanya dihadapi dengan kemarahan para
buruh suku Zulu yang tidak mau mengikuti garis itu. Kira-kira 20
orang tewas dalam anarki yang bermula sejak Senin dan mereda
Sabtu yang lalu itu. Sepuluh di antaranya mati oleh tindakan
polisi.
Di Rhodesia, negeri lain agak ke utara yang juga dikuasai
minoritas kulit putih, pertempuran dengan gerilyawan hitam
berjangkit lagi. Di ibukota Salibury pekan lalu pernyataan
pemerintah mengatakan tujuh orang gerilyawan lagi tewas -- dan
jumlah itu tahun ini menjadi 902 orang.
Tak kurang seram adalah orang-orang kulit putih di Namibia atau
Afrika Barat Daya yang dikendalikan oleh Republik Afrika
Selatan. Mereka pekan lalu itu sedang menyelenggarakan kongres
Partai Nasional di ibukota Windhoek. Tapi para delegasi
cepat-cepat pulang ke kota masing-masing. 26 Agustus sepuluh
tahun yang lalu, pertempuran pertama terjadi antara pejuang
kemerdekaan kulit hitam dengan pasukan Afrika Selatan. Sepuluh
tahun kemudian, hari Kamis pekan lalu itu, kaum nasionalis hitam
menyatakan hari itu sebagai "Hari Namibia". Dan diperkirakan
kegiatan gerilya akan meningkat lagi. Di ibukota Tanzania, Dar
es Salaam, seorang wakil SWAPO (Southwest African Peoples
Organization) -- yang merupakan gerakan kemerdekaan yang diakui
PBB -- mengancam akan melancarkan perang "gaya Vietnam" bila
Afrika Selatan memberikan "kemerdekaan" hanya kepada
boneka-bonekanya di Namibia.
Wilayah ini, bekas jajahan Jerman yang kemudian oleh Liga
Bangsa-Bangsa dititipkan kepada Republik Afrika Selatan sebagai
daerah mandat, seharusnya mendapat kesempatan pemilihan bebas 31
Agustus minggu ini sebagaimana ditentukan PBB. Tapi nampaknya
Republik Afrika Selatan hanya akan mundur dari Namibia dengan
membagi wilayah seluas 820.000 Km2 itu dalam daerah-daerah yang
masing-masing dihuni oleh ras yang berbeda-beda. Ini sesuai
dengan doktrin apartheid ("keterpisahan") -- di mana si kulit
putih menempati kedudukan yang di atas. Maka dalam sidang-sidang
yang membicarakan kemerdekaan Namibia itu SWAPO tidak diajak
serta ....
Tapi rupanya pergolakan terus-menerus sukar bisa dicegah. Apa
yang terjadi di Soweto dan kemudian menjalar ke pelbagai tempat
di Afrika Selatan mengisyaratkan itu dengan jelas. Soalnya
seperti sepele mula-mula: sebuah protes terhadap keharusan
memakai bahasa Afrikaan di samping bahasa Inggeris (dalam
perbandingan 50-50) di sekolah-sekolah hitam. Mula-mula para
dewan sekolah dan guru yang menolak. Tapi kemudian juga para
murid, yang nampaknya menjadi lebih militan dalam tahun-tahun
belakangan ini -- terutama yang berumur sekitar 16 tahun. Mereka
ini, yang waktu kecil di sekolah dasar diajar dengan bahasa suku
mereka (Zulu, Xhosas dan Tswana), pada tahap berikutnya harus
memakai dua bahasa asing sekaligus. Tentu saja mereka lebih
ingin memilih satu saja, dan itu adalah bahasa Inggeris. Bahasa
Inggeris membuka kesempatan banyak sebagai bahasa internasional,
dan juga merupakan bahasa antar orang hitam sendiri di kota-kota
besar. Sementara itu bahasa Afrikaan -- yang akarnya adalah
bahasa Belanda -- merupakan bahasa orang putih yang menindas
mereka.
BEGLTULAH di pertengahan Juni 10.000 murid sekolah Soweto
berkumpul ke Stadium Orlando, untuk menyatakan perasaan mereka.
Mereka berumur antara 12 sampai 20 tahun. Mereka membawa
semboyan-semboyan seperti "Enyahlah Afrikaan!" dan "Viva
Azania". ("Azania" adalah nama untuk Afrika Selatan yang
diberikan oleh para anggota Gerakan Pelajar Afrika Selatan --
kelompok yang banyak tampil dalam protes itu). Tak lama
kemudian polisi tiba, kebanyakan juga berkulit hitam, tapi
dipimpin perwira putih, dalam 10 kendaraan. Apa yang kemudian
terjadi merupakan fakta sejarah sudah: polisi menembak -- dengan
peluru betul-betul -- dan kerusuhan hebat terjadi. 140 orang
tewas dan 1000 lebih luka-luka. Dengan begitu kejadian 16 tahun
yang lalu berulang lagi. Di Namibia, 10 Desember 1959, penduduk
hitam yang mau digusur dari Windhoek, ke "Katutura" (dalam
bahasa Heroro artinya "kami tak punya tempat milik sendiri")
berdemonstrasi. Pasukan pemerintah malam itu melepaskan peluru
dan 11 orang tewas. Di Afrika Selatan sendiri beberapa bulan
kemudian peristiwa Sharpeville terjadi: Maret 1960, demonstran
hitam ditembaki polisi, dan 74 orang terbunuh sekaligus.
Kekerasan dalam bentuk yang telanjang ataupun secara tidak
langsung agaknya memang bagian dari struktur yang ditegakkan di
Afrika Selatan. Sejarah apartheid bisa ditarik panjang ke abad
ke-17 ketika bangsa Portugis menduduki Angola dan Mozambique.
Atau sampai ketika masuknya bangsa Belanda -- atas nama VOC yang
juga menguasai Indonesia -- sejak koloni Tanjung Harapan
didirikan oleh Ian van Riebeck di tahun 1652. Perluasan daerah
kekuasaan oleh para pendatang Belanda kemudian menyebabkan
banyak terjadinya bentrokan dengan suku pribumi -- terutama
antara para trekboer (peternak) dengan suku Khosa. Mungkin dari
masa inilah orang berbicara tentang "jiwa laager" yang konon
masih merupakan ciri orang puth di Afrika Selatan. Dalam
sejarah negeri ini, laager adalah suatu lingkaran kereta, yang
roda-rodanya diikat dengan cabang-cabang duri yang tebal: dalam
lingkaran yang berlaku sebagai benteng itu orang kulit putih
mengumpulkan keluarga mereka, bersiap denan bedil, menunggu
orang-orang hitam mendekat untuk menyerang. Mereka selalu merasa
dalam ancaman. Untuk hidup terus, mereka merasa perlu menindak
orang-orang yang mereka takuti.
Rasa selalu terancam oleh mayoritas itu bersamaan pula dengan
rasa lebih unggul. Orang orang hitam selalu dilihat sebagai
buruh murah. Kemenangan Inggeris terhadap orang-orang Boer,
dalam perang panjang yang ganas yang berakhir menjelang awal
abad ke-20, tak merubah itu. Bahkan setelah Inggeris memberikan
hak memerintah sendiri bagi mereka, orang putihlah yang memegang
sepenuhnya kekuasaan politik di atas orang pribumi Afrika, dan
di atas orang kulit berwarna serta orang India di wilayah itu,
meskipun- orang putih cuma minoritas.
Maka dengan mudahnya di tahun 1913 dikeluarkanlah Undang-Undang
Tanah Pribumi atau Native's Land Act. Lewat ini, orang hitam
dibatasi jumlah tanah yang bisa mereka miliki. Dan agar menjadi
buruh murah, mereka digeser dari posisi sebagai petani bagi
hasil dan penyewa tanah menjadi hanya penerima upah. Di bawah
undang-undang itu -- serta beberapa undang-undang lain yang
kemudian menyusul hanya sekitar 13% tanah diperuntukkan bagi
orang hitam yang jumlahnya lebih 4 juta, sementara 87%
disediakan bagi orang putih yang cuma satu seperempat juta.
Dan tanpa tanah, orang-orang hitam pun memasuki kota-kota.
Sampai kini pun kurang-lebih 33% orang pribumi, yang oleh orang
putih disebut "Bantu" tinggal di daerah perkotaan. Tapi di awal
1930-an orang putih dari pedalaman juga ternyata membanjiri
kata-kota. Mereka miskin, tak punya kecakapan, tak terdidik --
dan kalah bersaing dengan orang hitam yang punya kecakapan lebih
dan bersedia melakukan kerja kasar. Dan bila orang hitam masih
bisa hidup lumayan dengan dibantu keluarga mereka, orang putih
melarat itu harus hidup dari upah belaka. Bagi si putih ini
kurang adil. Maka para penguasa dan para kapitalis kulit putih
pun pada akhir Perang Dunia II memutuskan untuk mengkhususkan
kota bagi kepentingan si 'Afrikaner". Nasib si hitam, sekali
lagi bertambah buruk.
1948, Partai Nasional Afrikaner menang. D.F. Malan menjadi
perdana menteri, sampai 1954. Ia ternyata berhasil didukung oleh
orang kulit putih yang berbahasa Inggeris, dan tak cuma oleh
orang Afrikaner yang setia. Demikian juga penggantinya, J.G.
Strijdom. Keduanya adalah tokoh-tokoh pembela supremasi putih.
Keduanya menafsirkan apartheid sebagai salah satu cara untuk
memaksakan berlakunya baaskap -- kemajikanan mereka di atas
kelompok ethnis yang lain. Aparthei sendiri, sebagaimana
dinyatakan sebagai garis politik oleh orang Afrikaner, "bertugas
menjaga dan mempertahankan identitas rasial penduduk kulit
putih". Juga "menjaga dan mempertahankan identitas bangsa-bangsa
pribumi sebagai kelompok rasial yang terpisah, dengan kesempatan
untuk berkembang ke arah satuan-satuan yang berpemerintahan
sendiri". Tak kurang merdu dari itu, apartheid juga berbicara
tentang perlunya "hargadiri dan saling menghormati antara
pelbagai ras di negeri ini". Doktrin ini juga mendukung "prinsip
umum pemisahan wilayah antara orang Bantu dengan orang putih".
Memang, tak terlalu jelek kedengarannya. Bahkan doktrin ini
didukung oleh sementara ahli antropologi serta kaum
administrator yang bermaksud melindungi masyarakat-masyarakat
tradisionil Afrika dari perubahan sosial yang berlaku cepat.
Tapi sebagaimana di tahun 1968 ditanyakan oleh Toivo Hermann ja
Toivo -- seorang guru dan tokoh SWAPO yang dihukum penjara 20
tahun -- dalam pidatonya di pengadilan: "Perpisahan, katanya,
merupakan proses yang alamiah. Tapi kalau begitu, kenapa ia
diterapkan dengan cara paksa? Dan mengapa orang kulit putih yang
memiliki keunggulan?".
Pertanyaan itu tak terjawab -- karena para pendukung apartheid
memang tak akan bisa menjawab. Juga Verwoerd tidak. Ada yang
menilai bahwa perdana menteri Afrika Selatan yang ke-3 ini
seorang pemikir radikal dulunya, dan bahwa ia berbeda dari
Malang ataupun Strijdom. Verwoerd konon bertolak dari anggapan
bahwa orang hitam tidak dari dasarnya lebih rendah ketimbang
orang putih, dan ia menolak semangat baaskap.
Tokoh kelahiran Amsterdam (1901) yang dibesarkan di Afrika
Selatan ini memang pada mulanya seorang ilmiawan. Ia gurubesar
muda usia yang cemerlang di Universitas Stellenbosch, di bidang
psikologi, yang kemudian pindah ke bidang sosiologi. Ia
selanjutnya menjadi editor Die Transvaller, milik partai
Nasional, ketika umurnya baru 36. Sebelas tahun kemudian, ia
terpilih jadi senator.
Waktu itulah ia mengembangkan gagasannya di kalangan kecil
intelektuil Afrikaner dan para pernimpin Gereja Reformasi
Belanda -- dengan cara berhati-hati. Sebab ia tahu buah
fikirannya bertentangan dengan mayoritas orang putih di
negerinya. Dalam fikiran ini, seperti tercermin dalam buku Has
the Aftikaner a Future, yang ditulis oleh rekan dekatnya C.D.
Scholtz, masa depan bangsa Afrikaner terletak dalam pemisahan
teritorial, atau bahkan perpisahan total. Tapi ketika ide ini
dilontarkan secara terbuka di tahun 1951, dalam kongres Cereia
Reformasi Belanda, baik Malan ataupun Strijdom mengecamnya
sebagai "tidak realistis".
Namun sebagai menteri urusan bangsa pribumi sejak 1950, Verwoerd
tak tinggal diam. Tentu saja kesempatan sepenuhnya baru tercapai
ketika ia mengantikan Strijdom yang meninggal dunia September
1958. Kebijaksanaan pokok Verwoerd lahir dalam Undang-Undang
Peningkatan Swa-Tantra Bangsa Bantu di tahun 1959. Di situ orang
pribumi ditaruh dalam tujuh tempat "pemukiman kembali"
(resettlement) -- semacam cagar alam yang disebut "Bantustan".
Tapi dalam keadaan yang sudah berlangsung sejak Undang-Undang
Tanah Pribumi berlaku, wilayah pemukiman kembali itu hanya
meliputi 13% dari seluruh Afrika Selatan -- karena taulah
selebihnya dari negeri seluas 1.200.000 Km2 itu merupakan milik
si kulit putih. Maka seperti yang dilihat para pengritiknya
itulah kelemahan ide Verwoerd. Komisi Tomlinson yang dibentuk
Verwoerd sendiri di tahun 1954 sudah melaporkan, bahwa dalam
kondisi yang terbaik sekalipun "Bantustan-Bantustan" yang
diciptakan itu tak akan mampu menyerap seluruh penduduk hitam
Afrika Selatan yang ada waktu itu. Apalagi bila bertambah.
Sekarang saja jumlah orang hitam sudah 18 juta sementara orang
putih baru 4 juta.
Rencana Verwoerd praktis tak jalan. Di tahun 1960 peristiwa
berdarah di Sharpeville terjadi. Sementara itu para ketua suku
-- para pemimpin tradisionil Afrika yang posisinya hendak
dipulihkan kembali, tak selamanya bisa bekerja sesuai dengan
pesanan. Mereka tahu: ikut baris pemerintah akan menyebabkan
mereka dibenci rakyat, tapi ikut garis rakyat menyebabkan akan
dimarahi pemerintah. Di beberapa daerah ketua suku yang
menyokong partheic bahkan dibunuh penduduk. Di Transkei, yang
melaksanakan pemilihan Banlustannya yang pertama tahun 1963,
pemerintah putih terpaksa menyatakan keadaan darurat hingga
kini. Sementara itu suku Zulu baru bersedia menerima "swa
tantra" gaya Verwoerd setelah 10 tahun dibujuk. Dan
BantustanBantustan itu toh masih tetap harus tergantung kepada
ekonomi Afrika Selatan. Meskipun begitu, dengan sikap keras
kepala yang sudah merupakan cirinya, pemerintah Afrika Selatan
ternyata meneruskan konsep Bantustan itu ke Namibia . . .
1966, di parlemen, Verwoerd mati terbunuh -- dua hari sebelum
Perdana menteri itu merayakan ulang tahunnya yang ke-65.
Pembunuhnya ternyata seorang kulit putih, yang mungkin agak
sinting, dan kini disiksa dalam penjara (lihat: Kisah Dari
Penjara hal 11 ). Itu tak berarti tak ada perlawanan dari orang
hitam dan berwarna lain -- juga orang kulil putih yang progresif
-- yang sejak 1955 mendirikan gerakan bersama dalam bentuk
Congress Alliance. Bahkan meskipun para pemimpin gerakan ini
setahun kemudian sebentar ditangkapi, militansi meningkat terus.
Di tahun 1958 Pan-Africanist Congres (PAC) dibentuk, dan dalam
demonstrasinya di tahun 1960 itulah pembunuhan di Sharpeville
terjadi. PAC kemudian dinyatakan terlarang. Dengan begitu ia
mengalami nasib seperti Partai Komunis Afrika Selatan yang
dilarang 9 tahun sebelumnya -- dan juga African National
Congress (ANC) yang berdiri sejak 1917.
Maka apa alternatif lain, selain cara kekerasan? Ketika Oktober
1966 orang kulit putih pertama mati di rumahnya terbunuh oleh
gerilyawan bersenjata jelaslah bagi pemerintah Afrika Selatan
"terorisme" tak akan dapat dihindarinya. Dan ketika Balthazar
Johannes Vorster menggantikan Verwoerd, nampaknya kehidupan
negeri itu memang harus makin menjurus ke sana.
Orang yang pernah jadi menteri pendidikan, kesenian dan ilmu
Pengetahuan ini juga kemudian adalah menteri kehakiman, polisi
dan penjara. Tokoh sayap kanan yang keras ini sengaja dipilih
Verwoerd buat jabatan itu -- setelah peristiwa Sharpeville, dan
setelah Verwoerd yakin bahwa tangan besi diperlukan. Vorster
segera bertindak. Setiap penentang politik rasial pemerintah ia
bekuk. Dan ketika ia dilantik jadi perdana menteri seminggu
setelah kernatian Verwoerd, ia berkata: "Saya akan terus menurut
jalan apartheid". Orang memang mencatat bahwa ternyata ia tidak
setegar seperti yang diperkirakan semula. Tapi apa yang akan
dilakukannya setelah kerusuhan di Soweto?
Segera setelah Soweto, yang ditunjukkan pemerintah ialah apa
yang disebut orang Afrikaner sebagai Kragdadigheit atau sikap
tegas. Vorster bermaksud untuk tak memberi kesan, bahwa ia
gampang didesak-desak oleh gelombang demonstrasi. Kerusuhan yang
terjadi, menurut pemerintah, hanya karena penunggangan
sekelompok kecil agitator. Mereka tak didukung secara berarti
oleh mayoritas bangsa pribumi yang 18 juta. Kebanyakan orang
hitam, kata Menteri Kehakiman James Kruger "mendukung pemerintah
untuk apa yang dilakukannya dalam meningkatkan hidup mereka".
Perkelahian yang terjadi antar orang hitam beberapa hari setelah
itu -- ketika para buruh suku Zulu menolak dipaksa untuk mogok
oleh para pemuda militan -- memang bisa mengesankan bahwa Kruger
benar. Persatuan antar orang hitam dalam menghadapi apartheid
memang masih lemah. Tak ada pemimpin yang memang tumbuh dari
kalangan mereka sendiri: kebanyakan sudah diamankan oleh polisi
Vorster, atau melarikan diri ke negara tetangga -- atau ikut
gerakan di bawah tanah. Pemimpin yang ada adalah pemimpin yang
hanya dapat restu dari atas.
Keadaan itu menyulitkan pemerintah Vorster juga. Dengan siapa,
dari kalangan kulit hitam, penguasa kini dapat berkomunikasi,
bila diperlukan? Pendapat umum di Afrika Selatan selalu mendesak
agar ada konsultasi tetap antara orang putih dengan orang hitam.
Dan Menteri Pendidikan untuk Orang Pribumi, Michiel C. Botha,
memang terpaksa bertemu dengan para pemimpin kulit hitam untuk
berdialog, setelah terjadinya kerusuhan. Tapi yang ditemuinya
hanyalah para tokoh masyarakat hitam setempat, yang terdiri dari
orang bisnis -- di antara yang 1% dari penduduk hitam yang kaya
di Soweto -- yang bahkan tak punya status sebagai dewan
perwakilan kota. Dengan dipotongnya kegiatan politik rakyat
kulit hitam, proses politik yang perlu untuk kehidupan bersama
pun terpotong juga. Mentalitas laager dari penguasa yang serba
curiga seperti menderita paranoia itu memang sudah parah benar.
Dan itu tak akan tertolong oleh keadaan. "Kita tahu bahwa
kejadian seperti ini tetap akan ada bersama kita bertahun-tahun
yang akan datang", kata Sir de Viliers Graaff, pemimpin partai
oposisi United Party setelah peristiwa Soweto.
Tak pelak lagi. Tapi mungkin kelak bisa tambah parah. Di negeri
tetangga mereka, Anggota pemerintahan Presiden Neto makin
berkonsolidasi -- dan mudah diperkirakan kekuatan Marxis yang
dibantu Soviet ini tak akan bersikap lunak kepada Afrika
Selatan. Apalagi Vorster pernah mengirim tentaranya membantu
pihak yang melawan Net dalam perang saudara yang baru lalu. Di
Mozambique, pemerintahan Frelimo kian terang-terangan dikagumi
para pemuda hitam yang tergabung dalam SASO (himpunan pelajar
kulit hitam). Dan tak kurang penting ialah perkembangan di
Namibia. Daerah yang harus berakhir minggu ini sebagai daerah
mandat yang dipegang Afrika Selatan itu merupakan calon ajang
perang gerilya SWAPO, yang menganggap "kemerdekaan" pemberian
orster sebagai kedok terusnya apartheid.
Your future is with Vorster. Masa depan anda bersama Vorster.
Begitu tulis poster pemilu di Afrika Selatan yang lalu. Mungkin
-- tapi setidaknya hari depan putih itu akan terus terkepung di
benua hitam. Apartheid bisa bertahan dengan kekuatan senjata,
mungkin nanti juga senjata nuklir. Tapi hidup dengan selalu siap
tempur pada akhirnya merusak diri sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini