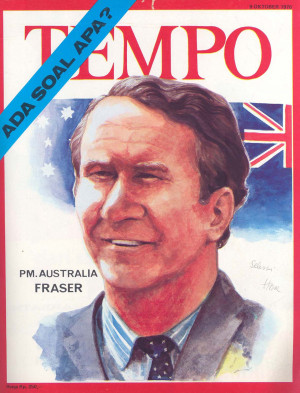Beberapa waktu yang lalu Goenawan Mohamad dari TEMPO mergadakan
perjalaran di Australia Berikut ini adalah dari
catatan-catatanya yang baru kali ini sempat diterbitkan:
LANSKAP AUSTRALIA
Lanskap Australia punya keindahan yang tak acuh. Seperti kebun
karang. Tidak permai, kekar, tanpa puspa ragam. Warna hijau cuma
redup, diselingi kulit pohon yang terkadang putih. Atau daun
kuning -- mungkin weeping willows -- yang terjurai.
Karang-karang, memberi aksen purba kepada bukit-bukit.
Dan bukit-bukit itu, sangat bersahaja, seakan-akan tak
habis-habisnya.
Seseorang yang terbiasa dengan kesesakan pulau Jawa akan segera
merasakan satu kesan kuat di sini: ruang yang berlebih-lebihan.
Atau keharusan mengakui jarak. "Jarak merupakan ciri Australia",
tulis sejarawan Geoffrey Blainey dalam The Tyrarny of Disance,
"sebagaimana gunung-gunung merupakan ciri Switzerland". Jika
anda tak percaya bagaimana besarnya ukuran negeri ini, bacalah
ensiklopedi. Orang Australia percaya itu.
Di sebuah jamuan di Canberra seorang penyair yang mengajar pada
universitas di sini heran, waktu ia mendengar dari seorang
diplomat (yang pernah tinggal di Amerika Latin) bahwa ternyata
Brazilia lebih luas ketimbang Australia. "Mana mungkin?", seru
seorang gadis yang ikut mendengarkan.
MAKANAN AUSTRALIA
Menjadi tamu lebih banyak enaknya daripada menjadi tuan rumah,
kadang-kadang. Di jamuan makan di rumah seorang peternak di
Adelong -- sebuah daerah peternakan yang terpencil di pelosok
New South Wales -- seorang tamu asing yang kurus disodori
potongan daging yang besar. "Ukuran steak anda sebanding dengan
besarnya negeri anda"katanya sopan. "Tolong berilah saya daging
yang sebanding dengan besarnya negeri saya". Dia orang Belgia.
Selama di Australia, saya tak tahu apakah saya telah mencicipi
makanan Australia atau belum. Yang jelas saya makan makanan
Indonesia, Vietnam, barangkali Yunani dan yang pasti Cina dan
Spanyol. Saya tak berani bertanya dan meminta la specialite de
la maison di sini. Sebab ada kemungkinan bahwa itu tak enak.
Saya ingat cerita Bung Karno yang mengernyitkan muka waktu
terpaksa mencicipi air susu kuda di Mongolia.
Menanyakan makanan khas Australia barangkali juga sama halnya
dengan menanyakan "kebudayaan Australia". Dan itu tak mudah buat
dijawab. Soal ini di Indonesia juga berat dan mungkin tak perlu.
Tapi di sebuah diskusi informil di Melbourne ada pertanyaan yang
menarik: Akankah kebudayaan Australia kelak terus merupakan
kebudayaan yang bertopang pada tradisi Anglo-Saxon, sesuai
dengan klas yang berada di atas? Sejauh mana para pendukung
tradisi itu mau memperkenankan pluralisme dalam kebudayaan,
dengan makin banyaknya para imigran dari Yunani, Italia, Asia
Tenggara, orang-orang Jepang, Tionghwa dan lain-lain?
Di Adelaide sebuah sekolah swasta yang tua dan terkemuka
memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran
yang bisa dipilih untuk diikuti. Itu hasil permintaan para orang
tua murid. Tapi kepala sekolahnya yang sudah tua, yang datang
dari Inggeris, dengan sikap angker dan keyakinan yang tak minta
didebat berkata, kira-kira: "Sebenarnya di samping Inggeris para
murid harus belajar bahasa Jerman dan Perancis -- sebab
Barat-lah sumber mereka". Waktu itu saya menanyakan apakah kini
anak Australia lebih banyak belajar bahasa Jepang. "Of course,
the Japs would like it, but. . ", jawabnya.
DASI DI AUSTRALIA
Satu kalimat dari sebuah lakon Oscar Wilde: "George tidak perlu
dasi. Dia 'kan mau pergi ke Australia".
Kolumnis Ross Campbell dalam The Bulletin pertengahan Juni itu
memulai tulisannya dengan suatu sinyalemen genting tentang wajah
Australia dewasa ini: "Ketegangan makin bertumbuh antara dua
fihak -- orang yang memakai dasi dan mereka yang tidak".
Menyedihkan, bagi Campbell, bahwa yang tidak pakai dasi
nampaknya makin bertahan maju. Mereka ini menguasai dunia
show-biz dan radio, dan di bagian-bagian penting bidang
periklanan serta TV. Bahkan mulai memasuki pers. Dalam suatu
resepsi di sebuah galeri seni rupa, seorang wanita berbisik
kepada Campbell: "Tahukah kau bahwa cuma kau yang pakai dasi di
antara hadirin di sini?". Campbell hampir saja memutuskan masuk
ke kamar kecil dan mencopot dasinya.
Dari Brisbane (setelah jamuan santai dengan orang-orang
universitas yang tak berdasi), saya harus terbang ke Sydney.
Acara: langsung setelah tiba, makan malam dengan Dr. Jean
Battersby, wanita pertama dalam badan eksekutif dari Dewan
Kesenian Australia. Dari sana ke Gedung Opera Sydney yang
tersohor itu, untuk nonton pertunjukan perdana sebuah opera.
"Harap pakai black-tie", begitu diberitahukan oleh pengantar
saya di atas pesawat. "Anda punya?", tanyanya, agak cemas. Ya,
jawab saya, saya punya dasi warna hitam. Saya tunjukkan dasi
yang saya simpan di saku jas. "Bukan itu", jawab si pengantar.
Kemudian saya tahu bahwa yang dimaksud ialah dasi kupu-kupu
berwarna hitam, yang dipakai dengan baju putih berenda, dan jas
khusus. Saya belum pernah memakainya seumur hidup, dan malam itu
saya juga tak memakainya. Selama nonton opera (yang tak saya
ingat judulnya), saya teringat Oscar Wilde . . .
SYDNEY NOLAN
Kata seorang sarjana Indonesia yang pernah tinggal di AS dan
kini mengajar di Australia: "Di AS terasa adanya kreatifitas
setiap kali, selalu ada gairah kepada yang baru. Di Australia,
tidak". Kata seorang kenalan lain: "Orang Australia suka merasa
'kurang berbudaya' dan berusaha keras mengejar 'ketertinggalan'
mereka dengan berlebihan -- misalnya lihat saja Gedung Opera
Sydney".
Tapi di Lanyon, di sebuah rumah kuno agak di luar Canberra,
terhimpun lebih dari 20 karya Sydney Nolan. Pelukis ini, kini
hampir 60 tahun, memang tinggal di London. Tapi mungkin ia bisa
lebih jelas ketimbang novelis Patrick White, yang mendapat
Hadiah Nobel, untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut
"ketertinggalan" Australia itu hanyalah bayangan dari "tirani
jarak jauh" yang ditanggungkan negeri ini.
Nolan bagi saya adalah seorang pelukis utama di dunia sekarang,
salah satu pertanda betapa pentingnya Australia dalam seni rupa
kini. Kenyataan ini biasanya tak diakui, karena tak dikenal. Di
Indonesia, bekas koloni Belanda, orang terus-menerus hanya
terpesona oleh Van Gogh sampai dengan Karl Appel. Tapi Appel
rasanya cuma mewakili semangat Eropa yang lagi pegal-pegal, dan
Van Gogh merupakan ikhtiar yang mengharukan, dari seorang yang
terdesak untuk menangkap apa yang berharga dari dunia yang tanpa
humor. Nolan sebaliknya bisa bermain-main, melucu, sendiri
dengan mithosnya yang sederhana tentang penjahat Ned Kelly tokoh
cerita rakyat Australia yang sebenarnya tak luar biasa itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini