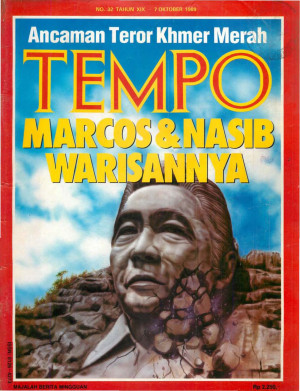DITH Pran adalah kesengsaraan, kesengsaraan Kamboja. Orang Kamboja yang bekerja sebagai pembantu koresponden asing -- Sydney Schanberg, yang menulis untuk harian The New York Times -- kemudian jadi penghuni kamp selama pemerintahan Pol Pot (1975-1978). Kisahnya di jadikan film The Killing Fields, 1985, dan menambah keyakinan dunia terhadap kekejaman Khmer Merah. Akhirnya Dith Pran, lewat Muangthai, hijrah ke AS. Kini ia bekerja sebagai juru potret di The New York Times. Agustus lalu ia, 47 tahun, mengunjungi tanah airnya, bekas "Ladang Pembantaian", bersama tujuh anggota Cambodia Documentation Commission, sebuah organisasi hak asasi, atas undangan Perdana Menteri Hun Sen. Berikut cuplikan laporannya yang diterbitkan dalam The New York Times Magazine, 24 September. SEPULUH tahun di Amerika, saya masih tetap mempunyai mimpi yang sama: menjadi budak di kamp pekerja Dam Dek. Dalam mimpi itu sekali lagi saya menjadi penghuni kamp bikinan Pol Pot itu, menyaksikan rekan-rekan saya dihajar cambuk. Saya mengenakan piyama hitam-hitam, bertelanjang kaki, bekerja di sawah, di bawah sengatan panas matahari dan hujan lebat. Saya disiksa, sementara yang lain dikumpulkan dengan tangan terikat, untuk dibawa keluar kamp dan dibunuh. Saya sering omong sendiri ketika tidur kadang-kadang menangis, dan ketika istri saya membangunkan saya, saya masih terus menangis. Baru setelah sadar, saya yakin bahwa saya berada di Brooklyn, bukan tidur di Dam Dek. Saya marah, lalu mengutuk Khmer Merah. Pagi yang cerah, 17 Agustus yang lalu, dengan pesawat Vietnam carteran, saya mendarat di pelabuhan udara Pochentong, Phnom Penh. Terakhir kali saya lihat pelabuhan udara ini April 1975, ketika pasukan Amerika mundur kocar-kacir di tengah gempuran roket Khmer Merah. Kembali ke Kamboja adalah kerinduan saya bertahun-tahun. Saya ingin bertemu adik perempuan saya, satu-satunya saudara kandung yang masih hidup, dan ziarah di kuburan orangtua dan sanak famili. Ibu saya meninggal dua tahun lalu. Ayah, seorang pegawai pemerintah, mati kelaparan ketika Pol Pot berkuasa. Tiga saudara laki-laki saya (dua orang menjadi tentara Lon Nol, satu menjadi mahasiswa), dan seorang saudara perempuan, semuanya dibunuh Khmer Merah. Saya ingin melihat Kamboja sebelum pasukan Vietnam ditarik mundur. Karena saya khawatir, kesempatan itu tak ada lagi. Saya takut perang saudara segera pecah, begitu Vietnam pulang. Di bandar udara saya disambut dengan karangan bunga. Juga sudah menanti Sydney Schanberg. Dulu, sayalah yang biasanya berdiri di pelabuhan udara, menunggu Sydney yang posnya berada di Singapura. "Saya kehilangan waktu hampir satu hari gara-gara kamu," sambut Sydney. "Saya dulu juga menunggu kamu. Masih ingat?" jawab saya. Saya dulu asisten Sydney, selama dua tahun, 1973-1975. Ketika ia bekerja untuk harian The New York Times. Sekarang dia kolumnis untuk Newsday, dan berada di Phnom Penh untuk pertunjukan perdana film The Killing Fields. Dalam perjalanan menuju Monorom Hotel, tempat saya menginap, saya melalui jalan yang dulu bernama Kampuchea Krom (Kamboja bagian bawah). Istilah ini untuk mengingatkan bahwa bagian tenggara kerajaan Khmer beberapa abad lalu dijajah Vietnam. Nama itu memang dimaksudkan untuk mengajar orang-orang Kamboja membenci Vietnam. Kepada generasi saya ketika di bangku sekolah, diajarkan bahwa nenek-moyang kami yang kalah bertempur, mati dalam siksaan orang-orang Vietnam. Mayoritas orang-orang Kamboja tetap tak pernah percaya kepada orang Vietnam, walaupun mereka sadar telah dibantu Vietnam menyingkirkan Khmer Merah, yang telah membunuh penduduk lebih dari satu juta orang. Di bawah pemerintahan yang sekarang, nama jalan itu diubah menjadi Kampuchea Vietnam. Setiap pagi, restoran di pinggir jalan selalu penuh dengan pembeli. Saya heran juga bahwa di jalan-jalan dan tempat umum seperti itu cuma terdapat beberapa tentara, itu pun tanpa senjata. Di zaman rezim Lon Nol yang didukung Amerika, tentara berkeliaran di tempat umum dengan peluru terlilit di bahunya, dan granat bergantungan di pinggang. Di pasar Thom Thmey (pasar bebas) terpancang papan pengumuman: dilarang membawa sepeda, motor, bahan peledak, senjata panian atau pendek ke dalam pasar. Kehidupan tampaknya normal. Pasar sibuk, dan toko-toko tetap milik pribadi. Di zaman Pol Pot, hanya sedikit beras dijual kepada penduduk. Tujuannya, agar kami menjadi lemah sehingga tak cukup kuat untuk melawannya. Padahal, saya percaya, persediaan beras waktu itu banyak. Sekarang toko-toko makanan dipenuhi beras dan makanan segar. Juga terdapat barang selundupan seperti sabun, kosmetik, baju, makanan kaleng dari Muangthai dan Singapura. Di timur pasar ada sebuah taman, yang di masa Pangeran Norodom Sihanouk berkuasa, 1960-an, ditanami mangga. Ketika Pol Pot datang, mangga ditebangi dan taman dijadikan kebun kelapa, dengan pupuk mayat dan darah rakyat yang dibunuhnya. Rezim yang sekarang mengubah kebun kelapa itu menjadi taman lagi. Phnom Penh masih kekurangan listrik. Air ledeng berkurang terutama pada musim kemarau. Sanitasi buruk, selokan pembuangan air macet, di musim hujan banjir. Dulu hal itu tak pernah terjadi. Pasar gelap bahan bakar mobil kembali muncul. Pelacuran juga. Sauk, atau suap, merajalela. Di kota-kota, polisi terbiasa dengan sauk. Penduduk kelihatan miskin, meski lingkungan tetap hijau dan pasar penuh dengan barang serta makanan. Keterisolasian Kamboja -- hanya diakui oleh Vietnam, Laos, India, dan blok Soviet -- mengakibatkan kayu, karet, beras, dan ikan laut tak bisa diekspor ke lebih banyak negara. Turisme, yang sebelum perang menjadi sumber pendapatan negara paling besar, dan macet di zaman Khmer Merah, kini mulai bangkit perlahan-lahan. Saya mencoba jalan-jalan sendiri, menegur sapa orang-orang, dan tak seorang pun mengusut saya. Saya merasa seperti tidak di negeri komunis. Bagi kebanyakan orang Kamboja, nampaknya tak soal apakah mereka diperintah Lon Nol atau Hun Sen (tetapi Pol Pot soal lain, tak seorang pun kepingin dia kembali). Yang mereka khawatirkan adalah perang yang mau tak mau akan melibatkan anak-anak mereka. Mereka cemburu kepada polisi yang memperoleh pendapatan ekstra dari sauk. Mereka mengkritik pejabat pemerintah yang hidup dengan hak-hak istimewa dan mengirim anakanaknya belajar ke luar negeri. "Anak orang miskin menjadi tentara. Anak orang kaya menjadi polisi. Anak pejabat dan partai sekolah di luar negeri," kritik itulah yang saya dengar. Sabtu subuh saya pergi ke Wat Lanka, salah satu kuil terbesar di Phnom Penh. Dulu di sini ada 500 pendeta, kini tinggal 15. Khmer Merah melarang segala macam upacara agama. Tahun ini pemerintahan Hun Sen menyatakan Budhisme sebagai agama negara lagi. Masjid-masjid juga dibolehkan kembali dipakai para muslimin dan muslimat. Tapi gereja masih tetap ditutup. Sekitar pukul 08.00 kami terbang ke Siem Reap, tempat saya lahir dan dibesarkan, 225 km barat daya Phnom Penh. Kami berhenti dekat ladang pembantaian, yang terakhir saya lihat di awal 1979, ketika tentara Vietnam memerintahkan orang-orang Khmer menggali tulang-tulang tengkorak yang dikubur di parit-parit. Kami mengunjungi sebuah rumah, bekas pos tentara yang dibiarkan apa adanya. Rumah tanpa jendela dan pintu yang dibiarkan dimakan hujan dan angin itu, yang dinding-dindingnya bolong karena peluru, ternyata masih menyimpan sejumlah tulang-belulang dan tengkorak. Untuk pertama kali sejak tiba di Kamboja, saya betul-betul terguncang. Di kawasan inilah famili, kawan, dan tetangga tinggal. Saya tahu, Ayah mati karena kelaparan, tapi saya tak tahu bagaimana dan kapan saudara-saudara saya dibunuh. Saya duga mereka dibunuh di sekitar sini. Lama saya mencoba menguasai perasaan, dan menyentuh beberapa tulang tengkorak. Siangnya saya pergi ke rumah saudara perempuan saya. Bis berhenti kira-kira 100 meter dari rumah kami, tempat Sam Proeuth, saudara perempuan saya yang 12 tahun lebih muda dari saya, tinggal. Saya keluar dari mobil dan memberi salam kepada tetangga yang masih saya kenal. Saya lihat adik perempuan saya berlari menyongsong . Kami berpelukan, lama sekali. Kami menangis melepas rindu. Adik saya kelihat an pucat, nampak tidak sehat. Terakhir kali saya lihat dia, ketika ia dibebaskan dari kamp 30 km dari Dam Dek. Waktu itu kami sama-sama hampir tak bisa mengenal, karena kami berdua begitu kurus dalam baju tua dan kaki telanjang. Saya kehilangan hampir semua gigi, karena buruknya makanan sementara kaki penuh dengan infeksi karena banyak berjalan di tanah penuh berisi rabuk tahi binatang. Ketika di kamp kami terkena malaria Proeuth menderita lebih lama. Dia sempat melihat adik perempuan dan Ayah mati kelaparan, serta adik laki-laki termuda diambil Khmer Merah. Sampai kini ia menderita trauma. Diantar oleh sanak famili saya naik ke rumah orangtua, menemui Meak Oth, satu-satunya bibi dari Ibu. Kami kemudian berziarah ke tempat abu jenazah keluarga disimpan. Tiba saatnya kami diterima PM Hun Sen di kantornya. Di pintu ruang konperensi, Hun Sen sudah menunggu. Saya membungkuk sambil merapatkan tangan. Dia melakukan hal yang sama. Di sudut ruangan wartawan nasional dan internasional dari surat kabar maupun radio dan televisi siap mengabadikan pertemuan ini. Hun Sen tahu persis kekuatan berita dan pentingnya foto peristiwa ini. Ia menyilakan kami duduk. Kami saling memanggil dengan sebutan bang, sebutan untuk orang yang lebih tua. Saya, sebagai juru bicara delegasi, meminta komentar dia tentang persoalan hak asasi. Ia berbicara dengan sangat ramah dan menjawab dengan menyenangkan. Walaupun tak pernah tamat SMA, Hun Sen terkesan sangat berpendidikan. Soal hak asasi erat kaitannya dengan Khmer Merah, kata Hun Sen. "Ini permintaan kami sejak dulu, kita harus mencegah kembalinya rezim Pol Pot. Tanpa menerima ini, penindasan akan terus berlangsung." Ia mengkritik Sihanouk dan Son Sann, yang memisahkan persoalan hak asasi dan Khmer Merah. Dalam pembicaraan 90 menit itu, saya terkesan oleh kepiawaiannya dalam politik. Terakhir ia mengatakan, lima orang Kamboja dari rombongan kami yang sudah jadi warga negara AS, kalau mau, bisa memperoleh paspor Kamboja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini