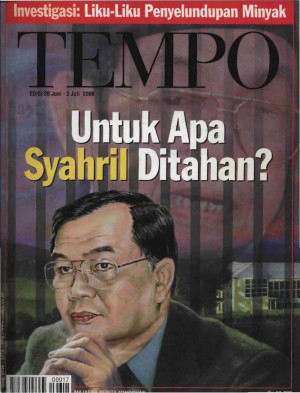Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tokyo basah oleh hujan. Tetapi rintik-rintik itu tak menghalangi penduduk metropolitan itu keluar rumah, pada Minggu dua pekan lalu. Memang, penanggalan nasional Jepang pada hari itu adalah hari pemilihan umum untuk anggota majelis rendah, Diet. Tapi ternyata warga Tokyo—paling tidak yang terlihat hari itu—terutama perempuan yang berdandan warna-warni itu, tidak mendatangi bilik-bilik suara, melainkan menyerbu toko-toko di Shinjuku, yang menawarkan diskon akhir musim panas. ”Saya tidak peduli dengan kegiatan politik,” kata Miho Kawakami, seorang karyawati perusahaan jasa perjalanan wisata.
Sementara itu, hasil pemilu menunjukkan bahwa perwakilan kaum perempuan di Diet meningkat, yaitu dari 23 menjadi 35 kursi. Di antara pemenangnya terselip seorang kandidat termuda, yang menjadi anggota parlemen pertama perempuan dari Okinawa. Ada juga dua gubernur perempuan pertama di Osaka dan Kumamoto. Tak ketinggalan, Yuko Obuchi, 26 tahun, anak mendiang Perdana Menteri Keizo Obuchi, yang juga ikut menjadi kandidat dari Partai Liberal Demokrat (LDP).
Pentingkah peran perempuan Jepang dalam proses politik? Bukankah sudah diketahui umum, secara kultural perempuan Jepang diperlakukan diskriminatif?
Memang, kandidat perempuan yang mengikuti pemilu kali ini mencapai jumlah terbesar dalam sejarah Jepang, yaitu di atas 200 kandidat. Tapi, menurut catatan Serikat Inter-Parlemen, perwakilan perempuan Jepang di parlemen, di antara negara-negara maju, termasuk yang terendah. ”Saya kira masa kejayaan perempuan di Jepang belum tiba,” kata Miwako Yuasa dari lembaga swadaya masyarakat Citizen Network.
Menurut Yuasa, sistem pemilu itulah yang merugikan perolehan kursi untuk kandidat. Sistem yang memadukan sistem kursi tunggal di distrik dengan perwakilan proporsional itu mengakibatkan pilihan pemilih terpecah. Sebab, mereka diharuskan membuat dua pilihan, yaitu untuk kandidat yang bersangkutan dan untuk partai. Yoko Hara, anggota parlemen termuda yang berusia 25 tahun, misalnya, kalah pada sistem kursi tunggal tapi berhasil masuk dalam perwakilan proporsional partai.
Artinya, pemilih Jepang masih enggan memilih kandidat perempuan secara personal. Kalaupun mereka masuk dalam parlemen, hal itu disebabkan oleh partainya. ”Pokoknya, jika kandidat perempuan itu tak terkenal, memiliki organisasi yang mendukung dan memiliki sumber dana yang besar, jangan harap bisa terpilih dalam single seat,” kata Yuasa.
Kurangnya preferensi pemilih terhadap kandidat perempuan bisa disebabkan oleh perjuangan kandidat perempuan yang kurang gigih. Yuko Obuchi, misalnya, sama sekali tidak mengampanyekan program yang jelas. Bahkan Yuko, yang lulusan Universitas Seijo, Tokyo, walaupun sudah rela berkeliling desa untuk kampanye, yang diucapkannya hanyalah kata pujian atas kebaikan almarhum ayahnya.
Greget pertempuran kandidat perempuan dalam pemilu kali ini memang jauh berbeda dengan periode Takako Doi dari Partai Sosialis Jepang (PSJ) pada pemilu 1989. Pada saat itu, Doi mengampanyekan penurunan pajak konsumsi, yang terutama membebani ibu-ibu rumah tangga. Doi juga menyerang skandal seks yang dilakukan oleh bekas perdana menteri Sosuke Uno, hingga Uno mengundurkan diri. Alhasil, PSJ bisa menghasilkan kursi oposisi terbanyak sepanjang sejarah, walaupun masih jauh dari perolehan LDP. Bahkan saat itu Doi berhasil memompa semangat perempuan agar terlibat dalam pembuatan kebijakan politik.
Tampaknya, masa kejayaan Doi sudah berlalu. Pada pemilu kali ini, Doi juga tak berhasil mengulangi pukulan telak ke LDP. Isu-isu yang ditawarkan oleh kandidat perempuan lainnya juga tak berhasil memompa semangat bersatunya ”suara dari dapur”. Padahal, sesungguhnya, isu yang beredar seperti pembenahan hukum untuk kejahatan remaja, pajak konsumsi dan insentif kesejahteraan sosial, bisa diwakili dengan baik oleh kandidat perempuan.
Semua persoalan itu masih ditambah dengan posisi perempuan di Jepang yang relatif kurang menguntungkan. Masih ada lelaki yang memperkenalkan istrinya sebagai kanai (orang di dalam rumah) atau gusai (istri yang bodoh). Tampaknya, memang masa Ratu Himik—penguasa Jepang menurut legenda—belum kembali di Negeri Matahari Terbit itu.
Bina Bektiati (Jakarta) dan L.N. Idayanie (Tokyo)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo