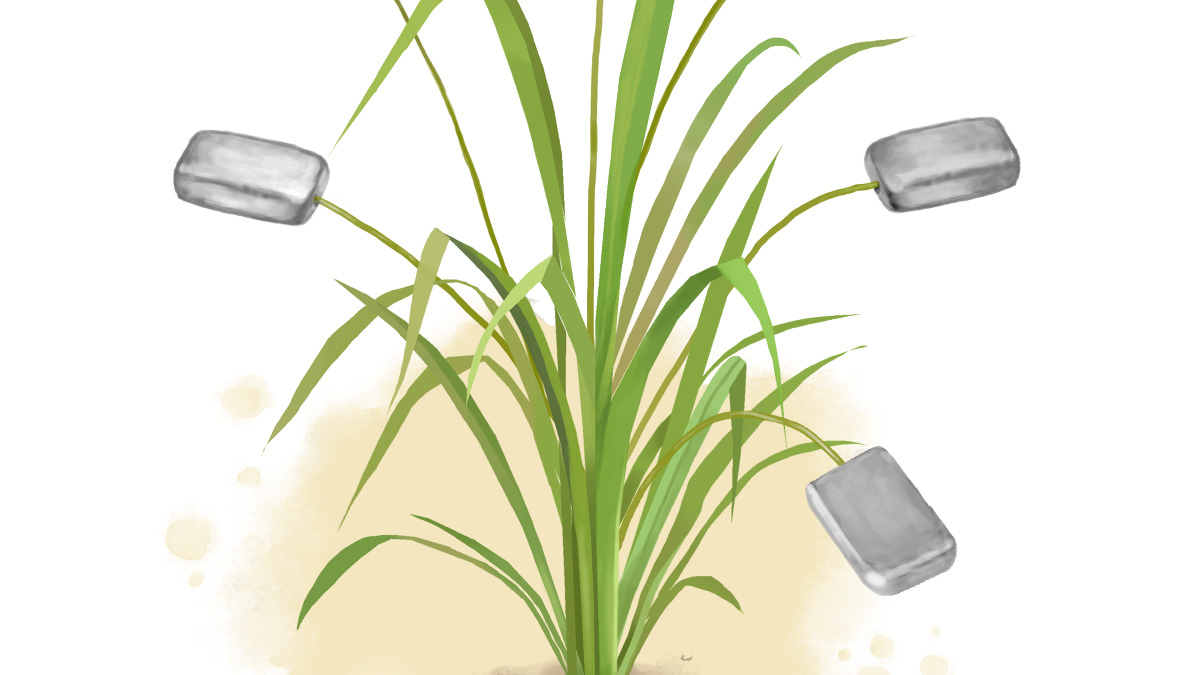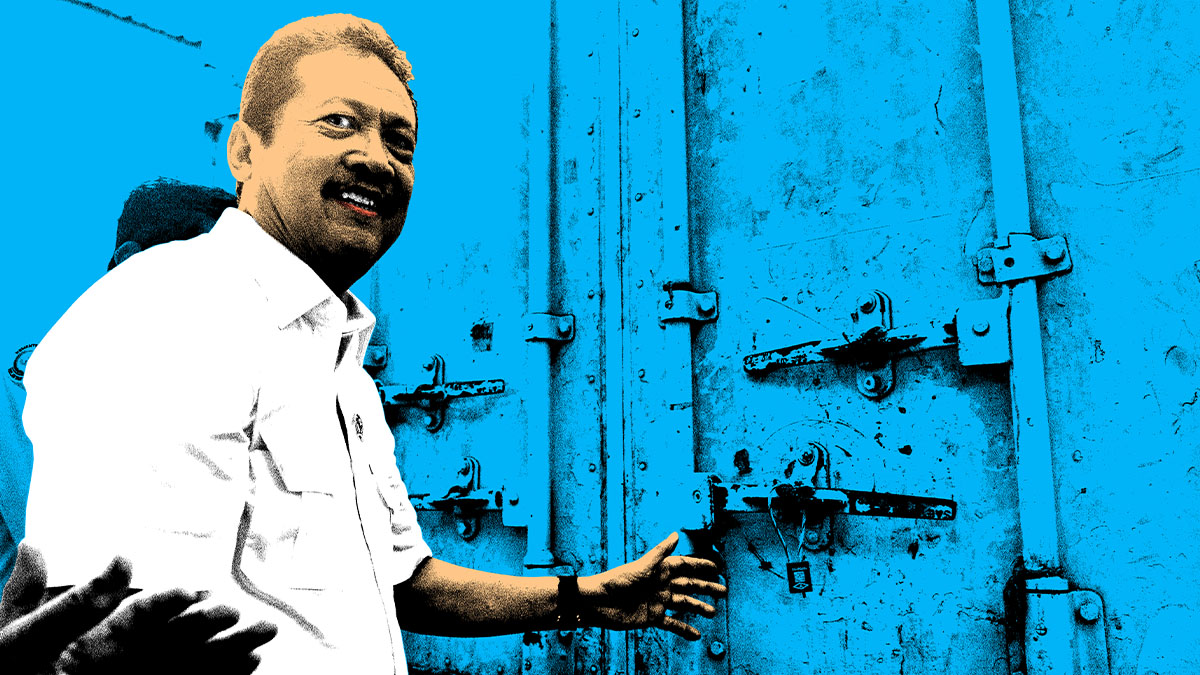Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, mengubah kehidupan nelayan.
Perusahaan diduga membuang limbah cair yang membuat air laut keruh dan berlumpur.
Aktivitas pabrik smelter memicu polusi udara dan infeksi saluran pernapasan.
KEHIDUPAN Daud Upin dan Rianti berubah drastis sejak kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah. Pesanggrahan Daud dan Rianti yang tak jembar berjarak sekitar 2 kilometer dari fasilitas smelter nikel di kawasan IMIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Pasangan suami-istri yang tinggal di Dusun Kurisa, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, itu kini menggantungkan periuknya pada limbah besi yang dibuang perusahaan pengolah nikel ke laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Daud, 55 tahun, sebelumnya mencari nafkah sebagai nelayan. Pesisir Bahodopi dulu merupakan laut biru yang elok tak tepermanai. Namun aktivitas pabrik smelter nikel yang membuang limbah ke laut membuat air keruh dan berlumpur. Karena itu, tak ada lagi ikan yang bersarang di terumbu. “Ikan susah sekali ditangkap,” katanya di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, Rabu, 19 Februari 2025.
Menurut Daud, dia sudah lama tak melaut. Alasannya, nelayan mesti menempuh perjalanan lebih jauh sampai ke tengah laut untuk mendapatkan ikan. Perjalanan itu membuat nelayan seperti Daud harus menambah solar untuk perahunya. Itu pun belum tentu ia pulang dengan muatan penuh ikan karena sedimen di dasar laut sudah tercemar lumpur.
Untuk mencari nafkah buat keluarganya, Daud dan Rianti yang hidup dengan enam anaknya kini mengumpulkan limbah besi bekas milik perusahaan. Besi-besi itu dibuang perusahaan ke laut. Daud dan Rianti biasanya menggunakan perahu ketintingnya untuk berburu besi rongsok di laut.
Di teras rumah mereka, ada dua gerobak dorong yang besinya berkarat. Daud baru saja mengangkatnya dari pesisir Bahodopi. Besi itu akan dilego ke pengepul. Jika rezeki mereka sedang bagus, pengepul bisa memberi Rp 100 ribu untuk setiap besi bekas yang dikumpulkan Daud dan Rianti. “Uangnya bisa untuk makan sehari-hari,” ujar Rianti.
Sebagaimana menjadi nelayan, pekerjaan Daud memulung besi di laut tak selalu mulus. Petugas keamanan perusahaan smelter kerap melarangnya mengambil besi di laut. Daud bercerita, dia pernah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Bahodopi karena kegiatannya mengumpulkan barang rongsok milik perusahaan. Polisi pernah menahannya lima hari. “Namun dilepaskan dengan alasan kemanusiaan,” tuturnya.
Nasib malang juga dialami Yusman, 57 tahun. Nelayan asal Desa Fatufia itu kesulitan menangkap ikan belakangan ini. Padahal ikan di pesisir Bahodopi dulu sungguh berlimpah. Yusman pernah punya keramba untuk menampung beragam jenis hasil laut, di antaranya ikan kerapu dan sotong. “Tangkapan sekarang minim sekali,” ucapnya.
Sejak smelter nikel hadir, sumber air bersih bagi warga pun tercemar. Debu batu bara dari cerobong pembangkit listrik tenaga batu bara beterbangan ke permukiman. Yusman dan tetangganya mesti berlangganan air kemasan untuk kebutuhan minum dan memasak.
Keluhan lain adalah soal pembuangan air bahang dari pabrik pengolahan mineral. Air bahang ini merupakan limbah cair yang mengandung hawa panas. Menurut Yusman, air laut ikut-ikutan menjadi panas karena bercampur dengan air bahang. Padahal warga pesisir, khususnya anak-anak, gemar berenang ketika matahari terik. “Airnya sekarang panas,” kata Yusman.
Centre for Research on Energy and Clean Air berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies menggelar riset berjudul "Membantah Mitos Nilai Tambah dan Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel" pada Februari 2024.
Dalam penelitian itu, tim memproyeksikan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar Rp 3,64 triliun dalam 15 tahun mendatang jika industri nikel terus beroperasi. Mereka meriset tiga kawasan utama pengolahan nikel, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kerugian itu disebabkan oleh ekosistem yang rusak, termasuk kawasan perairan.
Di sekitar pabrik smelter IMIP, masyarakat juga mengeluhkan polusi udara dari abu dan asap yang dikeluarkan pembangkit listrik batu bara. Hayati, warga Desa Fatufia, mengeluhkan kualitas udara yang terus memburuk. “Beberapa kali saya sesak napas karena debu yang terbang ke permukiman,” ujar perempuan 47 tahun itu.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut mencapai 80.713 kasus. Angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Bahodopi yang menjadi lokasi berdirinya kawasan IMIP dengan 66 ribuan kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Ashar M. Ma'ruf mengatakan jumlah kasus infeksi pernapasan meningkat setelah adanya aktivitas industri pengolahan nikel. “Kasusnya terjadi pada penduduk di rentang usia 9-60 tahun,” ucapnya.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali itu sejalan dengan riset Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia—organisasi yang meneliti kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam—yang dirilis pada Agustus 2024. Berdasarkan riset berjudul "Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10, PM2.5, dan SO2 pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur, dan Labota", tim menemukan sedikitnya 55 ribu kasus infeksi pernapasan. Jumlah itu termasuk 438 kasus pneumonia atau radang paru-paru pada balita.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Sunardi Katili menyebutkan tiga faktor yang merusak lingkungan di Kabupaten Morowali. Pertama, pembangkit listrik batu bara. Kedua, pengoperasian smelter nikel. Ketiga, jetty atau dermaga khusus untuk bongkar-muat batu bara. “Daya rusak lingkungannya sangat besar,” tutur Sunardi.
Dimintai tanggapan mengenai berbagai kerusakan lingkungan akibat pengolahan nikel di kawasan IMIP, Head of Media Relations Department IMIP Dedy Kurniawan mengirim jawaban tertulis pada Kamis, 6 Februari 2025. Dedy menyebutkan perusahaannya mengantongi izin pembuangan limbah cair ke laut.
Izin itu dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 103/1/KLHK/2021. Menurut Dedy, baku mutu air bahang yang dapat dibuang ke laut mesti memiliki temperatur di bawah 40 derajat Celsius. “Suhu air bahang IMIP sekitar 33,2 derajat Celsius,” ujarnya.
IMIP, kata Dedy, juga tak melarang warga mengambil limbah besi di laut. Perusahaan hanya mencegah warga masuk ke area pembangunan dua jetty yang masih dalam tahap konstruksi. Menurut dia, perusahaan bahkan menyediakan zona khusus yang dapat dilalui nelayan.
Ihwal pencemaran udara, Dedy mengklaim IMIP telah memakai teknologi untuk menekan emisi dari aktivitas smelter. Perusahaan memantau kualitas udara secara berkala dan berupaya melakukan transisi energi dengan mengurangi penggunaan batu bara. “Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya sudah mulai berjalan,” katanya. ●