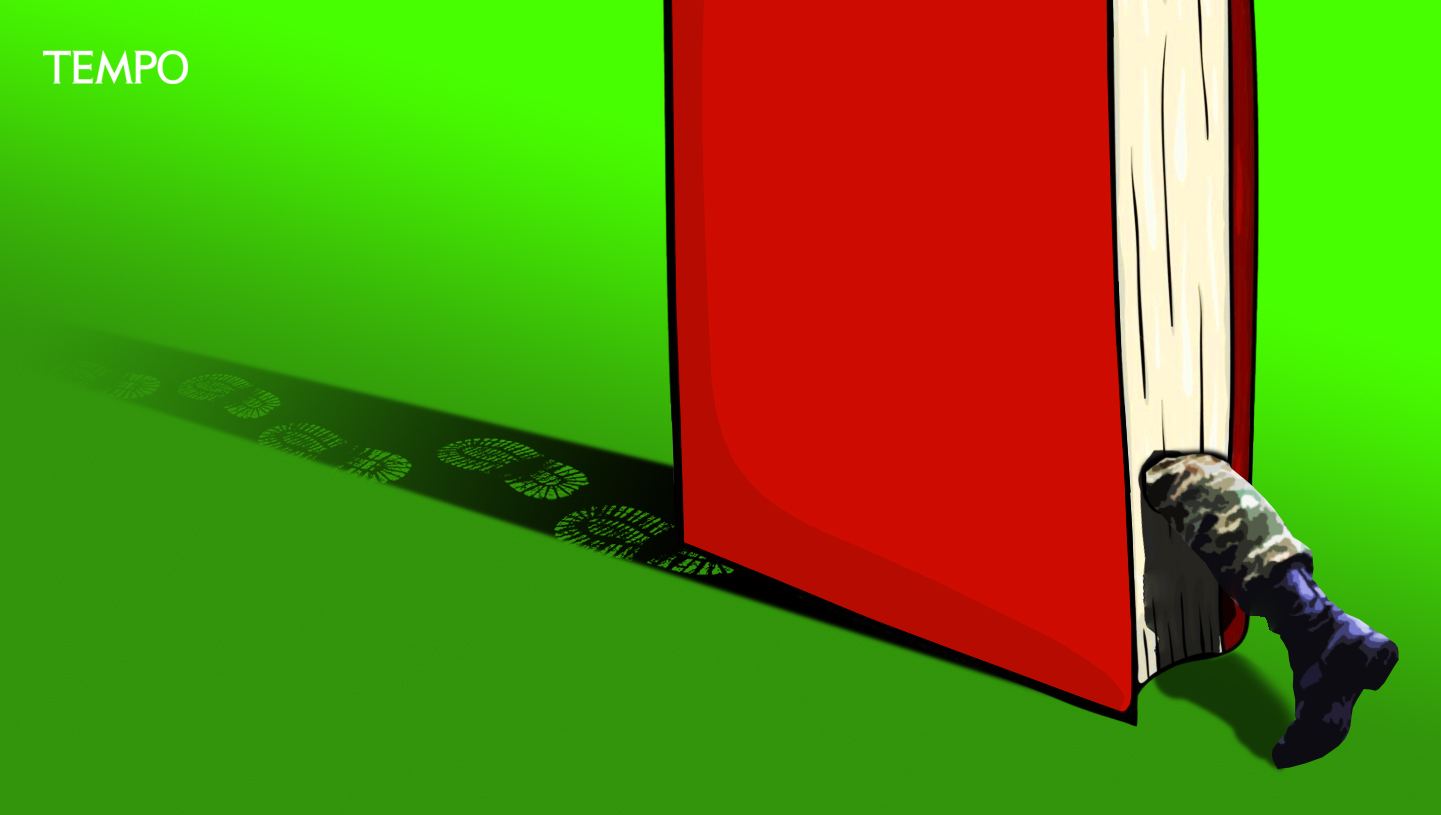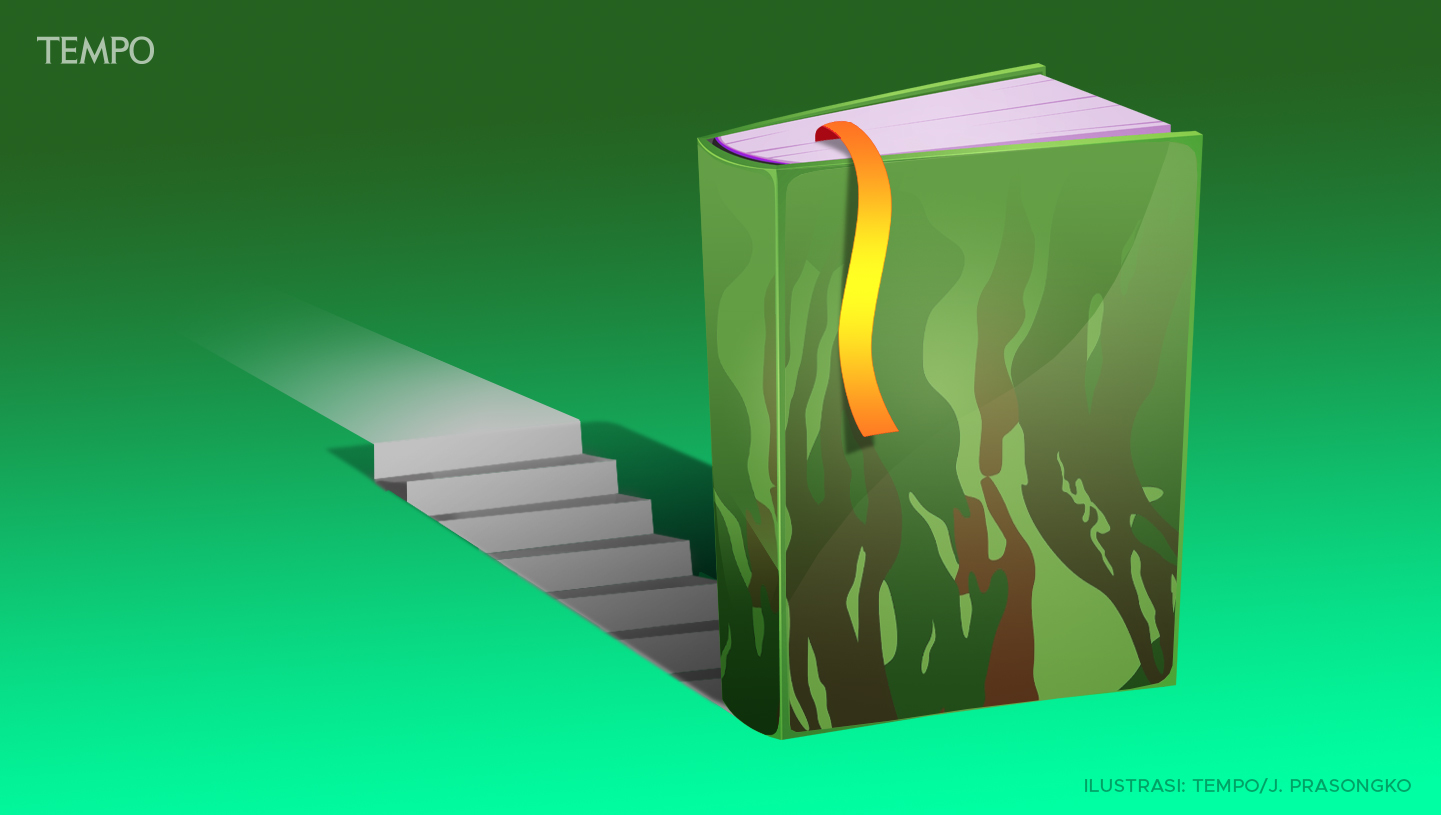Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Jokowi menggencarkan pembangunan yang cenderung mengabaikan lingkungan dan masyarakat.
Penambangan batu andesit untuk bendungan Bener di Purworejo akan menjadi contoh nyata.
Perlawanan aktivis sosial memberi harapan masih adanya kontrol publik.
BENDUNGAN Bener di Purworejo, Jawa Tengah, kelak akan menjadi monumen pembangunanisme ala Joko Widodo (Jokowi). Diklaim buat “menyejahterakan masyarakat”, bendungan justru dibangun dengan menyingkirkan kehidupan banyak orang, terutama penduduk Desa Wadas, wilayah sumber batu andesit, material utama proyek itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo