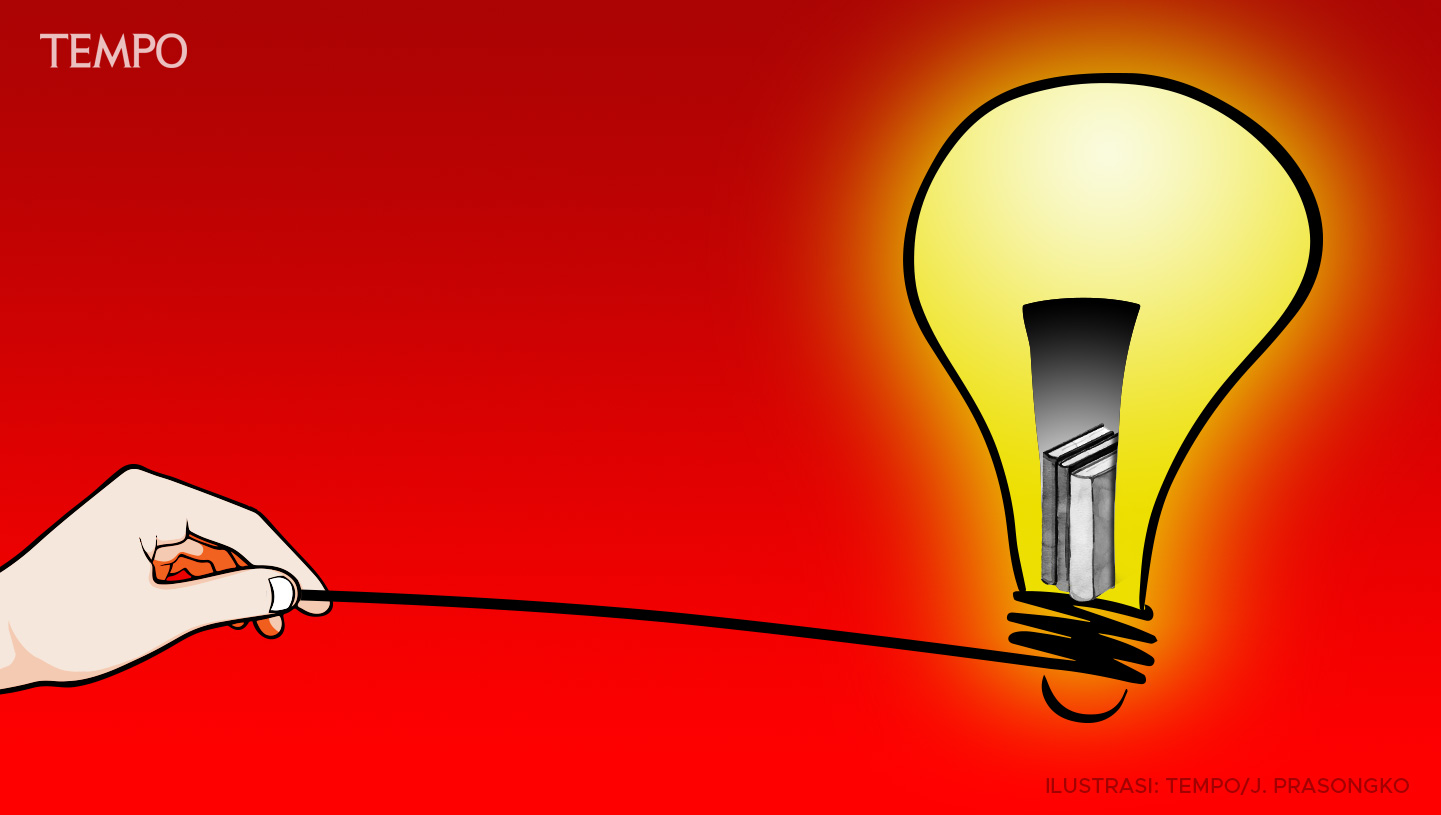Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Kembalinya Taliban menguasai Afganistan tak lepas dari peta geopolitik.
Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi kemenangan Taliban?
Kemungkinan menguatnya kelompok intoleran patut diwaspadai.
APA yang patut kita cemaskan dari jatuhnya Afganistan ke tangan Taliban? Satu yang terpenting adalah bangkitnya euforia kelompok Islam radikal di Tanah Air. Mereka yang mengaitkan kemenangan Taliban dengan kebangkitan “Islam” dalam pengertian yang paling banal: Islam sebagai teologi konservatif yang ditegakkan dengan pedang dan pertumpahan darah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo