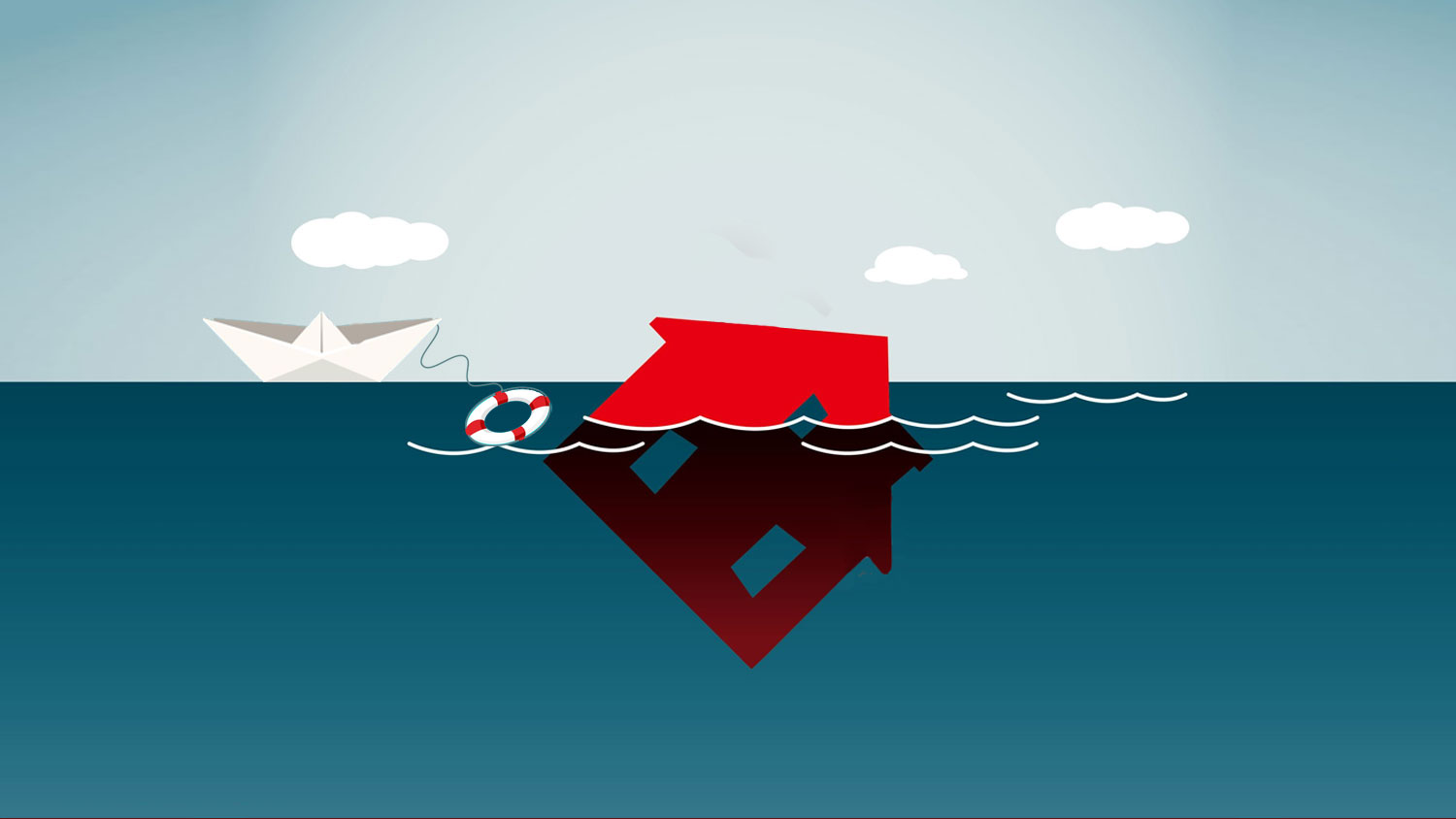Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Para penulis besar menulis kitab yang menggugat Tuhan.
Dari Divina Commedia Dante hingga Kitab Kesengsaraan Fakhruddin Attar.
Attar jauh lebih dalam dan merisaukan.
ANAKNYA tewas, terbunuh, dan ibu itu menangis, membuka hijabnya, membungkuk, memeluk. Penyair Fakhruddin Attar dari Iran abad ke-13 menggambarkan adegan itu tak hanya tentang kesedihan, tapi juga kemarahan:
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo