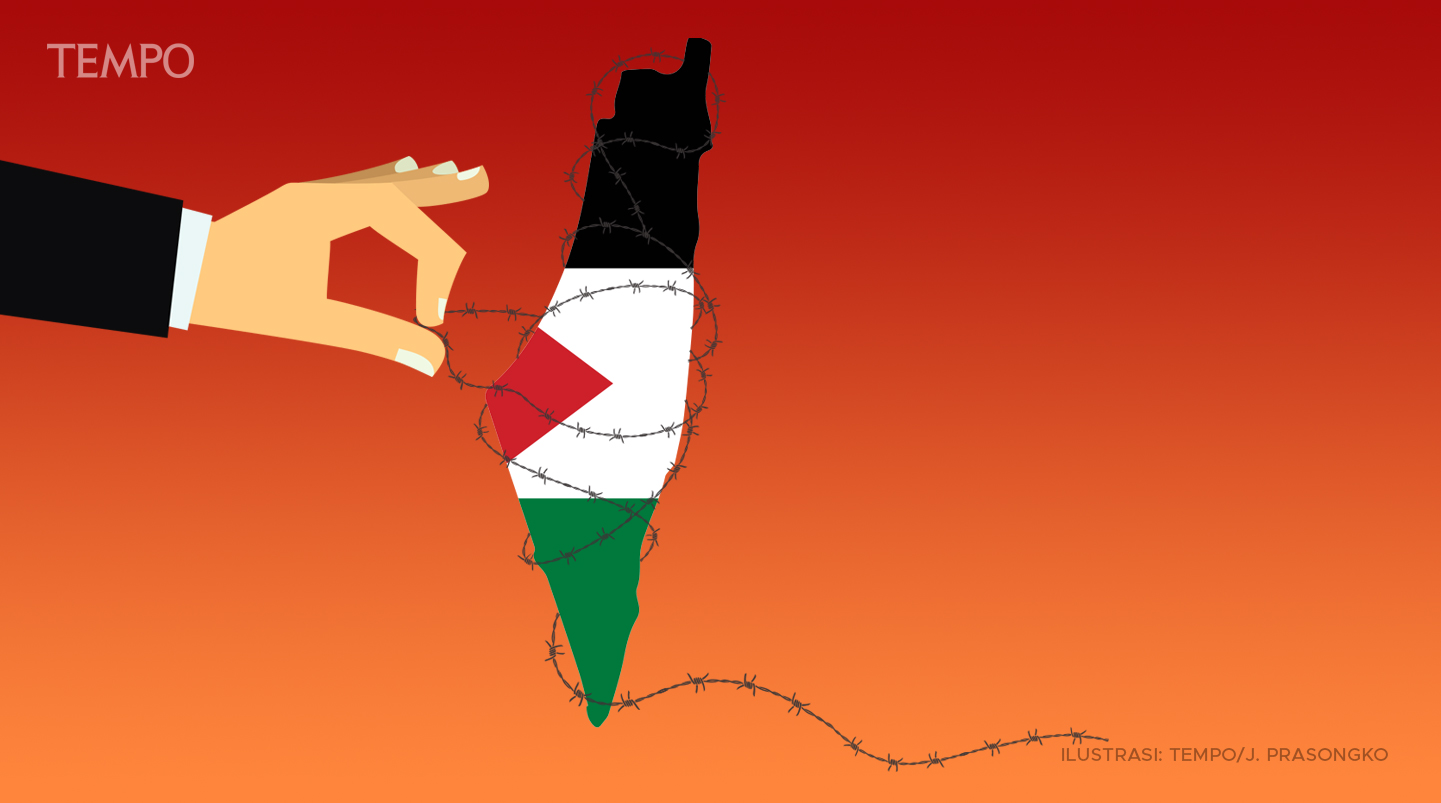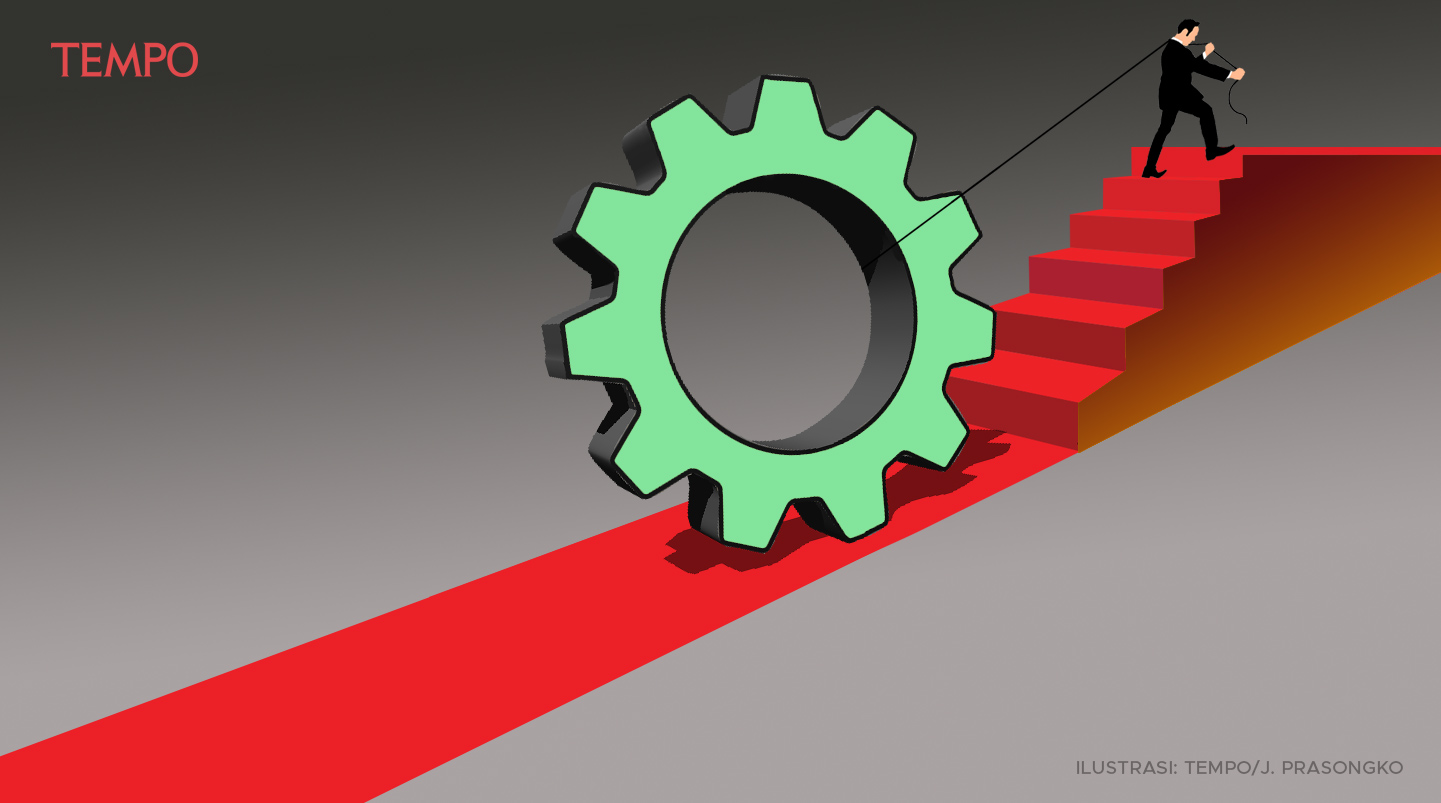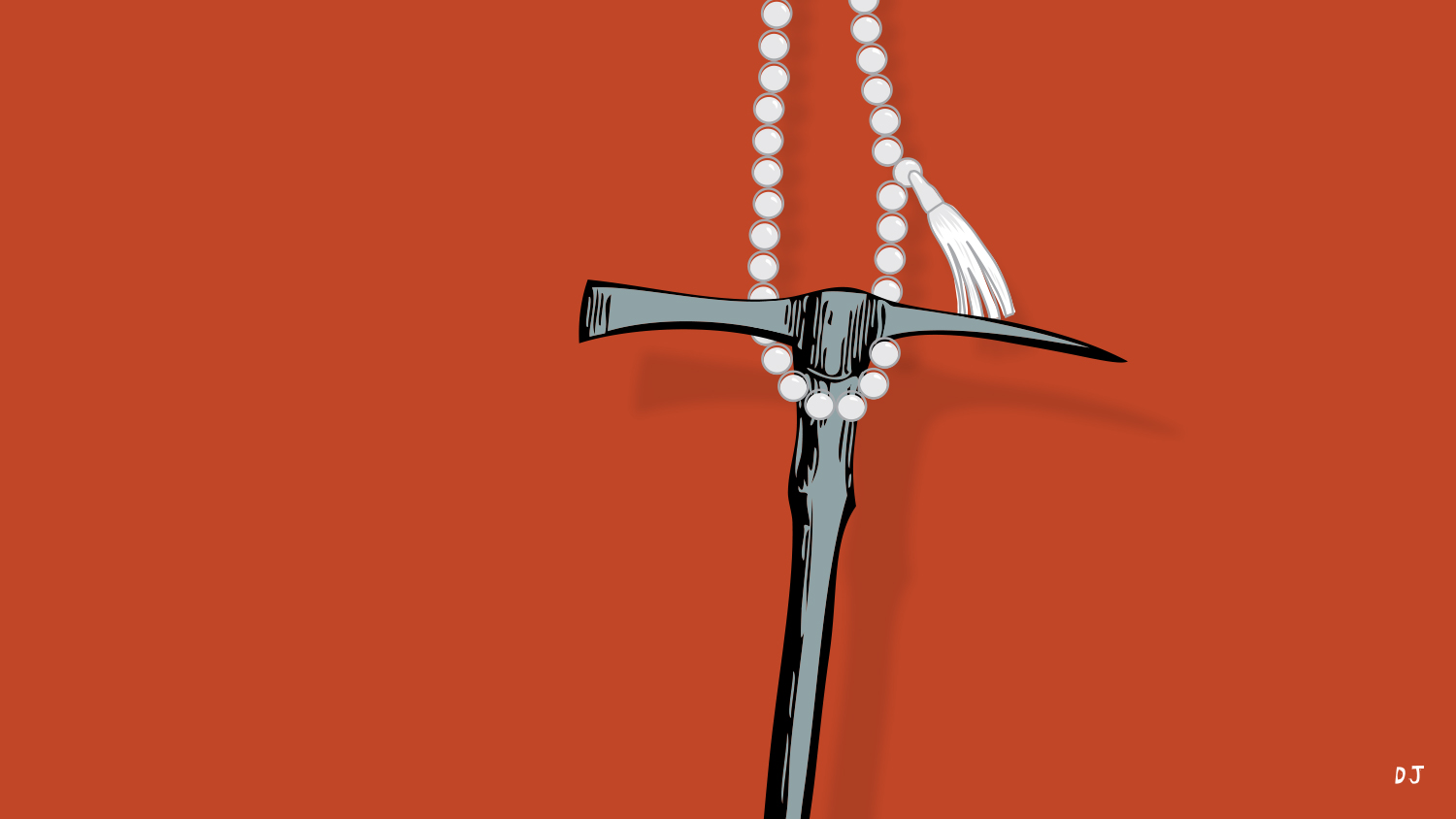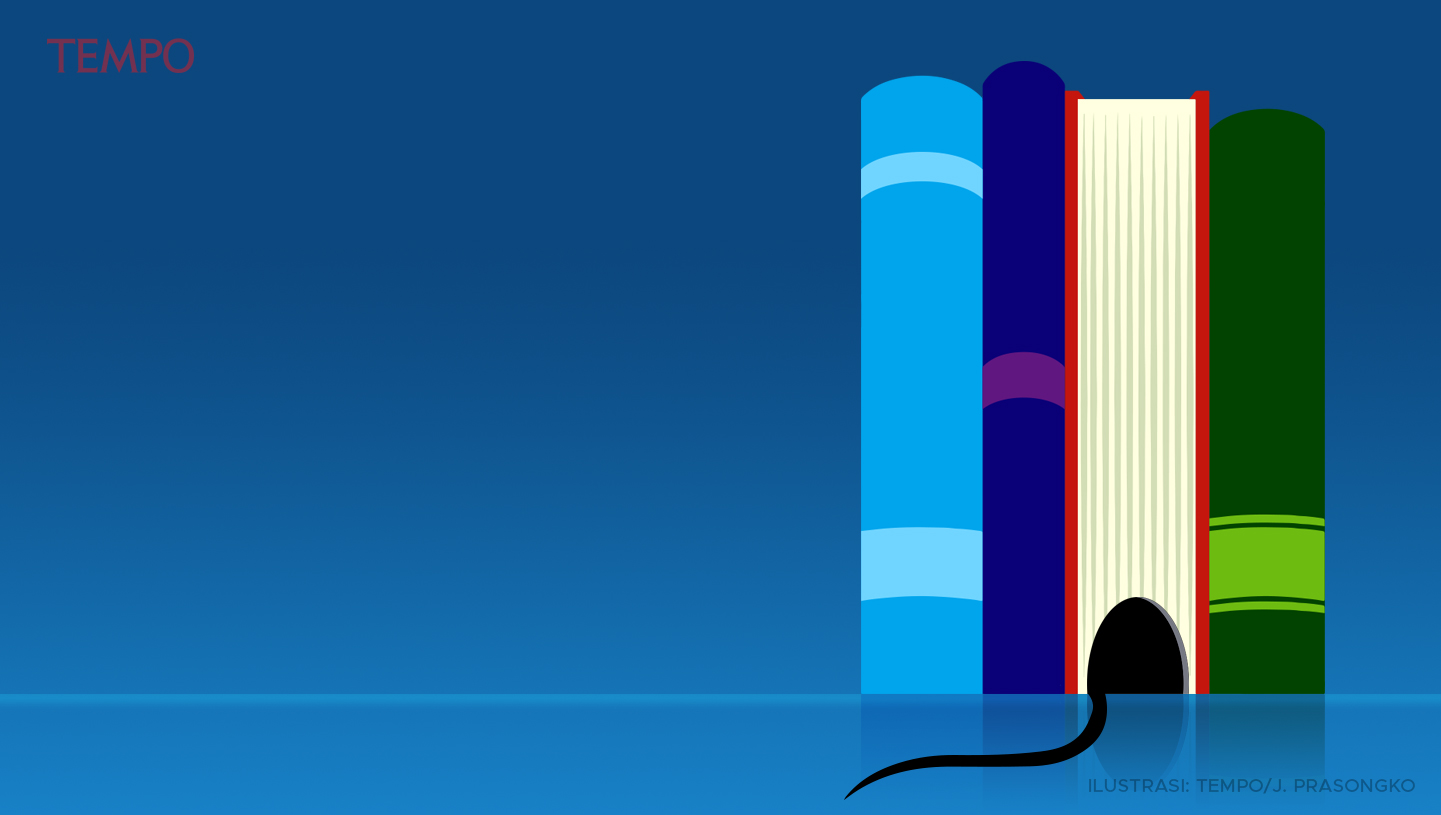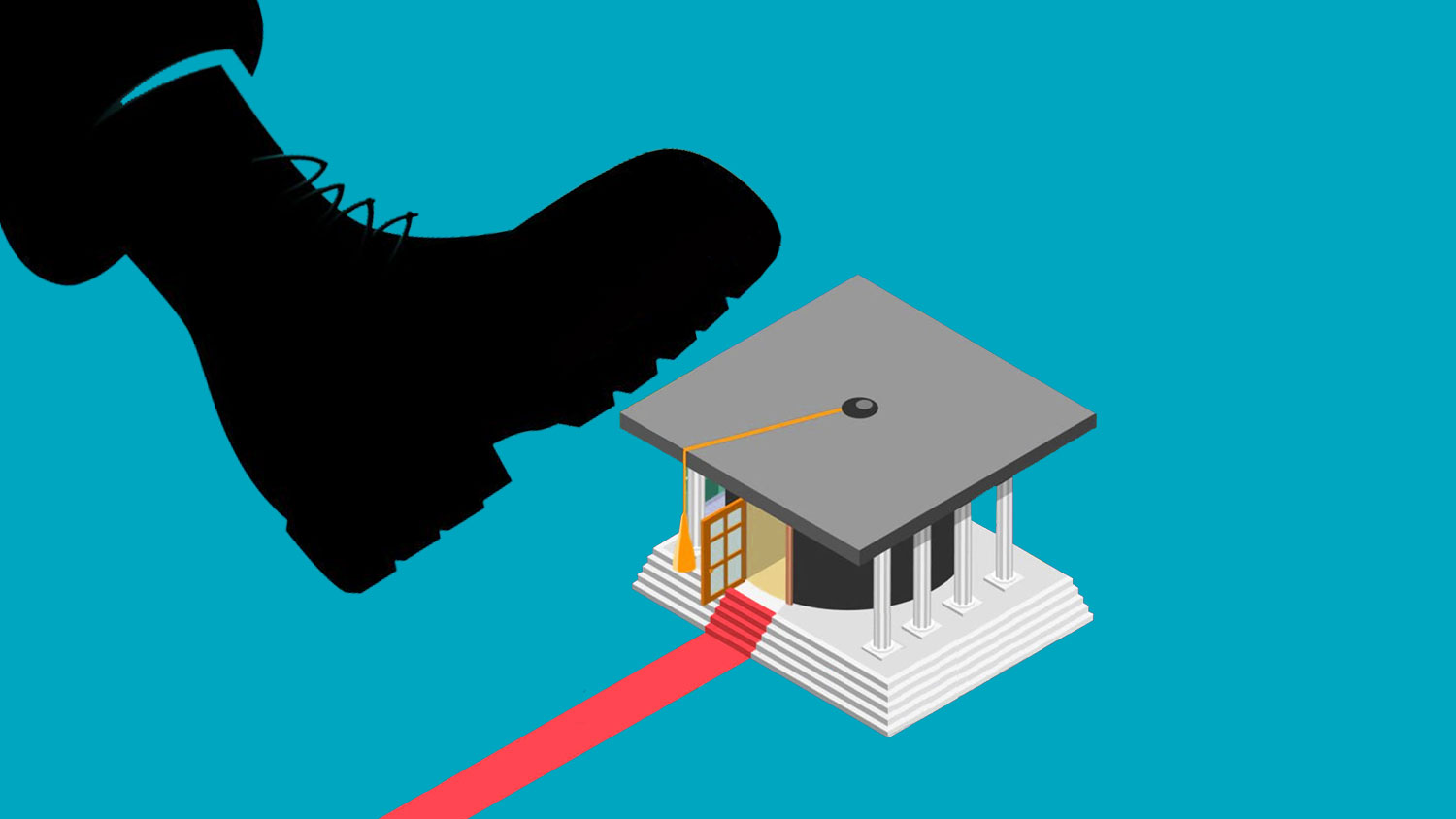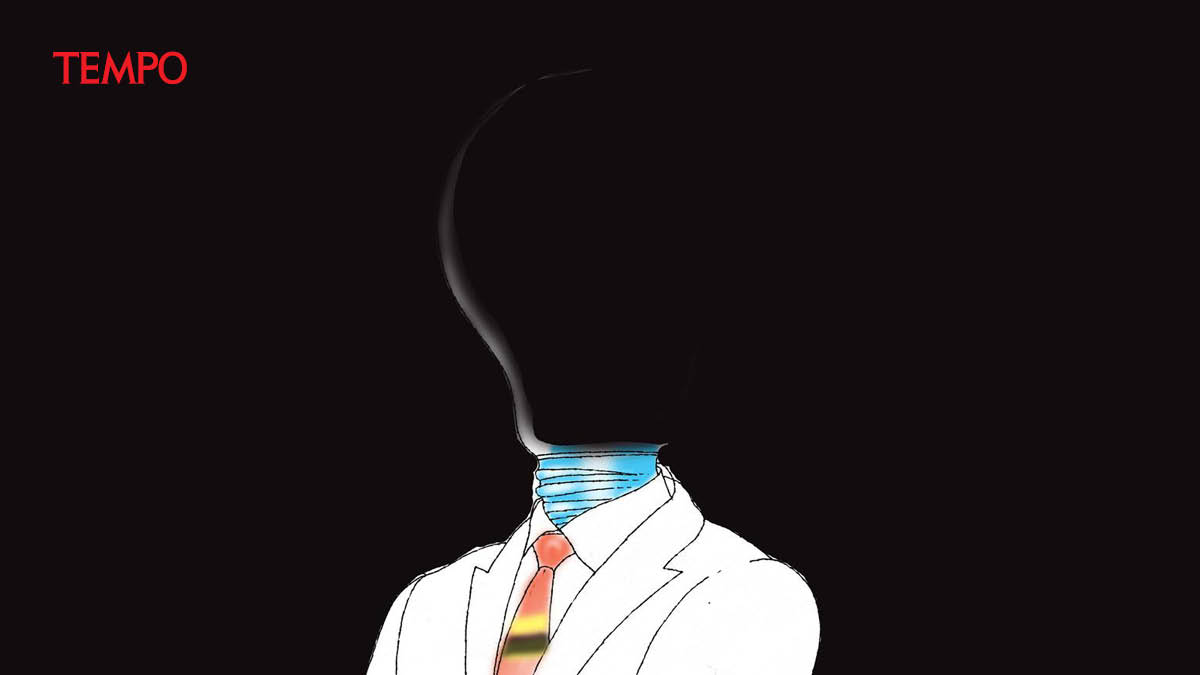Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Bernadinus Steni
Peneliti pada Institut Penelitian Inovasi Bumi (Inobu)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Kementerian Pertanian baru-baru ini mengalokasikan anggaran Rp 2,7 triliun untuk meningkatkan produksi rempah-rempah. Sasarannya adalah mengembalikan kejayaan rempah-rempah masa silam, termasuk pala. Tulisan ini akan berfokus pada pala sebagai contoh nyata untuk menyoroti program ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pelaku perdagangan pala saat ini sudah banyak berbeda dibanding pada zaman kolonial Belanda, ketika pala berada di zaman keemasan perdagangan dunia. Pelakunya kini tidak lagi semata petani, negara, dan pedagang, tapi juga ada agen atau pengepul, pemberi kredit, penyedia benih, dan transportasi. Semua itu bergerak dalam rantai pasok pala yang kompleks, sejak pembukaan lahan, pembenihan, penyiangan, perawatan, panen, pemilahan buah, pengeringan, hingga pemasaran. Sepanjang jalur tersebut, petani adalah yang paling rentan. Ironisnya, hampir 100 persen pala berasal dari kontribusi perkebunan rakyat.
Kementerian Pertanian (2016) mencatat, lahan perkebunan pala didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 169.103 hektare atau 99,69 persen total lahan perkebunan pala secara nasional. Pada 2017, estimasi produksi per tahun dari perkebunan rakyat tercatat 34.516 ton atau 99,75 persen dari produksi nasional. Nilai ekspor tahunan pala sebesar US$ 64,398 juta dengan volume ekspor 11.549 ton. Data itu menunjukkan bahwa pala merupakan tanaman rakyat, bukan bikinan kapital skala besar dari perusahaan-perusahaan raksasa.
Institut Penelitian Inovasi Bumi (Inobu) bekerja sama dengan AKAPe Foundation dan Pemerintah Kabupaten Fakfak telah melakukan pemetaan berbasis poligon atas lahan petani dan pendataan yang komprehensif dari hulu sampai hilir mata rantai pala. Dalam setahun belakangan ini telah terpetakan 246 petani pala dengan luas lahan 633,6 hektare di tiga kecamatan dan 20 desa. Beberapa isu paling mendasar yang ditemukan dalam proses pemetaan ini adalah sebagai berikut.
Pertama, sulitnya membedakan benih jantan dan betina merupakan masalah unik dalam pengembangbiakan pala. Benih jantan tak berbuah. Masalahnya, pala itu diketahui jantan atau betina setelah enam tahun kemudian. Saat ini sudah tersedia inovasi melalui teknik sambung pucuk (grafting). Aceh sudah mengembangbiakkannya, tapi masih perlu diuji dan disebarluaskan ke daerah lain. Kedua, budi daya pala diwariskan secara turun-temurun dan ditopang tradisi yang kuat. Petani memang perlu digerakkan agar sistem pertanian pala lebih efisien.
Ketiga, standar pengelolaan pasca-panen semestinya mulai merefleksikan standar global, yang mencerminkan kepentingan konsumen. Konsumen negara maju, seperti Uni Eropa, makin rewel terhadap urusan keamanan pangan. Dalam beberapa tahun ini, banyak keluhan kadar aflatoksin (senyawa pemicu kanker) dan campuran kimia ekstra yang sekonyong-konyong muncul pada pala kita. Hal itu diduga kuat berasal dari penanganan pasca-panen yang tidak sepatutnya. Untuk itu, petani perlu diperkenalkan dengan standar-standar baru ini.
Keempat, mata rantai perdagangannya masih panjang. Hal itu merugikan petani dan pala rentan terpapar materi lain yang akan mempengaruhi pala. Pemerintah daerah perlu memangkas mata rantai itu. Pembangunan gudang bisa menjadi salah satu solusi.
Kementerian Pertanian mencoba menjawab masalah ini dengan kebijakan, seperti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pala. Semua ketentuan itu mengarah pada pengelolaan pala secara profesional, mengikuti standar agronomi, keamanan pangan, keberlanjutan, dan legalitas.
Tantangannya adalah bagaimana menjembatani jarak antara bahasa regulasi dan kenyataan sosial petani tradisional. Dibutuhkan proses pendampingan yang intensif agar standar dalam kebijakan itu terinternalisasi ke dalam budaya lokal. Hal tersebut memastikan tidak hanya kepatuhan pada hukum, tapi juga kelanjutannya secara sosial. Selain itu, sistem sertifikasi benih harus bisa mencegah praktek monopoli agar tidak berujung pada tambahan biaya bagi petani pala.