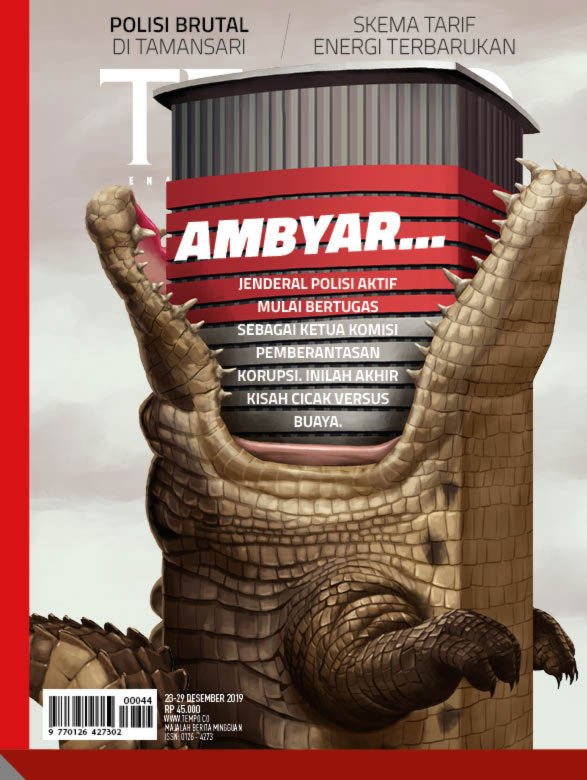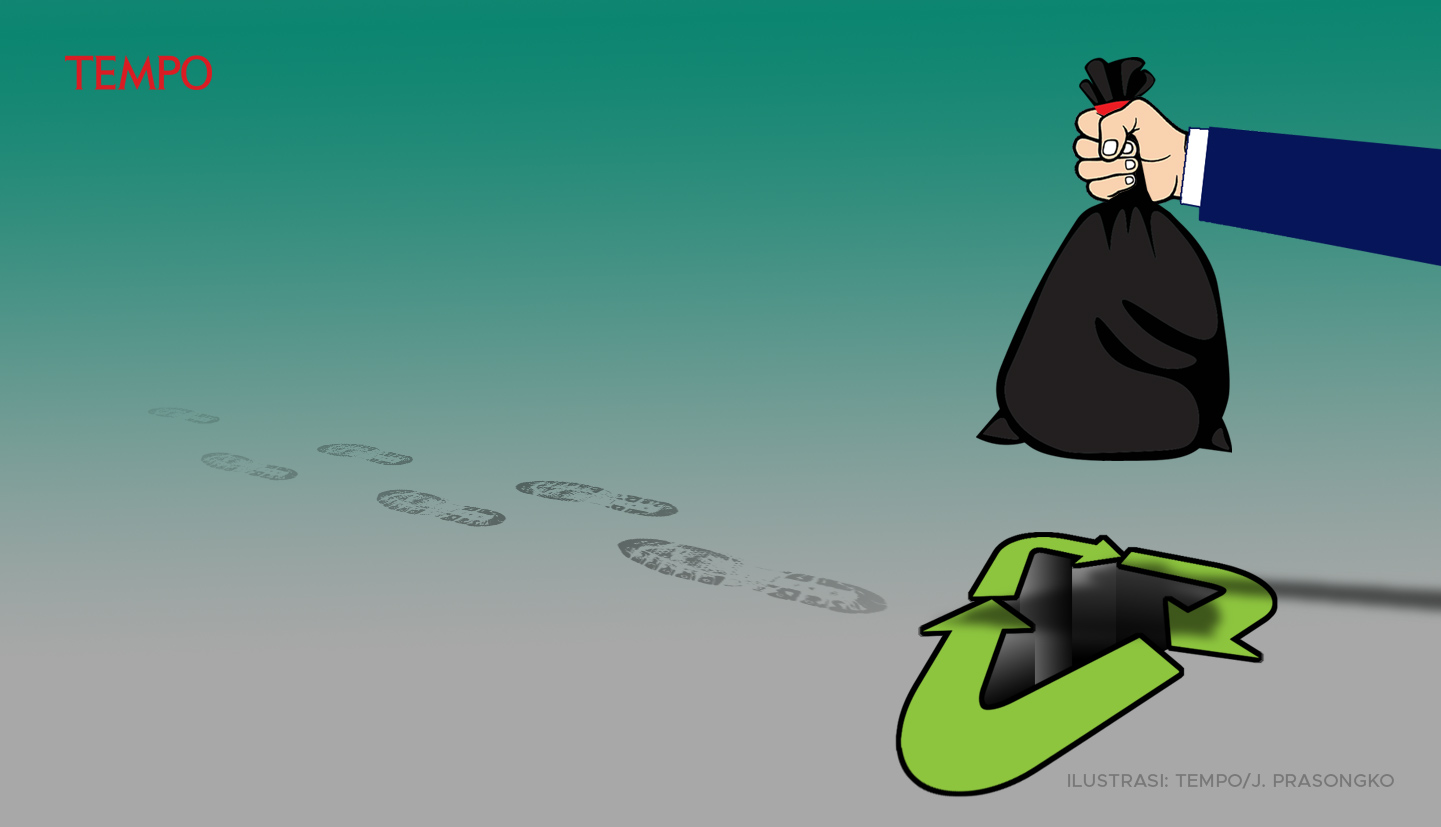Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

HARI yang ajaib itu 19 Mei 1824, atau 21 Ramadan 1751. Dalam otobiografinya Pangeran Diponegoro menulis bahwa di hari itu ia diminta datang ke Gunung Rasamuni oleh seseorang yang tak berumah tak beralamat. Ia perlu menghadap Ratu Adil. Orang itu siap menemaninya pergi.
Diponegoro pun berangkat. Sesampai di kaki gunung, pengantarnya tiba-tiba menghilang. Tapi di puncak Rasamuni ia lihat wajah yang bercahaya. Konon cahaya itu beradu terang dengan sinar matahari. Matahari meredup.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo