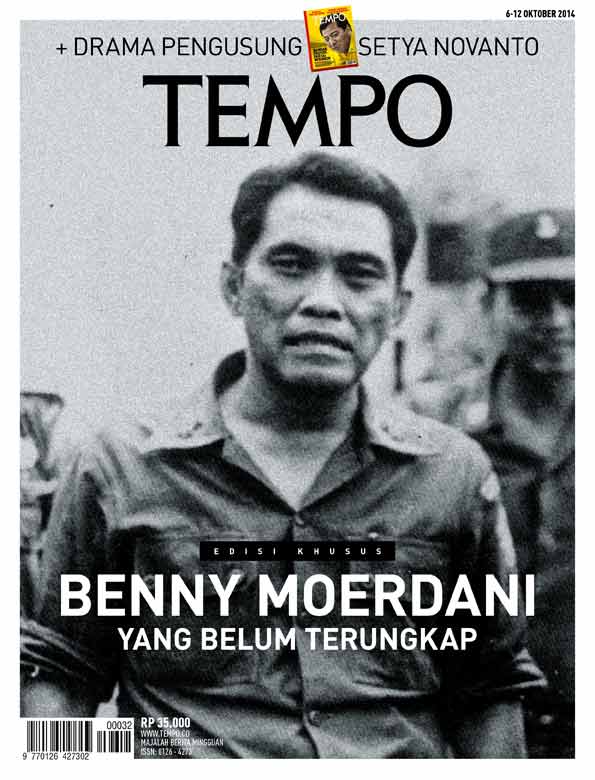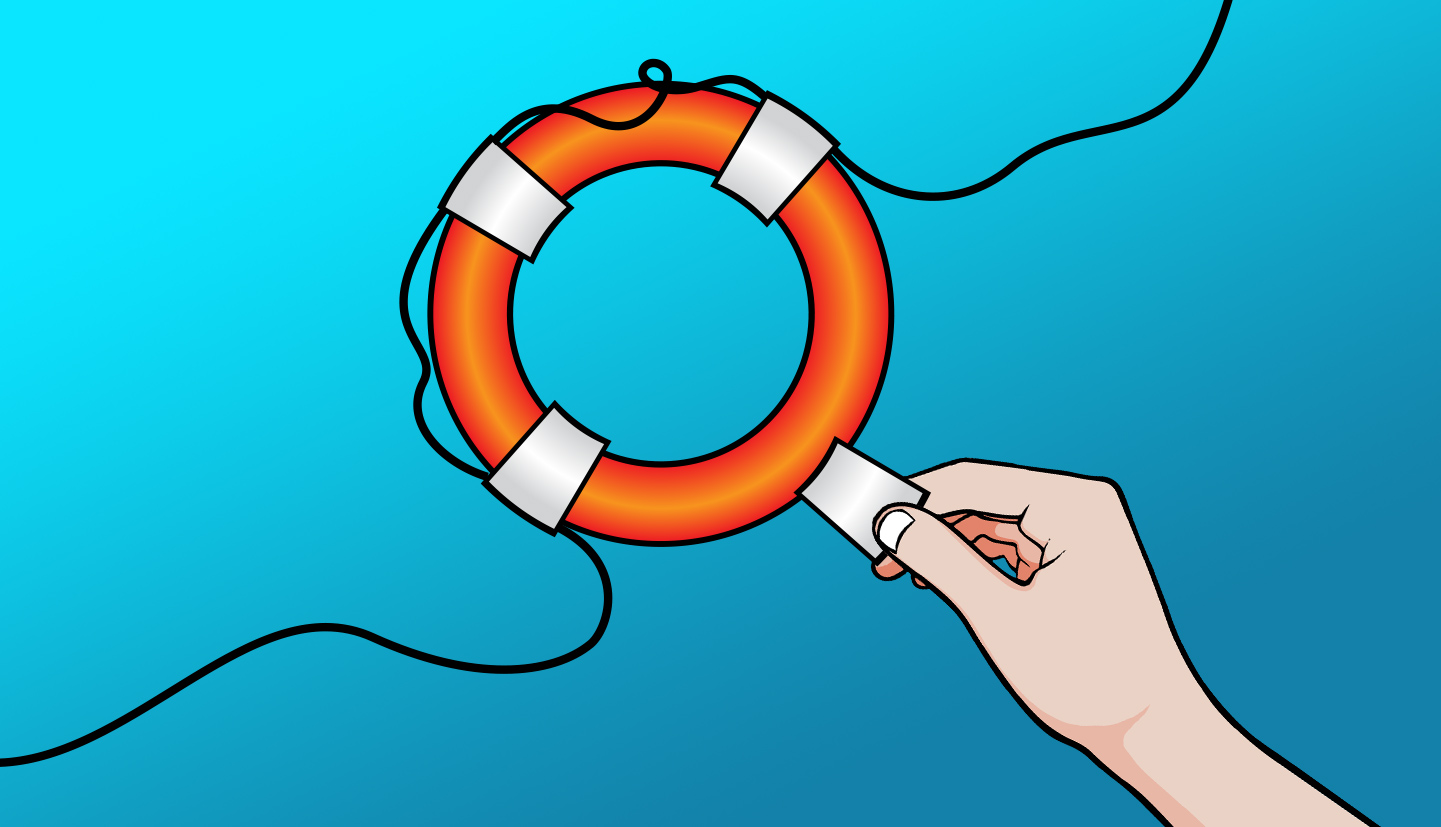Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sebuah asteroid yang sangat-sangat kecil, ada seorang raja yang duduk di atas takhta tanpa didampingi siapa pun. Jubah besarnya berjela menutupi seluruh planet mini itu. Tak ada tempat bagi yang lain. Syahdan, dalam dongeng Pangeran Kecil Antoine de Saint-Exupéry yang termasyhur ini, sang pangeran mengunjungi tempat raja yang kesepian itu. Melihat seorang tamu datang, raja itu pun gembira. "Nah, ini ada rakyat," ia berseru.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo