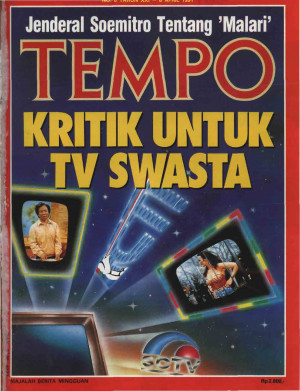DI sekitar kita selalu ada Rama, Shinta, Dasamuka, Anoman, Les- mana, dan Kaca Lopian. Sejak abad mitos sampai dekade realitas, selalu ada Rama yang Shinta terkasihnya dicuri Dasamuka. Selalu ada Dasamuka yang punya kesiapan retorika sepuluh wajah. Selalu ada Anoman yang mempertaruhkan hidupnya untuk sesuatu yang bukan sanak bukan kadangnya. Selalu ada kepiawaian dan kewaskitaan Lesmana berkat Kaca Lopian: cermin peneliti muatan dan gerak sejarah, kaca futurologis pemantul hari esok ke hamparan tanah hari ini. Hanya saja, mereka bisa berubah atau berkembang. Rama bisa tidak ngotot mencari kekasihnya. Shinta dalam struktur dunia modern mungkin tak dituntut untuk setia selama dalam cengkeraman Rahwana. Rumus piramida ketakberdayaan bisa memaafkan noda yang memerciki kehormatannya, sebab kita telah sepakat untuk mencurigai puritanisme. Bahkan, di tengah kesuntukan ritme profesional, kita bisa pura-pura tak mengkhawatirkan kemungkinan skandal Shinta-Dasamuka. Pola pemahaman hidup modern yang spesialistik, ornamental, dan parsial bisa membuat kita kehilangan grand theory dan grand strategy untuk menangkap keseluruhan sepuluh wajah Dasamuka, melainkan terpuruk pada tangkapan perwajah tanpa ingat integralitasnya dengan sembilan wajah yang lain. Padahal, konfigurasi sepuluh wajah pasti berisi sepuluh topeng kebaikan, keluhuran, kemuliaan. Wajah asli, yakni yang jahat, tentulah wajah kesebelas, terletak di balik yang sepuluh. Sedangkan Lesmana modern bisa berupa kaum profesional yang inti fungsi kesejarahannya tak lagi terpusat pada kejujuran terhadap realitas dan nilai. Ia barangkali ilmuwan-pujangga yang menggenggam Kaca Lopian sebagai komoditi utama. Muatan data dan analisis kaca itu mungkin justru dijual kepada Dasamuka, atau di saat lain, kaca itu tak lagi konsisten teksturnya sehingga yang tampak di mata Lesmana adalah keterbalikan realitas. Kalau sudah begini, Anoman sengsara. Implementasi pengabdiannya jadi kacau karena peta pihak-pihak telah rancu: Lesmana mengalami splits, Dasamuka ada dalam Rama dan Rama ada dalam Dasamuka, sementara Shinta ber-secret conspiracy dengan Raja Alengka. Ilmu berkata: hidup ini tak lagi hitam dan putih. Anoman pun kehilangan tempat tinggal nilai. Hakikat dan fungsi "kera putih"-nya, yakni keberpihakan total terhadap kebenaran, jadi retak-retak dan terpotret sebagai "wajah sok pahlawan". Pilihan lainnya, jika tak lagi ia lakukan "putih"-nya: Anoman tinggal kera. Di sekitar kita, tak hanya selalu ada Rama, Shinta, Dasamuka, Lesmana, dan Lopian, tapi juga kera. Dalam multi-idiom Dasamuka, kera terkadang disebut cecunguk, kutu loncat, atau munyuk. Mungkin ini semua bisa diasumsikan sebagai dekadensi peradaban Ramayana. Tetapi dasar manusia, juga barangkali karena kehidupan selalu ditandai keseimbangan, harus kita catat bahwa dekandensi itu berlangsung beserta tumbuhnya nilai-nilai lain yang berbanding terbalik dengannya. Manusia itu komplet. Segala kebocoran kebrengsekannya cenderung selalu diimbangi pernik-pernik cahaya budi emasnya. Kalau pertengkaran dan dendam antara Rama dan Dasamuka telah melebar dimensinya -- tak sekadar menyangkut keadilan dan hak atas Shinta, melainkan telah pula jadi problem psikologis, politis, dan kultural -- formula penyelesaiannya bisa meningkat dari skenario "Shinta dikembalikan ke Rama dan Dasamuka dipenjarakan" ke skenario "Rama menang, Dasamuka menang". Model "kearifan" semacam ini terpaksa dirancang tidak sekadar untuk menghindarkan kemungkinan loosing face pada Dasamuka, tapi juga karena secara struktural kasus perampokan Shinta itu menyangkut posisi dan otoritas kaum Dewata nun di singgasana nan tinggi. Jadi, formula problem solving bertahan pada konsistensi struktural, maka "dijamin" akan mengguncang seluruh jagat Ayodya dan Alengka. Maka, diaculah filosofi "menang tanpa ngasorake". Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Menang tanpa si kalah mengetahui bahwa ia kalah. Bahkan si pemenang bisa jadi tak pernah diketahui oleh mata sejarah sebagai pemenang. Formula ini berusaha mempahlawankan semua pihak: Dasamuka, Rama, Lesmana, Anoman, bahkan para yang dianggap kera. Mungkin terdapat nuansa kepalsuan di dalamnya. Juga eufemisme dan kecengengan. Tapi yang ingin diupayakan oleh formula ini sesungguhnya adalah meningkatkan mutu kebudayaan manusia dari dikotomi konvensional yang mempolarisasikan si kalah dengan si menang, si pahlawan dengan si terkutuk, si luhur dengan si bangsat. Biarlah dunia olahraga tak berkutik dalam kemapanan kalahmenangnya. Tapi setiap olahragawan tetap manusia yang bisa memahami kemenangan sejati adalah kesanggupan menaklukkan diri sendiri. Biarlah pertarungan politik dan peperangan militer riuh rendah dengan kalah-menangnya, sepanjang manusia menyadari bahwa jika output kemenangannya adalah keberkuasaan atas pihak lain, ada nilai yang lebih tinggi yang sanggup melihat keberkuasaan dalam konteks seperti itu sebenarnya adalah kekalahan. Tataran nilai itu pula yang menyediakan acuan nilai di sana tak ada kalah menang di antara suami dan istri, di antara pergaulan kemanusiaan, serta di dalam cakrawala yang diidamkan setiap kebudayaan. Formula "pasca-kalah menang" mendorong manusia bergeser dari kekuatan dan kekuasaan yang membelah manusia jadi kawan dan lawan, sopo siro sopo ingsun, kita dan mereka menuju cinta kasih, kearifan, dan kebesaran jiwa yang menyatukan, mensenyawakan, mensehatikan, dan mensejiwakan. Tetapi, jangan lupa, formula yang kedengarannya indah dan luhur ini, boleh jadi, sebenarnya semacam pragmatisme yang terpaksa dipilih di ujung lorong-lorong kebuntuan dan ketakberdayaan struktural. Kemudian, jangan lupakan pula, kemungkinan formula ini jadi bumerang: Rama yang telah merasuk ke dalam intensitas kesengsaraan dan dendam sedemikian rupa tak akan pernah sudi merelakan Dasamuka terlindung sepuluh topengnya. Sedangkan Sang Dasamuka juga tak sedia jadi pengemis untuk dilindung-lindungi dari kemungkinan loosing face.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini