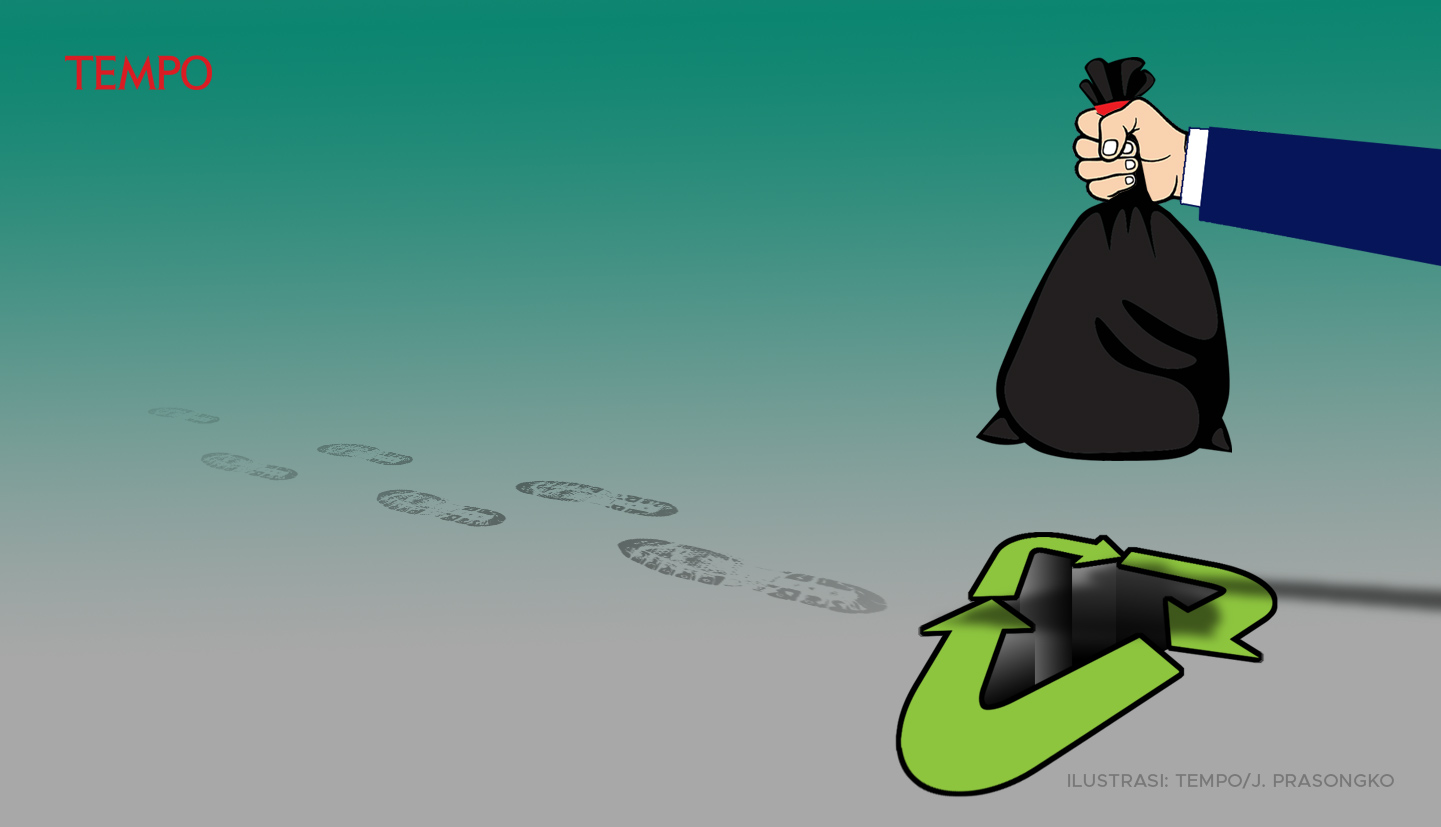Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arah pemberantasan korupsi bisa jadi buyar jika yang sedang jadi tersangka dibela partai politik masing-masing hanya atas dasar setia kawan saja. Para tersangka perkara korupsi itu umumnya tersangkut kasus dugaan penyimpangan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang akhir-akhir ini banyak dibongkar kejaksaan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo