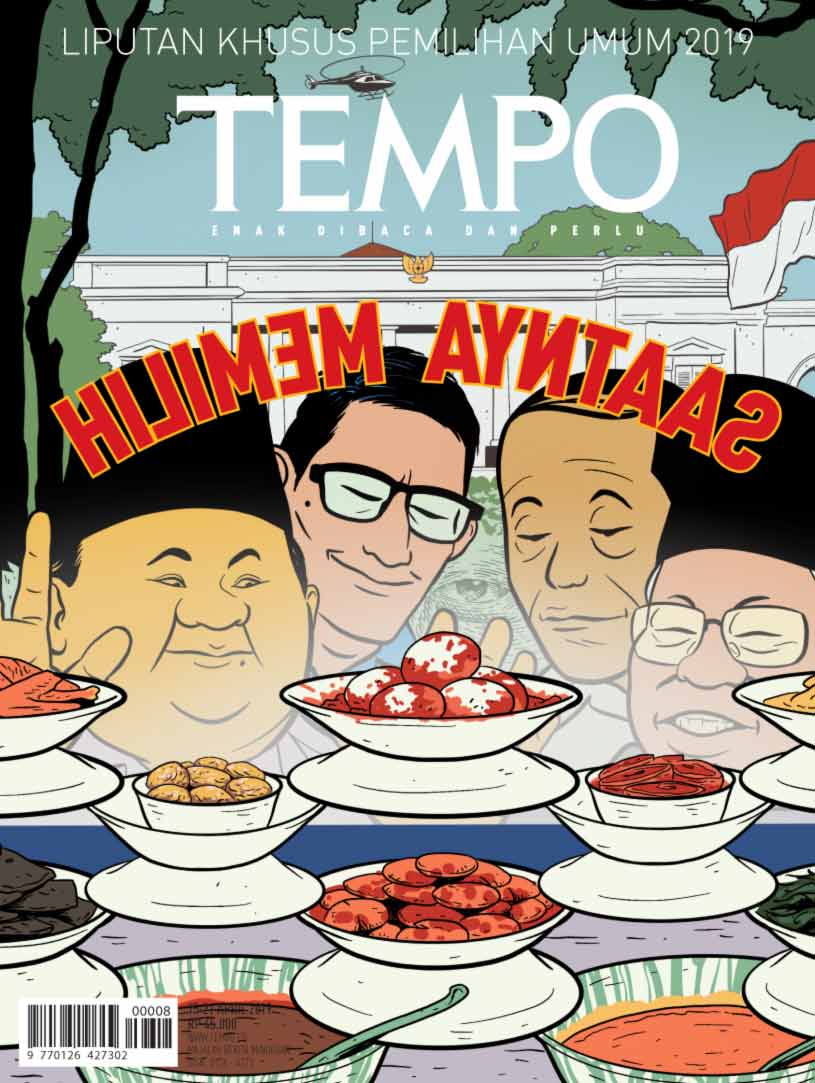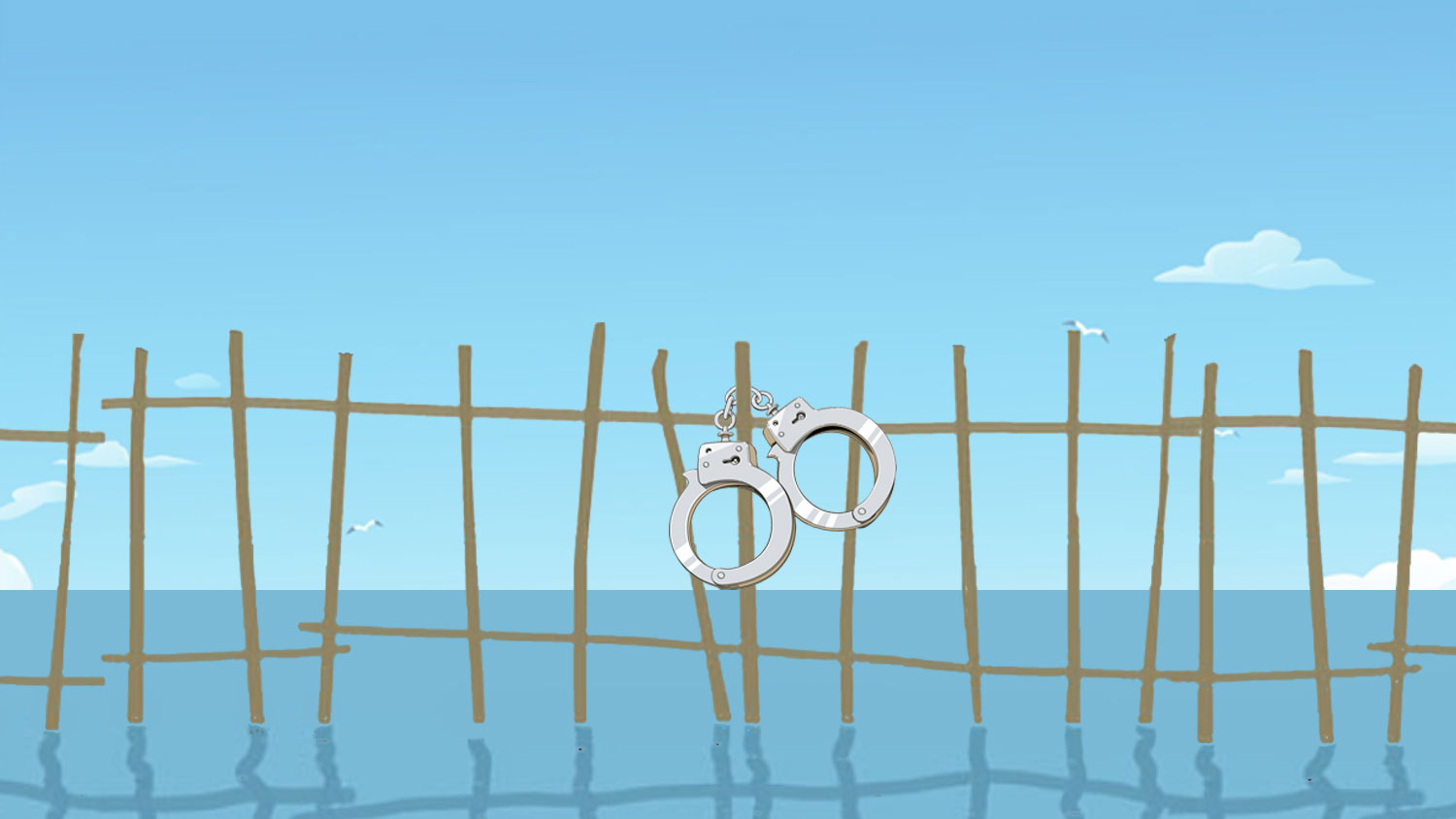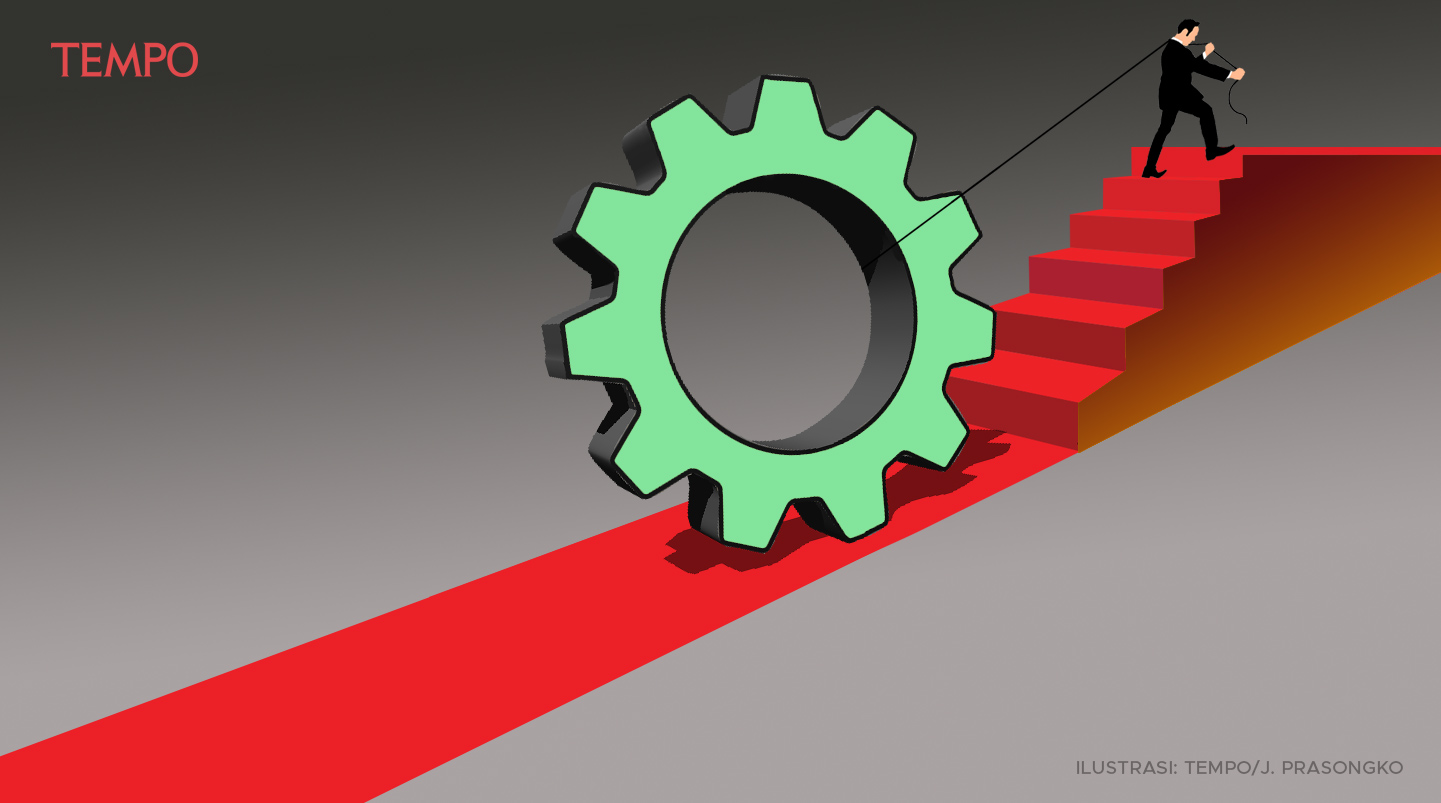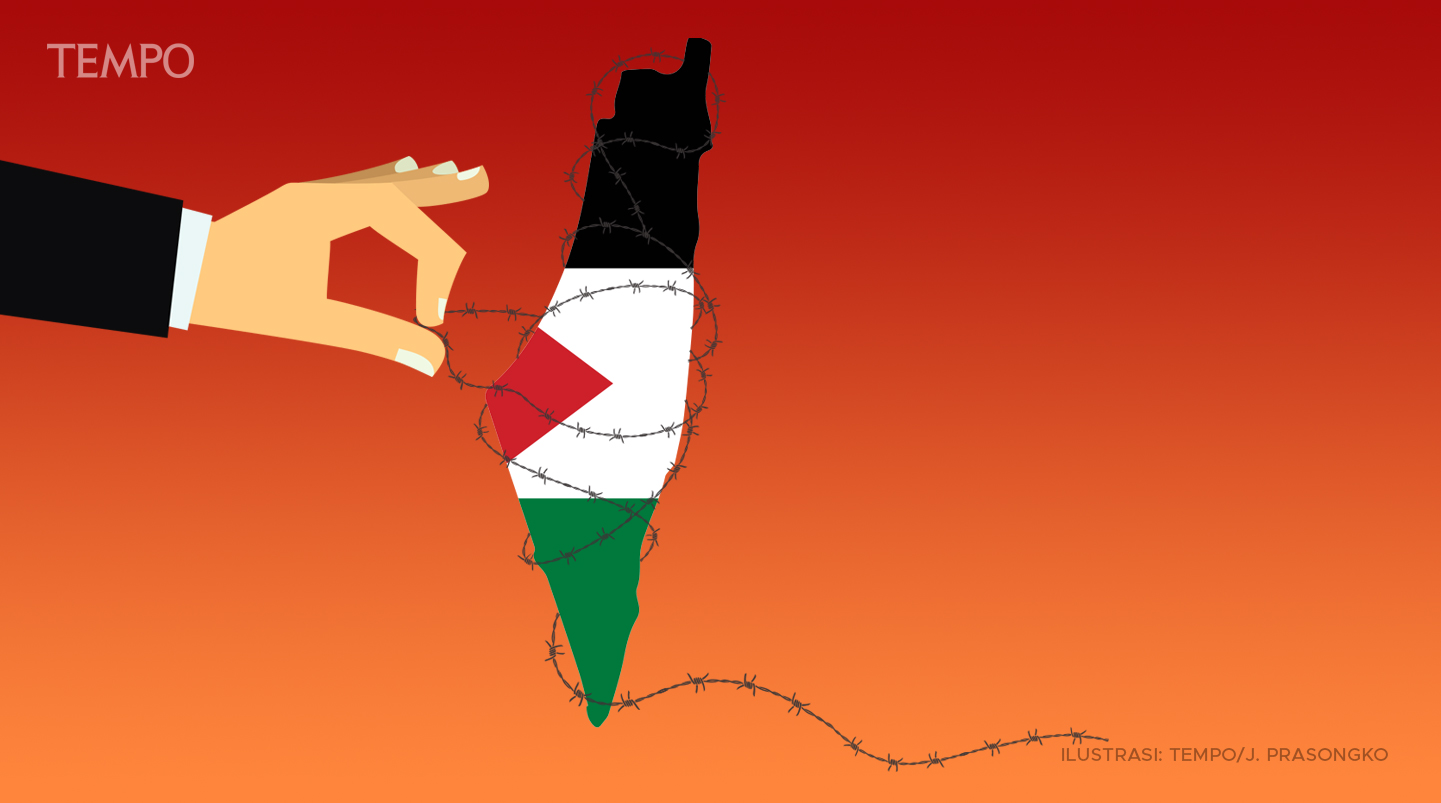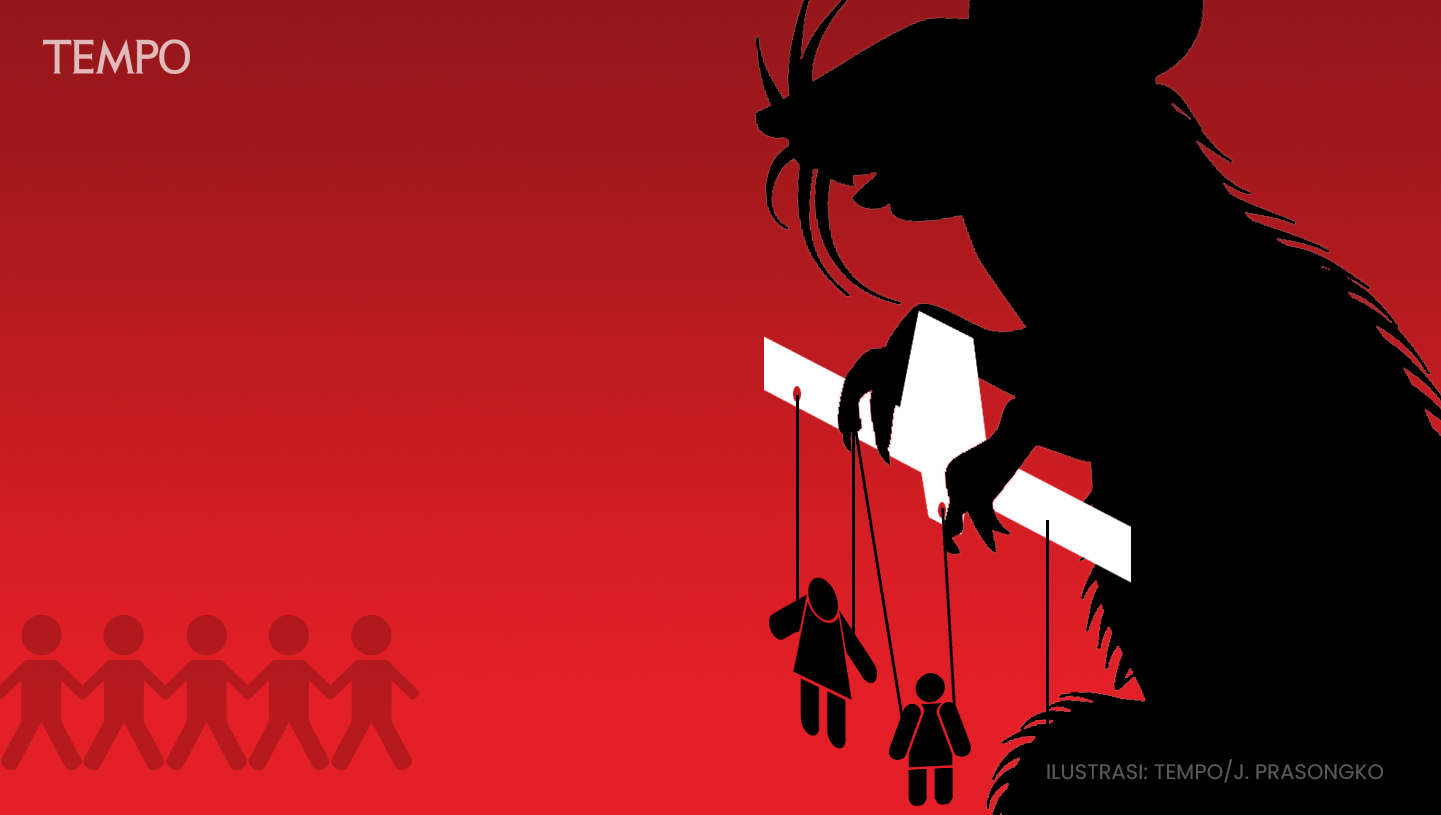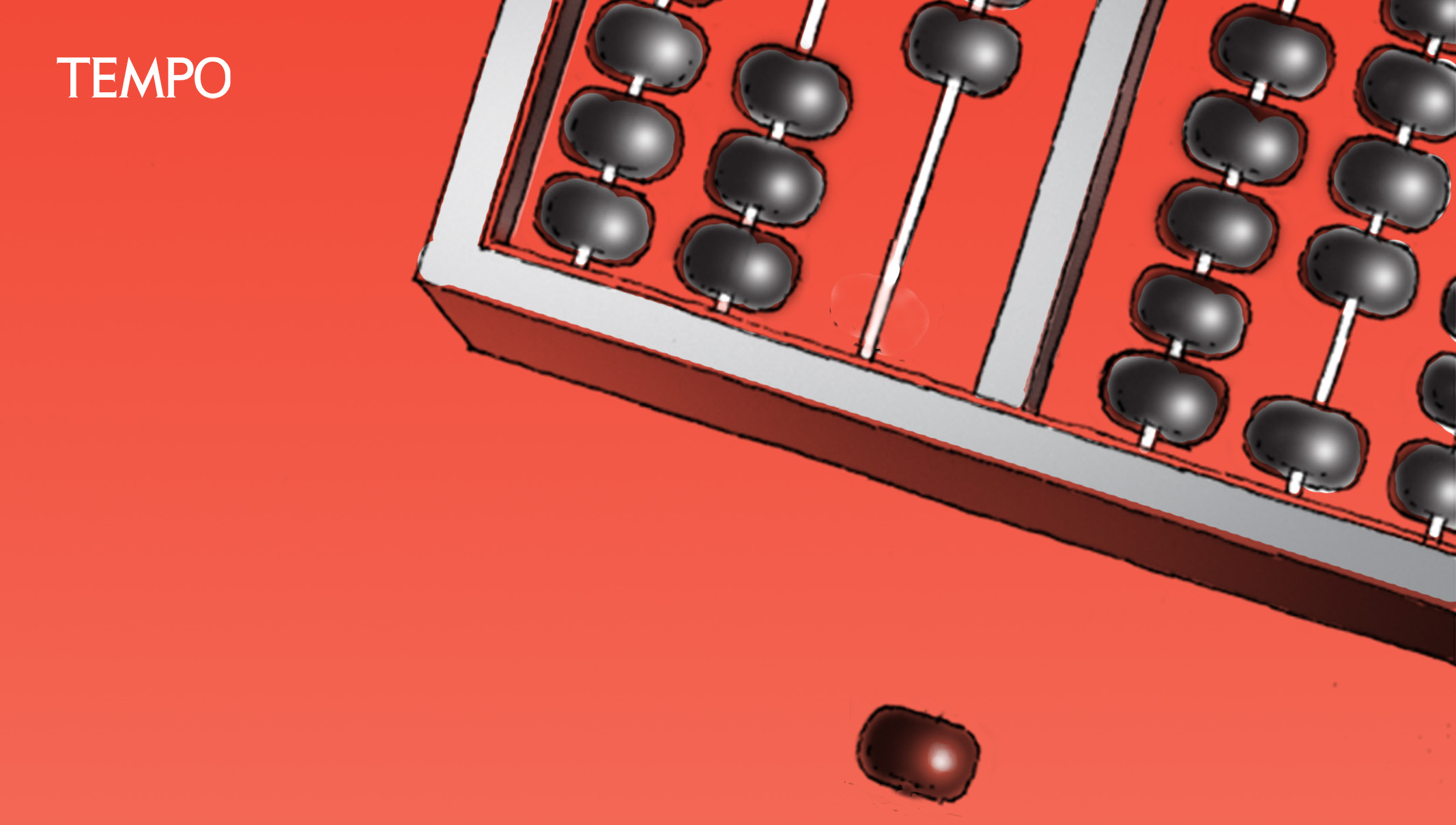Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DI Najaf, sejarah dibangun dari kehilangan. Pada suatu hari di tahun 1982 saya bersembahyang asar di Masjid al-Imam Ali, masjid utama kota itu, di mana khalif ke-4 dimakamkan, dua hari setelah ia menanggung luka pedang seorang asasin. Duduk menatap mihrab, saya merasa masa silam lekat di aura ruang itu. Di bawah kubah besarnya yang berkilau emas, lewat gerbang-gerbangnya yang tinggi lebar, sebidang luas interior dihiasi mosaik warna biru kehijauan. Dan di ruang dalam, sebuah makam berteras persegi ditempati tiga pusara….
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo