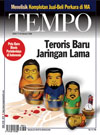Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Siapakah pelaku bom Bali pada awal bulan ini? Tiga pekan setelah peristiwa laknat itu terjadi, polisi belum dapat mengungkap identitas mereka. Sementara ini yang ada baru dugaan. Misalnya tentang tiga kepala yang ditemukan di lokasi pengeboman dan disangka sebagai jasad para pengebom bunuh diri. Foto wajah ketiga jenazah yang sepatutnya masih dapat dikenali ini telah disebar ke seluruh penjuru Tanah Air tapi jati diri mereka belum juga dapat dipastikan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo