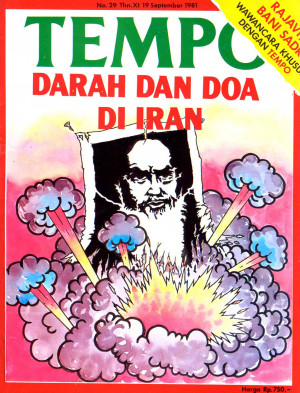BENDA bulat yang mirip tangki air terbuat dari aluminium pekan
lalu diperagakan di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN), Jakarta. Diduga selongsong bahan bakar roket, bekas
meluncurkan sebuah satelit bumi, benda itu akhir Maret lalu
menimpa kebun milik seorang petani di Desa Biauw, Kabupate
Gorontalo, Sulawesi Utara. Desa di Kecamatan Sumalatta itu
berpenduduk jarang, terpencil dan agak sukar dicapai. Itu
sebabnya cukup lama waktu berlalu hingga berita jatuhnya benda
setinggi 1,55 m itu sampai di telinga LAPAN, baru awal Juni.
Beratnya hanya 50 kg--dapat diangkat dua orang dengan mudah.
Tapi garis tengahnya lebih 1 m, tak bisa masuk pintu pesawat
terbang biasa. "Untuk mengangkutnya dari Sulawesi kami terpaksa
minta bantuan pesawat angkutan AURI," ujar Soesetyo, staf LAPAN
yang mengurus benda itu sampai di Jakarta.
Peristiwa itu agaknya menyorot lagi betapa pentingnya segera
terwujud suatu prosedur nasional: Bagaimana menanggulangi
kejadian semacam itu?
Ketika Skylab bakal jatuh dua tahun lalu, semua data sudah
diumumkan. "Sudah diketahui ia bakal jatuh di mana," ujar dr. R.
Sunaryo, Marsda (Purn) TNI AU, Ketua LAPAN.
Perjalanan Skylab konon setiap saat diikuti LAPAN. "Tanpa ada
prosedur sudah ada alert nasional, suatu kesiagaan berbagai
instansi, termasuk Hankam," ujar Sunaryo. Namun hal yang
ditakutkan waktu itu hanya tampak jatuhnya saja, karena
diketahui benda itu tidak mengandung zat radioaktif atau racun
lainnya.
"Prosedur yang kita butuhkan itu ialah untuk menghadapi kejadian
sewaktu-waktu, tanpa diketahui di mana, " ujar Sunaryo lagi. Dan
Panitia Sementara Nasional ke-Antariksaan (Patarnas Antariksa)
kini sedang merumuskannya. Patarnas yang diketuai R. Sunaryo
sendiri, dibentuk akhir 1978 sebagai perwujudan suatu gagasan
LAPAN. Di situ hadir 22 instansi pemerintah, termasuk Hankam.
Yang lebih mendasar, tentunya, penyusunan Hukum Antariksa
Nasional. "Kami merumuskan masalahnya dan mengadakan pengkajian
pendahuluan," ujar Sunaryo, menjelaskan peranan Patarnas. "Kalau
sudah menyangkut pembentukan hukumnya, itu harus melalui BPHN
(Badan Perencana Hukum Nasional)." Berlau buat Indonesia, Hukum
Antariksa Nasional itu seyogyanya selaras dengan Hukum Antariksa
Internasional. Persoalan lagi ialah hukum internasional itu
masih dalam proses pembentukan.
Sejak satelit buatan pertama, Sputnik, diluncurkan Uni Soviet (4
Oktober 1957), manusia mulai menyadari kebutuhan akan landasan
hukum yang mengatur penggunaan antariksa sebagai bidang kegiatan
internasional yang baru. Kesadaran ini punya analogi dalam
proses yembentukan hukum laut dan udara.Tahun 1958, sudah ada
suatu komitad hoc PBB yang mengkaji berbagai problem legal dan
teknis serta menjajaki kemungkinan terwujud suatu persetujuan
internasional mengenai antariksa. Desember 1959, forum ad hoc
ini menjadi permanen dengan nama Komite tentang Penggunaan
Antariksa Secara Damai (Komite Antariksa). dengan 24 negara
anggotanya.
Langkah penting tercapai Januari 1967, ketika 63 negara,
menandatangani Persetujuan Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara
dalam Mengeksploitasi dan Memanfaatkan Antariksa, Termasuk Bulan
dan Benda Langit Lainnya. Persetujuan Antariksa ini dalam 17
pasal menegaskan kembali semua kesepakatan yang pernah dicapai
sebelumnya. Saat ini hampir semua negara di dunia turut
menandatangani persetujuan itu, termasuk Indonesia.
Persetujuan ini mencakup prinsip bahwa tidak ada satu negara pun
berhak menyatakan pemilikan atas sebagian antariksa atau benda
langit. Antariksa itu tetap terbuka bagi siapa saja dan
eksplorasi serta pemanfaatannya harus memenuhi kepentingan semua
negara demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Amerika Serikat
maupun Uni Soviet, misalnya, tak diperkenankan membuat batas
atau memiliki sebagian bulan. "Tak diperkenankan mengklaim
pemilikan di atas sana," ujar Prof. Henri Wassenbergh, ahli
hukum antariksa dan udara di Universitas Leiden, Negeri Belanda.
Tapi kebebasan antariksa itu justru akan menguntungkan negara
yang memiliki teknologi untuk mengarunginya. "Memang demikian,"
ujar Wassenbergh. Mencoba menjamin kepentingan bersama dalam
suatu persetujuan sangat sedikit punya makna legal menurut
profesor itu. Kecuali terwujud kerjasama antara negara, tak akan
mungkin tercegah negara itu mengejar kekuasaan atau memaksanya
membagi kekayaannya. Kerjasama ini pun bukan suatu kewajiban
legal. Menurut Wassenbergh, bukan lagi saatnya, seorang astronot
bisa dianggap duta umat manusia. Bahkan prinsip antariksa yang
bebas dan tak dapat dimiliki sudah mulai usang. "Semakin besar
kepentingan manusia menjangkau antariksa, ia akan--seperti
halnya di perairan internasional dan dasar samudra--membela
kepentingan nasionalnya," ujar Wassenbergh.
Ia pun yakin bahwa konsepsi tenung anuriksa itu akan ditinjau
kembali dan kebebasan kawasan itu hanya di luar batas, tempat
kepentingan nasional belum ada manfaat konkrit. Kolonisasi
antariksa oleh negara besar hanya bisa dicegah tampaknya hanya
melalui persetujuan negara sedunia tentang prinsip legal yang
mengatur koperasi internasional.
Betapa peliknya masalah hukum anuriksa itu terungkap dalam suatu
aspek yang sangat mendasar, ialah penentuan batas antara kawasan
antariksa dan kawasan udara nasional. Batas itu, "justru sumber
kontroversi," komenur Wassenbergh.
Secara longgar kini batas itu dianggap berada di antara
ketinggian 110 dan 160 km di atas permukaan bumi. Ini bersumber
dari kaidah bahwa pada ketinggian ini sebuah benda tak bertenaga
dapat mengitari bumi dalam suatu orbit bebas. Namun dengan
meningkatnya teknologi dan bermunculan satelit telekomunikasi
dan cuaca yang berada dalam posisi tetap di atas ekuator,
berbagai negara mulai merasa risih. Terutama negara sepanjang
ekuator itu. Tahun 1976, sejumlah negara, termasuk Indonesia
mengajukan usul menaikkan kawasan kedaulatan nasional sampai
ketinggian 36.000 km.
Ketinggian ini memang merupakan orbit lintasan satelit
geostasioner, hingga posisinya tidak berubah relatif terhadap
bumi karena kecepatannya sama dengan perputaran bumi. Bila
wilayah kedaulatan nasional naik sampai ketinggian itu, negara
pemilik satelit itu paling tidak harus minta izin pada negara
yang bakal "ditempati."
Siapa Pemilik Puing
Soal itu serta-merta ditolak dunia internasional. Sejak itu
posisi Indonesia lebih moderat, mungkin juga didorong kenyauan
bahwa satelit nasional Indonesia, Palapa, bermukim di atas
perairan internasional, sebelah selatan Sri Lanka. Kini
Indonesia tidak secara eksplisit menentukan suatu ketinggian,
tapi batas itu.hendaknya bisa menjamin perkembangan ilmu dalam
memanfaatkan antariksa.
Tapi Indonesia juga tidak melupakan masalah satelit geosusioner,
apalagi saat ini di atas wilayah Irian Jaya sebuah satelit
pengamat cuaca Jepang bercokol. "Hendaknya tentang masalah itu
diadakan suatu pengaturan khusus, yang juga bisa menjamin
kepentingn negara yang ada di bawahnya," ujar Ketua LAPAN. Ini
diakuinya sebagai aspek hukum antariksa yang paling mendesak
bagi Indonesia. "Kita ingin ini segera terwujud hukumnya,"
ujarnya. "Justru karena semakin jenuh."
Kejenuhan agaknya tidak hanya di kawasan orbit geostasioner.
Saat ini ribuan benda buatan manusia mengitari bumi pada
berbagai ketinggian. Sebagian terbesar habis terbakar dalam
atmosfir bumi bila jatuh kembali. Namun ada saja kemungkinan
benda itu tidak habis terbakar, hingga menimpa wilayah suatu
negara berdaulat. Ini yang menjadi kenyataan Maret lalu di
Gorontalo. Juga ketika satelit Soviet Cosmos 954 menimpa Kanada
1978 dan ketika Skylab menyebar sebagian puingnya di wilayah
Australia (1979.
Menghadapi kenyataan demikian banyak negara saat ini berpegang
pada Konvensi PBB tentang Tanggungjawab Internasioal atas
Kerusakan Akibat Benda Antariksa. Konvensi itu --disahkan tahun
1972--lebih disempurnakan tahun 1975 dengan Konvensi PBB tentang
Kewajiban Mendaftar Benda yang Diluncurkan ke Antariksa.
Dalam kasus kejatuhan puing roket di Goronulo itu mungkin
Indonesia tidak akan mengajukan klaim. "Masalahnya tidak begitu
berat, dan tidak menimbulkan kerugian," ujar Sunaryo.
Siapa pemilik puing itu? LAPAN masih menunggu reaksi dari
kedubes negara yang bersangkutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini