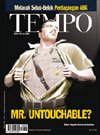Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
LADANG bom itu adalah perairan Taman Nasional Komodo. Di selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu bom ikan menjadi "menu" sehari-hari para nelayan. Bom adalah cara gampang menangkap ikan yang dikenal nelayan sekitar Pulau Komodo sejak 1950-an. Pada 1980, nyaris tak ada sejengkal laut pun yang tak pernah disinggahi bom. "Pada tahun itu seluruh kawasan ini telah menjadi ajang pengeboman ikan," kata Matheus Halim, Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Kebiasaan itu yang membuat doktor pencinta lingkungan ini gulana. Bom-bom amatiran itu pun menjelma menjadi petaka: melumatkan separuh terumbu karang di perairan taman nasional seluas 170 hektare.
Padahal laut Komodo dulu dikenal kaya fauna dan juga flora. Penelitian yang dilakukan The Nature Conservancy (TNC) pada 1995 mencatat perairan Komodo memiliki keragaman jenis karang dan ikan yang luar biasa tinggi. Di sana ditemukan tak kurang dari 253 spesies karang dan 734 spesies ikan.
Kerusakan itu mengiris-iris perasaan Helen E. Fox. Doktor biologi kelautan dari Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat, itu trenyuh saat menyelam di sana. Penyelaman tersebut kemudian mencetuskan ide untuk merehabilitasi perairan yang indahnya konon hampir menyamai Laut Banda yang terkenal itu.
Januari 1998, tiga tahun berselang setelah penelitian TNC itu, di bawah langit biru di atas perahu motor yang melaju, Helen mewujudkan impiannya. Berkali-kali ia harus membenamkan kepalanya dalam topi yang lebar. Dia berdiri di perahu yang dipenuhi batu-batu sungai dan gunung, adonan semen dan jala. Itulah hari pertama ia "menyemai" batu ke laut. "Batu-batu ini untuk membantu rehabilitasi terumbu karang yang rusak karena dibom," kata Helen, ahli konservasi laut senior pada World Wildlife Fund for Nature (WWF) Amerika Serikat, kepada Tempo. Kulit putihnya terbakar matahari. Tapi ia tak peduli. Tangannya tetap memindahkan bebatuan itu ke laut biru. Batu-batu itu diharapkan menjadi rumah bagi terumbu karang yang tersisa.
Pada batu-batu itulah terumbu karang berlindung. Batu itu dalam bahasa ilmiah berfungsi sebagai substrat, tempat karang merekatkan diri dan tumbuh. Kehadiran substrat, kata Halim, amat vital. Menurut dia, jika dalam waktu enam jam benih karang (planula) tak menemukan substrat tempat bergayut atau menempel, sang benih pasti akan mati. Pengeboman telah membuat benih karang kehilangan tempat berpijak karena bebatuan laut telah luluh-lantak menjadi puing-puing, tak bisa ditempeli planula. "Batu-batu itu terlalu kecil dan tidak stabil untuk tumbuh," ujar Soeharsono.
Di antara lautan puing bekas bom ikan itulah Helen menempatkan bebatuan bersama rekan-rekannya dari The Natural Conservancy, yakni Dr Peter J. Mous dan Jos S. Pet, Andreas Muljadi (TNC), dan Roy L. Caldwell. Pada awal proyek rehabilitasi, mereka menjajal tiga jenis substrat, yakni batu sungai, adukan semen, dan jaring. Mereka ingin tahu teknik mana yang paling murah, efektif, dan yang terpenting bahannya gampang didapat dari lokasi setempat. Ternyata, batu yang diusung Helen adalah jawabannya. "Sebab, paling berhasil dan mudah dikembangkan dalam skala besar," kata Helen.
Pada awal-awal proyek rehabilitasi, Helen mencemplungkan batu-batu itu di sembilan lokasi berskala sedang (100 meter persegi) dan empat lokasi dengan skala luas (lebih dari 1.000 meter persegi). Luas terumbu karang yang direhabilitasi itu kini mencapai 6.000 meter persegi. Kehadiran batu tersebut mempercepat penempelan bayi-bayi terumbu karang.
Ketika pertama kali memulai proyek ini, Helen menjajal teknik pencangkokan. Caranya, bayi-bayi karang itu ditempelkan pada batu, baru kemudian disemai ke laut dengan jarak tanam tertentu. Planula-planula itu rupanya tumbuh cepat. Menurut Helen, itu bukti bahwa alam Komodo sangat bersahabat dengan terumbu karang—kandungan nutrisi pada laut, sinar matahari, angin, arus laut, dan banyak faktor lainnya cocok dengan sang terumbu karang. Jadi, di Komodo tak perlu mencangkokkan bayi karang seperti di perairan Ujung Kulon dan Kepulauan Seribu. Cukup sediakan tempat berpijak tiga dimensi yang stabil: batu kali atau batu cadas. Bahkan koloni acropora, karang terbanyak di Indonesia, di laut Komodo bisa bercabang-cabang hingga berdiameter 60-80 sentimeter hanya dalam waktu empat setengah tahun. Berdasarkan catatan Helen, dalam dua tahun, di setiap meter ditemukan 12,46 bayi karang baru yang menempel pada bebatuan.
"Angka pertumbuhan itu," kata Helen, "bersaing dengan terumbu di Banda." Banda memang dikenal sebagai laut paling cocok untuk terumbu karang di Indonesia. Bandingkan dengan beberapa metode rehabilitasi lain yang pernah dilakukan di tempat lain. Di Maladewa, misalnya, penelitian Clark dan Edwards mencatat perlu waktu tiga setengah tahun agar karang bisa menghasilkan benih karang sebanyak 11,9 sampai 13,0 tempelan tiap meter persegi. Di Singapura, dengan substrat dari tiang beton, angka penempelan karang baru itu 16,4 buah per meter persegi dalam waktu 11 tahun.
Pesatnya pertumbuhan karang itu, menurut Jos S. Pet, Manajer Kelautan The Nature Conservancy wilayah Asia Tenggara, juga bisa dilihat dari luas daerah yang tertutup karang keras, tempat terumbu karang bercokol dan melambai-lambai. Hanya dalam lima tahun, daerah yang tertutup karang meluas sekitar 60 persen. Padahal di Singapura butuh waktu 11 tahun untuk membuat karang keras menutupi 31 persen dari areal percobaan.
Prestasi di Komodo itu juga dipuji Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Soeharsono. Doktor ahli laut itu menilai, dibandingkan dengan di Maladewa, pertumbuhan karang di Komodo jauh lebih baik. "Itu berarti daya dukung lingkungan di daerah tersebut masih bagus mendekati kondisi di perairan Banda," katanya. Dia bercerita, laut Banda porak-poranda pada 1987 gara-gara Gunung Banda meleduk. Namun, alam kemudian mampu menyehatkan kembali terumbu karang di sana dalam waktu tujuh tahun. "Luas areal yang tertutupi karang mencapai 80-90 persen," ujarnya. Padahal, daerah-daerah lain di Indonesia umumnya butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mengukir prestasi serupa yang dicapai Banda.
Dari sisi ekonomi, teknik rehabilitasi menggunakan batu kali atau cadas itu juga paling irit. Helen menuturkan, di pantai Florida, AS, untuk membuat substrat dari semen butuh biaya US$ 1.500 (sekitar Rp 14,4 juta) per meter persegi. Adapun di Maladewa, ongkos pembuatan batu buatan ini mencapai US$ 40 sampai US$ 160 (Rp 380 ribu hingga Rp 1,5 juta) per meter persegi. Bandingkan dengan batu yang dikumpulkan Helen, yang biayanya hanya US$ 5—kurang dari Rp 50 ribu—tiap meter persegi. Ini sudah termasuk biaya penyediaan batu kali, transportasi, sewa perahu, dan upah tenaga kerja.
Temuan Helen itu, meski sederhana, adalah terobosan penting buat Indonesia. Sudah lama negeri seribu laut ini sengsara karena kerusakan terumbu. Berdasarkan data Soeharsono, penangkapan ikan dengan bom diperkirakan telah menjadi penyebab terpangkasnya pendapatan nelayan, pelaku pariwisata, dan kawasan konservasi. Kerugian itu konon mencapai US$ 570 juta hingga US$ 3 miliar (Rp 5,4 triliun hingga Rp 28,8 triliun) untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebuah kerugian yang membuat miris.
Agus Hidayat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo