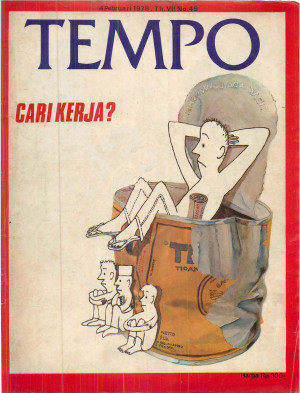MENGAPA Pejambon? Daerah yang kini dikenal sebagai tempat
Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta itu dulu adalah
kampung yang terkenal lantaran pohon jambunya.
Dan mungkin daerah Gambir juga terkenal lantaran pohon gambirnya
Menteng karena pohon menteng Baccauren racemosal Begitu pula
Cempaka Putih, Gandaria, Ketapang, Bungur, dan sebagainya. Bisa
dibayangkan dari situ: Jakarta dulu adalah bumi yang rimbun
bervariasi.
Bayangan ini dilontarkan oleh pimpinan Fakultas Biologi
Universitas Nasional (Unas) kepada Gubernur DKI Tjokropranolo,
yang meletakkan batu pertama laboratorium biologi Unas di
Ragunan, Pasar Minggu, dua pekan silam. C.J. Sugiarto M.Sc,
Wakil Dekan fakultas itu mengharapkan agar para sejarawan mau
membantu para ahli biologi menyelidiki asal-usul nama pepohonan
yang banyak tersebar - dan diabadikan? -- dalam nama kawasan di
Jakarta.
Mungkin untuk kenangan juga. sebagai balasjasa atas bantuan DKI
menyumbangkan tanah 6000 MÿFD serta uang Rp 25 juta buat membangun
gedung laboratorium itu Unas menghadiahkan dua bibit pohon kepada
Gubernur: pohon ketapang ~(Terminalia catappa Linn) untuk ditanam
di daerah Ketapang, dan pohon salak ~(Salacca edulis Reinw) untuk
ditanam di daerah Condet, yang dulu terkenal salaknya. Kedua
batang pohon yang baru semeter tingginya itu diserahkan secara
simbolis oleh Rektor Unas sendiri, Prof. Takdir Alisyahbana.
Sayangnya: Mono
Fakultas Biologi Unas tentunya tak sekedar ingin memugar
berbagai kampung dan kawasan di Jakarta dari sudut sejarahnya
semata-mata. Pertimbangannya seperti diutarakan Sugiarto kepada
TEMPO lebih menyangkut Penghijauan dan kestabilan eko-sistem
kota Jakarta sendiri.
"Dari sudut penyegaran udara," katanya, "penghijauan yang
dilakukan DKI memang sudah baik." Dinas Pertamanan DKI menanam
banyak pohon besar yang menyaring zat asam arang (CO2) di udara,
dan menghasilkan zat asam (O2) bagi pernatasan manusia. Sehingga
udara terasa lebih segar, dan sejuk.
Sayangnya, pepohonan yang ditanam menjurus pada satu jenis saja.
Semacam monokultur. Terutama monokultur accacia (akasia) yang
memang cepat tumbuh sehingga sudah populer di mana-mana. Di
kampus Fakultas Kedokteran UKI di Cawang misalnya, pohon-pohon
akasia dengan bunga kuningnya yang menjurai-jurai telah
menciptakan suasana teduh, segar dan hijau. Agak terlambat, tapi
tetap berarti, ialah usaha di kampus LPKJ yang hampir tanpa
pohon itu: sebatang akasia dimulai di antara lantai.
Selain cepat tumbuh, akar akasia kaya dengan butir zat lemas,
sehingga mempersubur tanah untuk penghijauan selanjutnya. Tanpa
perlu banyak menghambur-hamburkan urea--yang berasal dari minyak
bumi yang semakin langka itu.
Namun akasia yang sangat digemari DKI itu sebenarnya bukan pohon
asli di kawasan pantai seperti Jakarta. Juga pohon itu--atau
mahoni, flamboyan dan angsana yang juga banyak ditanam Dinas
Pertamanan DKI - tak menghasilkan buah atau biji yang digemari
burung yang dulu juga tergolong "penduduk Jakarta."
Karena itu agaknya usaha Seksi PPA (Perlindungan & Pengawetan
Alam) DKI melepaskan burung-burung di Jakarta, tak banyak
hasilnya. Soalnya, bagi burung jalak-jalakan itu kurang sekali
habitat (lingkungan hidup) yang sesuai di kawasan DKI ini. Atau
mengutip ucapan Sugiarto: "Penghijauan yang monokultur itu,
diduga telah merubah ekologi asli daerah ini."
Dua Kupu-kupu di London
Kalau begitu, mengapa tak mengubah penghijauan yang monokultur
dengan penghijauan yang bervariasi? Itulah yang tersirat dalam
penghadiahan bibit ketapang dan salak Condet kepada penguasa
tunggal DKI itu. "Di Gang Asem misalnya," kata Sugiarto,
"marilah kita tanam pohon asem kembali." Dan di jalan Ketapang
pohon ketapang, di Pejambon pohon jambu.
Kata Sugiarto kepada Gubernur: "Kan lebih enak kalau sore hari
kita bisa menikmati udara segar, sambil mendengar kicau burung.
Bukan burung di sangkar, tapi burung yang terbang bebas."
Bagi Sugiarto, yang menyebut gagasan ini "monumen hidup di
tengah monumen beton," masalahnya bukan sekedar kenikmatan sore
hari. Ia mengambil contoh kota London. Digambarkannya betapa
pentingnya keseimbangan ekologis antara kota, pepohonan, burung
dan manusia itu. "Ada dua jenis kupu-kupu di London, yang
mengadakan adaptasi terhadap debu industri di kota itu,"
katanya. Yang satu berubah warnanya jadi kelabu, yang lain tetap
kuning. Burung pemakan kupu-kupu itu, hanya mampu melihat yang
kuning. Sedang yang kelabu lolos. Padahal kedua jenis kupu itu
suka merusak tanaman. Tapi setelah kupu yang kelabu lolos dari
seleksi alamiah itu, dan populasinya tak terkontrol lagi oleh
burung, tanaman di kota London juga lebih banyak dirusak. Dan
London terancam tandus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini