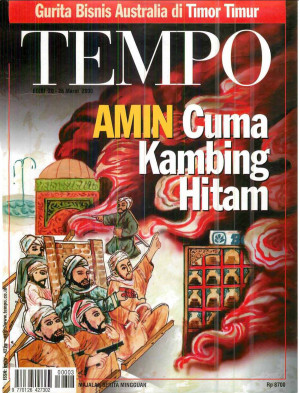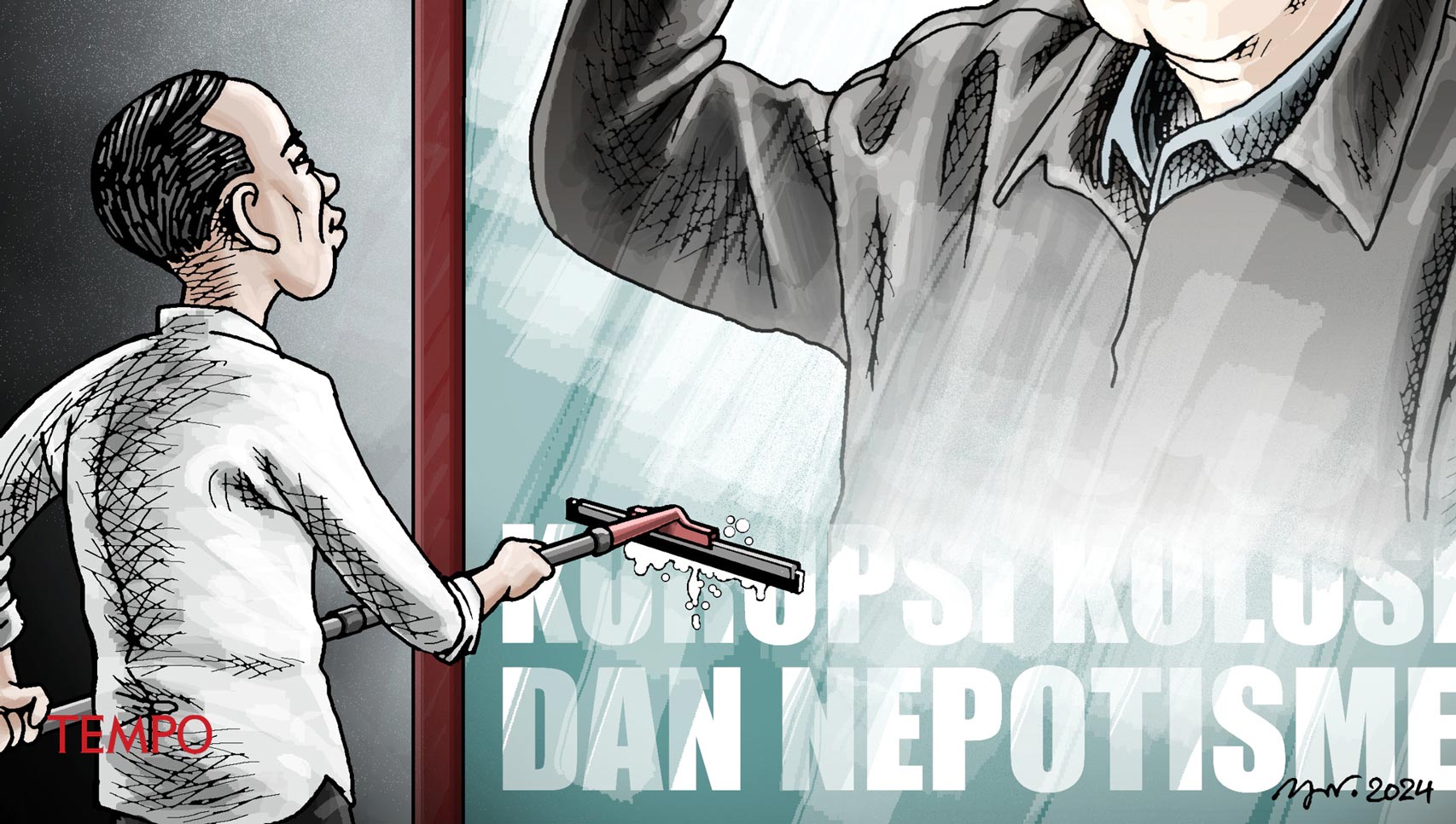Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
”Barang siapa menguasai informasi, ia akan menjadi pemenang”. Agaknya para politisi di negeri ini sedang berlomba-lomba menjadi ”pemenang”. Era ”monopolitik”, yang pada masa lampau kerap kali muncul di TVRI, tampaknya telah berubah bentuk, tidak lagi didominasi oleh televisi pemerintah. Sekarang, siapa saja yang berani membayar boleh menyampaikan visi politiknya di televisi swasta. Tampaknya itulah yang menjadi model dewasa ini dan diminati kelompok atau individual politik tertentu, yaitu melalui blocking time.
Model penyampaian visi politik semacam ini ramai diperbincangkan banyak kalangan ketika Setiawan Djody dan Kantata Revolvere-nya mendominasi siaran beberapa televisi swasta—SCTV, TPI, dan Indosiar—selama kurang lebih dua jam penuh tanpa iklan.
Tindakan Setiawan Djody itu pada era reformasi dan demokratisasi ini sebetulnya wajar saja. Sebagai seorang yang terjun dalam kancah politik praktis, tentunya Djody berkepentingan untuk menyosialisasikan pemikiran-pemikirannya agar diketahui khalayak banyak, sementara televisi butuh pemasukan demi kelangsungan bisnisnya. Klop.
Lalu, mengapa tindakan semacam ini dianggap telah melanggar hak konsumen mendapatkan informasi alternatif? Anggapan semacam ini menurut saya bernuansa fasis dan merupakan logika ”pembodohan” terhadap masyarakat. Atau, logika itu dikembangkan karena ada hal lain seputar diri Djody di masa lalu? Saya hanya ingin mengajak kita semua belajar bersikap dewasa dalam menilai sesuatu. Jika Djody dianggap telah merampas hak konsumen, laporkan saja ke polisi dan seret ke muka pengadilan.
Pada zaman Orde Baru, banyak hak-hak konsumen telah dilanggar. Contohnya, ketika Bapak Soeharto dan para konglomerat kroninya melakukan blocking time atas siaran televisi milik rakyat (baca: TVRI) sambil berjalan-jalan di kandang kerbau milik Pak Harto di Tapos. Masih banyak lagi hal-hal serupa di masa lampau yang menuntut pembelaan para pejuang hak-hak konsumen.
Teori jurnalistik mengatakan, sebuah tayangan televisi yang dikemas sebagai satu karya jurnalistik harus memenuhi kode etik, misalnya harus seimbang dan tidak memihak. Fenomena Setiawan Djody itu tidak bisa dipersalahkan. Yang harus dipersoalkan justru adalah para pewawancaranya, Eep Saefulloh dan Mohammad Sobary, yakni mengapa seolah-olah mereka ketika itu seperti ”murid mendengarkan gurunya menjelaskan sesuatu hal”. Akibatnya, jadilah acara itu semacam ”pidato tunggal” Djody.
Mestinya, Eep dan Sobary bersikap mewakili rasa ingin tahu masyarakat. Misalnya, apa yang dimaksud Djody dengan Kantata Revolvere, revolusi kebudayaan atau sosial-demokrat generasi ketiga, yang kerap kali ia ungkapkan dalam wawancara itu. Apakah Djody sedang merancang suatu ”pemberontakan” lewat jalan revolusi, sehingga demi rencananya itu ia merasa perlu menggunakan media televisi untuk mengajak kita mendukung rencananya itu?
Pada tataran inilah diperlukan peran pewawancara yang kritis, agar ia tidak mengundang mispersepsi yang dapat merugikan para pemirsa ataupun orang yang diwawancarai. Intinya, gejala blocking time ”politik” dalam tayangan televisi swasta adalah buah reformasi, yang banyak melahirkan politisi baru dan partai politik di panggung perpolitikan nasional yang butuh ruang untuk menyampaikan berbagai visi politik mereka pada khalayak di negeri ini.
Agar tidak terjadi complaint atas tayangan model itu, perlu kode etik tentang blocking time ”politik” dalam tayangan televisi kita, khususnya televisi swasta, ketimbang kita berdiskusi apakah itu melanggar hak konsumen atau tidak. Wong, aturan atau kode etiknya saja belum ada!
ERICK B.
Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo