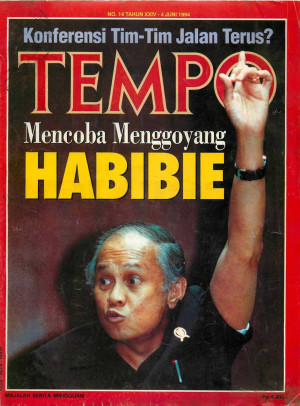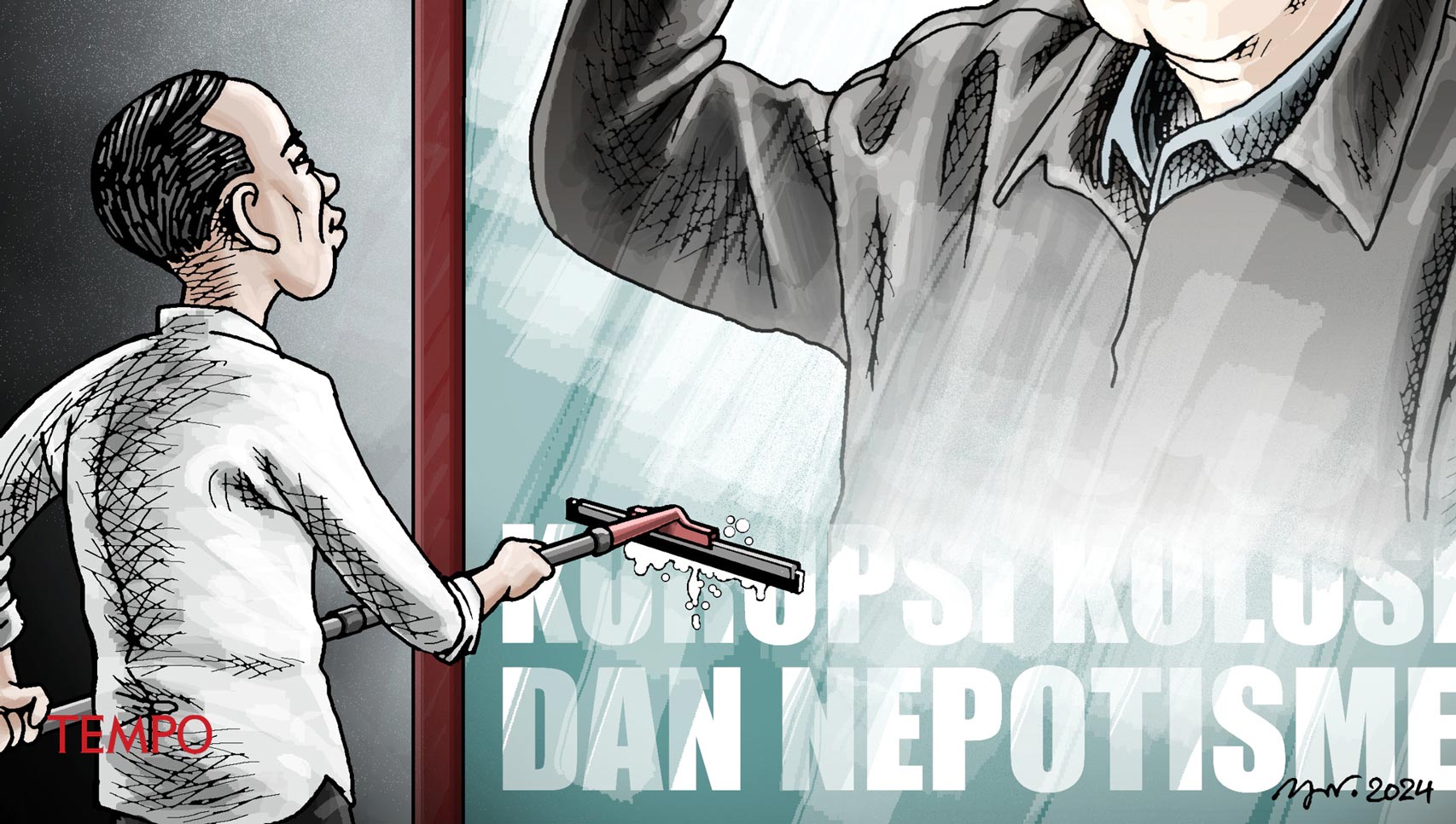Memanfaatkan Situasi Setelah Deregulasi SEJAK deregulasi perbankan dilancarkan pada 1988, industri perbankan di Indonesia tak pernah sepi dari goncangan. Tiap tahun kita menyaksikan ada bank-bank yang dilanda kesulitan. Peristiwa ini menimbulkan berbagai macam penafsiran. Salahkah deregulasi perbankan ? Atau, sudah siapkah bank-bank diberi kebebasan dalam melakukan operasinya ? Atau, deregulasi merupakan sesuatu yang baik untuk pertumbuhan industri perbankan, tapi beberapa pengusaha yang serakah, baik yang mempunyai perusahaan didalam kelompok atau diluar kelompok bank, memanfaatkan situasi untuk mengeduk keuntungan sebanyak- banyaknya atas pengorbanan bank. Pemerintah sendiri nampaknya tidak tahu pasti apa yang mesti dilakukan. Berbagai peraturan telah dikeluarkan baik yang memperketat atau yang melonggarkan gerak gerik bank. Reaksi dan respons bank-bank terhadap sebuah peraturan perbankan memang sulit diantisipasi. Itulah sebabnya, BI, sebagai lembaga yang tugasnya mengawasi kesehatan bank-bank nampak agak kedodoran dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Banyak bank yang melakukan pelanggaran L-3 misalnya lewat begitu saja. Tak ada sanksi, tak ada peringatan dini, tahu tahunya banknya sudah megap megap. Ada beberapa alasan kenapa sulit bagi BI untuk melaksanakan fungsinya dengan konsekwen. Mungkin kurang tenaga, atau menghadapi persekongkolan politis yang kuat, atau karena beberapa peraturan pemerintah ternyata tidak praktis untuk dipenuhi. Tapi yang paling sulit mungkin adalah mengawasi bank- bank yang jumlahnya melonjak sejak lima tahun terakhir. Dalam waktu lima tahun sejak Pakto 1988, jumlah bank meningkat dari 111 pada 1988 menjadi 231 pada 1993. Jumlah kantor bank naik lebih pesat lagi , dari 1700 pada 1988, menjadi 4500 pada 1993. Perkembangan pesat ini menghadapkan BI dengan masalah pelik, bagaimana melakukan pengawasan yang efektif. Kekurang mampuan BI dalam melakukan pengawasan memperbesar risiko timbulnya krisis perbankan.Dan situasinya nampaknya masih runyam, kalau dilihat, bahwa tenaga tenaga perbankan yang tersedia tidak sebanding dengan lonjakan permintaan. Mutu, tenaga yang kurang memadai ini masih akan menimbulkan beberapa goncangan dalam industri perbankan. Deregulasi, yang berarti meningkatnya persaingan memaksa bank- bank untuk melakukan penyesuaian. Dan penyesuaian ini nampaknya cukup berat terutama bagi bank-bank pemerintah. Sejak deregulasi perbankan, kinerja bank-bank pemerintah terus merosot. Mereka masih kaget menghadapi gebrakan bank swasta yang sangat agresip. Masalah mereka menjadi lebih rumit dengan selalu adanya tekanan-tekanan dari pejabat tinggi lewat katabelece, yang menghalangi bank-bank pemerintah mempraktekkan prinsip-prinsip perbankan yang murni. Mungkin karena deregulasi perbankan merupakan sesuatu yang baru, sehingga dampaknya sering kali tidak diduga, pemerintah , selama lima tahun terakhir ini mengeluarkan serangkaian peraturan yang menunjukkan masih adanya trial and error. Setelah meledak pada 1990 dan 1991, bisnis perbankan lesu. Pertumbuhan kredit yang seret cukup menghambat perkembangan moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Sampai akhirnya pada Mei 1993, pemerintah "menyetel" lagi beberapa peraturan, yang memperlonggar ruang gerak bank. Bangkit Lagi Setelah Lesu PERBANKAN, setelah pertumbuhannya agak tertekan pada 1991 dan 1992, pada 1993, mulai bergairah lagi, dan menghasilkan pertumbuhan aset yang lebih besar. Aset seluruh perbankan naik 28% pada 1993, setelah pada 1991 dan pada 1992, masing masing hanya naik 14% dan 12%. Pertumbuhan aset bank sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan kredit yang diberikan, karena pinjaman merupakan komponen aset yang paling besar dan paling penting. Ada beberapa faktor, kenapa pertumbuhan aset pada 1991 dan 1992 agak rendah. Pertama, masih adanya dampak kebijaksanaan kredit ketat (TMP) pemerintah. Kedua makin ketatnya peraturan BI yang digunakan untuk memonitor kesehatan bank. Dan yang tak kalah pentingnya, situasi dunia usaha yang tidak menentu dilihat bank-bank sebagai mempunyai risiko yang besar, sehingga bank- bank sangat hati hati dalam memberi kredit. Mereka lebih suka menempatkan dananya di SBI yang suku bunga cukup tinggi, dan aman, tanpa ada risiko. Larisnya instrumen SBI sebagai tempat penyaluran dana perbankan ini menjebabkan melonjaknya posisi SBI pada 1991 dan 1992, yang mengakibatkan BI harus menanggung beban sekitar RP 1 triliun untuk membayar bunga SBI yang pada 1991 berkisar antara 18% dan 15% pada 1992. Pada akhir 1991, posisi SBI mencapai Rp 11 triliun, pada hal awal tahun baru berjumlah Rp 1,5 triliun. Pada akhir 1992, posisi SBI melonjak dua kali lipat menjadi Rp 21 triliun. Kemampuan bank-bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat pada 1993 juga cukup mengagumkan. Dana masyarakat yang ditarik bank-bank pada 1993, melonjak 90%. Ini terjadi justru pada saat, suku bunga deposito turun. Bank bank swasta memang nampak lebih agresip dalam menarik dana masyarakat, dengan mengeluarkan berbagai produk baru disertai berbagai pemberian hadiah yang cukup merangsang. Kenaikan dana masyarakat sebesar 90% ini , lebih besar dari kenaikan pada 1992 yang hanya 13% dan kenaikan pada 1991 , sebesar 67%. Prestasi bank-bank pemerintah dalam meningkatkan pengumpulan dana masyarakat cukup bagus. Dana pihak ketiga yang berhasil ditarik BNI meningkat 27%. Yang berhasil ditarik Bank Exim dan BBD, masing masing naik 34% dan 22%. Hanya BRI dan BDN yang lamban dalam meningkatkan dana masyarakat ini. Dana yang ditarik BRI hanya naik 5%, dan yang ditarik BDN naik 7%. Ironisnya, justru Bapindo yang berhasil meningkatkan dana masyarakatnya dengan spektakuler. Dana masyarakat yang berhasil ditarik Bapindo pada 1993 melonjak 97%, atau kenaikan hampir dua kali lipat. Kemungkinan besar ini terjadi sebelum terungkapnya kredit macet. Disamping itu, promosi Bapindo lewat iklan di RCTI yang dilakukan dengan gencar, pada saat itu, nampaknya cukup berhasil untuk menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di Bapindo. Di jajaran bank swasta papan atas dan tengah, beberapa bank berhasil meningkatkan penarikan dana masyarakat lebih dari 50% seperti Bank Danamon, Bank Universal dan Bank Harapan Sentosa. Kenaikan deposito perbankan juga akibat adanya perobahan status beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang menurut UU Perbankan 1992 mereka sekarang menjadi bank umum, yang dapat menerima deposito atau simpanan dari masyarakat. Bank PDFCI misalnya, dana masyarakatnya pada akhir 1993 mencapai Rp 205 miliar, padahal setahun sebelumnya, waktu masih menjadi LKBB dana pihak ketiganya cuma Rp 6 miliar. Deposito Uppindo dan Ficorinvest, keduanya mantan LKBB, pada 1993 meningkat masing masing dengan 217% dan 289%. Jumlah kredit yang diberikan seluruh bank-bank pada 1993 meningkat 24%, setelah pertumbuhannya tertekan pada 1992, dimana kredit hanya bertambah 13%. Bank bank pemerintah, yang masih menghadapi masalah permodalan yang kecil dan kredit macet, selama 1993, lebih banyak melakukan konsolidasi dari pada melakukan ekspansi kredit. Langkah mereka dalam penyaluran kredit sangat hati hati, dan tidak seagresif bank-bank swasta. Ekspansi kredit bank-bank pemerintah cukup moderat. BNI, bank pemerintah terbesar, menambah kreditnya dengan 17%, padahal dana masyarakat yang dikumpulkannya naik 27%. Bapindo, yang berhasil meningkatkan dana masyarakat hampir 100%, hanya meningkatkan kreditnya 12%. BRI, BDN dan Exim, masing masing hanya menambah kreditnya dengan 6%, 9% dan 8%. Kredit BBD, bahkan turun 0,8%, padahal dana masyarakat yang dikumpulkannya naik 22%. Perkembangan ini berbeda dengan yang terjadi pada bank-bank swasta papan atas. Pada umumnya mereka sangat agresip dalam meningkatkan kredit, dan tingkat kenaikannya lebih besar dari kenaikan dana yang dikumpulkannya dari masyarakat. Bank Danamon, Lippo Bank dan bank Panin misalnya meningkatkan pemberian kreditnya lebih dari 50%. Kekecualian hanya terjadi pada bank swasta terbesar BCA. Pada 1993, posisi kredit BCA hanya naik 5%. Sebagai refleksi adanya kondisi perbankan yang lebih baik, maka laba seluruh bank-bank pada 1993 meningkat 94%, yang merupakan titik balik dari kondisi pada 1991 dan 1992, dimana saat itu, laba seluruh bank masing masing turun 2% dan 9%. Kenaikan laba sebesar itu, terutama disebabkan meningkatnya laba bank-bank pemerintah kecuali Bapindo, yang merupakan satu satunya bank pemerintah yang mengalami penurunan laba. Laba BDN misalnya naik 215% menjadi Rp 190 miliar. Laba BNI naik 52% dan laba BBD naik 73%. Diantara bank swasta, BII merupakan bank swasta yang menghasilkan laba terbesar. Pada 1993, laba BII meningkat 39% menjadi Rp 166 miliar. BCA saja, yang asetnya lebih dua kali lipat aset BII, hanya memperoleh laba Rp 100 miliar. Dan sekalipun aset BII jauh dibawah aset bank-bank pemerintah, tapi laba BII lebih besar dari laba yang diperoleh Bank Exim, BBD atau BRI. Motor Penggerak Kredit Bank PAKET peraturan perbankan bulan Mei 1993, ( Pakmei ) dikeluarkan pemerintah sebagai respons terhadap sikap perbankan yang terlalu hati hati dalam pemberian kredit. Pada kuartal pertama 1993, menjelang dikeluarkannya Pakmei, kredit bank hanya naik 1%. Bank-bank bersikap hati hati dalam memberikan kredit, karena khawatir melanggar rasio-rasio yang ditetapkan Bank Indonesia, hingga bisa mengurangi tingkat kesehatannya. Mereka lebih senang menggunakan kelebihan dananya untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ). Simpanan dalam bentuk SBI ini, disamping bunganya relatif tinggi, juga aman. Lebih aman, dari pada disalurkan sebagai kredit ke pengusaha, karena situasi bisnis masih belum menentu. Penyaluran kredit dalam situasi seperti ini, dinilai bank, mempunyai risiko tinggi. Dengan banyaknya dana bank yang disimpan dalam bentuk SBI, maka jumlah SBI terus meningkat sejak triwulan dua 1992, sampai triwulan satu 1993, padahal, suku bunga SBI dalam jangka waktu yang sama terus turun. Pada akhir Juni 1992, posisi SBI masih Rp 15,5 triliun. Pada akhir tahun 1992, posisi ini naik menjadi Rp Rp 20,6 triliun, dan pada triwulan satu 1993, posisinya naik lagi menjadi Rp 23 triliun. Pada akhir Juni 1993, setelah Pakmei, posisi SBI turun menjadi Rp 18,7 triliun. Suku bunga SBI, antara Juni 1992 dan 1993 turun dari 16,5% menjadi 9,6%. Akibat tertumpuknya dana perbankan sebagai SBI, maka beban BI dalam membayar bunga SBI ini cukup berat, yang memaksa BI untuk terus membuat SBI kurang menarik. Sementara itu, BI, sudah mulai melakukan pengawasan yang ketat terhadap perbankan. Ukuran dan rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank benar benar diberlakukan oleh BI. Ketatnya pembatasan-pembatasan ini juga merupakan salah satu sebab, bank -bank kurang berani meningkatkan pemberian kreditnya. Keadaan ini mengakibatkan, bahwa dalam triwulan pertama 1993, bank-bank pemerintah, hanya menambah pemberian kreditnya 1,3%, dan bank-bank swasta nasional hanya menambah 0,5%. Dengan dikeluarkannya Pakmei pada Mei 1993, pembatasan- pembatasan yang dihadapi perbankan, seperti dalam penghitungan CAR dan LDR, sudah dilonggarkan. Ini berarti perbankan menjadi lebih leluasa untuk melonggarkan ekspansi kreditnya. Pakmei dikeluarkan pada saat, suku bunga mulai turun, dan kegiatan investasi meningkat. Maka pada triwulan kedua 1993, kita menyaksikan "peledakan" pemberian kredit perbankan. Dalam triwulan itu, kredit perbankan melonjak dengan 8,4%, atau hampir menyamai jumlah kenaikan kredit untuk seluruh tahun 1992. Pelonjakan kredit ini ternyata 90% berasal dari bank swasta nasional. Kredit dari bank pemerintah hampir tidak bertambah. Ini merupakan indikasi bahwa beberapa bank pemerintah mempunyai masalah dalam besarnya kredit yang bermasalah, disamping juga masih kecilnya modal. Situasi seperti ini dengan sendirinya tidak mungkin mendukung ekspansi kredit. Karena itu, dalam triwulan kedua itu, kredit dari bank pemerintah cuma naik 0,1%. Kenaikan kredit bank swasta nasional mencapai 22,1%. Lemahnya pertumbuhan kredit bank pemerintah, dan kuatnya pertumbuhan kredit bank swasta ini terus berlangsung sampai menjelang akhir 1993. Selama sebelas bulan pertama 1993 sampai Nopember, aliran kredit perbankan sudah jauh lebih deras dari aliran pada 1992. Kredit bank meningkat 18%, atau dua kali lipat pertambahan pada 1992. Kredit bank swasta nasional naik 40%, sedang kredit bank pemerintah hanya naik 4%. Dominasi bank pemerintah terhadap pangsa pemberian kredit turun dari 55% pada 1990 menjadi 48% pada 1993. Ekspansi kredit yang besar, seperti yang terjadi pada 1993, diperkirakan tidak akan berulang lagi pada 1994. Bank-bank pemerintah, yang menguasai hampir 50% kredit perbankan, masih mengalami beberapa masalah, seperti besarnya kredit macet, dan masih kecilnya modal. Bank swasta, yang merupakan motor ekspansi kredit pada 1993, diperkirakan akan bersikap lebih hati hati lagi, dengan mencuatnya ke permukaan masalah kredit macet yang dialami bank-bank pemerintah. Disamping itu, mereka masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pemberian kredit KUK sesuai dengan ketentuan. Hanya bank asing dan bank campuran yang nampaknya mempunyai peluang untuk melakukan ekspansi kredit yang cukup besar. Namun pangsa kredit mereka hanya 8%, jadi tidak mempunyai dampak yang cukup berarti bagi pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Kenapa Kaget Dengan Kredit Macet ? PADA Pebruari 1993, ketika Booz Allen & Hamilton, sebuah konsultan manajemen mengungkapkan perkiraannya tentang besarnya kredit bermasalah bank-bank di Indonesia yang mencapai 5- 20% dari kredit yang diberikan, banyak orang tidak percaya. Dari mana BAH memperoleh perhitungan itu ?. Perhitungan BAH menunjukkan bahwa ROA 5 bank pemerintah terus merosot sejak 1987, dan mencapai titik terendahnya pada 1992, bahkan memproyeksikan hasil negatip pada periode berikutnya. Empat tahun sebelumnya, atau satu tahun setelah deregulasi perbankan 1988, Kenneth R. Wynn, seorang analis keuangan dan Presdir PT Multicor, sebuah merchant banking di Jakarta, memperingatkan akan terjadinya krisis perbankan, bila masalah kualitas manusia tidak diperhatikan. Deregulasi perbankan, mengakibatkan peledakan permintaan terhadap tenaga perbankan yang profesional. Masalahnya adalah bahwa untuk industri perbankan, yang penting bukan saja profesionalisme, tapi juga integritas, moral dan etika dari pelaku-pelaku perbankan. Tanpa ini, perbankan tak akan memperoleh kepercayaan dari publik. Pernyataan Wynn dan perkiraan BAH tentang besarnya kredit bermasalah ternyata memang menjadi kenyataan. Indikasi pertama tentang kebenaran ini dikemukakan oleh Mansjurdin Nurdin, salah satu direktur BI, yang mengemukakan di depan Komisi VII DPR pada Desember 1993, bahwa enam bank pemerintah telah melanggar "legal lending limit" dan bahwa mereka mempunyai cukup banyak kredit bermasalah. Dikatakannya, bahwa dari pemeriksaan terhadap 50 nasabah terbesar pada tiap bank pemerintah, diperoleh indikasi kuat, bahwa bank-bank pemerintah telah melanggar ketentuan tentang L-3. Gambaran mendetil tentang kredit bermasalah ini kemudian diberikan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad kepada DPR, beberapa waktu kemudian. Jumlah kredit bermasalah yang dialami bank-bank pemerintah pada Oktober 1993 menurut Mar'ie mencapai Rp 15 triliun, atau 21%, dari jumlah kredit yang diberikan. Angka ini ternyata tidak jauh meleset dari perkiraan BAH. Jumlah kredit bermasalah ini terus meledak sejak 1990. Pada waktu itu, jumlahnya baru Rp 3,2 triliun, atau 6% dari jumlah kredit. Pada 1991, jumlahnya melonjak lebih dua kali lipat menjadi Rp 7 triliun , atau 11% dari jumlah kredit. Pada 1992, jumlahnya meningkat lagi menjadi Rp 12 triliun, atau 17% dari jumlah kredit. Dengan demikian, peningkatan kredit yang terjadi selama empat tahun terakhir selalu diikuti dengan peningkatan kredit bermasalah. Untuk mengetahui latar belakang peristiwa ini, memang perlu diingat situasi perbankan diakhir tahun 1980-an. Dengan adanya deregulasi perbankan, bank-bank tiba tiba kebanjiran deposito dari masyarakat, yang tertarik dengan suku bunga yang sudah tidak diatur pemerintah lagi, tapi diserahkan kepada pasar. Bagi bank ini merupakan beban biaya, dan hanya bisa ditutup dengan menyalurkan dana ini sebagai kredit. Terjadi persaingan sengit diantara bank-bank untuk memberi kredit kepada perusahaan-perusahaan. Begitu sengitnya persaingan , sehingga penilaian proyek nasabah untuk pemberian kredit dengan gampang dilakukan, tanpa analisa yang hati hati. Bahkan ada bank-bank pemerintah, yang menawarkan dana begitu saja kepada nasabahnya, "untuk dipakai sewaktu waktu". Bagi pegusaha yang jeli, saat itu merupakan kesempatan yang luar biasa untuk mendapat kredit dengan gampang. Mereka melakukan "blow-up", meninggikan biaya investasi proyek atau pabrik yang diajukan. Kelebihan kredit yang diperoleh, digunakan untuk apa saja semau dia. Kredit bisa diperoleh tanpa prosedur yang wajar, dan tanpa kolateral yang memadai. Kolusi antara penjabat bank dan pengusaha tak terelakkan. Maka ketika pemerintan melakukan TMP pada 1991, bank-bank dan nasabah, kelabakan, karena ternyata kredit yang diberikan bank tersebut, tidak jelas penggunaannya, tidak menghasilkan seperti yang dijanjikan dalam proposal proyek, dan si nasabah tak mampu membayar bunga, dan akhirnya, pembayaran bunga dan jumlah pokoknya macet. Tentu saja yang mengalami kredit bermasalah bukan saja bank- bank pemerintah, tapi juga bank swasta. Tapi persentase kredit bermasalah mereka lebih kecil, dari bank pemerintah, dan dibawah persentase nasional. Pada Oktober 1993, ketika kredit bermasalah bank-bank pemerintah mencapai 21% dari jumlah kredit, persentase kredit bermasalah secara nasional adalah 16%. Setahun sebelumnya, perbandingan kedua angka ini adalah 17% untuk bank pemerintah dan 13% untuk nasional. Persoalan kredit macet dengan sendirinya membawa dampak negatip yang cukup luas, bukan saja dalam lingkup nasional, tapi juga internasional. Lembaga-lembaga keuangan di luar negeri yang mempunyai relasi dengan bank-bank disini mulai merasa khawatir terhadap keandalan bank-bank di Indonesia. L/C yang dibuka Bapindo kabarnya sudah tidak diterima oleh bank korepondennya di luar negeri. Sementara itu, bank bank luar negeri, yang semula bergairah untuk memberi pinjaman kepada perusahaan- perusahaan Indonesia mulai mundur teratur. Banyak perjanjian kredit yang semula akan diperpanjang , tidak diteruskan. Mereka bersikap menunggu perkembangan selanjutnya. Disamping "credit rating" bank-bank Indonesia turun di pasar internasional, dampak negatip juga terjadi pada "country risk" Indonesia. Akibatnya, apabila pemerintah maupun swasta akan mencari pinjaman di luar negeri, mereka harus membayar bunga dengan premi untuk risiko, hingga bunga yang dibayar, lebih tinggi dari yang seharusnya. Bukan Sekadar Katabelece DITENGAH ramainya skandal kredit macet lebih dari Rp 1,3 triliun kepada Edy Tansil, Bapindo menyiarkan laporan keuangan tahun 1993. Sebagai bank, memang Bapindo punya kewajiban untuk menyiarkan kepada masyarakat laporan keuangannya secara periodik. Tapi kali ini, publikasi laporan keuangan Bapindo 1993, lewat iklan, terasa sebagai suatu lelucon. Juga terasa sebagai ikhtiar untuk menetralisir sorotan masyarakat terhadapnya selama ini. Atau Bapindo ingin bersikap sinis terhadap publik yang mencelanya ? Bapindo menunjukkan bahwa mereka pada 1993 memperoleh laba sebelum pajak Rp 65 miliar. Ini jumlah yang luar biasa, karena tiga kali lipat jumlah kumulatip laba tahun tahun sebelumnya. Percayakah anda terhadap angka laba Bapindo ? Ini tergantung, apakah laba tersebut sudah termasuk penghapusan ("write off") kredit macetnya. Kalau belum, maka laporan keuangan Bapindo tidak bisa diterima tanpa reserve. Dan beberapa kejanggalan memang segera nampak dari laporan keuangan Bapindo. Jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp 9,6 triliun. Padahal jumlah giro dan deposito hanya Rp 4,7 triliun. Dari jumlah kredit sebesar itu, satu orang ( Edy Tansil ) memperoleh 10% jumlah kredit yang diberikan, dari ( mungkin ) ratusan nasabah Bapindo. Luar biasa memang. Modal Bapindo, ditambah cadangannya hanya sekitar Rp 700 miliar, diantaranya Rp 600 miliar merupakan modal yang disetor pemerintah. Berarti kredit untuk satu orang ( Edy Tansil ) berjumlah sekitar 140% modal Bapindo. Ini pelanggaran berat, karena menurut peraturan BI, satu orang nasabah tidak boleh menerima kredit lebih dari 20% modal bank. Pada satu saat, kredit macet harus dihapus, dan dibukukan sebagai kerugian. Memang tidak berarti 100% dibukukan sebagai kerugian. Tapi berapa ? Lima puluh persen ? Tujuh puluh lima persen ? Berapapun angka yang anda pilih, hasil perhitungan akan menunjukkan bahwa modal Bapindo akan habis, bahkan tidak cukup untuk menutup kerugian kredit macetnya Edy Tansil. Ini belum termasuk kredit macet nasabah lain, yang pasti ada. Dengan perkatan lain, dengan musibah tersebut, Bapindo, sebagai badan hukum, secara yuridis, dan tehnis sudah bangkrut. Musibah kredit macet macet Rp 1,3 triliun kepada Eddy Tansil, nampaknya merupakan klimaks dari kemerosotan kinerja Bapindo yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1987. Pada saat itu, ROA Bapindo mengalami puncaknya dengan mencatat 2,1%. Ini menunjukkan betapa efisiennya Bapindo dalam memutarkan asetnya. Tapi sejak itu, ROA Bapindo terus merosot. Dari 2,1% pada 1987, ROA-nya turun menjadi 1,8% pada 1988, dan turun lagi menjadi 1,1% pada 1990. Pada 1992, ROA-nya cuma 0,31%, sebelum turun lagi menjadi 0,26% pada 1993. Yang mendesak sekarang ini bagi pemerintah adalah membantu Bapindo untuk membayar bank acceptance (B/A) yang jatuh waktu. Ini perlu untuk mempertahankan kredibilitas Bapindo diantara lembaga-lembaga keuangan lainnya. Soalnya, kepercayaan bank- bank koresponden Bapindo sudah sirna dengan terjadinya kredit macet ke Eddy Tansil. L/C yang dibuka Bapindo kabarnya sudah tidak diterima lagi oleh bank-bank korespondennya. Pemerintah belum mengumumkan secara rinci B/A Bapindo yang jatuh tempo. Tapi diperkirakan sekitar US$ 350 juta atau sekitar Rp 750 miliar akan jatuh tempo bulan April ini. Jelas Bapindo tak punya uang tunai untuk membayar sebanyak ini. Dana dan cadangan berupa kas dan simpanan di BI yang dimiliki Bapindo pada akhir 1993 hanya berjumlah Rp 210 miliar. Memang ada pinjaman subordinasi pemerintah Rp 972 miliar yang bisa dikonversikan sebagai modal. Cuma masalahnya, dana ini sudah terpakai untuk biaya operasional. Satu satunya sumber dana Bapindo adalah pencairan call moneynya yang pada akhir 1993 masih berjumlah Rp 1,3 triliun. Ini biasanya adalah dana jangka pendek yang segera bisa dicairkan. Kunci pemecahan masalah pelik yang dihadapi Bapindo sekarang ini adalah menggenjot labanya. Dan ini tentu saja bukan tugas ringan. Benar bahwa Bapindo memperoleh laba sebelum pajak Rp 65 miliar pada 1993. Tapi ini lebih rendah dari yang diperoleh pada 1992 yang berjumlah Rp 75 miliar. Lagi pula jumlah Rp 65 miliar tersebut menyembunyikan kelemahan struktur laba itu sendiri. Dari transaksi rupiah, mungkin karena berbagai rentetan kredit macet Bapindo mengalami rugi Rp 104 miliar. Hanya karena transaksi valasnya untung Rp 169 miliar, maka pada akhirnya Bapindo memang mendapat laba. Kalau pemerintah harus memberi injeksi dana kepada Bapindo, tidak mungkin dana tersebut diambil dari APBN. APBN 1994/95, apalagi dengan harga minyak yang masih dibawah perkiraan, akan lebih ketat lagi, hingga proyek-proyek yang dananya sudah dianggarkanpun belum tentu memperoleh dana sepenuhnya. Tapi pemerintah nampaknya masih punya jalan. Pemerintah, seperti kita ketahui masih mempunyai 25% saham Indocement. Ini diperoleh ketika, pada 1985, Indocement hampir bangkrut karena melakukan ekspansi kapasitas produksi yang berlebihan. Untuk membantu mereka, pemerintah menyuntikkan dana US$ 350 miliar. kalau harga saham Indocement sekarang ini sekitar Rp 16.000, maka pelepasan saham pemerintah di Indocement akab menghasilkan dana sekitar Rp 1,3 triliun, yang mungkin akan cukup untuk melunasi kewajiban-kewajiban Bapindo kepada pihak ketiga. Memburuknya kinerja bank-bank pemerintah sebenarnya sudah nampak sejak 1990. Kecuali BNI dan BTN, rasio laba terhadap aset (ROA) bank-bank pemerintah terus merosot. Pada 1993, ROA bank-bank pemerintah dibawah 1, kecuali untuk Bank Exim dan BTN, yang masing masing mencatat ROA 1,0 dan 1,2. ROA Bank Rakyat Indonesia pada akhir 1993 hanya 0,42, sedikit dibawah ROA Bapindo. Antara 1990-1993, ROA Bank Bumi daya merosot dari 0,63 menjadi 0,51. ROA Bank Dagang Negara, turun dari 1,2 menjadi 0,9. Dan ROA Bapindo merosot dari 1,9 menjadi 0,4. Diluar Bapindo, bank-bank pemerintah yang lain nampaknya mengalami sedikit perbaikan dalam kinerjanya. Longgarnya kondisi moneter dengan turunnya suku bunga, telah mendorong bank-bank pemerintah menaikkan lagi kreditnya sekalipun dengan sikap yang lebih hati hati. Kalau laba sebelum pajak Bapindo pada 1993, merosot 13%, maka laba ( sebelum pajak ) BNI misalnya naik 52%, laba Bank Exim naik 17%, laba BBD naik 73%, laba BRI naik 45%. Laba BDN naik 215% , cukup spektakuler, dari Rp 60 miliar pada 1992, menjadi Rp 190 miliar. Semula laba mereka dari transaksi rupiah banyak yang rugi, sehingga sebagian besar keuntungan berasal dari transaksi valas. Kini hanya BRI dan Bapindo saja yang rugi dari transasksi rupiahnya. BBD, yang selalu rugi dari teransaksi rupiahnya, pada 1993 bahkan mulai mencatat keuntungan Rp 1,4 miliar, atau 0,1 % dari total keuntungan. Kesulitan yang dihadapi bank-bank pemerintah, nampaknya mencapai puncaknya pada kuartal terakhir 1993. Publikasi yang luas tentang kredit macet yang dialami bank-bank pemerintah mulai terasa akibatnya terhadap aliran dana yang masuk bank- bank pemerintah. Barangkali untuk pertama kali dalam sejarah, terjadi penurunan deposito yang masuk dalam satu kuartal. Pada kuartal empat, deposito bank-bank pemerintah turun Rp 1,2 triliun. Jumlah deposito pada akhir 1993, berjumlah Rp 61,7 triliun, turun dari Rp 62,9 triliun tiga bulan sebelumnya. Ini berarti bahwa deposito yang berada ditangan bank-bank pemerintah tinggal 43,5% seluruh deposito, dibanding 45,8% pada akhir 1992. Dan ini berarti bahwa bank-bank swasta berhasil menggaet sebagian besar dana masyarakat. Turunnya deposito yang masuk bank-bank pemerintah mempunyai arti yang cukup penting. Apakah ini berarti kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank pemeritah mulai turun ? Atau , apakah ini menandakan bahwa bank-bank swasta makin mendapat kepercayaan dari masyarakat ? Semula, kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah memang tidak tergoyahkan. Pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung bank-banknya, berapapun biaya yang harus dikeluarkannya. Karena itu, ada persepsi dalam masyarakat, bahwa bank pemerintah tidak mungkin bangkrut, dan karena itu menyimpan uang di bank pemerintah jauh lebih aman dari menyimpan uang di bank swasta. Oleh karena itu, sekalipun kinerja bank-bank pemerintah diketahui kurang baik selama ini, kemampuannya untuk menarik deposito dari masyarakat tetap kuat. Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank- bank pemerintah akan diperlukan waktu yang cukup lama. Membenahi mismanajemen dan kredit bermasalah yang selama ini melanda bank-bank pemerintah bukan urusan mudah. Karena adanya faktor politis, pembedahan radikal terhadap bank-bank pemerintah sulit dilakukan. Dilain pihak, bank-bank swasta makin bertambah agresip, dan akan menjadi saingan yang makin berat. Pangsa deposito masyarakat yang akan masuk dan pangsa kredit yang akan diberikan bank swasta akan makin besar, dan dalam waktu dekat, dominasi perbankan di Indonesia akan berpindah tangan dari bank pemerintah ke bank-bank swasta. Pendulum Regulasi SEJARAH deregulasi perbankan di Indonesia cukup panjang. Deregulasi sektor perbankan dimulai pada 27 Oktober 1988 (Pakto 27), yang bisa dianggap sebagai sebuah "big bang". Dengan sekali pukul, izin pendirian bank baru, termasuk bank campuran asing, yang sebelumnya sama sekali tertutup, dibuka lebar lebar. Bank, yang dulu sulit bergerak,langsung dibebaskan melakukan ekspansi dengan dipermudahnya prosedur pendirian kantor, termasuk kantor cabang, serta diturunkannya cadangan wajib atau "reserve requirement" menjadi 2% aktiva. Sejak itu jumlah bank baru yang lahir tiap tahun sejak 1988 rata rata 20. Jumlah bank swasta nasional, yang pada 1988 masih berjumlah 63, pada September 1993, sudah berjumlah 155, kenaikan lebih dari dua kali lipat. Yang lebih dramatis adalah meledaknya jumlah kantor-kantor cabang. Dengan diperingannya syarat syarat pendirian kantor cabang, pada 1989, jumlah kantor cabang bank di seluruh Indonesia meningkat 850, dan peningkatan ini rupanya masih terus berlangsung . Pada 1990, jumlah kantor bertambah lagi dengan 950, dan setahun berikutnya meningkat lagi dengan 684. Pada 1992, situasi ekonomi yang tidak menentu, serta adanya pengetatan peraturan perbankan yang dikeluarkan, peningkatan jumlah kantor agak mereda. Bank-bank lebih memusatkan perhatiannya pada konsolidasi usaha, organisasi dan manajemen. Pertambahan kantor pada 1992 tercatat hanya 160. Pertambahan kantor pada 1993 ( September) hanya 131. Jumlah seluruh kantor perbankan pada September 1993 tercatat 4538. Penyebaran geografis kantor bank ini ternyata tidak merata. Dari jumlah kantor tersebut, 1441 kantor bank , atau hampir sepertiga berada di DKI Jaya. Tempat kedua terbesar diduduki Jawa Timur dengan 646 jumlah kantor bank. Bagi bank, pertambahan kantor berarti pertambahan investasi yang harus dilakukan untuk menjaring nasabah ditempat lain. Penambahan kantor berarti peluang untuk meningkatkan deposito maupun peluang untuk meningkatkan kredit, dan akhrinya rentabilitas. Menjadi masalah adalah bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga profesional untuk menangani pertambahan kantor - kantor bank yang dalam tiga tahun antara 1989-1990 meningkat dengan 2519 itu ? Kekurangan tenaga perbankan memang terasa sekali pada saat itu, sehingga terjadi pembajakan besar besaran karyawan bank oleh bank lain. Pemenuhan tenaga -tenaga perbankan yang dilakukan dengan tergesa gesa ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas mereka, karena ini akan berpengaruh terhadap kualitas perbankan sendiri. Beberapa bank yang lahir pada masa pasca Pakto 1988 berhasil tumbuh cepat, terutama bank-bank yang merupakan bagian kelompok perusahaan besar. Bahkan dalam waktu singkat mereka bisa menjadi bank devisa .Diantara kelompok ini bisa disebut antara lain, Bank Subentra milik Sudwikatmono, NusaBank, milik kelompok Bakrie, dan Modern Bank. Pertumbuhan mereka lebih cepat dari bank-bank yang lahir sebelum Pakto. Dan mereka juga dianggap sehat, karena parsyaratan menjadi bank devisa, harus sehat selama 24 bulan terus menerus. Memang tak gampang menjadi bank devisa. Karena itu sampai sekarang, baru ada sekitar 35 bank devisa dari lebih 200 bank yang ada. Khawatir terhadap mutu perbankan, pemerintah kemudian mengeluarkan serangkaian peraturan baru bertubi tubi dengan berbagai nama: Pakjan (Paket Januari 1991), Paktri (Paket Pebruari 1991) dan UU Perbankan 1992. Pelbagai rintangan mulai ditegakkan. Ada syarat kecukupan modal, ada syarat syarat menjadi direksi, ada larangan untuk pemberian kredit untuk usaha tertentu ( jual beli saham ) dan ada keharusan memberi kredit kepada pengusaha kecil. Aturan-aturan baru tersebut, ternyata dianggap belum cukup. Pada Oktober 1992, keluar beberapa regulasi baru yaitu PP 70, 71, 72 dan 73. Peraturan ini lebih istimewa dari peraturan sebelumnya. Pertama, karena peraturan tersebut merupakan SK Presiden, bukan SK Menteri. Kedua, dalam PP ini, izin pendirian bank yang semula gampang diperoleh, kini menjadi jauh lebih sulit. Sebab, syarat modal disetor minimal, yang dulu cuma Rp 10 miliar untuk bank umum, kini dinaikkan menjadi Rp 50 miliar. Dengan syarat semacam ini, para bankir dan pengamat berpendapat, sudah sangat jarang pengusaha yang berminat. Ketiga, syarat buat direksi dan pemegang saham diperketat lagi. Peraturan perbankan yang cenderung makin ketat itu memang bisa dimengerti. Sejak Pakto 1988, sampai turunnya PP 70, perkembangan perbankan memang meledak. Dalam masa itu, permohonan pendirian bank baru yang masuk ke Departemen Keuangan mencapai lebih 1800 permintaan. Permohonan pendirian bank campuran yang berjumlah 19 semuanya dikabulkan. Sedangkan permohonan pendirian bank swasta umum sebanyak 75 dikabulkan. dalam waktu sekitar empat tahun, jumlah bank di Indonesia naik dua kali lipat. Perkembangan ini tercermin dari lonjakan aset perbankan. Dalam waktu empat tahun sejak Pakto, dana yang dihimpun perbankan melonjak tiga kali lipat, dari Rp 37 miliar , menjadi Rp 110 miliar. Peningkatan yang terjadi pada bank swasta lebih fantastis: dari Rp 11 triliun naik empat kali lipat menjadi Rp 47 triliun. Ekspansi besar besaran itu, dicapai diantaranya dengan pembukaan kantor-kantor cabang dan cabang pembantu yang menjadi lebih mudah. Sampai Maret 1991 saja, jumlah kantor bank didalam negeri ( tak termasuk BPR dan BRI Unit Desa) naik lebih dua kali lipat, dari 1928, menjadi 4538 buah. Sementara kantor cabang di luar negeri naik dari 22 menjadi 52 buah. Akibat perkembangan yang pesat ini, maka bank-bank swasta Indonesia yang sepuluh tahun lalu masih mengelelola aset milyaran rupiah kini menjadi raksasa yang mengelelola aset triliunan rupiah. Aset BCA misalnya pada akhir 1993 telah mencapai Rp 16 triliun. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah siapkah, manajemen untuk menjalankan jumlah aset yang melonjak itu ? Pertanyaan ini timbul, karena dalam perkembangannya ternyata beberapa bank mengalami berbagai masalah. Kredit macetnya terus bertambah. Mereka mulai melakukan praktek-praktek yang berbahaya. Misalnya, mereka mulai berani melakukan perdagangan valas secara "margin trading". Atau mengambil posisi valas yang terlalu berani ("net open position" atau selisih antara kewajiban dengan aktiva valas terlalu besar ) Banyak praktek berbahaya yang dilakukan ini sebenarnya melanggar aturan aturan yang ada. Misalnya , pemberian kredit lebih besar ketimbang ketentuan "legal lending limit" (LLL). Situasi berbahaya ini memang ternyata menimbulkan beberapa musibah. Sejak 1988, ada beberapa bank mengalami krisis, sekalipun mereka kebanyakan adalah bank-bank kecil, seperti Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Perkembangan Asia ( yang telah merjer dengan Bank Kredit Universal) menjadi Bank Universal dan Bank Pertiwi. Bank besar pertama yang menampakkan tanda tanda goyah adalah Bukopin. Bank ini sempat mengalami kesulitan likwiditas, karena kredit yang macet yang diberikan tanpa kriteria agunan yang jelas.Sesudah itu yang membuat gemetar pemerintah dan masyarakat adalah musibah yang menimpa Bank Duta. Sebelumnya memang tak ada yang menyangka bahwa Bank Duta bakal tertimpa musibah. Bank yang mayoritas sahamnya itu dimiliki Yayasan Darmais dan Super Semar itu, dalam neraca keuangannya pada Juni 1990 menunjukkan jumlah asetnya Rp 2,7 triliun. Dana masyarakatnya berjumlah Rp 2,1 triliun, dan pinjaman yang diberikan berjumlah Rp 1,7 triliun. Dengan rasio pinjaman/deposito seperti ini, terkesan bahwa Bank Duta bersikap konservatif. Tak ada yang mengetahui bahwa uang nasabah ini ternyata digunakan untuk bermain valas. Kegiatan ini memang tidak dibukukan, sehingga tidak terungkap dalam laporan keuangan.Mereka berani melakukan posisi "margin trading" terbuka selama berbulan bulan, sehingga ketika hari perhitungan datang, kerugian yang sangat besar tak bisa dihindarkan. Dengan kerugian yang mencapai US$ 417 juta bank tersebut dapat dipastikan ambruk dan tamat riwayatnya, bila para pemegang saham tidak buru buru memberi suntikan dana segar. Krisis berikutnya yang cukup menyita perhatian pemerintah adalah krisis Bank Summa. Bank Summa mengalami musibah karena kreditnya yang sebagian besar disalurkan kepada grup perusahaan sendiri ( Summa Grup ) ternyata macet, karena proyek-proyek yang dibiayainya gagal. Pada saat dilikwidasi, aset Bank Summma hanya tinggal Rp 700 miliar dari jumlah semula Rp 1,9 triliun. Sesudah bank Summa, yang mengalami krisis berikutnya adalah sebuah bank baru yang lahir setelah Pakto 1988, yaitu Bank Sampoerna. Bank yang sebenarnya bagus ini, -- modalnya Rp 30 miliar, lebih besar dari yang dipersyaratkan -- akhirnya harus rontok karena sebab yang sama seperti yang dialami bank Summa: pinjaman kepada pemegang saham yang akhirnya tidak bisa dikembalikan. Padahal sebelumnya, Bank Sampoerna awalnya membuat "start" yang baik. Produknya cukup inovatif, sehingga dana yang dikumpulkan dari masyarakat cukup besar, seperti tabungan three in one dan Tabungan Puri Mandiri. Bank ini sempat ditolong dana darurat dari pasar uang. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Kesulitan keuangan bank ini memaksa dua pemegang sahamnya Putera Sampoerna dan John Rahman melepas sahamnya kepada Bank Danamon. Sejak itu, Bank Sampurna resmi seluruhnya dimiliki oleh Bank Danamon. Peristiwa-peristiwa diatas telah memicu pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan baru dibidang perbankan. Setelah kasus Bank Duta misalnya, muncul Pakfeb, yang isinya antara lain adalah aturan mengenai margin trading dan pengeleloaan aktiva valas. Dalam paket itu disebutkan posisi devisa neto -- aktiva valas dikurangi pasiva valas -- bank, tak boleh lebih 20% modal.Margin trading yang semula tak diatur, sesudah paket ini menjadi dibatasi. Jumlah maksimal yang boleh dilakukan cuma 10% modal, sementara bagi klien ditetapkan 10 kali margin deposit. Bank juga dilarang mengambil posisi terbuka dan jika sudah terdapat potensi kerugian sebesar 5% modal, kediatantrading harus dihentikan. Kemudian untuk mengekang pertumbuhan bank, dalam Pakfeb muncul aturan tentang syarat menjadi pemilik dan pengurus, syarat pendirian kantor bank ( minimal dalam 12 bulan terakhir, 10 bulan harus sehat ), syarat kecukupan modal (CAR), syarat pembentukan cadangan untuk keperluan tertentu, dan pengetatan aturan LLL. Juga dilarang kredit untuk pembelian saham, serta menerima saham sebagi jaminan utang. Dalam perkembangannya, aturan aturan ini dengan mudah dilanggar, lewat begitu saja tanpa kena sanksi dari BI. Atau memang BI tak mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kasus Bank Summa dan bank Sampoerna adalah bukti nyata ketidak mampuan BI dalam melakukan fungsinya sebagai polisi perbankan. Kedua bank ini jelas melanggar LLL . Larangan kredit untuk pembelian saham juga tak terlalu diindahkan. Seperti diberitakan, William Soeryadjaya, menjadikan saham Astranya sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dari bank- bank, diantaranya adalah Bank Danamon dan BDN. Juga, untuk mengatasi kredit macet kepada satu perusahaan, bank sering malah membiayai pengambil alihan perusahaan tersebut oleh perusahaan lain, yang dinilai akan mampu memperbaiki kondisi perusahaan yang diambil alihnya. Dalam pengambil alihan semacam ini, jual beli saham, yang dibiayai dengan kredit jelas tak bisa dihindarkan. PP 70 dibuat antara lain untuk memperkecil kemungkinan pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Dalam PP ini,pelbagai ketentuan yang sudah muncul dalam pakfeb dimunculkan lagi. Misalnya, soal larangan direksi bank punya jabatan rangkap, serta larangan susunan direksi dari orang yang masih punya hubungan keluarga. Dengan larangan semacam ini, kemungkinan pemberian kredit kepada perusahaan milik seorang direksi atau milik pemegang saham berkurang. Apalagi, kecuali dua larangan tersebut ada larangan-larangan lain, seperti larangan anggota direksi, sendiri atau sekelompok, memiliki saham sebuah perusahaan lebih dari 25%. Kemudian, untuk meredam minat mendirikan bank yang masih besar, modal setor minimal dinaikkan menjadi Rp 50 miliar. Karena bisa saja seorang mendirikan bank dengan modal pinjaman -- sesuatu yang selama ini banyak terjadi -- keluarlah aturan tambahan: sebuah perusahaan hanya boleh memiliki saham disebuah bank, maksimal sebesar modal sendiri perusahaan tersebut. Artinya, tak bisa perusahaan meminjam uang untuk dipakai sebagai modal mendirikan bank. Satu satunya ketentuan yang berbau deregulasi dalam PP ini adalah diperbolehkannya investor asing membeli saham bank sebesar 49% dari saham yang beredar. Ketentuan ini bisa benar benar bermanfaat. Jika investor asing berminat, saham bank bisa membaik harganya -- dan ini berarti peluang bank yang go public untuk memperbaiki struktur modalnya. Harus diakui bahwa peraturan peraturan baru tersebut sangat sulit untuk dipantau bagi BI. Misalnya, bagaimana BI bisa tahu bahwa seorang direktur bank mempunyai lebih 25% saham disebuah perusahaan ? Atau, bagaimana BI bisa tahu bahwa modal yang dipakai untuk mendirikan bank bukan modal pinjaman ? Begitu juga dengan mengawasi LLL. Bank, adalah institusicash yang setiap hari angkanya berobah. Untuk memantau apakah ada pelanggaran ketentuan LLL, BI harus memeriksa bank setiap hari. Ini akan makan waktu lama, dan tenaga yang cukup ahli. Semakin besar asetnya, semakin sulit untuk dipantau. Itu hanya untuk satu bank. bayangkan bagaimana repotnya BI karena yang harus dipantau lebih 200 bank . Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ini, menurut beberapa pengamat, adalah dengan menyeleksi betul aturan yang bakal dipakai. Aturan yang sudah bersifat tehnis perbankan -- misalnya tentang L-3 -- relatip lebih mudah untuk dimonitor. Sedangkan aturan yang tidak berkaitan dengan tehni perbankan ( seperti pelbagai persyaratan untuk direksi ) sebaiknya tidak usah diberlakukan, karena sulit mengawasi pelaksanaannya. Aturan yang sangat berguna dalam menjaga kesehatan bank, dan yang gampang pelaksanaannya seperti yang berkaitan dengan angka ngka neraca akan lebih gampang memonitornya. Dengan catatan bahwa Akuntan Publik yang meng-audit laporan keuangan bank benar benar dapat dipercaya. Memang ada risiko, bahwa angka laporan keuangan sebagian bisa merupakan hasil rekayasa, tapi kemungkinan ini kecil . Pada umumnya syarat tentang modal minimum, syarat kecukupan modal, serta pelbagai cadangan untuk aktiva berisiko, mudah untuk dimonitor. Dampak uang cukup terasa dari serangkaian peraturan perbankan tersebut, terhambatnya pertumbuhan kredit, karena bank-bank bersikap ekstra hati hati dalam pemberian kredit. Akibatnya pertumbuhan moneter terganggu, dan PDB Indonesia pada 1992 hanya tumbuh 6,2% setelah setahun sebelumnya tumbuh diatas 7%. Kredit yang disalurkan bank-bank pada 1992 hanya naik 7%, padahal likwiditas meningkat 21%. Akhirnya pada Mei 1993, pemerintah mengeluarkan paket peraturan perbankan baru ( Pakmei ) yang melonggarkan beberapa pengetatan yang dibikin sebelumnya. Dalam perhitungan CAR misalnya, laba tahun lalu dapat dimasukkan sebagai komponen modal. Sebelumnya hanya 50% yang boleh dimasukkan dalam perhitungan modal. Disamping itu, dalam perhitungan LDR, pengertian deposito tidak dibatasi pada dana pihak ke tiga saja, tapi juga bisa memasukkan unsur modal sendiri. Dan mulai Desember 1994, bank tidak perlu lagi menyediakan cadangan untuk SBI, dan pembentukan cadangan diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Kalau ada pengetatan dari Pakmei, maka itu menyangkut aturan L-3, dimana kredit kepada grump sendiri dibatasi 20%, tidak lagi 50% seperti semula. Ini hal yang positip, karena ketergantungan kepada grup sendiri dikurangi, yang berarti penyebaran risiko yang lebih baik. Aturan ini juga memberi kemungkinan berkembangnya pasaran kredit sindikasi, satu hal dari masih harus banyak dipelajari oleh bank-bak terutama bank-bank swasta. Hambatannya adalah bahwa bank-bank yang selama ini pasar kreditnya tergantung dari kelompok perusahaannya sendiri harus mencari nasabah baru. Hal ini tidak mudah, dan kalau dapat, nasabah baru ini belum dikenal baik .Dengan kelonggaran- kelonggaran ini, maka diharapkan lenih mudah bagi untuk melakukan ekspansi kredit tanpa khawatir, angka angka rasionya menabrak rambu-rambu yang dipasang BI dalam menentukan tingkat kesehatannya. Dampak Pakmei memang segara terasa. Pertumbuhan kredit yang pelan sampai Maret 1993, sejak April, tumbuh dengan cepat. Swasta yang makin berotot APA yang menarik tentang BII ? Bank milik Eka Tjipta Widaja dari kelompok perusahaan Sinar Mas ini telah muncul sebagai bank swasta yang paling kokoh. Labanya sebelum pajak pada 1993 yang mencapai Rp 166 miliar, merupakan laba tertinggi diantara laba yang diperoleh bank-bank swasta. Asetnya jauh lebih kecil dari aset bank - bank pemerintah , tapi laba BII lebih tinggi dari laba yang diperoleh Bank Exim atau BBD atau BRI. Atau bandingkanlah dengan BCA, bank swasta yang terbesar. Aset BCA pada akhir 1993 berjumlah Rp 16 triliun, atau lebih dua kali lipat aset BII. Tapi laba BCA Rp 66 miliar lebih kecil dari laba BII. Laba BII pada 1993, merupakan laba ketiga terbesar diantara seluruh bank-bank, hanya dibawah laba BNI dan BDN. Ini prestasi yang sama dengan yang dicapai pada 1992, ketika laba yang diraih BII hanya dibawah BNI dan Bank Exim. Aset BII pada 1993, meningkat 47%, lebih besar dari peningkatan pada 1992 sebesar 33%. Peningkatan aset, berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, tidak didominasi oleh peningkatan pinjaman. Tapi surat berharga dan tagihan lain melonjak dari hanya Rp 117 miliar menjadi Rp 1,4 triliun. Kredit yang diberikan hanya naik 34%, lebih rendah dari pertumbuhan aset. Sekalipun peningkatan ini lebih tinggi dari peningkatan pada 1992, tapi bagian kredit dari total aset terus merosot dari 82% pada 1991, menjadi 74% pada 1992, dan 67% pada 1993. Sifat hati hati BII dalam melakukan ekspansi kredit yang dilakukan pada 1992 nampaknya masih dipertahankan. Pada 1992, kreditoutstanding BII hanya naik 20%. Ini merupakan pencerminan strategi BII yang bertahan karena kekhawatiran adanya dampak negatip dari krisis yang melanda Bank Summa. Portfolio pinjaman BII pada 1993 nampaknya mengalami perbaikan dari 1992. Penghasilan dari bunga pinjaman meningkat 13% pada 1993, dibanding dengan kenaikan hanya 0,8% pada 1992. Peningkatan sebagian besar berasal dari meningkatnya volume kredit outstanding, karena suku bunga pinjaman pada 1993 sudah turun dari tingkat pada 1992. Pengaruh turunnya suku bunga pinjaman ini tercermin dari turunnya rasio antara penghasilan bunga dan posisi rata rata kredit outstanding , yang turun dari 19,8% pada 1992 menjadi 17,6% pada 1993. Pada 1993, BII nampaknya berhasil menekan biaya bunga. Penurunan suku bunga deposito yang diberikan kepada para deposannya, turun lebih cepat dari penurunan suku bunga kreditnya. Biaya bunga BII hanya naik 4% menjadi Rp 495 miliar. Akibatnya, marjin bunga mengalami kenaikan cukup berarti, dari 26% pada 1992 menjadi 34% pada 1993. Dalam mengatur portfolio pinjamannya , strategi BII adalah mencapai keseimbangan antara kredit untuk retail dan kredit untuk corporate. Pada 1994 ini, BII berusaha untuk memperbesar kreditnya ke sektor retail, dengan pertimbangan bahwa risiko sektor retail bisa didistribusi secara lebih baik, dibanding dengan kredit untukcorporate yang untuk satu nasabah bisa mencapai puluhan miliar. Bidang usaha baru yang telah cukup menghasilkan adalah pemberian KPR. beberapa waktu lalu BII dengan gencar mempromosikan KPR Express. Kalau pada 1992, KPR baru mencapai Rp 70 miliar, maka pada 1993 KPR ini telah lebih dari Rp 200 miliar. Dan peningkatan kredit terbesar pada 1993 terjadi pada sektor properti, bisnis yang sedang tumbuh pesat akhir akhir ini. Dalam hal ini, pola yang dilakukan BII memang tidak berbeda dengan yang terjadi pada bank bank lain. Bisnis properti menarik perbankan untuk pemberian kredit, karena risikonya dinilai kecil, sedang agunannya, seperti tanah dan bangunan bisa dilihat dan dinilai dengan jelas, bahkan selalu mengalami apresiasi. Dengan marjin bunga yang meningkat cukup besar, maka biaya operasional seperti biaya tenaga kerja, yang pada 1992, dikekang dengan ketat, pada 1993 nampak mulai dilonggarkan. BII yang mempunyai 129 kantor cabang dan 4700 karyawan ini, pada 1993 harus meningkatkan biaya gaji dan upah karyawan dengan 25%, dari Rp 54 miliar pada 1992 menjadi Rp 68 miliar pada 1993. Tapi kenaikan Rp 14 miliar ini tentunya kurang berarti pada saat penghasilan dari bunga naik dengan Rp 87 miliar. Dari segi permodalan, posisi CAR (capital adequacy ratio) BII per Desember 1993 hanya 7,1%, dibawah persyaratan minimum yang ditetapkan BIS (Bank for International Settlements) yang 8%. Tapi bagi BII ini bukan masalah, karena pada awal 1994 ini BII telah menerbitkan rights issue dengan menawarkan 52,7 juta saham senilai Rp 211 miliar. Dana ini, disamping merupakan dana murah bagi BII, juga akan berfungsi sebagai faktor yang akan memperkuat modalnya. Dengan kokohnya kedudukan BII dalam perbankan di Indonesia, BII juga sudah siap untuk melebarkan sayapnya dalam bisnis jasa keuangan lainnya. Pada 1992, BII mendirikan BII Investment Management, yang akan terjun dibisnis fund management. Beberapa pendekatan sudah dilakukan dengan fund management di luar negeri. BII melihat prospek yang bagus untuk bisnis ini di kawasan Asia. BII juga melirik pandangannya ke Cina, pasar terbesar dan terpenting saat ini di Asia. Lewat anak perusahaannya di Hongkong, BII Finance Company Ltd , BII telah membentuk usaha patungan dengan China Venturetech and Investment Corporation CVIC, sebuah perusahaan modal ventura milik pemerintah Cina, yang akan menggarap bisnis keuangan di daratan Cina. BCA Setelah Ngebut BANK Central Asia adalah bank swasta terbesar, dan unik. Strateginya selama lima tahun terakhir didasarkan pada obsesi untuk menjadi yang terbesar, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Dan ini dilakukan kalau perlu dengan mengorbankan pertumbuhan laba. Sudah beberapa tahun pemegang sahamnya tidak menerima pembagian dividen. Laba yang ditahan tidak dibagikan sebagai dividen, tapi dikapitalisasi sebagai modal. Penekanan strategi pertumbuhan mengakibatkan kinerja yang kurang mengesankan. Return on Asset, ROA-nya pada 1993 hanya 0,62%, lebih rendah dari ROA bank-bank swasta besar lainnya seperti Bank Danamon (0,75%), BII (2,4%), Lippo Bank (1,4%) dan Bank Bali ( 2,2%). Strategi pertumbuhannya memang memberi hasil yang mengesankan. Pada 1988, tahun dikeluarkannya deregulasi perbankan (Pakto), aset BCA masih Rp 2,3 triliun. Dalam dua tahun asetnya melonjak hampir tiga kali lipat. Dua tahun berikutnya asetnya melonjak lagi dengan dua kali lipat. Pada akhir 1993 kemarin, asetnya sudah mencapai Rp 16 triliun. BCA merupakan satu satunya bank swasta yang peringkat asetnya terselip diantara jajaran bank- bank pemerintah. Asetnya kurang lebih sama dengan Bank Exim, dan lebih besar dari aset Bapindo. Aset bank swasta kedua terbesar, Bank Danamon, jauh dibawah aset BCA, hanya Rp 8,2 triliun. Dana masyarakat yang terkumpul pada 1993 mencapai Rp 13,6 triliun, lebih besar dari dana yang dikumpulkan BDN ( Rp 12,6 triliun) dan Bank Exim ( Rp 11 triliun). dalam waktu yang sama, kredit yang diberikan berjumlah Rp 9,8 triliun, lebih besar dari kredit yang diberikan Bank Exim ( Rp 9,1 triliun ). Portfolio kredit BCA masih mencerminkan pola yang khas bank swasta, dimana sebagian besar kredit diberikan kepada sektor perdagangan. Menyusul industri kimia dan industri makanan yang masing masing memperoleh 13,7% dan 13,3% dari pemberian kredit. Sudomo Salim dan dua anaknya ( Andree dan Anthony) yang menjadi pemegang saham terbesar BCA juga mempunyai industri kimia dan industri makanan yang cukup besar. Sejak Pakto 1988, BCA membuka kantor-kantor cabang secara besar besaran di berbagai daerah. BCA, yang pada 1988 baru mempunyai 50 kantor cabang, sekarang ini sudah mempunyai 437 cabang diseluruh Indonesia, ditambah 7 kantor cabang di luar negeri. Cabang BCA dapat anda temui di hampir semua kabupaten di seluruh Indonesia. Pada 1992, ketika pertumbuhan industri perbankan agak tertekan, BCA masih menambah 116 kantor cabang dan menambah 4700 karyawan. Sekarang ini BCA mempunyai 17600 karyawan. Hasil ekspansi besar besaran ini memang sudah terlihat. Jumlah nasabah BCA, yang pada 1988 baru berjumlah 400.000, sekarang sudah mencaoai 3,2 juta. Dalam waktu yang sama, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 13,6 triliun. BCA tidak saja mengeluarkan investasi yang besar untuk pendirian kantor cabang. Dia juga mengeluarkan biaya besar untuk otomatisasi operasinya. BCA telah mempunyai jaringan telekomunikasi sendiri (BCA LINK), dimana lewat salah satu satelit pemerintah Indonesia, 200 cabang BCA dihubungkan secara on linedengan kantor pusatnya. Jaringan Automated Teller Machine (ATM) sekarang ini sudah mencaoai 115 yang tersebar di 19 kota besar sehingga merupakan jaringan ATM yang terbesar di Indonesia. Bank koresponden BCA kini sudah berjumlah 772 bank di 81 negara. Tidak semua bisnis BCA tumbuh cepat. Kartu kreditnya ,BCA Card, sudah tidak tumbuh secepat tahun 1990. Omset kartu kreditnya sudah mencapai sekitar Rp 900 miliar, dan ada 150.000 pemegang.Saingan gencar dari Citibank -- yang sekarang mempunyai 300.000 pemegang hanya dari tiga cabang -- telah menghambat pertumbuhan bisnis kartu kredit BCA. Strategi BCA pada 1993 adalah "pertumbuhan yang terkendali". Setelah lari cepat selama empat tahun. memang logis, kalau BCA mengerem kecepatannya dan melakukan konsolidasi. Pada 1993, aset dan kredit yang diberikannya hanya naik 14%, tingkat pertumbuhan yang paling rendah selama empat tahun. Untuk menahan arus deposito BCA harus menurunkan suku bunga deposito, hingga suku bunganya yang paling rendah diantara bank swasta. BCA akan memusatkan usahanya dalam pembenahan internal. Cabang- cabang akan dibuat lebih sehat, dan lebih efisien supaya lebih menguntungkan. Kalau strategi ini berhasil, BCA akan bisa memperbaiki kinerjanya pada 1994 nanti. Sebagian besar saham BCA dimiliki oleh keluarga Sudomo Salim, pemilik Salim Grup. Sudomo, dan dua anaknya Anthony dan Andree masing masing memiliki 23% saham. Sedangkan Sigit Harjojudanto mempunyai 16%, dan Siti Hardijanti Hastuti mempunyai 14%. Mereka bukan orang sembarangan. Dapat dimengerti kalau mereka tidak memerlukan pembagian dividen BCA tiap tahun. Karena itu keuntungan bersih BCA tiap tahun dikapitalisasi , sehingga modal BCA terus meningkat, dan hanya Rp 103 miliar pada 1988, menjadi Rp 1,1 triliun. Dengan modal yang kokoh seperti ini, BCA jelas tak berminat untuk go public . Seperti dikatakan Presiden Direktur BCA Abdullah Ali : "Oom Liem kan bisnisnya banyak. Laba yang diperolehnya dari luar BCA juga besar. Karena itu, tidak mengambil laba BCA, tidak menjadi masalah ". Prospek 1994 SETELAH pada 1993, perbankan bangkit lagi dengan meyakinkan, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, bagaimana dampaknya terhadap pergerakan suku bunga pada 1994 ? Sejak 1991, memang kita menyaksikan pergerakan turun suku bunga. Kalau tingkat bunga deposito 3 bulan dan kredit modal kerja pada Juni 1991 masih tercatat rata-rata 25% dan 27%, maka pada akhir tahun 1991 masing masing sudah menurun menjadi rata rata 22% dan 25%. Selanjutnya mengalami menurunan menjadi rata rata 17% dan 22% pada akhir 1992, dan menurun kembali pada akhir 1993 menjadi masing masing 12% dan 18%. Walaupun tingkat penurunan cenderung melemah, namun kecenderungan itu masih berlanjut sampai akhir Maret 1994, sehingga tingkat bunga deposito rata rata sudah berada sekitar 10% dan modal kerja sekitar 17,5%. Tren penurunan suku bunga depsotito ini akan terhambat lagi oleh adanya faktor eksternal. Bank Sentral AS dalam bulan April menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali. Persepsi nasabah adalah sekarang bahwa suku bunga dalam dolar lebih menguntungkan dari pada deposito dalam rupiah. Gejala penarikan rupiah untuk di belikan dolar memang sudah terjadi. Maka untuk mengerem aliran rupiah ke dolar ini, beberapa bank sudah menaikkan suku bunga deposito lagi. Bank- bank berkepentingan untuk meningkatkan dana dari masyarakat, karena mereka nampaknya ingin memanfaatkan peluang meningkatnya kebutuhan akan kredit pada 1994. Mereka bersiap melakukan ekspansi pemberian kredit untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bank-bank pemerintah yang masih lemah. Bila ini terjadi, maka kita akan menyaksikan berperannya bank-bank swasta nasional sebagai motor penggerak ekspansi kredit selama dua tahun berturut turut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini