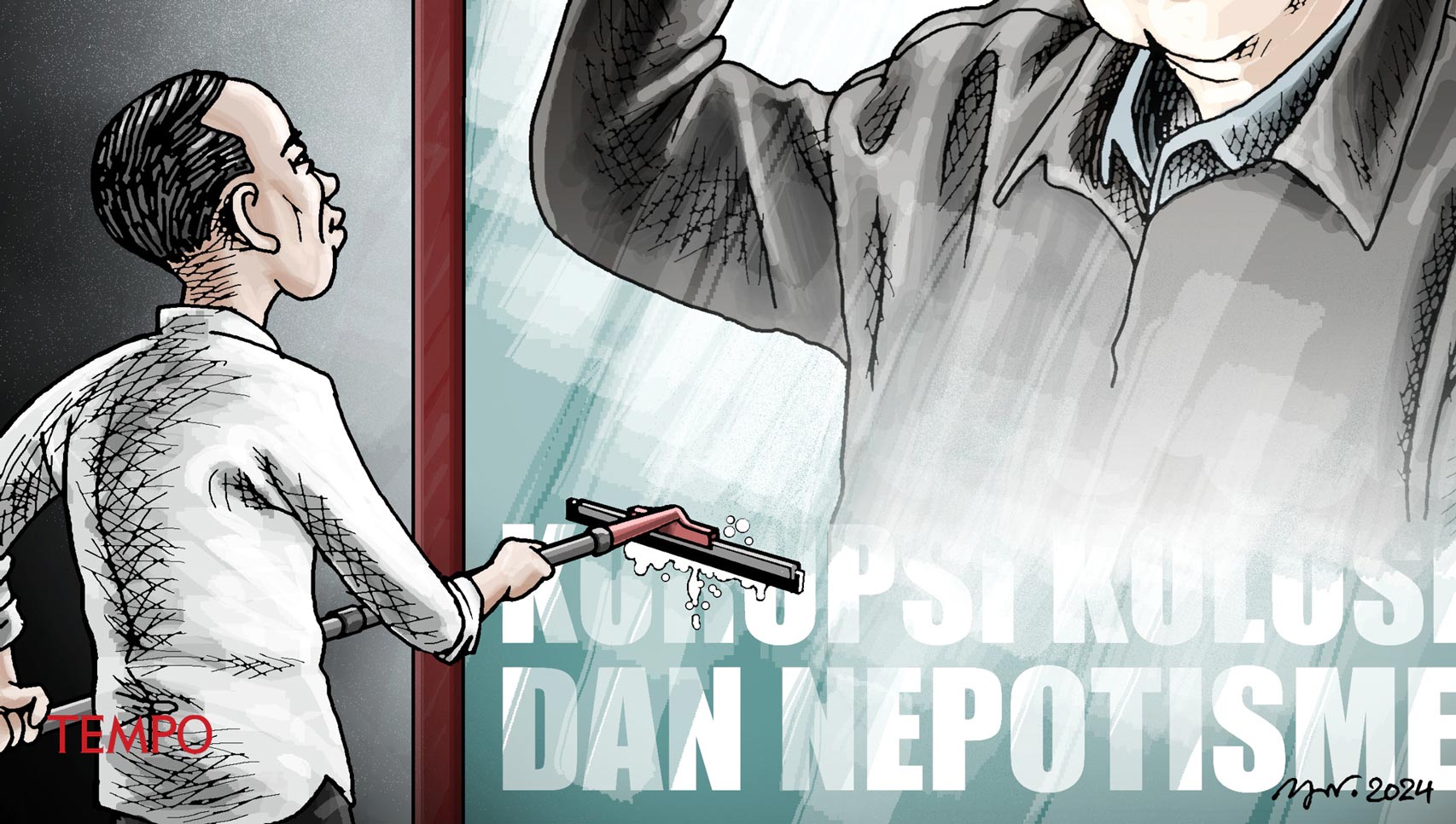Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aki balapan dengan umur….” Lelaki berambut putih tersebut menyebut dirinya ”aki”—sebutan kakek dalam bahasa Sunda. Memang ia terlihat sudah sangat sepuh. Siang itu, di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki, ke mana saja dia membutuhkan tongkat, sekalipun saat duduk. Rosihan Anwar, yang berada di sebelahnya, sesekali mengusap-usap punggung lelaki itu, ketika ia tersendat berbicara.
Sang aki adalah Achdiat K. Mihardja, pengarang novel tersohor Atheis (1949) yang kemudian pada tahun 1974 difilmkan oleh Syumanjaya. Sejak tahun 1960 menetap di Australia, tiba-tiba di usia 93 tahun ia muncul mengabarkan bahwa sebuah kisah panjangnya telah selesai.
”Judulnya Manifesto Khalifatullah,” tuturnya. Serangkaian pertemuan di Bandung dan Jakarta menimbulkan keharuan saat ia menyatakan kisah panjangnya (ia menyebut demikian karena karya tersebut terlalu panjang untuk dikatakan cerpen, terlalu singkat untuk disebut novel) merupakan pergulatannya di hari uzur, sebelum kalah oleh waktu. ”Semangatnya mengagumkan,” komentar budayawan Rahman Arge. Tahun ini juga sesungguhnya Balai Pustaka menerbitkan ulang novelnya, Debu Cinta Bertebaran (1973).
”Beliau itu bukan pengarang produktif,” kata Ajip Rosidi. Setelah Atheis, karyanya hanya Bentrokan dalam Asrama (drama, 1952), Keretakan dan Ketegangan (kumpulan cerpen 1956), Kesan dan Kenangan (kumpulan cerpen, 1960), lalu Debu itu, Belitan Nasib (kumpulan cerpen 1975), Pembunuh dan Anjing Hitam (kumpulan cerpen, 1975), dan Pak Dullah in Extremis (drama, 1977).
Atheis telah cetak ulang 26 kali. ”Yang menarik, selalu ada revisi,” Ajip mengamati. Edisi baru—Debu Cinta, misalnya—mengalami perubahan di sana-sini. Achdiat mendefinisikan novel-novelnya sebagai roman gagasan. Debu Cinta menceritakan tokoh bernama Rivai, yang datang ke Sydney sebelum Gestapu, dan di sana dia mengalami pergolakan pemikiran tentang ideologi. Sesuatu yang, menurut Ajip, membuat deskripsi suasana tak begitu tajam. ”Misalnya, ketika ia menggambarkan kehidupan diplomat kita, sama sekali tak tecermin.”
Novelnya sering menampilkan perbenturan antara agama dan ideologi, dan itu mungkin lantaran latar belakangnya. Lahir di Cibatu, Garut, 1911, dari golongan menak, yang menurut Achdiat kelas dua, ia aktif dalam pergerakan yang progresif juga religius. Pernah bekerja di harian Bintang Timur, Balai Pustaka, P&K, dan menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia. Ia mempelajari tarekat—aliran Qadariyah Naqsabandiyah dari Kiai Abdullah Mubarak—tapi juga belajar filsafat kepada Pater Dr Jacob S.J. dan Prof Dr R.F. Beerlin di Universitas indonesia. ”Kecenderungan Aki akhirnya ke sosialisme religius,” katanya.
Menurut Achdiat, kisah panjangnya itu berkaitan dengan persoalan yang disodorkan Atheis. Atheis, kita ingat kisah tentang pertemanan Hasan, seorang pemuda religius, dan Rusli, aktivis kemerdekaan yang cenderung kekiri-kirian. Saat dilayarperakkan oleh Syumanjaya, dialog-dialog Hasan-Rusli begitu hidup dan persoalan yang disodorkan begitu bernas.
”Sudah terpikirkan oleh Saudara, mengapa misalnya dunia dan kehidupan ini selalu kacau saja, padahal agama sudah beribu-ribu tahun dipeluk manusia?,” kata Rusli kepada Hasan.
”Karya terbaru Aki berinti ketidaksetujuan atas sekularisme yang menyepelekan Tuhan,” demikian ia bercerita. Setelah 40 tahun berdiam di negeri orang, agaknya ia makin menyelami gagasannya terdahulu. ”Banyak teman baik Aki di Canberra yang ateis, setengah ateis, atau sekurang-kurangnya tidak peduli Tuhan.”
Seperti tergambar dalam film dokumenter tentang kehidupan sehari-hari Achdiat yang dibuat Tinuk Yampolski, Suara dari Jaman Pergerakan, meski telah pensiun dari mengajar di Australian National University, Canberra, ia tetap aktif. Penyakit kataraknya membuat bila ia membaca harus dengan bantuan kaca pembesar. Untuk menulis, lebih dulu ia merekam suaranya dengan tape, lalu rekaman itu ditranskrip oleh orang lain. Ia terlihat masih antusias berdiskusi dengan para doktor di ANU. ”Titel Aki MBS, manusia biasa saja,” guraunya.
Sutan Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Poerbatjaraka, Adinegoro, Ki Hajar Dewantara, Dr Sutomo, pemikir-pemikir yang tulisan perdebatannya pernah dihimpun Achdiat dalam buku Polemik Kebudayaan, telah lama meninggal. Ia ingat saat itu antar-mereka terjadi diskusi hangat soal orientasi ke Timur atau Barat. ”Semenjak dahulu Aki memilih perkawinan Faust dan Arjuna.” Maksudnya, menoleh ke Barat tanpa menanggalkan Timur. Dan itu dipegangnya terus. Di Australia justru ia makin ke ”jalan Hasan”.
”Judul Manifesto Khalifatullah ya mungkin terlalu ambisius. Tapi, menurut Aki, kita harus kembali ke ketuhanan.”
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo