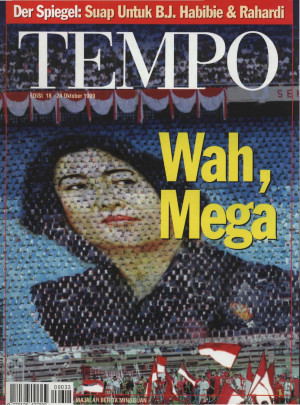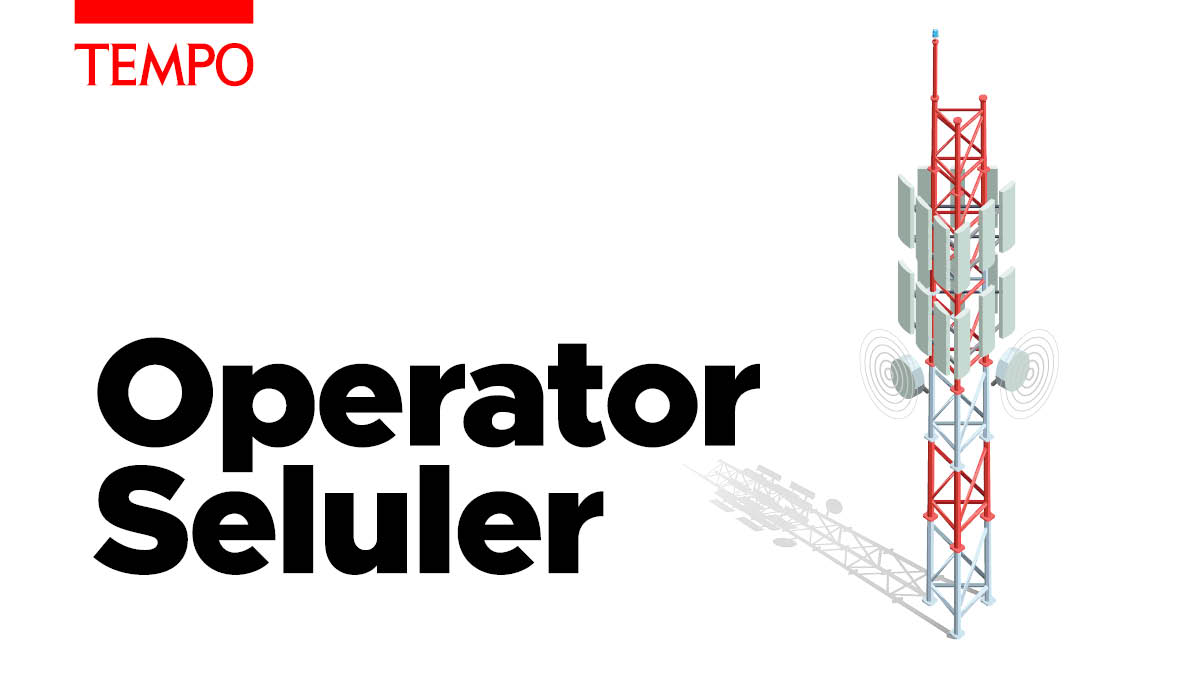| MERAH BOLONG | | Naskah dan sutradara | : | Rachman abur |
| Grup teater | : | Payung Hitam |
| Tempat | : | Teater Utan Kayu |
SEORANG pemain bertopeng masuk pentas. Ia menyunggi ember kaleng. Di samping seonggok kerikil, di pentas arena itu juga dipasang tiga buah bandul batu yang menggantung diam. Berjalan terseok, pemain itu menuang kerikil merah ke atas onggokan kerikil abu-abu itu. Ia lalu menggaet bandul batu itu sehingga berayun mengelilingi pentas. Ia dan bandul batu itu berkejar-kejaran mengelilingi pentas. Ia terengah-engah, akhirnya terkapar. Lalu, muncul tiga pemain bertopeng menyunggi ember. Ketiganya terseok mengitari pentas. Dari dalam ember-embernya, ketiganya menuang batu-batu memenuhi pentas. Kemudian, muncul seorang pemain bertopeng memikul sepasang ember. Ia terseok mengitari pentas sambil menuang batu-batunya. Empat di antara lima pemain itu lalu bermain dengan bandul-bandul batu itu. Seorang di antaranya mau mengadu bandul batu itu dengan kepalanya.
Begitulah adegan-adegan lakon Merah Bolong yang dipentaskan grup Teater Payung Hitam dari Bandung, di Teater Utan Kayu, akhir Oktober silam. Dengan kuat, mereka menggambarkan ritual penderitaan rakyat miskin yang tergelar susul-menyusul di hadapan mata kita. Itulah realitas kehidupan rakyat kita dewasa ini. Rakyat miskin yang memakai celana pendek dengan topeng-topeng yang menyeringai dengan rambut palsu awut-awutan. Ember, sekop, pikulan, kerikil, batu, hanyalah sejumlah alat peraga yang dimiliki rakyat miskin yang tak bisa menolong apa-apa.
Dua hari setelah Gus Dur dan Megawati dipilih menjadi presiden dan wakilnya, mereka sudah ditimpuk kritikan rakyatnya pada 22 Oktober. Begitulah yang dilakukan grup Teater Payung Hitam, yang berdiri pada 1983. Jika pada pertunjukan tahun 1997 grup ini mengkritik Presiden Soeharto dengan lakon Merah Bolong Putih Doblong Hitam, kali ini, dengan lakon Merah Bolong, mereka mengkritik Megawati. Apa pasal? Paling tidak, ada masalah pokok yang sangat sulit diatasi: pengentasan kemiskinan. Justru karena Mega terkenal menjadi tumpuan harapan kaum tertindas, grup teater ini mengingatkannya. Musuh kita memang ada tiga: kemiskinan, keterbelakangan, dan penyakit.
Tiga hal itulah yang dicecarkan terus-menerus kepada pemerintah oleh Rachman Sabur, sang sutradara. Agaknya, inilah ramalan Sabur bahwa akhirnya Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur mengundurkan diri sebelum cukup penuntasan masa jabatannya.
Selama ini, pementasan Payung Hitam meliputi di antaranya Musik Kaleng (1990), Kaspar (1997), Kata Kita Mati (1998), dan Tiang + Tiang (1999).
Pertunjukan "teater gebuh" (yang menyatukan tubuh pemain dengan elemen panggung, situasi sosial, kondisi penonton, dan pertunjukan "tanpa naskah") Payung Hitam ini memikat. Ia kaya, multitafsir, solid, dan mencekam. Kerikil dan batu-batu berserakan sungguh mengancam para penonton yang duduk berkeliling menyatu dengan pemain. Dengan menginjak, menendang, mengais, para pemain itu dengan mudah dapat melontarkan batu-batu itu ke arah penonton. Dalam hal ini, sang sutradara boleh diacungi jempol. Para penonton, yang biasanya pasif dan selalu meminta disuguhi tontonan yang enak, baru tahu rasanya diteror, sekarang. Setiap detik penonton dibikin cemas oleh batu-batu itu. Langsung pikiran melayang ke arah para demonstran yang biasa melemparkan batu-batu.
Menjelang pertunjukan berakhir, sebuah potret Megawati muncul di balik kain merah besar yang bolong-bolong. Sabur meminta Ibu Wakil Presiden ini terus mengawasi dan menolong rakyat miskin, seperti yang dijanjikannya. Sedangkan pemain tanpa kepala (kostum yang besar menyembunyikan kepalanya) mengingatkan pada peran para provokator yang gentayangan mengacaukan suasana kehidupan sosial politik. Yang mengejutkan adalah munculnya pemain bocah (umur 12 tahun, mengaku bernama Wahyu Bandido), berbugil ria, mengitari pentas sambil menyigi orang yang terkapar itu. Lalu, lambang kaum duafa ini mengubur orang yang tergeletak itu dengan mengucurkan kerikil merah ke tubuhnya. Secara detail, pertunjukan ini juga menyuguhkan adegan yang menarik. Napas sang terkapar yang terengah menyebabkan onggokan kerikil di dadanya turun-naik mengikuti gerak napasnya, bagai lembah gaib di suatu tempat entah di kawasan mana dari daerah penderitaan manusia yang fana itu.
Danarto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini