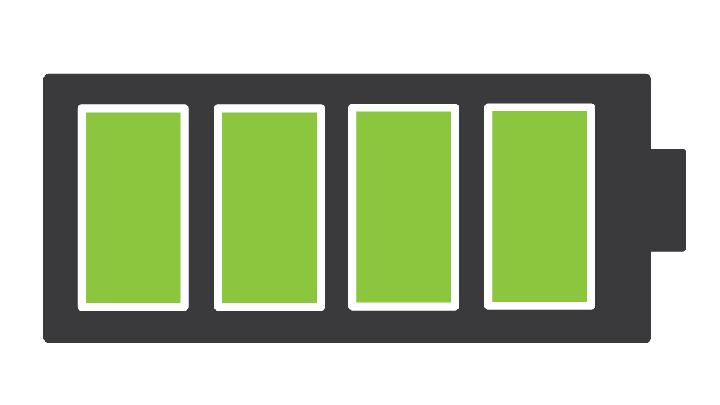Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI dunia para ahli taksonomi hewan yang sepi publikasi, ada seorang Djoko Tjahjono Iskandar yang kerap bikin kejutan. Pada pengujung 2014, pakar herpetologi dari Institut Teknologi Bandung ini mempublikasikan artikel ilmiah berjudul "A Novel Reproductive Mode in Frogs: A New Species of Fanged Frog with Internal Fertilization and Birth of Tadpoles". Artikel setebal 14 halaman yang dimuat di jurnal internasional bergengsi PLOS ONE ini mendeskripsikan spesies baru: katak beranak-melahirkan.
Limnonectes larvaepartus yang ditemukan di Desa Uaemate, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ini katak yang unik. Tak bertelur, ia melahirkan kecebong—fase anakan atau larva pada katak. "Kecebong juga ditemukan di dalam rahim katak betina," kata Djoko Iskandar ketika ditemui di ruang kerjanya di kampus Ganesha ITB, Selasa pekan lalu.
Sebelum ini, pada 2008, Djoko juga bikin geger dunia kecil itu dengan spesies baru temuannya: katak tanpa paru-paru (Barbourula kalimantanensis). Katak berkepala pipih asal Kalimantan ini tak punya paru-paru—organ pernapasan utama yang dijumpai pada mayoritas katak.
Hari itu kampus Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB tampak sepi. Kuliah libur. Djoko mengetik santai di meja panjang di kantornya di ruang pengajar program studi biologi. Makalah dan kertas bertumpuk-tumpuk di lemari besi. Beberapa awetan spesies kadal dalam nampan berisi alkohol terlihat.
Laboratorium tempatnya biasa bekerja sedang direnovasi. Biasanya, saat tidak mengajar, meneliti, atau membimbing mahasiswa seperti ini, bersama peneliti asing dan didanai kampus luar negeri, Djoko suka "berburu" katak atau reptil jenis baru. "Indonesia sangat kaya, terutama Papua karena hutannya masih banyak," ujar pria 64 tahun kelahiran Bandung ini.
Nama D.T. Iskandar mungkin kurang akrab di telinga masyarakat umum. Sama halnya dengan herpetofauna—istilah kelompok satwa reptil dan amfibi—yang menjadi bidang keahlian Djoko. Namun nama Djoko cukup mentereng di kalangan peneliti taksonomi hewan di mancanegara. "Kalau di luar negeri, pakar herpetologi dari Indonesia yang dikenal ya Djoko Iskandar," kata Mirza Kusrini, peneliti herpetologi dari Institut Pertanian Bogor.
Dari sekian banyak ragam satwa, Djoko memang menjatuhkan pilihan pada herpetofauna. Ia telah meneliti hewan melata selama 30 tahun terakhir. Dulu, seusai tamat sarjana dari ITB pada 1975, Djoko sempat bekerja di Museum Zoologi Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Bogor, Jawa Barat. Ia mengurusi tetek-bengek soal reptil selama tiga tahun, sebelum menjadi dosen di kampus Ganesha—sebutan kampus ITB, Bandung.
Djoko melanjutkan studi hingga meraih gelar master pada 1981 dan doktor tiga tahun kemudian. Keduanya dari Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, Prancis. Pilihan risetnya pada katak dan reptil diputuskan setelah ia meraih gelar doktor di bidang mamalia kecil, seperti tikus dan kelelawar, serta kembali mengajar di ITB. "Sebab, hewan amfibi mudah ditemukan," ujarnya.
Hasrat Djoko mempelajari katak makin menggebu lantaran riset tentang hewan "dua alam" ini surut popularitas sejak setengah abad silam. Guru besar bidang ekologi dan biosistematika ini pun terlecut untuk menghidupkan kembali tradisi penelitian katak di kampusnya. Tapi hal itu tidak mudah. Katak hanyalah sebagian dari keluarga besar kelas Amfibia, taksa hewan vertebrata yang berisi lebih dari 7.000 spesies di seluruh belahan bumi. Sangat beragam.
Dalam taksonomi atau ilmu tentang identifikasi dan pengelompokan hewan, Amfibia terdiri atas tiga bangsa, yaitu Anura, Caudata, dan Apoda. Katak termasuk anggota Anura, amfibi tak berekor yang paling beragam, anggotanya tak kurang dari 6.455 spesies. Mereka berbeda dengan Caudata (salamander, berbentuk mirip kadal) dan Apoda (caecilia, berbentuk mirip cacing atau ular). Tentu saja mustahil mempelajari semuanya. Itu sebabnya, Djoko memutuskan hanya berfokus pada satu marga atau genus katak, yakni Limnonectes.
Katak berbeda dengan kodok. Sama-sama anggota bangsa Anura, tapi lain suku atau familia. Katak termasuk suku Ranidae, sedangkan kodok Bufonidae. Seperti dikutip situs Livescience, katak dan kodok dibedakan secara mudah lewat tampilan kulit dan kaki mereka. Kebanyakan katak memiliki kaki yang panjang, tubuh ramping, dan kulit mulus licin berlapis lendir. Adapun kodok umumnya berkaki pendek, bertubuh gemuk, berkulit tebal dan kasar, serta dipenuhi benjolan atau bintil.
Djoko sengaja memilih marga Limnonectes karena katak dari genus ini banyak dimanfaatkan sebagai makanan dan barang ekspor. Sebarannya terbilang luas di Asia Tenggara. Bahkan 60-70 persen spesies katak dari genus Limnonectes berlompatan di seantero Nusantara, dari Sumatera hingga Papua. Genus katak ini sangat beragam dan tersebar. "Diperlukan paling tidak tiga kali seumur hidup (untuk memahami semua anggota genus ini)," ucapnya.
Dalam dunia yang satu ini, Djoko merintis karier dari nol. Bahan riset awal reptil dan katak di Indonesia yang dicarinya sangat tidak memadai. Bahkan, di masa mulanya sebagai peneliti, Djoko pernah kecele ketika berniat mencari katak Limnonectes di Sulawesi pada siang hari. "Saat itu belum ada gurunya," katanya. Belakangan, dia mengetahui bahwa katak buruannya ternyata lebih aktif pada malam hari alias makhluk nokturnal.
Untuk mempelajari genus Limnonectes, Djoko dan rekan penelitinya di ITB terbang ke Eropa dan Amerika untuk mengetahui semua spesies katak yang dikenal di dunia. Ketertarikannya bertambah karena mayoritas anggota genus Limnonectes tidak terdapat di negara tetangga. Djoko meyakini riset tentang genus ini bisa mengantar peneliti Indonesia untuk studi bertaraf dunia. "Anggota genus ini hampir semuanya endemis sehingga kita bisa selalu berada di garis depan ilmu pengetahuan," ujarnya.
Keyakinan Djoko dibuktikan saat memaparkan orasi ilmiah di Aula Barat ITB pada 14 Juni 2003. Ketika itu ia menyampaikan temuan sedikitnya 30 spesies Limnonectes di Sulawesi. Salah satunya Limnonectes sp., yang ditemukannya bersama K.N. Tjan, dan belakangan diidentifikasi sebagai spesies baru Limnonectes larvaepartus. Katak ini tercatat sebagai satu-satunya spesies katak di dunia yang melahirkan kecebong.
L. larvaepartus sebenarnya pertama kali ditemukan dalam ekspedisi Juni-Agustus 1989 di Dumoga Bone, kini menjadi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara. Sejak itu hingga 20 tahun berikutnya, Djoko dan tim peneliti rutin mendatangi Sulawesi untuk meneliti katak tersebut. Awalnya mereka mendapatkan satu-dua ekor katak betina. Setelah katak mati dan diawetkan, terlihat kecebong di larutan pengawet. "Kami duga katak itu membawa kecebong di punggungnya," tutur Djoko. Setelah katak tersebut dibawa ke ITB dan dibedah, mereka kaget. Ternyata di dalam perut dua katak betina juga ada kecebong.
Temuan menakjubkan itu langsung dilaporkan kepada R.F. Inger, guru sekaligus sahabat Djoko dalam penelitian katak serta reptil sejak 1976. Inger, kini 92 tahun dan masih aktif meneliti, saat itu langsung terbang dari Chicago, Amerika Serikat, ke Bandung. Ia, kata Djoko, terpesona oleh fenomena luar biasa itu dan meminta Djoko segera mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah. Namun Djoko menahan diri. Ia memilih melengkapi laporan risetnya dengan meneliti jenis katak unik itu hingga lebih dari 100 ekor. Barulah akhir tahun lalu artikel ilmiah tentang L. larvaepartus diterbitkan.
Mirza Kusrini juga meneliti L. larvaepartus dan menerbitkan artikel dengan judul berbeda, dua hari berselang. Penelitian Mirza dan tim lebih berfokus pada biologi reproduksi L. larvaepartus. Hasil penelitiannya menunjukkan cara fertilisasi dan reproduksi katak ini memang istimewa. "Untuk katak, ini sesuatu yang benar-benar baru," ujarnya. Bahkan cara katak jantan membuahi betinanya masih misterius, mengingat katak tidak memiliki organ serupa penis. "Belum ditemukan bagaimana caranya ia memasukkan sperma."
Bagi Djoko, setiap ekspedisi pencarian spesies baru selalu memunculkan pengalaman menarik. Di Sulawesi, dia harus menyusuri jalur sungai pada malam hari untuk mendapati katak buruannya. Ia juga tak ragu menjelajahi belantara Papua untuk menemukan jenis katak yang bertelur di serasah dan dedaunan. Sebab, tidak semua katak bertelur di tepian aliran sungai atau genangan air.
Salah satu pengalaman yang berkesan adalah penemuan katak berkepala pipih di Kalimantan. Djoko pertama kali menjumpai katak itu dan mendeskripsikannya pada 1978. Namun, lantaran ia hanya mendapatkan seekor katak, spesimen itu dinilai terlalu berharga untuk dibedah. Akhirnya spesimen perdana itu hanya diawetkan. Baru pada 2007, Djoko dan tim kembali mendapatkan katak berkulit hangus itu di pinggir sebuah sungai di kawasan Taman Nasional Baka Bukit Raya, Kalimantan Barat.
Saat itu, dua ekor katak kepala pipih mati setelah beberapa jam dimasukkan ke ember kosong. Djoko sempat terheran mengapa katak itu bisa mati. Penasaran mencari penyebabnya, bangkai katak itu dibawa ke Bandung untuk dibedah di laboratorium ITB. Hasilnya mencengangkan karena kedua katak itu ternyata tidak mempunyai paru-paru. "Rupanya, mereka bernapas langsung dengan kulitnya," Djoko menuturkan. Penelitian lebih lanjut mencatatkan katak ini sebagai satu-satunya spesies katak yang bernapas tanpa paru-paru.
Petualangan Djoko meneliti herpetofauna sejak 1978 berbuah sekitar 30 spesies baru reptil dan amfibi. Kebanyakan jenis katak di Indonesia. Atas prestasinya itu, sejumlah peneliti asing pada 2011 memberi penghormatan dengan menyematkan namanya pada genus ular air Djokoiskandarus annulatus. Nama Djoko juga diadopsi untuk nama petunjuk jenis pada cicak bergelambir bertelapak kaki jembar (Luperosaurus iskandari), cicak terbang (Draco iskandari), katak cokelat terang (Polypedates iskandari), katak sawah (Fejervarya iskandari), dan katak Collocasiomya iskandari.
Sepak terjang Djoko sebagai profesor katak memang tidak main-main. Mirza Kusrini mengenal Djoko sebagai ilmuwan yang sangat konsisten menekuni bidang riset herpetologi. "Tidak hanya meneliti, tapi juga menulis," ujarnya. Djoko termasuk peneliti pertama yang menulis buku mengenai deskripsi jenis amfibi di Pulau Jawa dan Bali. Buku berjudul Amfibi Jawa dan Bali terbitan 1998 itu banyak diacu oleh mahasiswa. "Selama ini kita mesti cari buku dari Belanda atau negara lain."
Mantan anggota Kelompok Studi Herpetologi (KSH) yang kini menjadi dosen mata kuliah herpetologi di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Donan Satria Yudha, mengaku banyak terinspirasi dari Djoko. Pertemuan pertamanya dengan Djoko terjadi pada 2002 ketika ia berkunjung ke kampus ITB. Saat itu Donan—masih berstatus mahasiswa—bersama empat temannya bermaksud belajar mengenai metode identifikasi dan pengawetan herpetofauna langsung dari ahlinya.
Di kampus Ganesha, Djoko dengan antusias menjelaskan banyak hal kepada Donan dan kawan-kawan. Djoko bahkan membawa lima mahasiswa jurusan biologi itu berkeliling ke laboratorium dan ruang kerjanya. "Setelah kunjungan tersebut, kami menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam mengambil kajian herpetologi," ucap Donan. "Terbukti, saya mengambil skripsi mengenai fosil reptil di Indonesia."
Kini Djoko berharap ada lebih banyak peneliti muda yang mengikuti jejaknya menekuni riset reptil dan katak. Asa yang cukup wajar mengingat saat ini baru ada sekitar sepuluh peneliti yang benar-benar mendalami bidang herpetologi. Angka yang sangat sedikit untuk kawasan seluas Indonesia dengan keberagaman hayati yang tinggi. "Kekayaan alam Indonesia agar bisa dipelajari sendiri oleh anak bangsa sehingga bisa berdiri sejajar dengan peneliti asing," kata Djoko tentang cita-citanya.
Mahardika Satria Hadi, Anwar Siswadi (Bandung)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo