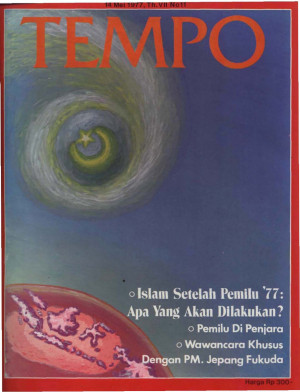PERBURUAN barang aneh di Kalimantan Tengah kini memasuki babak
baru. Bukan cuma keramik dan perunggu Cina yang dicari - untuk
dilego ke luar negeri dengan harga mahal - tapi juga karya suku
Dayak sendiri. Khususnya patung-patung kayu ulin, buatan para
penganut agama Kahanngan dalam upacara adat mereka.
Salah satu pusat perburuanpatung antik itu adalah desa Ampah,
ibukota kecamatan Dusun Tengah, kabupaten Barito Timur,
Kal-Teng. Desa ini (9000 jiwa) terletak 380 Km sebelah Utara
Banjarmasin. Dulu pusat kebudayaan suku Dayak Lawangan. Dari
sini tersebar patung ulin, rumah adat untuk ibadah Kaharingan,
sandung (rumah-rumahan kecil untuk tempat sesajen), serta
keriring (peti mati di atas tiang tinggi tempat menyimpan
sejumlah tengkorak panglima-panglima Dayak sekaligus). Bahkan
ada satu desa sebelum Ampah, Patung namanya. Di desa itu tinggal
seorang pemahat patung yang sudah tua Idut, pencipta sebagian
besar patung di desa Patung.
Larangan Sylvanus
Karena lebih mudah dicapai dari Banjarmasin ketimbang pusat
kebudayaan suku Dayak Kal-Teng lainnya, banyak orang asing dan
pribumi datang ke Ampah mencari patung ulin. Karyawan Pertamina
dan Union Oil - yang pernah lama berusaha mencari minyak di
kawasan hulu sungai Barito - dikabarkan sudah banyak memborong
patung itu. Ini cukup mengganggu penduduk, apalagi masyarakat
Dayaknya sendiri yang kebanyakan masih beragama Kaharingan.
Yang paling menghebohkan belakangan ini adalah dua orang
pedagang pribumi yang mengaku berasal dari Sumatera. Mereka
berusaha memborong puluhan patung ulin dari Ampah dan
sekitarnya. Penduduk mengadukan kedua orang itu pada polisi.
Gubernur Kal-Teng Reynout Sylvanus melarang diangkutnya
benda-benda budaya Dayak yang bersejarah itu ke luar dari
daerahnya.
"Di daerah ini, orang-orang Sumatera itu berhasil menyikat 200
patung ulin", ujar Nempel Kiki, seorang anggota Wanra di desa
Patung pada wartawan TEMPO G.Y. Adicondro. Di rumah Kiki sendiri
ada sebuah patung wanita - sudah rada"modern": mengenakan celana
dalam. Patung ini milik Kepala Kampung Patung yang disitanya
dari tangan pemburu patung Dayak. Tapi Nempel bersedia menjual
patung itu seharga Rp 15 ribu
Bahwa jumlah patung yang disikat sampai mencapai 200 diragukan
oleh penduduk lain. Memang, begitu cerita penduduk, ada seorang
pemuda di desa lain, yang bersama kawan-kawannya di malam hari
berhasil mencuri 30 patung ulin. Caranya: menggergaji atau
mencabutnya dari dalam tanah. Orang-orang Sumatera itu
menawarkan harga sampai Rp 25 ribu untuk sebuah patung.
Djaen, pemuda yang mengorganisir pencurian patung itu, kini
dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak diserahkan pada polisi,
sebab masyarakat di sini agak takut juga padanya. Soalnya, dia
pernah masuk tentara, dan dipecat karena tidak disiplin.
Orangnya suka berkelahi. Namun penduduk, yang tahu bahwa Djaen
sekedar alat dari para pedagang patung, menuntut pada polisi
supaya orang-orang Sumatera itu diusir dari sini.
Matahari Terbenam
Berbeda dengan di Bali misalnya, orang-orang Dayak itu memang
belum memahat patung untuk diperjual-belikan. Patung-patung yang
dipahat beramai-ramai dari batang pohon ulin (kayu besi) utuh
itu, didirikan sebagai tempat menambatkan kerbau. Kerbau itu
juga dibantai beramai-ramai oleh para lelaki - dalam rangka
pesta adat (aruh) Kaharingan.
Dari arah patung itu menghadap, dapat diketahui patung itu
didirikan selama pesta apa. Patung yang didirikan untuk upacara
penguburan pemuka masyarakat, menghadap ke arah matahari
terbenam. Wujudnya, lelaki atau perempuan, merupakan
penggambaran dari tokoh yang baru saja meninggal. Akibat
pengaruh masuknya tentara Belanda ke belantara Kalimantan,
panglima Dayak yang meninggal itu ada yang digambarkan dalam
seragam opsir Belanda: bertopi yang tinggi, sepatu bot, duduk di
kursi.
Sebaliknya, kalau patung atau beluntang itu menghadap ke arah
matahari terbit, itu tandanya peristiwanya gembira: pesta
pernikahan atau kenduri untuk mohon berkat bagi seisi desa.
Kenduri itu disebut buntang. Pesta berkabung yang dalam logat
Dayak Lawangan disebut wara itu, ada tiga tahap. Wara itu
sendiri adalah upacara penguburan mayat yang baru meninggal.
Pesta wara itu bisa makan waktu sampai seminggu, tergantung pada
tinggi-rendahnya status sosial tokoh yang meninggal. Untuk
menghormati yang meninggal, didirikanlah blunteng yang sekaligus
jadi tiang tambatan kerbau yang dibantai untuk upacara itu.
Pembantaian kerbau itu, pada dasarnya merupakan adu kejantanan
manusia ala matador Spanyol. Sang kerbau sebelumnya sudah
dibikin kalap dengan jalan ditombaki atau dibakar ekornya, tapi
tetap terikat dengan tali rotan, yang panjangnya bisa sampai 15
depa.
Selesai wara, mayat tokoh Dayak Lawangan ini dibiarkan dalam
tanah sampai tinggal kerangka. Saat itu, tibalah saatnya untuk
mengadakan upacara yang kedua, taloh. Upacara ini berlangsung
sederhana saja - hanya potong babi, tanpa mendirikan beluntang.
Di saat ini' tulang sang almarhum dimasukkan dalam sebuah guci,
belanai. Guci kl7usus itu disimpan dalam rumah-rumahan khusus
(sandung), sampai tiba saatnya untuk dipindahkan ke keriring.
Keriring adalah semacam peti mati yang tegak tinggi di atas
tiang pancang, tempat menyimpan tengkorak beberapa panglima
Dayak sekaligus.
Upacara pemindahan tengkorak dari belanai ke keriring itulah
yang merupakan upacara adat paling meriah. Bisa makan waktu
sampai 14 hari. Upacara ini usaha gabungan beberapa desa atau
beberapa puak Dayak yang leluhurnya masih saling berkerabat.
Segala material untuk pesta ini ditanggung bersama-sama.
"'DUPPA"
Dulu, keriring didirikan dekat atau di depan rumah adat dari
beberapa puak yang berdekatan. Tapi kini keriring yang dihiasi
ukiran kepala kerbau - mirip seperti tradisi Toraja di Sulawesi
Selatan - terisolir di tengah hutan kelapa. Ada juga yang tegak
di samping Sekolah Dasar. Namun di desa Pakali, 36 Km dari
Ampah, masih ada satu rumah adat yang lengkap dengan
keriringnya. Tapi bangunan itu kini terlantar. Anak suku Dayak
Lawangan Bawuh yang dulu tinggal di situ sudah menyingkir terus
ke hulu, dengan datangnya masyarakat Banjar dari Kal-Sel. Dan
beluntang yang ada di Pakali tertinggal begitu saja.
Untung Dinas Purbakala sudah masuk ke daerah itu guna melindungi
monumen Dayak yang mudah hancur itu. Trbukti dari pengelompokan
sejumlah patung-patung di Ampah, serta inskripsi tanggal
meninggalnya tokoh yang bersangkutan serta tanggal pendirian
beluntangnya. Lengkap dengan inskripsi 'DUPPA' di bawah
inskripsi tanggal sebagai bukti datangnya para arkeolog ke sana.
Hanya sayang, dari puluhan patung Dayak yang bertebaran di
hutan, bukit, padang dan peka rangan rumah penduduk asli, baru
segelintir kecil yang sudah diregistrater dan di 'meterai' oleh
Dinas Purbakala di Jakarta. Sebagian besar masih terancam
kelanjutan hidupnya oleh iklim dan manusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini