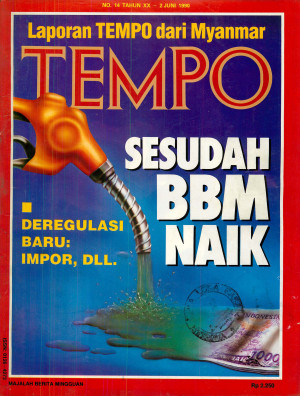TUA, penuh keriput, gendut lagi. Perutnya buncit bak tambur, dan pantatnya menyembul seperti bebek. Jambulnya putih menjuntai. Siapa lagi dia, kalau bukan tokoh dalam dunia pewayangan, Ki Lurah Semar Badranaya alias Sang Hyang Ismaya. Di Jawa Semar punya tiga orang anak: Gareng, Petruk, dan Ba- gong. Dalam cerita perwayangan, Semar berperan sebagai punakawan yang menjaga agar para tokoh Pandawa tetap berada pada garis kesatriaan. Namun, pertengahan Mei lalu di Fakultas Antropologi Universi- tas Hawaii, AS, Semar ditampilkan di pentas ilmiah. Alhasil, dia mengantarkan Sumastuti Sumukti, warga Amerika kelahiran Surakarta, menggaet gelar M.A. Tuti, panggilan akrab Sumastuti Sumukti, manulis, menulis tesis tentang tokoh punakawan itu -- ditilik dari pandangan masyarakat Jawa. Bagi Tuti, Semar merupakan tokoh yang punya karisma unik. "Di zaman modern ini, Semar masih sanggup tampil sebagai tokoh panutan. Itu menarik," ujarnya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, Tuti menjumpa kelompok masyarakat yang mendalami "paham" Semar -- tentang etika dan budi pekertinya -- untuk diamalkan. Buat melengkapi risetnya, Tuti terbang ke Solo dan Yogya dua tahun lalu menonton wayang kulit mewawancarai dalang-dalang, dan keluar masuk perpustakaan. Ia juga melakukan studi kepustakaan di Universitas Leiden (Belanda) dan Hawaii. Dalam pergelaran wayang kulit, Semar bersama ketiga anaknya hampir selalu muncul lepas tengah malam, dalam babak goro-goro yang banyak diisi dengan banyolan dan gending-gending yang segar. Pada babak ini, Semar lebih sering bertindak sebagai moderator, memberi umpan bagi ketiga anaknya untuk menggelindingkan humor. "Tapi Semar bukanlah sekadar pelawak," ujar Tuti. Munculnya Semar dalam goro-goro, menurut Tuti, berarti dia tampil untuk mengatasi persoalan. Sebab, goro-goro itu menjadi forum bagi keluarga Pandawa untuk berkonsultasi dengan Semar, untuk memecahkan kemelut yang tengah melanda. Biasanya Pandawa diwakili oleh Arjuna atau putranya, Abimanyu. Dalam diskusi itu Semar senantiasa mengemukakan pikiran-pikiran yang berpihak pada sikap bijaksana. "Semar merupakan lambang dari akal budi manusia," ujar Tuti. Namun, kebijaksanaan Semar itu tak menurun pada ketiga anaknya. Justru dalam diskusi itu Semar sering terlibat dalam perdebatan yang seru, tapi diwarnai humor, dengan Gareng, Petruk, maupun Bagong. Ketiga anak itu kerap mengajukan pikiran naif yang berpihak pada keuntungan go- longan. Maklum, "Mereka menjadi lambang dari nafsu manusia," kata Tuti. Kendati punya hubungan dekat dengan Pandawa, keluarga Semar lahir dari sejarah yang berbeda. Pandawa lahir bersama munculnya Kitab Mahabarata di India, sekian abad silam. Namun, "Tokoh Semar tak ditemui dalam kitab Mahabarata atau Ramayana," ujar Prof. Dr. Soedarsono guru besar sejarah kesenian di UGM Yogyakarta. Tuti memperkirakan Semar lahir pada abad ke-10, di Tanah Jawa. Pemunculannya tampak dari sebuah relief di Candi Jago Jawa Timur, Candi Sukuh dekat Solo, dan Candi Dieng dekat Wonosobo, Jawa Tengah. Dan kehadiran Semar itu baru digan- dengkan dengan cerita wayang Mahabarata pada abad ke-16. Semar, menurut mitos, lahir lewat sebutir telur milik Sang Hyang Tunggal, Sang Penguasa Semesta. Syahdan, telur itu pe- cah. Kulitnya menjadi sosok manusia setengah dewa bernama Togog alias Tejomantri. Pada saat yang sama, putih telurnya berubah menjadi Batara Narada, dan kuning telur menjadi Batara Guru. "Sedangkan Semar terjelma dari selaput telur," ujar Soedarsono. Lantas, setelah mereka dewasa, turunlah petunjuk dari Sang Hyang Tunggal. Batara Guru bertugas di Kahyangan dan memim- pin legiun dewa-dewa, didampingi Batara Narada. Tejomantri dititahkan mengabdi keluarga Kurawa, seteru Pandawa. Dan Semar ditunjuk sebagai punakawan Pandawa. Dalam posisi sebagai punakawan, menurut Sumastuti, Semar justru punya peran strategis. Dia digambarkan bisa mendengar aspirasi semua kalangan, baik elite keraton maupun para jelata kawulo alit. "Kalau jadi raja, dia tak leluasa berhubungan dengan banyak kalangan," ujar Tuti. Setelah menyimak episode-episode wayang kulit, Tuti sampai pada kesimpulan bahwa Semar merupakan simbol tiga hal: akal budi (human mind), kebijaksanaan (wisdom), dan kesemestaan (universe). "Itulah pandangan orang Jawa atas Semar," ujarnya. Akal budi, menurut Tuti, mengacu kepada konsep mikrokosmos, dan kesemestaan merujuk pada konsep makrokosmos. Jadi. Semar dianggap merupakan perpaduan antara mikro dan makro-kosmos. "Sungguh tak mengherankan jika kemudian figur Semar dijadi- kan panutan," tutur Tuti. Keteladanan Semar pun terus bergulir mengikuti arus zaman, bahkan tetap diterima oleh masyarakat Jawa pada zaman semodern kini. Nilai-nilainya tetap lestari, kata Tuti, "Karena wayang tak pernah memaksakan suatu ajaran." Wayang hanya menunjukkan bahwa ada ajaran seperti dilakonkan para tokohnya. "Penonton bebas memberi persepsi sesuai dengan kebutuhannya," kata Tuti. Nama Semar, menurut Tuti, berasal dari kosa-kata Jawa Kuno Smer, yang artinya ide, atau suatu produk buah pemikiran. Karena melambangkan akal budi manusia, Semar pun bisa diterima oleh sebagian seniman Islam Jawa. Manifestasinya terlihat pada gambar kaligrafi huruf Arab, berisi petikan ayat Quran atau hadis, yang membentuk postur Semar. Selain dibahas oleh banyak ahli Indonesia sendiri, ketokohan Semar pernah pula dipelajari oleh peneliti Jepang Masato Fukusima pada 1987, yang mempelajari eksistensinya lewat sekumpulan masyarakat di daerah Blora, Jawa Tengah, yang menganut "paham" Semar. Dalam aliran kebatinan itu, Semar muncul sebagai etika untuk mencapai hidup tenang dan damai. Semar memang sebuah ide. "Dia lahir lewat proses pemikiran yang matang," ujar Sumastuti. Putut Tri Husodo (Jakarta) dan I Made Suarjana (Hawaii)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini