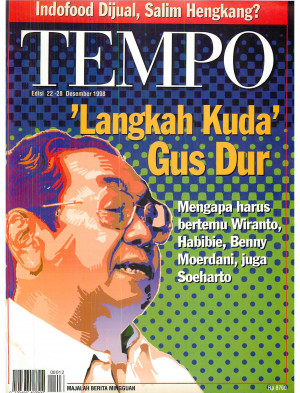Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Wilson sendiri, yang belakangan menulis buku berisi kisah sukses Soeharto, The Long Journey from Turmoil to Self-Sufficiency, meramal sang Presiden akan turun lima tahun kemudian pada 1993, yakni ketika masa jabatannya yang kelima usai.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo