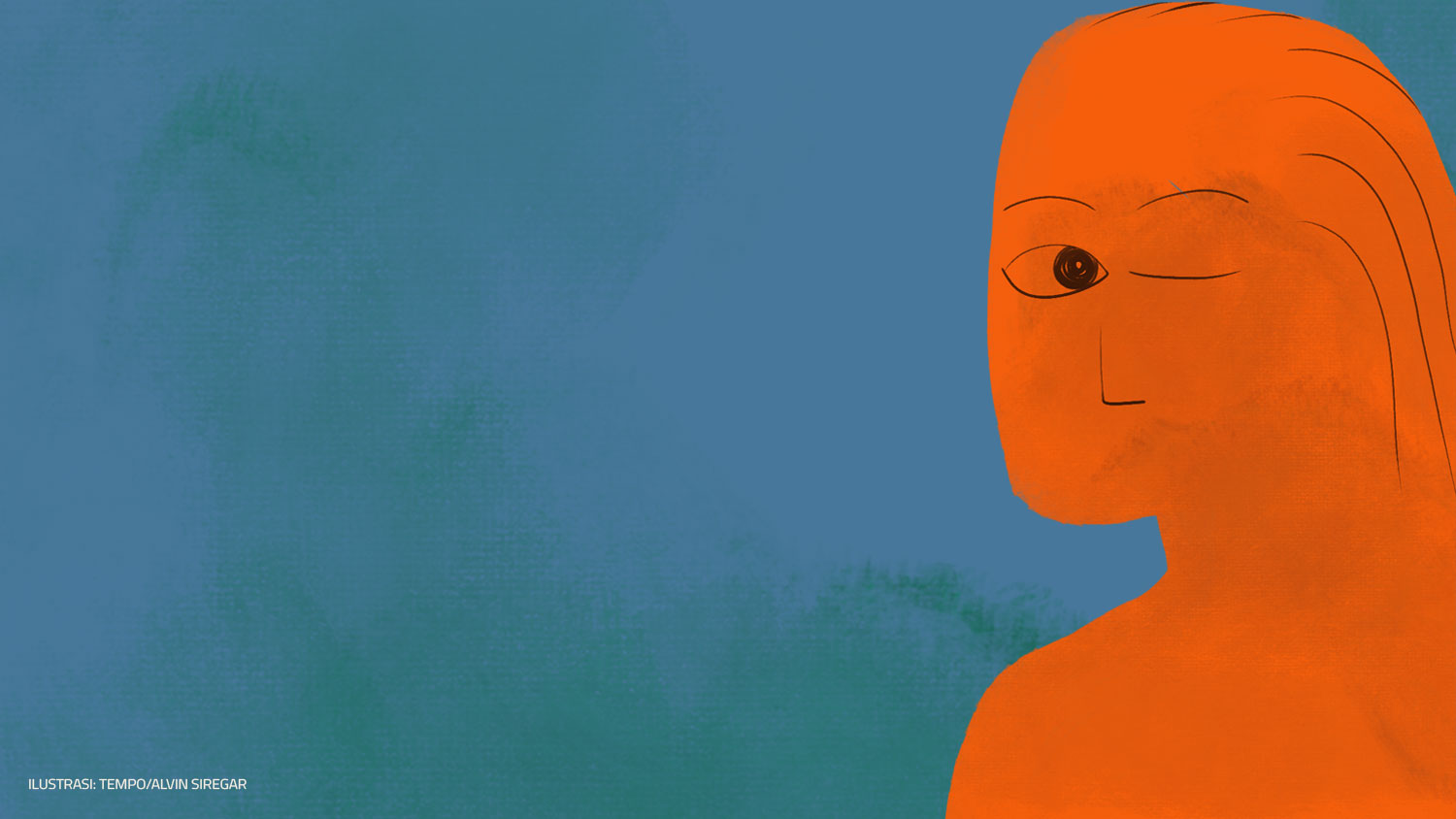Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PAMERAN “Manifesto” digelar lagi di Galeri Nasional Indonesia dan Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, 27 Juli-26 Agustus 2022. Program dua tahunan ini pertama kali digelar pada 2008 dengan tema “Percakapan Masa”, yang kala itu merujuk pada seabad Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Seiring dengan waktu, tema “Manifesto” berikutnya mendekat pada persoalan-persoalan aktual yang dominan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun ini, dewan kurator mengajak perupa menjadi penyaksi dan pengamat sosial lewat tema “Transposisi”.
Manifesto adalah julukan menarik lantaran dengan mudah menautkan kita pada Manifesto Politik-Usdek yang dicanangkan Presiden Sukarno pada 1959. Ini merupakan pernyataan populer yang mengajak bangsa Indonesia mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 serta mengerti sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Jangan lupakan pula Manifesto Kebudayaan, gerakan yang mencanangkan humanisme universal pada 1963, sekaligus menolak hegemoni politik dalam seni dan budaya.
Lantaran konotasi “manifesto” memang mepet-mepet ke arah sana, konten pameran ini juga “pernyataan sikap” para perupa terhadap situasi dua tahun terakhir. Yang tentu dikaitkan dengan kurun sebelumnya dan diproyeksikan ke masa-masa berikutnya. Pernyataan sikap itu diwujudkan dalam bentuk seni rupa.
Yang menarik, pernyataan sikap yang dibiarkan subyektif tersebut pada gilirannya menggumpal dan menjadi penyataan sikap semi-obyektif. Hal seperti ini terlihat dalam pameran yang dikuratori Suwarno Wisetrotomo, Citra Smara Dewi, Teguh Margono, dan Riski A. Zaelani tersebut. Misalnya, dalam pajangan terlihat dan terbaca karya seni yang (diam-diam) menatap khazanah kebudayaan asli Indonesia. Karya-karya tersebut mewacanakan unsur-unsur kebudayaan leluhur dengan mengacu pada tradisionalitas Nusantara. Atau bahkan mengangkat unsur-unsur seni tradisional dalam perwujudan seni rupa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo