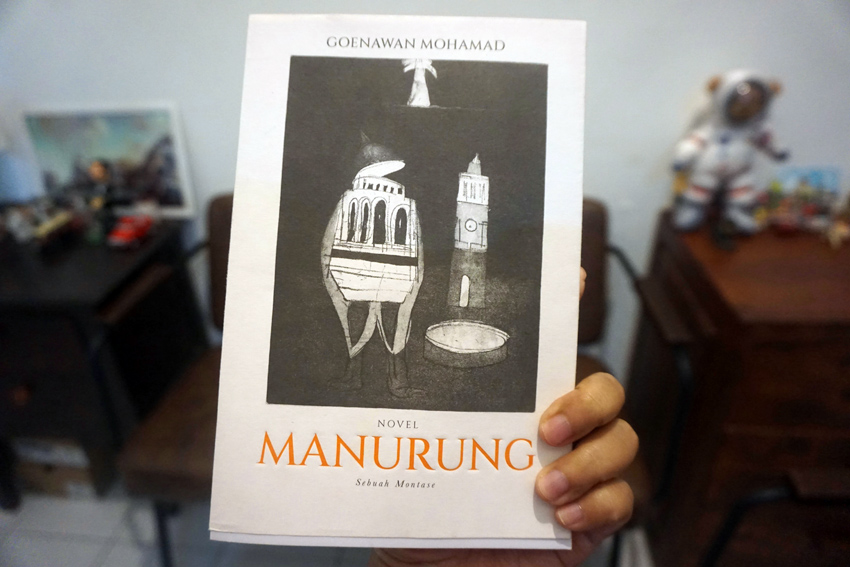Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NH. Dini adalah cerita yang tak pernah berhenti. Telah puluhan novel dan ratusan cerpen yang dia tulis. Sebagian besar diilhami kisah hidupnya sendiri. Sebuah bukti bahwa hidup perempuan bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin ini memang sungguh penuh warna.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo