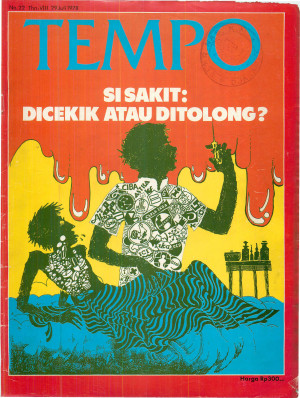HUM-PIM-PAH
Karya: Putu Wijaya
Sutradara: Sutarno S.K
Produksi: Teater Kail Jakarta
SEBUAH teater yang baik, pada akhirnya memang harus tetap tegar
sebagai sebuah teater yang bisa difahami. Betapapun buruknya --
atau absurnya. Ionesco misalnya, yang absurditasnya konon masih
berdasar pada simbol, di dunia Barat, ternyata juga masih bisa
difahami. Bahkan oleh anak-anak sekolah dasar -- di negerinya.
Apalagi Putu Wijaya. Ia bukanlah penulis lakon yang gelap, yang
karya-karyanya hanya dibuat untuk "kenikmatan diri sendiri."
Sebab kalau pun di sana ada berbagai lambang, yang oleh seorang
Rustandi Kartakusumah dikatakan "absurd", maka sesungguhnya ia
masih tetap bisa dimengerti.
Keyakinan bahwa Putu tampil dari dalam teater tradisionil,
agaknya menjadi dasar Sutarno S.K. untuk mengangkat
Hum-Pim-Pa/ke pentas Teater Arena TIM --pertengahan Juli yang
lalu.
Dengan set yang padat, Sutarno -- yang juga penata artistik --
menaruh sebatang pohon dengan tali-tali plastik sebagai daunnya.
Di sampingnya sebuah kursi, tumpukan level dan sebuah drum
aspal. Ini sudah pertanda baik.
Tontonan
Sebagai tontonan, sebagaimana terus-menerus disarankan Putu
dalam berbagai pementasannya, penampilan Teater Kail kali ini
sangat menarik secara fisik. Dengan kata lain bila fungsi naskah
dan "isi" dikesampingkan. Sutarno nampak menjadi tak pedulian.
Fungsi kata-kata, yang begitu banyak dan begitu cerewet dalam
lakon-lakon Putu, nyaris hanya muncul sebagai bunyi-bunyi yang
tak ada artinya. Sebagaimana bunyi ketukan bambu, pukulan drum,
gebrakan level dan teriakan seluruh pemain.
Memang disebut-sebut orang atau tokoh-tokoh yang bernama Korban,
Dedengkot dan Pelacur. Tapi mereka ditampilkan hanya melulu
sebagai lambang, bukannya sosok. Padahal, betapa pun kaburnya
perwatakan peran-peran itu, ia masih tetap memiliki sesuatu yang
boleh disebut karakter, jiwa pribadi, nama lambang dan juga
jasmani. Mereka masih memiliki rasa sakit, nestapa, harapan,
keluh kesah, keberanian, kebencian dan dendam pesimisme.
Setidak-tidaknya tak hanya teriakan, suara serak dan kebisingan
saja.
Padahal 'Kail' yang mulai beranjak dewasa dalam pementasannya
yang kedua setelah dibaptis jadi senior ini, memiliki semangat
yang tinggi. Apalagi mereka begitu kompak, terutama pada setiap
peranan orang banyak. Serta memiliki cukup kreasi dalam
penampilan gruping dan bloking, selain kerapian tata cahaya.
Itulah yang menyebabkan pertunjukan mereka tetap memiliki daya
pikat sampai akhir.
Seharusnya ia juga memiliki daya tangkap yang baik terhadap
naskah. Terhadap "isi", bila memang hendak memunculkan
fikiran-ikiran pengarangnya, bukan cuma dagingnya. Ini yang
belum jadi persoalan Sutarno. Ia tidak berusaha menjadi pembaca
yang sepadan.
Pementasan yang begitu menggebu, begitu nekad dan begitu
semangat itu, menjadi bagai kacang yang tak ada isi. Sebab terus
terang saja, sebagai penonton yang belum pernah membaca
naskahnya, saya tak bisa menangkap ide atau cerita apa-apa.
Padahal ini penting. Sama pentingnya dengan kewajiban pemain
untuk tidak hanya pandai bersuara lantang.
Penampilan juga harus bisa menyampaikan 'kandungan kalimat',
betapa pun verbalnya. Karena pada karya-karya Putu, verbalisme
hampir-hampir sudah menjadi ciri. Pada kalimat-kalimat itulah
jalan fikiran dan keresahan dituangkan. Apalagi sebuah teater
yang baik pada akhirnya memang harus tetap tinggal sebuah teater
yang bisa difahami. Betapapun buruknya -- atau absurdnya.
Noorca M. Massardi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini