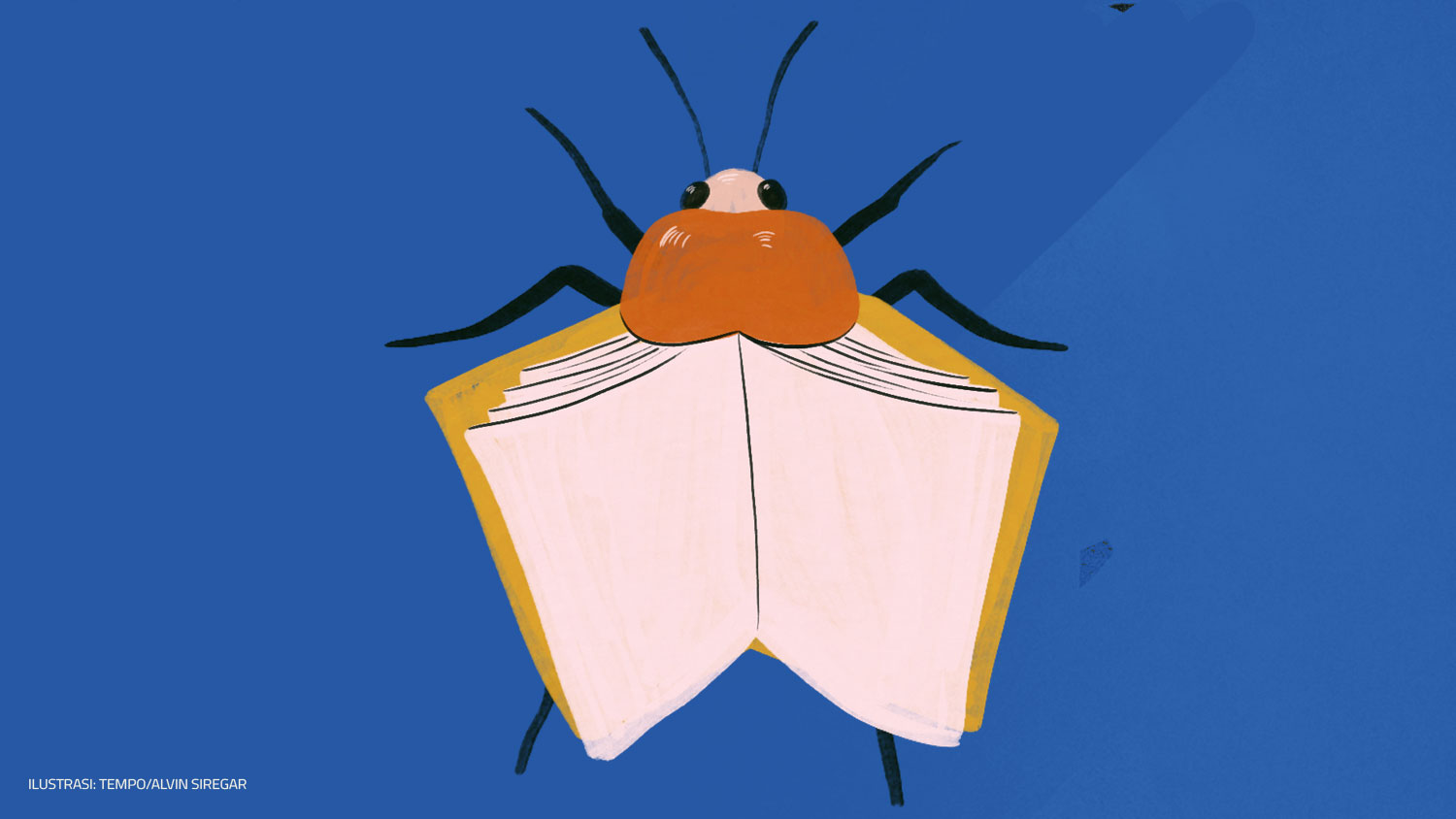Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Cerpen Gusti Aditya yang berkisah para perempuan tangguh di Rue Saint-Denis.
Ceritanya berlatar belakang lika-liku kehidupan malam di Paris.
Bermula dari pertemuan sang tokoh yang mabuk dengan Madame Mei.
KAU adalah jurnalis yang payah. Setidaknya itu yang kau ingat dari apa yang dikatakan jurnalis senior di sebuah acara kepenulisan di sekitar Panthéon. Barangkali amarah itulah yang membawa langkahmu menuju sebuah bar dan mabuk sepuasnya. Banyak lelaki hidung belang yang datang, ia menggodamu dan ingin menidurimu. Kau yang setengah sadar, hanya tertawa dan meringis. Penglihatan dan pendengaranmu menjadi buruk, kau merasa ada tangan asing yang mulai menyentuh leher dan pipimu. Setelah itu, hanya suara BUK yang lumayan keras kau dengar. Tiba-tiba lelaki hidung belang itu tersungkur, hidungnya keluar darah. “Rasakan tinju Madame Mei,” kata seorang perempuan di sampingmu. Hanya sampai situ yang kau tahu. Sisanya adalah kelabu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo