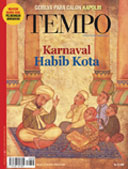Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Puluhan orang membawa suluh berlari cepat. Siluetnya memenuhi jalanan Kampung Kauman, kawasan muslim dekat Keraton Yogyakarta. Penduduk menyingkir. Sebagian lagi hanya berani mengintip keramaian itu. Satu tempat mereka tuju: langgar kidul milik Ahmad Dahlan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo