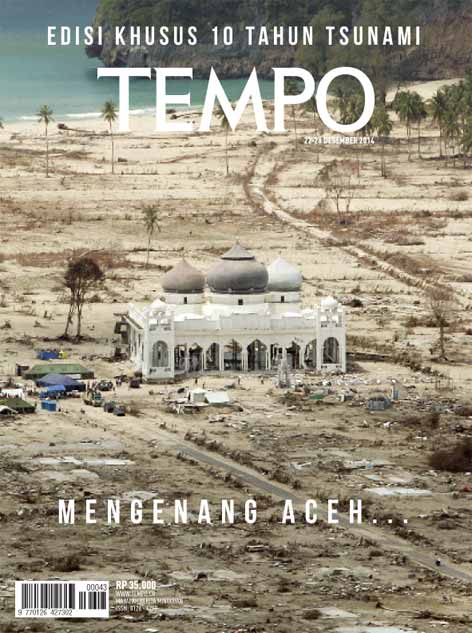Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI panggung, puisi itu hadir sekitar satu jam. Dua puluhan musikus mengisi bagian belakang panggung, bagian yang ditata mengesankan kapal. Lalu, di sudut kiri depan penonton, spiral besar mengerucut, hampir menyentuh garis atas bingkai panggung. Mungkin ini dimaksudkan sebagai menara, dengan tempat berdiri di atas, dan tangga yang tak terlihat oleh penonton. Di tempat berdiri itulah, sedikit di atas garis tengah, seorang vokalis melantunkan puisi yang dinyanyikan, dengan suara yang tinggi.
Musik lebih sering menggeresek bagai datang dari dalam balok yang digerus rayap. Hanya kadang ada dentam menyeling atau senandung piano atau sayatan instrumen gesek. Dan dua penutur, lelaki dan perempuan, lalu enam penari yang kadang keenamnya tampil bersama, kadang hanya empat atau tunggal atau sepasang, berkostum sepenuhnya putih. Di tengah pertunjukan, lampu yang meredup di depan dan terang di belakang menampilkan sekumpulan paduan suara.
Puisi itu dipersiapkan sejak awal, ketika dua penutur tampil ke panggung dari depan penonton dan membacakan intro dari puisi Gandari dalam sunyi: "Rekaman lima hari sebelum ibu para Kurawa itu membalut matanya…." Dan masih dalam sunyi yang bersih, mendadak seorang penari menjatuhkan diri, langsung bergulung ke samping agak menyerong; koreografi yang menyentak sekaligus mengawali satu jam pertunjukan yang liris. Musik, soprano, tari, bait-bait Gandari dalam wadah tata panggung yang minimalis dilengkapi gambar atau kata-kata berganti-ganti pada layar latar.
Tak ada kisah urut tersaji tentang ibu para Kurawa itu, atau tentang perang besar yang sampai padanya dari Sanjaya, seorang keponakan yang memiliki kesaktian bisa melihat Padang Kurusetra dari suatu jarak, dari istana. Pun nyanyian soprano itu lebih hanya terdengar sebagai nada tinggi, menyembunyikan kata-kata. Dan koreografi adalah tubuh-tubuh yang bergerak pada garis horizontal panggung atau garis diagonal, menggerakkan ruang.
Seluruhnya adalah ketegangan yang liris, yang tak merajut kisah, total niskala, hanya suasana. Lalu, sebelum suasana itu membuat letih imajinasi, terdengar suara penutur melontarkan kalimat-kalimat, membentuk imaji-imaji, bukan cerita, melonggarkan keniskalaan. /Di luar aula para dewa,/ ketika angkasa kosong, Brahma mencipta/ Kematian./
Sungguh suatu keutuhan yang tak memberi peluang untuk sejenak menduga: musikkah yang memenuhi panggung? Koreografi itukah yang menguasai ruang? Atau lantunan suara yang cenderung merayap tapi dengan artikulasi jelas yang membuat kita menangkap rasa dari liris yang niskala? Dan tata panggung yang minimalis kukuh, yang bertahan dari segala suara dan gerak? /"Mereka menghendaki aku, Kematian,/ Mereka menghendaki aku."/ Mungkin Gandari mendengar kata-kata itu./
Satu jam Opera Tari Gandari adalah sajian imaji-imaji. Keniskalaan itu memecah diri saat terlantun bait-bait yang mengandung kata-kata yang mensugesti. Kematian. Angkasa gemetar. Trowongan langit yang merendah. Medan catur yang panjang. Pion-pion yang bungkam.
Perang besar di Padang Kuru, perang keluarga Bharata, latar puisi Gandari, ibu yang kehilangan anak-anaknya, mungkin terbangun dalam imajinasi penonton, mungkin tidak. Namun ihwal manusia, hidup dan kematian, nasib yang menggerus harapan datang dari panggung tanpa kita harus paham, setengah paham, atau sedikit paham Bharatayudha. /Ia menari. Di pelukannya yang putih, ada mayat/ yang terpenggal/.
Dan kita mengenal atau tidak nama-nama dalam puisi Gandari, perang yang membunuh atau dibunuh, dendam yang tersimpan tanpa susut, datang dari paduan musik, tari, dan terutama bait-bait puisi itu. "Bhisma gugur/ dengan 100 liang luka/. Lalu beberapa menit sebelum semuanya berakhir, "Dan dengan wajah yang dingin, tuanku",/ kata sang utusan, "Drupadi mencuci rambutnya/ dalam darah/. Dan itu darah "Dursasana"/ "Darah anakku."
Opera Tari Gandari adalah karya yang menyapa kepekaan indra, dengan dimensi yang dalam. Ada kekuatan yang memukau untuk terjadinya "komunikasi pengalaman batin… komunikasi misteri kehidupan yang terdalam…", meminjam kata-kata Bambang Sugiharto dalam buku Untuk Apa Seni.
Hal itu tercapai, pada hemat saya, karena perpaduan segala unsur yang saling menguatkan, sama-sama tidak ingin menonjol, tapi dengan olah seni masing-masing yang diupayakan semaksimal mungkin. Musik, penutur puisi, koreografi, tata panggung. Hasilnya, seperti sudah disebutkan dalam tulisan ini, pertunjukan yang padu, hampir mengikat sepenuhnya. Hampir, karena menjelang akhir ada semacam jeda, dihadirkannya seorang ibu dari kelompok Kamisan, kelompok yang tiap Kamis melakukan protes damai di depan Istana Merdeka sejak hampir delapan tahun lalu.
Maria Katarina Sumarsih, ibu itu, mewakili orang tua yang kehilangan anak mereka di masa demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998 menentang pemerintah yang otoriter. Anak-anak itu, mahasiswa, hilang karena tewas terkena peluru tajam aparat keamanan, entah tentara entah polisi, karena segalanya belum jelas dan karena itulah mereka memprotes, menginginkan kejelasan, agar yang serupa tak lagi terjadi.
Apakah Maria Katarina dan orang-orang tua yang kehilangan anaknya adalah Gandari? Tapi pertanyaan dalam kepala saya ini tak berlanjut. Ada kisah yang disampaikan ibu di panggung yang saya rasakan sesuasana dengan Opera Gandari. Setelah seizin aparat, dengan sesobek kain putih sebagai bendera, Wawan, nama anak Katarina, mencoba menolong temannya yang terkapar di jalan, mungkin kena tembak. Namun, sebelum niatnya kesampaian, di dekat yang terkapar, Wawan pun terkapar. Peluru resmi yang digunakan aparat mengakhiri hidupnya. Sesudah itu, meja makan di rumah keluarga Katarina selalu sepi, hingga kini.
Mungkin yang ingin melihat sebuah pertunjukan yang utuh seutuhnya tanpa gangguan dari "luar" terusik oleh "adegan" ini. Memang, saya rasa masuknya adegan ini terasa ganjil, dan ini persoalan "teknis". Yang saya kira patut diingat, ide ini datang dari sutradara, adalah pertanyaan itu: untuk apa seni. Dan ini langsung mengingatkan pada Sanento Yuliman (almarhum), yang pernah menggugat seni rupa Indonesia ketika karya-karya seperti hanya ingin "aman dan nyaman", tema yang "menegangkan pikiran dan mengganggu perasaan dijauhkan".
Bagi saya, wacana Maria Katarina memang mengganggu perasaan, pada ketika itu. Namun itu perlu bila ia mendapatkan tempat yang pas. Menurut saya, tempat itu pas karena Opera Gandari menyuguhkan sajian "komunikasi batin dan pengalaman misteri kehidupan" yang utuh, dan Katarina membacakan kisahnya dengan suara datar, suara yang tak mengusik panggung seisinya.
Bambang Bujono, Pengamat Seni
Tony Prabowo:
Dalam Musik Sekarang Itu Harmoni dan Melodi Sudah Dibuang
Bagi banyak telinga orang, musik yang disajikan Tony Prabowo selalu terdengar susah. Beberapa orang bergurau, musik Tony tidak bisa disiulkan. Mereka membandingkannya dengan musik-musik pop atau klasik terkenal, yang bisa diingat-ingat melodinya dan disiul-siulkan saat senggang. Juga tatkala kita menyaksikan Opera Tari Gandari. Musik yang disodorkan Tony seolah-olah antimelodi. Tak ada, misalnya, nada-nada atau refrain yang menyentuh perasaan, apalagi sampai menimbulkan efek haru. Musik Tony seolah-olah dingin, anti-perasaan.
Tony memang dengan sadar memilih jalur musik demikian. Dalam membuat komposisi, dia suka mengeksplorasi wilayah-wilayah atonal. "Saya memilih atonal karena memang saya suka," katanya. Lahir di Malang pada 1956, Tony belajar biola di Sekolah Musik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian ia masuk Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta—sekarang Institut Kesenian Jakarta. Ia sempat berguru pada Slamet Abdul Sjukur. Dia sadar pilihan bermusiknya di jalur yang sepi. Ia juga sadar di sini orang tak betah mendengarkan musik kontemporer lama-lama. Toh, ia terus mempertahankan sikap estetisnya, tanpa mengendur sedikit pun—"menurunkan" standar musiknya.
Dan kali ini, untuk Opera Tari Gandari ini, ia tak ingin tanggung-tanggung. Ia mengajak Asko Schoenberg, salah satu orkestra kontemporer terbaik di dunia dari Belanda, untuk memainkan komposisinya. Orkestra ini tak sembarangan mau memainkan karya komponis kontemporer. Sebanyak 26 musikus Asko Schoenberg diterbangkan dari Belanda untuk memainkan karyanya. Berikut ini petikan wawancara wartawan Tempo Ananda Badudu dengan Tony Prabowo seusai geladi resik Opera Tari Gandari.
Komposisi Anda terdengar seperti musik antimelodi. Bisa jelaskan sikap Anda dalam bermusik?
Dalam musik sekarang itu harmoni dan melodi sudah dibuang. Saya saja dengan komposisi yang saya buat di Gandari merasa ketinggalan. Ini ketinggalan kalau dibandingkan dengan yang berkembang di Eropa. Idiom di Eropa sudah jauh ke mana-mana. Tapi, kalau saya mengejar apa yang berkembang di Eropa, kasihan pendengar di sini, tidak akan tahan.
Bisa jelaskan konsep musik atonal Anda?
Wah, panjang penjelasannya. Yang jelas, atonal itu menggunakan sistem 12 nada. Itu kebalikan dari tonal. Tonal kan dari mayor kembali ke mayor lagi. Kalau atonal, bebas ke mana-mana.
Butuh berapa lama menyelesaikan musik Gandari?
Butuh waktu 1 tahun 4 bulan. Prosesnya lama. Saya butuh waktu lama untuk bikin komposisi. Saya bikin partitur untuk 25 instrumen. Mulai menulis pada 1 Mei 2013, selesainya September 2014.
Bagaimana Anda bisa meyakinkan Asko Schoenberg memainkan komposisi Anda?
Nah, itu dia. Saya ini siapa sih? Saya ini siapa, yang berani-beraninya minta Asko yang "Tuhan"-nya musik kontemporer memainkan komposisi saya. Saya tegang sekali ketika meminta mereka memainkan komposisi saya. Saya modal nekat saja. Komunikasi pertama dengan mereka awal tahun lalu, lewat e-mail. Setelah itu, mereka lihat score yang saya bikin. Baru mereka setuju.
Kalau ternyata mereka tidak setuju, bagaimana?
Ya, cari ensambel lain. Ada calonnya. Tapi, kalau mereka sampai tidak setuju, saya malu setengah mati.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo