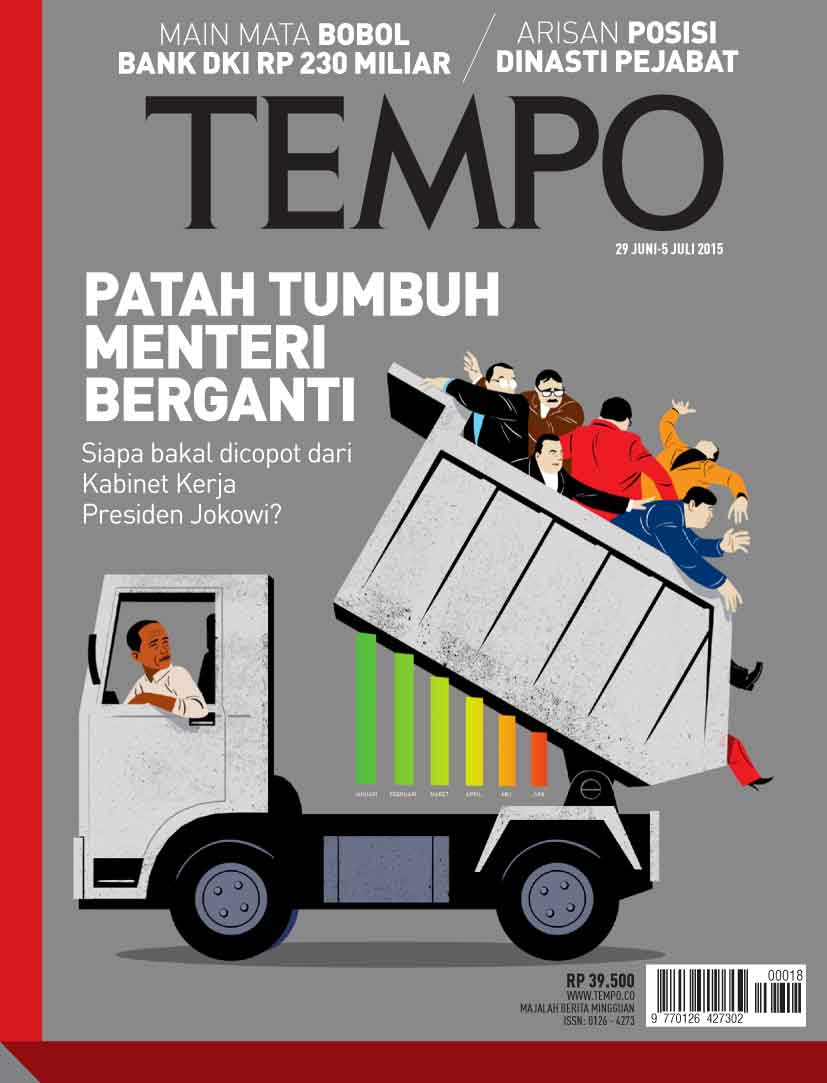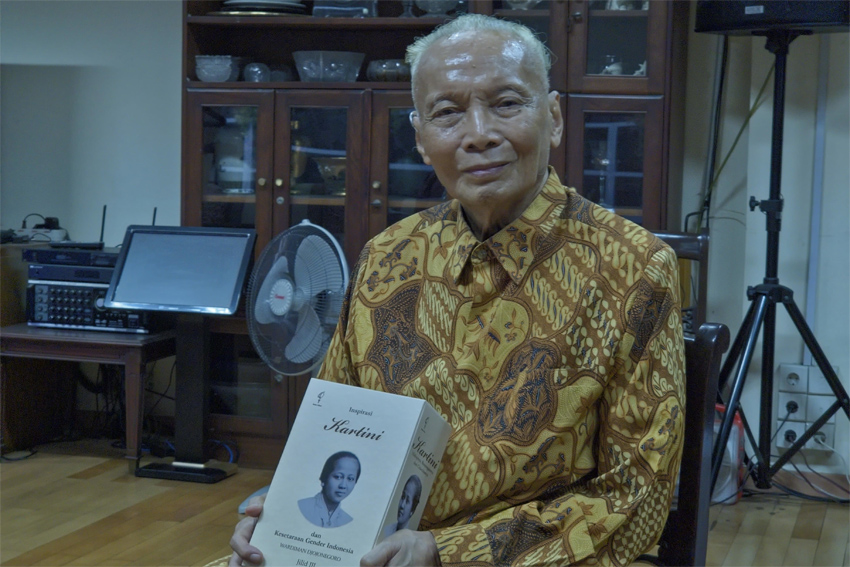Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebuah keluarga digambarkan sedang berkumpul menghadap ke meja panjang. Perjalanan hidup keluarga ini kacau. Mereka adalah Rosnah (Arsita Iswardhani), Rosyid Samudra (M.N. Qomaruddin), Mohammad Husen (Ari Dwianto), dan ibu dari keluarga ini (Erythrina Baskoro). Rosyid Samudra sangat membenci komunis. "Fuck komunis," katanya. Ia menjadi teroris di Afganistan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo