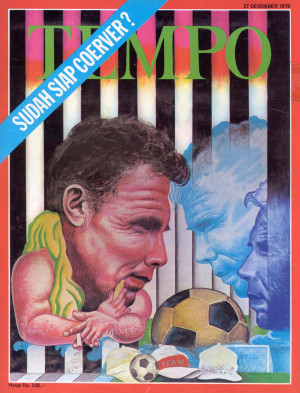BIASANYA, seorang anak muda: yang mulai berkarya belum dibebani
pertanyaan: untuk apa semua itu is kerjakan? Atau bagaimana
seharusnya. Begitu saja semacam kekuatan dari dalam
mendorongnya untuk berkarya. Tak jarang pula dorongan itu
terpancing ke luar karena melihat orang lain mengerjakan itu.
Demikianlah pelukis Sudarso, 61 tahun, yang akhir Nopember lalu
memamerkan 34 karyanya di TIM. Ia terdorong melukis karena salah
seorang langganan yang membeli telur dan susunya tak lain
adalah Affandi. Hal itu konkritnya bermula ketika Affandi
memberinya sejumlah sisa-sisa cat dalam tube-tube yang gepeng.
Dan dorongan itu semakin menjadi ketika Affandi beserta anak dan
isterinya berkunjung ke pondok Sudarso, dan menganjurkannya agar
terus menggambar.
Lukisan-lukisan Sudarto di TIM itu tidak semuanya baru: hanya 10
buah yang berasal dari tahun 70-an. Ini menarik. Kecuali
menunjukkan -kepada publik perkembangan karya-karyanya, sekali
gus mengundang simpati atas kerendah hatian - yang bukan
mustahil tak disengajanya. Kenapa? Bisa dikatakan bahwa
lukisan-lukisannya yang baik adalah yang dari tahun-tahun 60-an
ke belakang. Memang benar karya-karyanya dari akhir 60-an dan
70-an lebih cantik dan bersih. Namun kecantikan di situ rasanya
kecantikan karena make up.
Bandingkan misalnya Kerera Muntit (1946), Suasana Tahun 46
(1947). Isteriku (1947), Nenekku (1959), Mbok Mangun (1946),
dengan-Tri (1974), Potret Diri (1973), Perahu-perahu (1973 ).
Baju Merah (1975) atau Mbak Ami (1975). Deretan yang pertama
menunjukkan betapa sapuan-sapuan kuwasnya, komposisi warnanya
dan tarikan-tarikan garisnya hidup, ekspresip-- dan wajar.
Meskipun qua-teknik bisa disebut beberapa kelemahan: perspektif
warna yang kurang, Mngga pohon-pohon dan kereta muntit rasanya
pada satu bidang atau bentuk-bentuk pohon yang sama saja. Namun
itu semua justru menimbulkan apa yang disebut ekspresi itu.
Semuanya bukan terasa sebagai kelemahan namun sebagai suatu
bentuk di mana emosi-emosi tersalur - ke luar. Dan pelukis yang
kini biasanya disebut bergaya realistis ini bukan tak pernah
punya kecenderungan lain. Lihat misalnya Nenekku (1959). Lukisan
satu ini bidang-bidangnya punya kecenderungan kubistis yang
kuat. Sedang warna-warnanya menunjukkan keberanian Sudarso untuk
tidak sekedar menangkap dan menuangkan seperti apa adanya.
Serasa Lilin
Mungkin karena pribadinya yang tak begitu kokoh, di tengah
perjalanannya sebagai pelukis, di tengah suasana "realisme
sosialis" Lekra dan "romantisme dangkal" Basuki Abdullah tahun
60-an, justru muncul beban itu: untuk apa sebenarnya is melukis.
Dan seperti yang kita saksikan sekarang ini, ia memilih yang
terakhir - untuk melanjutkan hidupnya sebagai pelukis.
Muncullah sejak itu perempuan-perempuan cantik dengan kain
kebaya yang rasanya baru saja dibeli dari toko, dengan setting
yang tak masuk akal pemandangan dusun, sawah dan sebagainya -
bila dihubungkan dengan bentuk dan pose figurnya. Dan Sudarso
yang kiranya tak pernah secara sungguh-sungguh belajar apa itu
anatomi tubuh manusia, yang menangkap bentuk manusia hanya dari
luarnya, memang hanya memberikan pose-pose yang kaku,
bentuk,bentuk yang cantik namun serasa lilin: benda mati tak
berdarah. Benar, satu dua is pernah melahirkan lukisan-lukisan
yang halus, lembut warna dan garisnya. Misalnya Stagenan (1968).
Namun agaknya hanya satu kebetulan. Juga beberapa pemandangannya
yang menghadirkan warna-warna segar dengan goresan yang
meyakinkan. Bukan hanya karena yang macam ini sedikit jumlahnya,
tapi sebagai satu karya masih butuh dikembangkan - sedang
perkembangan selanjutnya, kita tahu, begitulah ....
Barangkali Sudarso masih bisa diharap, barangkali juga tidak.
Yang jelas sejarah akan mencatat juga, bahwa is pernah
menghasilkan karya-karya yang tak begitu buruk.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini