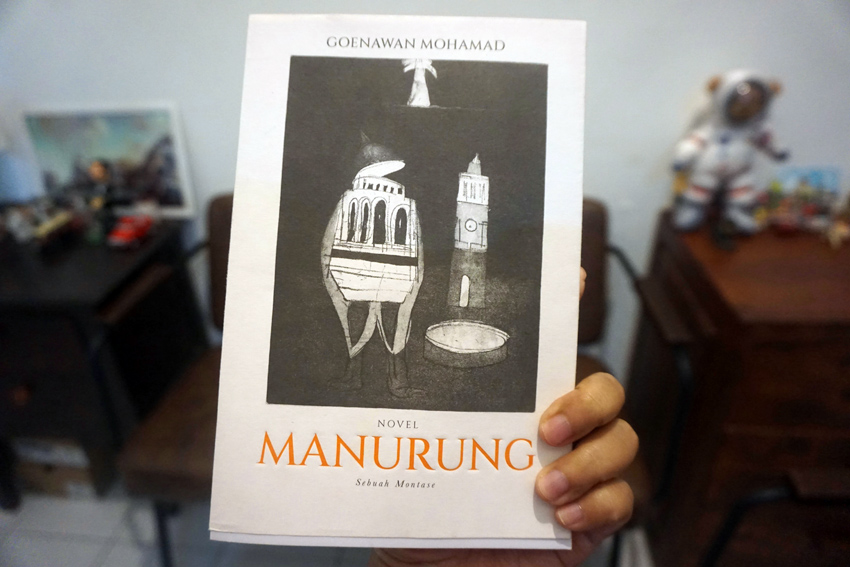Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Munculnya teater dengan bentuk yang inkonvensional, atau bahkan eksperimentalis macam Teater Sae plus para pengikut sesudahnya, memunculkan banyak kekhawatiran. Antara lain soal melorotnya kualitas aktor di jagat teater Indonesia karena bentuk pertunjukan semacam itu banyak memberi perhatian, fokus, dan pemaknaan pada benda, cahaya, kostum, dan peralatan panggung lainnya. Kekhawatiran ini juga—konon—akibat dominannya "teater sutradara", seperti yang kuat disinyalir dalam "pesta monolog" Jakarta, minggu lalu (TEMPO, 17-23 Mei 2004, hlm. 59-60).
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo