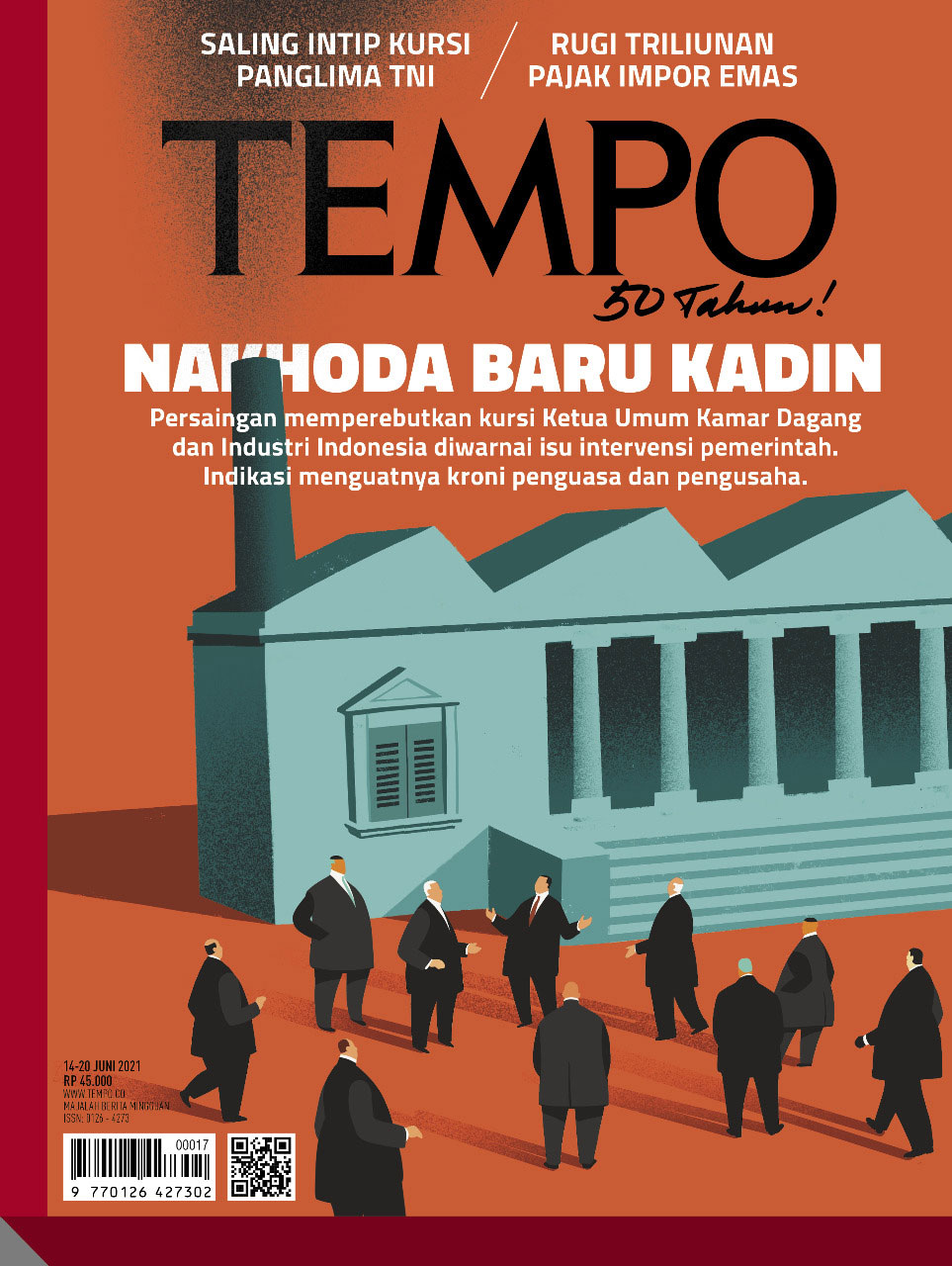Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

NADIAH Bamadhaj, 54 tahun, perupa berkebangsaan Malaysia dengan identitasnya yang hibrida, melihat bentuk submisif dari perempuan Jawa sebagai sebuah strategi untuk bertahan hidup dalam dunia yang keras, sulit, dan masih didominasi oleh laki-laki. Pergulatan panjang hidupnya selama 18 tahun di Yogyakarta membawanya pada cara pandang baru tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Lantaran konteks sosial politik dan sejarahnya, hal ini menumbuhkan gagasan yang berbeda tentang apa yang disebut sebagai tindakan feminis.
Dalam pameran “The Submissive Feminist” yang berlangsung di Kiniko Sarang Art Space Yogyakarta pada 5-26 Juni 2021, Nadiah Bamadhaj menampilkan instalasi-instalasi karyanya yang terutama menggunakan medium kertas dan arang untuk membawa narasi yang merefleksikan ketegangan dan pembelajaran atas makna menjadi perempuan dalam masyarakat Jawa. Refleksi ini telah dimulai bertahun-tahun lalu, ketika melihat tindakan orang Jawa yang “diam” dan “menerima” sebenarnya menunjukkan kekuatan mental dalam menghadapi tantangan kehidupan. Amatan atas tindak “diam” ini kemudian dipindahkan Nadiah menjadi salah satu karya yang sentral untuk memahami narasi ini.
Sebuah gambar bibir yang tertusuk oleh gagang wayang (biasanya terbuat dari tanduk binatang) diletakkannya di posisi tengah dari dinding utama galeri. Dinding ini memajang rangkaian instalasi yang terdiri atas lima bentuk berukuran cukup besar. Di sekitar citra bibir tersebut, Nadiah meletakkan ragam obyek lain. Itu adalah sebuah keris pada potret diri perempuan dari sisi belakang dengan punggung yang tertutup oleh kain batik bermotif parang rusak, wajah perempuan dan sebuah sisir rambut, serta sebuah almari rotan dengan pintu tertutup.
“Saya sendiri sebenarnya sudah lama tertarik pada simbolisme dan ikonografi Jawa, selain juga punya minat pada bagaimana membangun relevansi simbol itu dengan kehidupan keseharian. Jadi bukan hal baru juga kalau saya menampilkan simbol budaya Jawa dalam karya saya,” demikian penjelasan Nadiah. Nadiah terasa cukup lama absen dalam kancah seni rupa Indonesia. Pameran tunggalnya di Indonesia terakhir berlangsung pada 2004 di Komunitas Utan Kayu, yang bertajuk “Sixtyfive Now”, dan merupakan hasil penelitian panjangnya atas isu kekerasan 1965 di Indonesia. Setelahnya, hanya sesekali Nadiah muncul dalam beberapa pameran kelompok. Sebagian besar karyanya justru banyak dipamerkan di kota lain di Asia atau Eropa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo