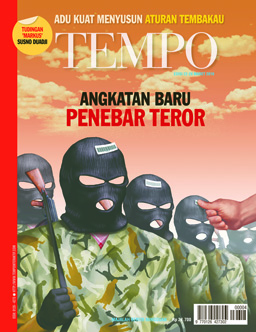Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KABAR menggetarkan datang bersama utusan dari surga. Malaikat belia itu Gabriel, yang membawa pesan sukacita dari Tuhan bagi perawan bernama Maria. Dari rahim anak dara itu akan terlahir seorang bayi, yang disebut kudus, ”Immanuel”, dan bernama Yesus. Mukjizat itu terjadi di kota kecil bernama Nazareth, lebih dari dua ribu tahun yang silam.
Itulah ”pelajaran dari (perspektif) Maria”, menurut para penekun Injil. Aib yang harus ditanggung Maria, tunangan Yusuf yang mengandung oleh Roh Kudus, sebaliknya menyiratkan amanat mengenai rahmat serta tanda kukuhnya iman. Visualisasi paling terkenal dari petikan kisah itu, tentu saja, adalah lukisan dan fresco yang menghiasi altar dan dinding gereja-gereja Abad Pertengahan di Eropa. Pada The Annunciation itulah Gabriel digambarkan merunduk takzim di hadapan Maria yang melekapkan kedua tangannya di dada.
Tradisi klasik The Annunciation itu digubah kembali oleh Ronald Manullang sebagai panel pertama dari empat karyanya, The Final Judgment (200 x 180 sentimeter; cat minyak di atas kanvas, 2009). Seri lukisan monokromatik ini, bersama karya sejumlah perupa muda lain, muncul pada pameran The Holocaust di Umah Seni (6-20 Maret 2010), galeri baru yang diresmikan akhir tahun lalu, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Pusat perhatian pameran ini adalah empat lukisan The Final Judgment. Paradoks-paradoks mendalam muncul melalui pelukisan tokoh serta tafsir personal-religius terhadap sosok pembangun rezim totalitarian di abad lalu, Reich ke-3 (Jerman Baru), pemimpin Nazi, Adolf Hitler.
Pada panel pertama, The Annunciation, malaikat itu datang mengunjungi sang Fuhrer. Jari telunjuknya—tak seperti lazimnya menuding ke atas—digambarkan ditekuk ke bawah, mengesankan kebimbangan. Hitler terjepit kursi, sedikit tersentak, dan tak acuh. Raut dingin sang tiran menyembul dari balik atribut kebesaran, topi berlambang palang bengkok dalam lingkaran dan lambang kejayaan Jerman. Guncangan kecil pada sang diktator ini dilukiskan dengan sangat baik oleh Ronald, kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, 1954, yang belajar seni rupa di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI, Yogyakarta (1974-1981).
Wajah Hitler menoleh ke pojok. Pundaknya sedikit terangkat, terdorong oleh pegangan erat tangan kanannya pada kursi. Lengan kirinya terjuntai ke bawah, menggamit ujung Mein Kampf—”kitab suci” perjuangannya yang sudah ditulis pada 1924—yang nyaris merucut. Sang despot digambarkan bertubuh perempuan, mulus seperti seorang model, tanpa cela. Ketelanjangan tersingkap begitu saja dari jubah panjang berwarna gelap, sekaligus melucuti kegarangan.
Setidaknya, muncul dua macam pembalikan pada seri lukisan The Final Judgment. Yang pertama lewat strategi visual bergaya parodi terhadap khazanah klasik The Annunciation itu sendiri. Pesan malaikat sebagai tanda rahmat, keterkejutan, dan akhirnya penyerahan iman Maria diparodikan habis-habisan menjadi pesan-pesan sekuler mengenai tubuh perempuan dan kekuasaan totalitarian.
Ketelanjangan dan kehamilan tubuh perempuan dalam seri lukisan ini memang bisa menyiratkan hubungan ”lurus” pandangan fasisme dengan perempuan. Tugas utama moral perempuan, menurut pandangan Nazi, adalah melahirkan anak yang sehat dan sempurna: laki-laki dengan ras Jerman ”murni”, bangsa Arya. Tapi Ronald membalikkan pandangan kehamilan, bukan lagi sebagai rahmat (bagi perempuan), melainkan sebagai sarana penghakiman atau hukuman fisik (bagi laki-laki). Di sini, gagasan kekuasaan nasional-sosialis (Nazi) yang militeristis-maskulin langsung berbenturan juga dengan kehidupan-kefemininan tubuh perempuan.
Pembalikan kedua—terungkap pada lukisan-lukisan berikutnya—adalah pandangan mengenai kekuasaan. Kekuasaan seakan datang dari dalam, dari pengalaman paling rahasia dan personal, dan riwayatnya juga akan berakhir melalui apa yang lebih-kurang bersumber dari sana. Tafsir lain akan mengatakan bahwa kekuasaan juga tumbuh melalui pendasaran religius.
Hitler sendiri, seperti pernah ditulis oleh Hugh Purcell, memandang dirinya tak kurang sebagai mesias. Ia adalah manusia yang merasa dipilih oleh takdir. Pidatonya, ”sebuah serangan pada telinga”, dengan vibrasi menggelegar, kerap berisi teks berlandaskan ajaran Yesus dalam Injil. Hitler mengatur kalender Nazi sesuai dengan penanggalan Kristen; Partai Nazi, layaknya komunitas religius, bahkan menerima ”pengampunan dosa umum”. Mengaku jijik dan tak pernah membaca Mein Kampf selembar pun, Ronald Manullang mengatakan, ”Kalau ditilik lebih dalam, semua tentang Holocaust tidak lepas dari pengaruh kekristenan.”
Dalam hening sepeninggal sang malaikat, Hitler mengelus perutnya yang membuncit. Ia mengenakan busana tidur berenda, seakan menanti realisasi kebenaran sang nubuat (Expecting New Born Baby). Sang tiran akhirnya menjadi ibunda bagi bayi yang sehat dan montok. Sifat keibuan dan kelembutan ditandai oleh kepalanya yang sedikit meleng, dan ujung telunjuknya menyentuh telapak kaki bayi. Tapi ”permata” ras kulit putih, mitos Arya yang diimpikan, itu mengidap penanda kebenaran yang lain: sebuah rajah di lengan, barisan nomor dalam kamp konsentrasi Auschwitz (The Fuhrer and Child).
Lukisan terakhir seri ini adalah The Crucifixion. Hitler tak lagi menatap lurus ke depan, tapi duduk menyamping dengan kepala sedikit merunduk. Kesepuluh jemarinya terangkum dalam sikap doa. Narasi pada karya ini mengisahkan akhir riwayat sang tiran berpangkat kopral pada hukum ”penyaliban”. Tentunya, tajuk lukisan ini sekaligus juga mengingatkan kita akan tradisi lukisan-lukisan penyaliban yang menampilkan sosok Yesus. Namun, melalui renungan dan kuas Ronald, ”penyaliban” (salib dengan corpus Yesus) merupakan sebuah instrumen dari dalam, dan bersama sang korban kini berbalik ”menyalibkan” sang tiran.
Ronald mengatakan, ”Hitler pernah memerintahkan massanya untuk menyerang (orang-orang) Yahudi, karena (mereka) telah menyalibkan Tuhannya. Itu yang mendasari panel keempat.”
Bagi Ronald, pandangan rasial anti-Semit—komponen utama Naziisme—itulah yang kini justru menjadi elemen penghakiman akhir bagi riwayat Hitler. Itulah narasi-narasi Ronald mengenai sang diktator yang telah mengguncangkan Eropa, mengawali gerakan fasisme dalam Nazi setelah Perang Dunia I, yang menjadi gerakan massa yang menggemparkan pada 1930-an.
The Final Judgment inilah yang lalu diperluas oleh lima seniman muda dari Bandung dan Bali menjadi The Holocaust. Dari Bali (Agus Sumiantara, 30 tahun); dari Bandung (Endira F.J., 26 tahun); Muhammad Reggie Aquara, 28 tahun; Muhammad Zico Albaiquini, 23 tahun; Yogie Ahmad Ginanjar, 29 tahun; dan satu dari Malaysia (Hamdan Omar).
Yogie melukiskan sosok Mickey berbaju pesulap yang dikerumuni para pejabat Nazi. Kekaguman akan sesuatu yang tak masuk akal seakan mengingatkan kita pada kegandrungan terhadap musik dan opera Wagner abad ke-19, yang membangkitkan ingatan akan mitos-mitos purba Jerman. Endira F.J., menggabungkan teknik lukis dan gambar, menampilkan citra tentara Nazi bersama seekor herder, binatang kebanggaan untuk mengamankan kamp-kamp konsentrasi. ”Kebinatangan” agaknya merupakan kritik halus seniman ini terhadap organ-organ menakutkan Nazi, seperti para anggota Gestapo dan Pasukan Penjaga (SS).
Sebuah karya menarik justru menyimpang dari pakem cerita-cerita besar di sekitar Nazi dan Holocaust, dari Zico Albaiquni. Zico merekam beberapa patah kata yang dilafalkan sejumlah orang bule, yakni ”Aw!”, ”Loh!”, ”Who!”, ”Akh!”, dan ”Bar!”. Kata-kata ini merupakan potongan dari sebuah ungkapan religius yang utuh: ”Allahu Akbar”. Rekaman video tanpa suara dan lima lukisan dengan citra bertumpuk yang ditangkap dari citraan mesin itu seakan hanya menghasilkan kekacauan dan kekaburan pelafalan.
Lukisan-lukisan Zico dengan cermat menangkap ”kebenaran” kekacauan dan tumpang-tindih ekspresi itu. Memori mengenai ekspresi para pengucap itu muncul lebih kuat ketimbang apa yang diucapkan. Bukankah kita memang sering terpenjara oleh pandangan akan yang asing, dengan semata mengandalkan identitas luar?
The Final Judgment telah melahirkan kembali Ronald Manullang—yang pernah terlibat Gerakan Seni Rupa Baru dan Kepribadian Apa (Pipa) pada 1970-an—ke panggung seni rupa kita. Dan agaknya The Holocaust melahirkan Zico. Putra sulung seniman Tisna Sanjaya ini boleh diharapkan menjadi pasca-bapaknya.
Hendro Wiyanto, pemerhati seni rupa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo